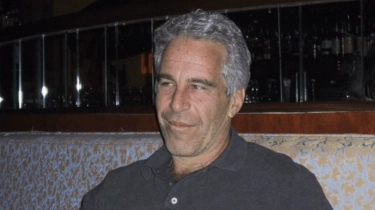Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden
KEPUTUSAN Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) memicu perdebatan luas di ruang publik.
Sebagian memandangnya sebagai langkah pragmatis agar Indonesia tetap terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Gaza.
Sebagian lain menilainya sebagai kompromi yang berisiko menggerus prinsip politik luar negeri Indonesia.
Perdebatan ini wajar. Namun, persoalan yang mengemuka sesungguhnya lebih mendasar daripada sekadar setuju atau tidak setuju terhadap BoP.
Persoalan itu terletak pada bagaimana keputusan strategis ini disiapkan dan disodorkan kepada Presiden Prabowo Subianto?
Dalam dunia internasional yang tidak pernah hitam-putih, Presiden seharusnya tidak dihadapkan pada pilihan yang sempit. Ia membutuhkan peta opsi yang lengkap, disertai penjelasan jujur mengenai risiko, manfaat, dan harga dari setiap pilihan.
Di titik inilah kinerja para pembantu Presiden, baik menteri, diplomat, dan aparat intelijen, patut ditinjau secara lebih serius.
Dari arah perdebatan publik yang berkembang, muncul kesan bahwa keputusan terkait BoP dihadirkan kepada Presiden dalam kerangka yang sangat minimalis: ikut atau tidak ikut.
Baca juga: Board of Peace dan Ujian Konstitusional Politik Luar Negeri
Pilihan biner semacam ini terasa miskin nuansa, padahal politik internasional justru merupakan ruang yang sarat gradasi, kompromi, dan kemungkinan alternatif. Dunia diplomasi jarang, bahkan hampir tidak pernah, bekerja dalam logika hitam-putih.
Jika kesan tersebut benar, maka persoalan utamanya tidak terletak pada Presiden sebagai pengambil keputusan akhir, melainkan pada kualitas masukan kebijakan yang disiapkan oleh para pembantunya.
Dalam situasi global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian, Presiden semestinya disodori bukan pilihan mentah, melainkan spektrum opsi strategis yang matang, lengkap dengan konsekuensi dan banderol harga dari setiap keputusan yang mungkin diambil.
Presiden dan masalah “pilihan mentah”
Dalam tata kelola negara modern, Presiden bukanlah operator teknis. Ia adalah pengambil keputusan strategis.
Justru karena itu, Presiden tidak seharusnya disuguhi data mentah atau opsi setengah jadi. Tugas para menteri, duta besar, dan aparat intelijen adalah mengolah realitas yang kompleks menjadi pilihan-pilihan strategis yang rasional, lengkap dengan risiko, peluang, dan harga yang harus dibayar.
Dalam isu BoP, yang tampak ke permukaan justru seolah Presiden dihadapkan pada dilema sempit: jika ikut, Indonesia mendapat akses; jika tidak, Indonesia tertinggal.
Narasi ini berbahaya karena menyederhanakan dunia internasional menjadi logika hitam-putih yang tidak pernah benar-benar ada.
Padahal, dalam praktik diplomasi, hampir tidak pernah hanya ada dua pilihan.
Politik internasional bukan referendum dengan dua kotak suara. Ia adalah arena negosiasi berlapis, dengan banyak jalur (track), banyak aktor, dan banyak ruang manuver.
Negara yang matang dalam diplomasi justru unggul karena kemampuannya menciptakan opsi baru, bukan sekadar memilih dari opsi yang disodorkan pihak lain.
Jika Indonesia hanya diberi dua opsi; ikut atau tidak ikut, itu menandakan kegagalan pada level perencanaan strategis. Bukan karena opsinya tidak ada, tetapi karena opsi-opsi itu tidak diproduksi.
Baca juga: Menyoal Dukungan PBNU pada Board of Peace
Di sinilah pertanyaan kritis patut diajukan: di mana peran Kementerian Luar Negeri? Di mana analisis Badan Intelijen Negara? Di mana jaringan duta besar Indonesia yang seharusnya menjadi mata dan telinga negara di luar negeri?
Diplomasi tidak pernah satu jalur
Dalam literatur hubungan internasional, dikenal konsep multi-track diplomacy. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat (track one), tetapi juga melalui jalur parlementer, kemanusiaan, keagamaan, akademik, bahkan bisnis.
Indonesia selama ini justru dikenal piawai memainkan berbagai jalur ini, terutama dalam isu Palestina.
Dengan modal tersebut, sangat sulit membayangkan bahwa Indonesia tidak memiliki opsi lain selain ikut penuh atau tidak ikut sama sekali.
Opsi-opsi alternatif itu sebenarnya banyak: ikut sebagai pengamat, ikut dengan klausul eksplisit, ikut terbatas pada isu kemanusiaan, atau bahkan tidak ikut, tetapi membentuk koalisi paralel bersama negara-negara Global South.
Jika opsi-opsi ini tidak sampai ke meja Presiden, maka masalahnya bukan kekurangan pilihan, melainkan kemiskinan imajinasi strategis di level pembantu Presiden.
Lalu, di mana analisis harga? Karena setiap pilihan kebijakan luar negeri selalu memiliki harga. Tugas utama para penasihat Presiden adalah memetakan harga tersebut secara jujur dan komprehensif.
Jika ikut BoP, apa harga reputasional Indonesia di mata pendukung Palestina? Jika tidak ikut, apa dampaknya terhadap akses diplomatik? Jika ikut bersyarat, bagaimana mekanisme keluar jika syarat dilanggar?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara normatif. Ia membutuhkan analisis mendalam, berbasis data, dan proyeksi jangka panjang.
Sayangnya, perdebatan publik menunjukkan bahwa dimensi “harga” ini tidak disampaikan secara terbuka. Seolah-olah keputusan dibuat dalam ruang sempit, tanpa spektrum opsi yang luas.
Ini bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi indikasi bahwa proses perumusan kebijakan mungkin tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, peran Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN menjadi sangat krusial.
Baca juga: Board of Peace dan Dilema Diplomasi Indonesia
Mereka bukan sekadar pelaksana, melainkan arsitek kebijakan. Mereka diharapkan mampu membaca pola, memprediksi arah, dan menawarkan jalan keluar yang kreatif.
Diplomasi bukan soal bereaksi cepat, tetapi soal membaca beberapa langkah ke depan. Jika inisiatif internasional dipimpin secara personalistik dan sarat kontroversi, justru di situlah kewaspadaan harus ditingkatkan, bukan diturunkan.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah Presiden sudah disuguhi semua skenario yang mungkin? Apakah ia diberi ruang untuk mengatakan, “Saya ingin opsi ketiga”?
Jika tidak, maka fungsi pembantu Presiden telah tereduksi menjadi penyampai pesan, bukan perumus strategi.
Ketika terobosan tidak diproduksi
Frederik Agung pernah mengatakan, “Diplomasi tanpa persenjataan bagaikan musik tanpa instrumen.”
Kalimat ini mungkin tepat bagi negara-negara besar dengan kekuatan militer yang dominan. Namun, bagi Indonesia, pengalaman sejarah justru menunjukkan sebaliknya.
Sejak masa merebut kemerdekaan hingga hari ini, kekuatan militer Indonesia tidak pernah benar-benar dirancang untuk menakut-nakuti dunia.
Untuk negara kepulauan yang luas dan majemuk, instrumen utama Indonesia bukanlah meriam, melainkan diplomasi.
Diplomasilah yang membuka jalan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Diplomasilah yang memungkinkan republik muda ini bertahan di tengah tarik-menarik kekuatan besar pada masa Perang Dingin, ketika Indonesia harus “mendayung di antara dua karang”.
Dengan diplomasi pula, Indonesia berhasil menjaga keutuhan wilayahnya, mengikat satu per satu pulau dari Papua di timur hingga Sumatera di barat dalam satu kesatuan politik yang diakui dunia.
Bahkan perluasan wilayah darat dan laut Indonesia – yang kini mencapai jutaan hektar di garis khatulistiwa – tidak dicapai melalui agresi militer atau unjuk kekuatan bersenjata, melainkan lewat meja perundingan, forum internasional, dan kesabaran diplomatik.
Dalam konteks ini, arti diplomasi bagi Indonesia nyaris bersifat eksistensial. Ia bukan sekadar alat kebijakan luar negeri, melainkan senjata politik paling masyhur yang membentuk dan menjaga Republik ini.
Sejarah diplomasi Indonesia juga menunjukkan bahwa terobosan-terobosan penting justru lahir dari situasi yang sulit.
Konferensi Asia-Afrika, peran aktif dalam Gerakan Non-Blok, hingga diplomasi kemanusiaan di berbagai kawasan konflik, semuanya berangkat dari keberanian untuk keluar dari logika dominan kekuatan besar. Indonesia tidak menunggu dunia menjadi ideal; ia menciptakan ruangnya sendiri.
Baca juga: Berhitung Manfaat dan Risiko Indonesia di Board of Peace
Di titik inilah ironi muncul dalam kasus keterlibatan Indonesia dalam BoP. Di tengah dunia yang semakin cair, multipolar, dan terbuka terhadap inisiatif baru, pilihan Indonesia justru terkesan direduksi menjadi hitam-putih: ikut atau tidak ikut.
Padahal, dunia hari ini menuntut kreativitas diplomatik, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap skema yang dirancang pihak lain.
Terobosan tidak akan pernah lahir jika Presiden hanya diberi pilihan standar. Diplomasi Indonesia tidak dibangun untuk sekadar memilih dari menu yang disodorkan kekuatan besar, melainkan untuk merancang menu alternatifnya sendiri.
Untuk itu, Presiden membutuhkan bahan bakar berupa ide-ide segar, analisis tajam, dan keberanian berpikir di luar kerangka yang mapan. Tradisi yang justru menjadi kekuatan historis politik luar negeri Indonesia.
Menyelamatkan martabat politik luar negeri
Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Indonesia telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Board of Peace, dan keputusan itu tidak dapat diputar ulang begitu saja.
Pada titik ini, perdebatan publik tidak lagi produktif jika berhenti pada penyesalan atau saling menyalahkan.
Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia mengelola keputusan yang sudah diambil agar tidak menjauh dari sejarah, jati diri, dan martabat politik luar negerinya sendiri.
Ke depan, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam politik global hampir pasti akan semakin sulit. Dunia bergerak menuju ketidakpastian yang lebih besar, kompetisi kekuatan yang kian tajam, dan ruang manuver yang semakin sempit bagi negara-negara menengah seperti Indonesia.
Dalam situasi semacam ini, pilihan kebijakan luar negeri justru akan semakin terbatas, sementara harga dari setiap pilihan akan semakin mahal.
Justru karena itu, pengalaman keterlibatan Indonesia dalam BoP semestinya dibaca sebagai pelajaran berharga bagi kita semua sebagai anak bangsa.
Pelajaran bahwa dalam dunia yang kompleks, kemampuan menciptakan opsi sering kali lebih menentukan daripada keberanian memilih satu opsi.
Di titik inilah peran para pembantu Presiden menjadi krusial. Menteri, diplomat, dan aparat intelijen tidak cukup hanya menyajikan data atau rekomendasi singkat.
Mereka dituntut menghadirkan analisis yang kaya, skenario berlapis, serta alternatif-alternatif yang mungkin terasa tidak lazim, tetapi justru relevan.
Presiden harus dibekali ruang berpikir yang luas, bukan dikunci dalam logika ikut atau tidak ikut.
Kedaulatan dalam politik luar negeri pada akhirnya bukan sekadar soal keberanian mengambil keputusan, melainkan kualitas proses yang melahirkannya.
Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu merancang pilihan-pilihannya sendiri, bahkan ketika dunia tidak menyediakan pilihan yang ideal. Inilah makna dari doktrin “politik luar negeri bebas-aktif” itu.
Dalam konteks inilah, kritik publik menemukan relevansinya. Bukan untuk menghakimi keputusan yang telah diambil, melainkan memperbaiki cara negara berpikir dan bertindak ke depan.
Jika diplomasi adalah senjata utama Indonesia sejak awal berdirinya republik, maka senjata itu hanya akan tetap tajam jika diasah dengan kecermatan, imajinasi, dan keberanian intelektual.
Board of Peace boleh menjadi satu episode. Namun, martabat politik luar negeri Indonesia akan ditentukan oleh apakah kita mampu belajar dari episode ini.
Dan memastikan bahwa di masa depan, setiap keputusan besar lahir dari proses berpikir yang lebih matang, lebih kreatif, dan lebih setia pada jati diri bangsa.