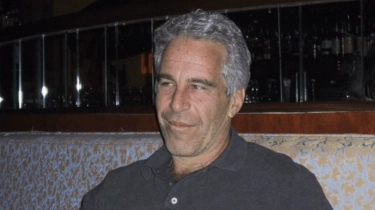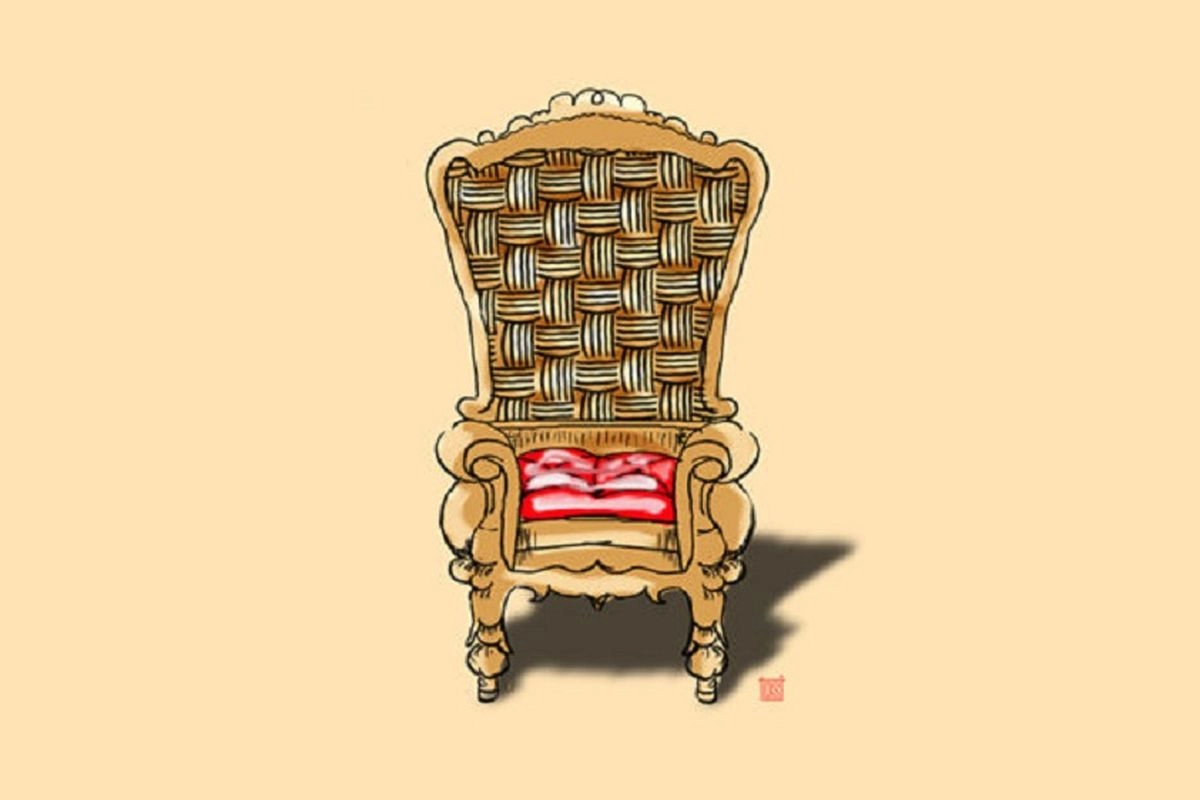
Dua Kali Kekuasaan, Sekali Demokrasi
DEMOKRASI selalu hidup dari harapan. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa masa depan tidak boleh dikunci terlalu dini.
Bahwa rakyat, dalam setiap siklus pemilu, berhak membuka kembali pilihan, menimbang ulang kepemimpinan, dan mengoreksi arah kekuasaan.
Karena itu, demokrasi sejatinya adalah ruang yang cair—bukan peta yang sudah digambar jauh sebelum waktunya.
Namun, wacana “dua kali kekuasaan” yang mengemuka belakangan ini menghadirkan bayang yang ganjil.
Pada akhir 2024 lalu, sebelum pemerintahan berjalan satu tahun penuh, publik sudah diajak berbicara tentang periode kedua.
Bahkan sebelum hasil kerja dapat dinilai secara objektif, masa depan sudah seperti disiapkan. Demokrasi pun perlahan kehilangan sifat dasarnya: ketidakpastian yang sehat.
Di titik inilah problemnya. Bukan pada boleh atau tidaknya seorang presiden maju kembali. Konstitusi kita jelas memperbolehkan dua periode.
Masalahnya justru terletak pada kapan dan bagaimana wacana itu dimunculkan. Ketika periode kedua dibicarakan sebelum periode pertama benar-benar dimulai, demokrasi tidak lagi menjadi proses terbuka, melainkan skenario yang disusun dari atas.
Baca juga: Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode: Kunci Pilpres 2029 Lebih Awal
Demokrasi bekerja dengan ritme. Ada waktu untuk berkampanye, ada waktu untuk memerintah, ada waktu untuk mengevaluasi, dan ada waktu untuk memilih kembali. Jika semua fase itu dipadatkan, demokrasi kehilangan napasnya.
Wacana dua periode yang muncul terlalu dini sesungguhnya adalah bentuk pemendekan waktu politik.
Masa depan dipanggil ke hari ini, seolah-olah publik tidak perlu menunggu hasil kerja, tidak perlu merasakan dampak kebijakan, tidak perlu menguji janji. Semua sudah dipastikan lebih dulu.
Dalam demokrasi yang sehat, periode kedua adalah reward—bukan setting. Ia diberikan oleh rakyat setelah melihat kinerja, bukan dirancang sejak awal.
Jika periode kedua diperlakukan sebagai rencana awal, maka pemilu berikutnya kehilangan makna substantif. Ia hanya menjadi formalitas dari keputusan yang sudah diambil jauh hari.
Demokrasi tidak mati karena kekuasaan panjang. Ia mati karena kehilangan waktu untuk berpikir.
Setiap kekuasaan hidup dari narasi. Bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari cerita tentang dirinya sendiri.
Dalam konteks wacana dua periode, narasi yang dibangun bukanlah tentang capaian atau program, melainkan tentang keberlanjutan, stabilitas, dan kepastian.
Kata-kata itu terdengar indah. Namun, di baliknya tersembunyi pesan lain: bahwa perubahan dianggap berisiko, bahwa alternatif dianggap tidak perlu, bahwa demokrasi sebaiknya tidak terlalu sering mengganti pemimpin.
Narasi semacam ini berbahaya bukan karena salah, tetapi karena menutup ruang imajinasi politik. Rakyat tidak lagi diajak membayangkan kemungkinan lain. Mereka diarahkan untuk percaya bahwa pilihan terbaik sudah tersedia, tinggal dilanjutkan.
Padahal, demokrasi hidup justru dari keberanian membayangkan yang lain. Ia bukan soal mempertahankan yang ada, melainkan membuka peluang bagi yang mungkin lebih baik.
Kekuasaan
Kekuasaan selalu ingin bertahan. Itu bukan dosa politik; itu naluri. Namun, demokrasi hadir justru untuk membatasi naluri itu. Ia menciptakan mekanisme agar kekuasaan tidak terlalu nyaman, tidak terlalu lama, dan tidak terlalu pasti.
Ketika wacana dua periode dimunculkan terlalu dini, yang terjadi bukan sekadar diskursus politik, melainkan pergeseran psikologis kekuasaan.
Baca juga: PSI: Partai Muda dalam Rumus Matematika Politik Lama
Pemerintahan mulai bekerja dengan asumsi bahwa ia akan berlanjut. Kritik menjadi kurang penting. Evaluasi menjadi formalitas. Oposisi dianggap gangguan, bukan kebutuhan.
Kekuasaan yang merasa dirinya akan panjang cenderung kehilangan rasa urgensi. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan diri, tetapi untuk mengamankan posisi.
Kebijakan tidak lagi dirancang untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menjaga citra keberlanjutan.
Di titik ini, kekuasaan berubah dari alat demokrasi menjadi tujuan itu sendiri.
Wacana dua periode jarang lahir dari rakyat. Ia hampir selalu lahir dari elite. Dari relawan, dari partai, dari lingkar kekuasaan yang merasa stabilitas lebih penting daripada dinamika.
Elite memiliki kepentingan yang sah: mereka ingin kesinambungan, akses, dan pengaruh. Namun, demokrasi tidak boleh hanya menjadi ruang kenyamanan elite. Ia harus tetap menjadi arena terbuka bagi rakyat untuk menentukan ulang arah.
Ketika elite terlalu dini membicarakan periode kedua, mereka sesungguhnya sedang memonopoli masa depan. Mereka bertindak seolah-olah suara rakyat di pemilu berikutnya sudah dapat diprediksi, bahkan diatur.
Di sinilah demokrasi kehilangan daya korektifnya. Rakyat tidak lagi menjadi subjek, melainkan objek dari perencanaan politik jangka panjang.
Demokrasi bukan hanya soal siapa yang memerintah, tetapi juga siapa yang berkesempatan memerintah. Regenerasi adalah jantung demokrasi. Tanpanya, politik berubah menjadi klub tertutup yang berputar di lingkar elite yang sama.
Wacana dua periode yang muncul terlalu dini secara tidak langsung mematikan proses regenerasi. Tokoh-tokoh potensial lain kehilangan ruang untuk tumbuh. Partai tidak lagi serius menyiapkan alternatif. Semua energi politik diarahkan untuk mempertahankan yang ada.
Padahal, salah satu fungsi utama demokrasi adalah membuka jalan bagi pemimpin baru, ide baru, dan pendekatan baru. Jika regenerasi dibekukan sejak awal, maka demokrasi berubah menjadi sistem pengulangan, bukan pembaruan.
Kekuasaan mungkin berlanjut, tetapi imajinasi politik berhenti.
Secara hukum, dua periode sah. Tidak ada yang melanggar konstitusi. Namun, demokrasi tidak hanya hidup dari hukum; ia hidup dari etika.
Baca juga: Lebih Prioritas Mana: MBG atau Penciptaan Lapangan Kerja?
Etika demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan harus memberi ruang bagi ketidakpastian. Bahwa masa depan tidak boleh dipastikan oleh mereka yang sedang berkuasa. Bahwa rakyat berhak menunda keputusan sampai mereka benar-benar melihat hasil.
Membicarakan periode kedua terlalu dini bukan pelanggaran hukum, tetapi problem etika. Ia menunjukkan ketergesaan untuk mengunci masa depan. Ia menandakan kurangnya kesabaran demokratis.
Demokrasi membutuhkan kepercayaan diri: percaya bahwa jika memang layak, rakyat akan memberi mandat kembali tanpa perlu disiapkan dari jauh hari.
Wacana dua periode juga menciptakan bayang lain: bayang-bayang kekuasaan lama yang masih kuat. Ketika mantan pemimpin masih aktif mengarahkan konfigurasi masa depan, demokrasi menghadapi situasi ambigu.
Siapa sebenarnya pusat legitimasi? Pemimpin yang sedang menjabat, atau tokoh yang telah selesai menjabat tetapi masih menentukan arah?
Dalam situasi seperti ini, demokrasi berisiko mengalami apa yang bisa disebut kekuasaan bayangan—kekuasaan yang tidak formal, tetapi sangat berpengaruh.
Demokrasi membutuhkan kejelasan peran. Masa lalu harus memberi ruang bagi masa kini untuk bekerja secara otonom. Jika tidak, maka pemerintahan berjalan di bawah bayang yang tidak pernah benar-benar pergi.
Republik dibangun atas asumsi bahwa kekuasaan bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang tak tergantikan. Setiap pemimpin hanyalah penjaga sementara dari mandat rakyat.
Ketika wacana dua kali kekuasaan dimunculkan terlalu dini, republik kehilangan salah satu prinsip dasarnya: kesadaran akan keterbatasan. Kekuasaan mulai diperlakukan sebagai proyek jangka panjang, bukan amanah sementara.
Republik yang sehat justru membutuhkan jeda. Jeda untuk berpikir, jeda untuk menilai, jeda untuk meragukan. Tanpa jeda, republik berubah menjadi mesin politik yang bergerak otomatis, tanpa refleksi.
Pada akhirnya, masalahnya bukan pada dua kali kekuasaan, melainkan pada sekali demokrasi. Jika periode kedua disiapkan sejak awal, demokrasi hanya diberi satu kesempatan: kesempatan untuk mengesahkan rencana elite.
Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi kejutan, koreksi, dan bahkan kegagalan. Ia bukan sistem yang menjanjikan kepastian, tetapi sistem yang menjamin kebebasan memilih ulang.
Ketika masa depan dipastikan terlalu dini, demokrasi kehilangan sifat eksperimentalnya. Ia tidak lagi menjadi proses, melainkan hasil yang sudah ditentukan.
Dan di situlah paradoksnya: kekuasaan mungkin berlanjut dua kali, tetapi demokrasi hanya dijalankan sekali.
Tag: #kali #kekuasaan #sekali #demokrasi