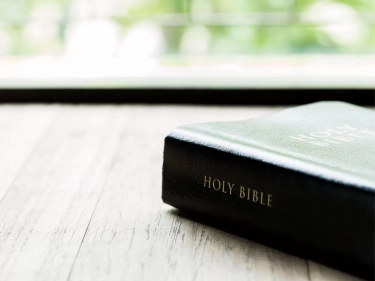Mabuk Kuasa dan ''Kebenaran Elektoral''
DALAM tahun politik yang kian mendekati ke waktu pemilihan presiden, semua diskursus tentang kebanaran dihipotesakan selalu berdimensi politis.
Dengan kata lain, ungkapan kebenaran dari siapapun berasal, apalagi dari kubu dan simpatisan paslon tertentu dianggap sebagai kebenaran yang bermotif kepentingan.
Ungkapan ini sejalan dengan teori filsuf Perancis Michel Foucault (1926-1984) yang melihat bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral dan objektif, tetapi merupakan hasil dari hubungan kekuasaan.
Pengetahuan digunakan untuk memengaruhi individu, mengontrol perilaku, dan menjaga ketertiban sosial.
Kaum terdidik dan intelektual yang sedang berada dalam tim pemenangan capres-cawapres akan mengerahkan pengetahuannya untuk melegitimasi kepentingan politik elektoralnya.
Watak rasionalitas, objektifitas, dan moralitasnya mau tidak mau harus dikoridori oleh kepentingannya.
Dengan fakta ini, maka tesis Michel Foucalt masih relevan untuk dilekatkan. Pandangan Foucalt ini beririsan dengan pandangan Niccolo Machiavelli (1469-1527) seorang filsuf, politikus, dan penulis Italia yang terkenal karena pemikirannya yang kontroversial dan cenderung realis dalam politik.
Menurut dia, manusia lebih memilih untuk mengambil keuntungan pribadi daripada mematuhi prinsip moral atau agama.
Pandangan ini tercermin dalam karyanya yang paling terkenal, “The Prince” (1532), dimana Machiavelli menyarankan bahwa seorang penguasa harus mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara yang diperlukan, bahkan jika itu berarti mengabaikan moral dan etika.
Menurut dia, penguasa harus berani menggunakan kekerasan, tipu muslihat, dan manipulasi untuk mempertahankan kekuasaannya.
Selain itu, Machiavelli juga menentang pandangan agama yang menganggap kebaikan hati dan moralitas sebagai hal yang utama dalam politik. Menurutnya, dalam politik, kebaikan hati dan moralitas hanya akan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan.
Sebagai seorang realis, Machiavelli sedang mengkonstruksi pengetahuannya atas realitas politik yang dialaminya. Pandangan ini bisa jadi sebagai bentuk otokritik bagi bangsanya terhadap relasi politik dan moral.
Namun pada saat yang sama, ia sedang mendeskripsikan secara induktif apa yang sedang terjadi. Karena pengetahuan, pada dasarnya berasal dari fenomena sosial sebagaimana keyakinan dari doktrin sosiologi pengetahuan yang pernah dikatakan oleh Karl Mannheim.
Kekuasaan dan kebenaran
Adu persepektif yang mengulas aneka gagasan substantif—apalagi di era media sosial yang serba cepat dan pendek—seringkali mudah terhalang oleh aneka gimik dan pandangan partisan yang mendominasi banyak percakapan publik.
Sementara kejernihan pandangan reflektif yang bermuatan nilai-nilai moral betapapun substantifnya tertutupi oleh kebenaran yang berdimensi kepentingan.
Kebenaran yang berdimensi moral sedang kalah saing dan ditundukan oleh kebenaran yang populer.
Kebenaran ilmiah yang bersifat rasional dan faktual yang dibungkus dengan paradigma survei dalam batas-batas tertentu telah menjadi propaganda tersendiri untuk memuluskan apa yang disebut oleh pakar ilmu filsafat Karlina Supeli sebagai operasi “rezim otokrasi elektoral”.
Suatu rezim yang dipilih secara demokratik, tetapi secara perlahan sedang membunuh demokrasi itu sendiri.
Ide terselubung “tiga periode” yang diucapkan oleh pejabat penguasa adalah cerminan dari mabuk kuasa dengan mengatasnamakan seruan moral, “demi keberlangsungan pembangunan” dan atas nama “kemajuan Indonesia”.
Suatu diksi propagandis yang bisa memengaruhi nalar publik. Jika itu dijadikan sebagai kebenaran pengetahuan, maka pengetahuan ini telah “berselingkuh” dengan ide politik perpanjangan kekuasaan.
Dan akhirnya, dalam realitasnya, ide perpanjangan kekuasaan telah menjelma dalam peristiwa hukum di Mahkamah Konstitusi dengan meminjam istilah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahnedra sebagai “penyelundupan hukum”.
Kebenaran hukum produk Mahkamah Konstitusi berjalan melenggang sambil menggendong cacat etika.
Meski dalam prinsip-prinsip demokrasi amat problematis, rezim otokrasi elektoral merasa dipandu oleh “kebanaran hukum” yang sah. Artinya, debat moral bukanlah penghalang untuk menjalankan sistem demokrasi prosedural.
Lagi-lagi, pandangan kontroversial Machiavelli tengah beroperasi dalam perjalanan politik bangsa ini.
Kebenaran rakyat
Karena doktrin demokrasi menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, maka ukuran demokratis atau tidak ditimbang dari keputusan rakyat itu sendiri.
Aneka isu dan fakta tentang kekeliruan moral seperti penyelundupan hukum, politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan ambisi politik pribadi dan keluarga, penggunaan alat-alat kekuasaan dan lain-lain akan dinilai oleh rasionalitas dan nurani rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik “kebenaran demokrasi”.
Di sini lantas muncul anomali antara persepsi kelas menengah terdidik (baik yang partisan atau nonpartisan) dan persepsi masyarakat awam yang jumlahnya mayoritas terhadap realitas.
Peristiwa pelanggaran etis di MK sebagai cacat demokrasi belum terdampak secara langsung terhadap penghukuman elektabilitas paslon tertuduh. Elektabilitasnya yang direkam oleh mayoritas lembaga survei tetap tinggi.
Anomali ini menyimpan banyak variabel penyertanya. Di antaranya adalah bahwa isu kaum intelektual tidak berbanding lurus dengan isu masyarakat awam.
Mengapa? Di antara penjelasannya adalah bahwa isu terbesar masyarakat biasa bukanlah pada pikiran, tetapi pada “rasa lapar” yang mudah didekati dengan aksi bantuan langsung tunai (BLT), berita makan gratis, sekolah gratis dan lain-lain.
Dengan demikian, konstruksi pengetahuan penguasa, disadari atau tidak, berhasil memengaruhi model pengetahuan rakyat. Dan itu artinya, kerusakan demokrasi bukan menjadi isu rakyat apalagi isu dan agenda rezim otokrasi elektoral.
Tag: #mabuk #kuasa #kebenaran #elektoral