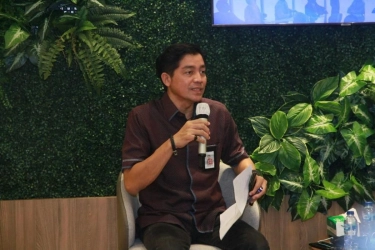Dosa Fiskal Whoosh Tak Seharusnya Dipayungi APBN
AKHIRNYA, Whoosh dipayungi APBN juga. Tidak ada yang lebih ironis dari proyek yang dilahirkan untuk membuktikan kemandirian fiskal, tapi justru berakhir dalam pelukan anggaran negara.
Itulah nasib Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), atau lebih dikenal dengan nama komersialnya, Whoosh.
Di balik kemasan kebanggaan nasional, proyek ini berdiri di atas narasi besar tentang kemandirian ekonomi bahwa pembangunan dapat dilakukan tanpa membebani APBN.
Namun, sembilan tahun setelah gagasan awalnya diumumkan, dan baru setahun sejak diresmikan oleh Joko Widodo, proyek yang dulu dipromosikan sebagai simbol modernitas Indonesia itu justru berakhir menggigit sumber kehidupan fiskal negara sendiri.
Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto mewarisi sesuatu yang lebih berat daripada rel baja: warisan kebijakan yang salah urus, tidak akuntabel, dan kini menuntut bailout dalam bentuk subsidi negara.
Ketika Jokowi menandatangani izin pendirian PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada 2015, ia berjanji proyek ini akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang tidak memakai dana APBN.
Namun, waktu telah membuktikan bahwa janji itu bukan sekadar ambisi, tetapi ternyata juga ilusi. Skema bisnis yang disebut business-to-business ternyata hanyalah kedok administratif dari struktur keuangan yang berlapis jaminan negara.
Ketika biaya membengkak dari estimasi awal 6 miliar dolar AS menjadi lebih dari 7,3 miliar dolar AS, dan utang kepada China Development Bank melonjak, negara akhirnya tak punya pilihan selain turun tangan.
Kini, PMN BUMN digunakan untuk menutup defisit, dan—seperti diramalkan oleh banyak ekonom termasuk Ignasius Jonan, Whoosh menjadi contoh bagaimana proyek politik dapat berubah menjadi beban fiskal ketika akuntabilitas dikorbankan.
Masalahnya bukan hanya soal uang, tapi tentang logika kebijakan yang keliru sejak lahir.
Jurnal akademik yang diterbitkan awal 2024 oleh dua ekonom China, Wang dan Jiang, berjudul Welfare Implications of a Mixed Ownership–Operations Structure of High-Speed Train, menjelaskan dengan sangat gamblang kesalahan desain semacam ini.
Mereka menemukan bahwa model mixed ownership and operation, di mana kepemilikan infrastruktur dan operasi kereta dipisahkan antara entitas berbeda, memang sering dipilih negara berkembang karena tampak “aman” dari beban fiskal langsung.
Namun dalam kenyataannya, model ini justru menciptakan konflik kepentingan antara pemilik aset yang mengejar stabilitas politik dan operator yang mengejar keuntungan komersial.
Hasilnya? Efisiensi sosial menurun, biaya koordinasi naik, dan pada akhirnya negara harus turun tangan menanggung beban.
Persis seperti yang kini terjadi di Indonesia. Dalam kerangka teori Wang & Jiang, struktur KCIC bisa dikategorikan sebagai mixed structure yang maladaptif untuk pasar besar.
Pasar transportasi Jawa Barat–Jakarta bukanlah pasar kecil yang bisa mengandalkan subsidi silang atau optimisme permintaan jangka pendek.
Ini pasar besar dengan sensitivitas harga tinggi, jarak pendek, dan tingkat substitusi moda transportasi yang tinggi, semua faktor yang membuat proyek semacam ini non-viable secara finansial tanpa subsidi.
Maka, apa yang kini disebut bantuan APBN sejatinya bukan kebijakan baru dari pemerintahan Prabowo, melainkan konsekuensi logis dari kesalahan desain lama.
Dengan kata lain, Whoosh sejak awal memang tidak mungkin berdiri tanpa APBN. Hanya saja, dulu pemerintah memilih menutupi kenyataan itu dengan retorika.
Tak heran jika Presiden Prabowo kemudian memanggil Ignasius Jonan ke Istana. Meski tak diakui terang-terangan oleh pihak Istana maupun Ignasius Jonan, pertemuan itu jelas berpusat pada proyek kereta cepat.
Jonan bukan sosok sembarangan. Sebagai mantan Menteri Perhubungan dan mantan Dirut PT KAI, bankir itu adalah salah satu dari sedikit pejabat yang secara terbuka menolak proyek ini pada masa awalnya.
Alasannya sederhana, proyek tidak layak secara ekonomi. Jonan pernah menegaskan bahwa membangun jalur kereta cepat antara Jakarta dan Bandung tidak rasional, karena jaraknya terlalu pendek untuk justifikasi investasi sebesar itu.
Namun, keberatan semacam itu dikalahkan oleh politik pencitraan, oleh hasrat membangun megaproyek berkecepatan tinggi di bawah bayang-bayang kompetisi regional.
Kini, delapan tahun kemudian, ucapan Jonan menjadi nubuatan, proyek ini benar-benar meleset dari proyeksi dan harus diselamatkan oleh uang publik. Rakyat juga yang akhirnya ketiban apesnya.
Situasi ini menempatkan pemerintahan baru dalam dilema moral dan fiskal. Di satu sisi, Prabowo tidak mungkin menutup proyek begitu saja.
Jalur sudah dibangun, kontrak sudah diteken, dan keterlibatan China terlalu besar untuk diabaikan. Banyak konsekuensi yang tidak ringan.
Namun, di sisi lain, melanjutkan proyek ini tanpa restrukturisasi berarti menumpuk risiko baru, yakni beban bunga utang, subsidi operasional, dan tekanan reputasi internasional.
Jika pemerintah memutuskan menghentikan proyek ini, konsekuensinya bisa lebih parah: potensi gugatan dari investor, kerugian politik di dalam negeri, dan citra negatif di mata Beijing.
Inilah dilema yang diwariskan seorang Jokowi kepada penerusnya. Whoosh itu bukan hanya kereta cepat dalam makna fisik saja, tetapi juga kereta politik yang melaju membawa beban fiskal negara tanpa rem, dan kini semakin sulit berhenti.
Jonan dipanggil ke Istana mungkin bukan untuk mencari kambing hitam, tapi untuk mencari arah. Meski ia mengaku tidak menyiapkan materi khusus, panggilan itu sudah cukup simbolik.
Ia adalah sosok yang menolak proyek ini ketika semua pejabat lain memilih diam atau setuju. Kini, di tangan Prabowo, ia mungkin diminta untuk membantu memperbaiki atau setidaknya menginventarisasi kerusakan yang ditinggalkan.
Bahwa seorang presiden baru harus memanggil kembali teknokrat lama untuk membenahi proyek warisan rezim sebelumnya menunjukkan betapa dalam luka kebijakan yang telah ditinggalkan.
Dan lebih dari itu, menunjukkan bahwa proyek besar tanpa akuntabilitas akhirnya menjadi proyek yang membahayakan legitimasi politik.
Namun, di balik perdebatan moral dan ekonomi, ada satu wilayah yang sering luput dibahas, yakni konsekuensi hukumnya. Secara prinsip, kesalahan kebijakan publik, bahkan yang fatal sekalipun, tidak serta-merta bisa dipidana.
Dalam hukum administrasi dan tata negara di banyak negara, dikenal konsep policy immunity, bahwa pengambil kebijakan tidak dapat dihukum hanya karena keputusan yang diambilnya ternyata salah arah, sepanjang keputusan itu masih berada dalam koridor wewenang jabatan dan tidak mengandung niat jahat atau penyalahgunaan kekuasaan.
Di Jepang, misalnya, pascaskandal korupsi proyek Shinkansen pada 1970-an, pemerintah tidak menuntut para pengambil kebijakan yang menetapkan rute kereta cepat, meskipun proyeknya merugi besar, karena dianggap kesalahan prediksi ekonomi, bukan tindak pidana. Yang diproses hanya pejabat yang menerima suap dari kontraktor.
Di China, kasus Liu Zhijun, Menteri Perkeretaapian yang memimpin proyek kereta cepat, baru dianggap kriminal karena ada aliran dana tidak sah dan manipulasi kontrak.
Sementara di Spanyol dan Italia, banyak proyek high-speed rail yang gagal finansial, tapi tak satu pun menterinya dipenjara, sebab tidak ditemukan pelanggaran hukum, hanya kegagalan kebijakan.
Logika yang sama berlaku di Indonesia. Sekalipun Jokowi berulang kali menyatakan bahwa proyek Whoosh tidak akan memakai APBN, lalu pada akhirnya pemerintah menggunakan APBN untuk menutup utang, hal itu memang tidak otomatis termasuk tindak pidana.
Ia adalah bentuk policy reversal, perubahan posisi fiskal akibat realitas ekonomi. Kesalahannya terletak pada penolakan mendengar peringatan para teknokrat, seperti Ignasius Jonan, yang sejak awal menyatakan desain pembiayaan proyek ini secara struktural pasti akan berujung pada keterlibatan APBN.
Namun, kelalaian mendengarkan masukan teknis tidak sama dengan korupsi. Selama tidak ada bukti bahwa keputusan itu diambil untuk memperkaya diri, kelompok, atau pihak tertentu, maka ia tetap termasuk dalam wilayah policy failure, bukan policy crime.
Di sisi lain, hukum tetap membuka pintu jika ditemukan unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of authority) atau manipulasi kontrak.
Pasal 3 Undang-Undang Tipikor memberikan dasar untuk menjerat pejabat yang secara sadar menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain dan merugikan keuangan negara.
Jika dalam proyek Whoosh ditemukan indikasi bahwa proses penetapan konsorsium, pembengkakan biaya, atau penjaminan utang melibatkan penyimpangan prosedural, maka penegakan hukum menjadi sah dan perlu.
Namun, bila kesalahan itu murni karena kelalaian kebijakan, karena mengabaikan studi kelayakan, menolak peringatan teknokrat, atau terlalu percaya pada optimisme politik, maka ia tetap berada di wilayah tanggung jawab politik, bukan pidana.
Itulah sebabnya, tanggung jawab utama proyek Whoosh hari ini tidak lagi terletak pada lembaga hukum, melainkan pada keberanian moral dan politik.
Pemerintahan baru boleh mewarisi beban, tapi tidak boleh mewarisi sikap diam. Beban utama pemerintahan baru bukan sekadar menyeimbangkan neraca fiskal, tetapi menyeimbangkan narasi, bagaimana mengubah proyek yang dulunya simbol kebanggaan menjadi pelajaran publik tentang strategisnya kehati-hatian fiskal.
Prabowo tidak punya waktu untuk mengulang kesalahan yang sama. Ia harus memutuskan apakah akan melanjutkan proyek dengan renegosiasi, atau melakukan intervensi diplomatik langsung ke Beijing untuk menegosiasikan ulang skema utang.
Dalam opsi pertama, pemerintah harus berani menata ulang struktur kepemilikan, mempertimbangkan integrasi vertikal antara operasi dan infrastruktur, seperti model Jepang atau Perancis.
Dalam opsi kedua, pemerintah harus berani mengambil jalur diplomasi berisiko, meminta restrukturisasi pinjaman langsung ke China Development Bank, bahkan lewat pertemuan tingkat kepala negara.
Namun, semua langkah itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah mau mengakui satu hal sederhana, bahwa proyek ini memang gagal dari sisi perencanaan.
Kesalahan itu bukan pada pekerja lapangan, bukan pada operator, tapi pada keputusan politik di tingkat tertinggi saat itu yang memaksakan proyek tanpa dasar ekonomi yang kokoh.
Tanggung jawab moral akan tetap melekat. Sebuah rezim yang ingin disebut berpihak pada rakyat seharusnya tidak mewariskan dosa fiskal kepada generasi berikutnya.
Karena itu, langkah paling ksatria bagi mereka adalah membantu pemerintahan baru mencari solusi, bukan diam di balik retorika “legacy project.”
Jika perlu, para pelaku utama proyek di masa lalu itu sendiri yang datang ke Beijing untuk meminta penyesuaian skema utang, bukan menyerahkannya kepada pemerintah baru yang tidak ikut mengambil keputusan di masa lalu.
Krisis Whoosh ini bukan semata tentang transportasi, tetapi tentang cara kita memandang negara. Sebuah negara yang rasional tidak boleh menjadikan proyek infrastruktur sebagai panggung politik.
Sebuah negara yang bertanggung jawab tidak boleh bersembunyi di balik narasi tanpa APBN ketika pada akhirnya rakyat juga yang harus menanggungnya.
Dan sebuah kepemimpinan yang berani bukanlah yang membangun proyek besar, tapi yang berani mengakui kesalahan besar.
Kini, pilihan ada di tangan sosok Presiden Prabowo: apakah ia akan menjadi penerus beban, atau pembaharu yang berani menutup bab kebohongan fiskal ini.
Apalagi kini beredar kabar bahwa sebagian pembengkakan biaya proyek Whoosh bukan semata akibat fluktuasi harga material, tetapi juga indikasi mark-up dalam proses pengadaan dan kontrak konstruksi.
Jika kabar ini benar, maka wilayahnya bukan lagi policy error, melainkan criminal deviation.
Dalam konteks seperti ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menunggu momentum politik, apalagi arahan kekuasaan.
Lembaga antirasuah itu mesti memeriksa seluruh rantai kontrak proyek—dari skema konsorsium KCIC, penjaminan melalui BUMN, hingga pembiayaan dari China Development Bank—tanpa pandang bulu.
Sebab, hanya dengan memastikan bahwa tidak ada korupsi di balik proyek sebesar ini, publik dapat kembali percaya bahwa negara masih punya urat nadi moral.
Bila KPK berani menelusuri kelebihan biaya hingga rupiah terakhir, itu bukan semata soal keadilan hukum, tetapi soal memulihkan rasionalitas: bahwa pembangunan nasional tidak boleh menjadi ruang gelap bagi penyelewengan yang berlindung di balik jargon kemajuan dan modernitas.
Duhai pemerintah, penggunaan APBN bukanlah kesalahan—selama ia digunakan terang untuk rakyat, bukan diam-diam untuk penunggang kekuasaan atau oknum siapapun yang numpang hidup.
Anggaran negara memang bukan alat mencari laba, melainkan sarana menjaga akal sehat ekonomi dan keadilan sosial.
Yang membuat Whoosh menjadi dosa fiskal bukan karena uang negara turun, melainkan karena sejak awal kebenaran fiskal dinafikan demi citra politik.
APBN boleh habis, tapi harus habis untuk rakyat, bukan untuk menutupi kebohongan kekuasaan.
Karena sesungguhnya, yang harus diselamatkan bukan hanya proyek Whoosh, melainkan kewarasan publik, bahwa jabatan boleh berganti, tetapi tanggung jawab tidak bisa ditinggalkan di stasiun kekuasaan.