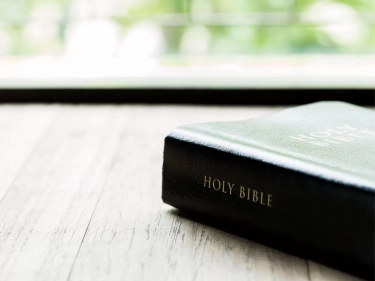Bahasa Kecurigaan Presiden
DALAM sejumlah pernyataan publik belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto kerap mengulang satu kalimat yang sama: “Saya curiga.” Frasa tersebut terdengar sederhana, bahkan manusiawi.
Seperti saat meresmikan kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026 lalu, presiden mengatakan bahwa ia mencurigai ada pihak yang sengaja membuat Indonesia bergantung pada barang-barang impor.
Di Januari ini, presiden juga melontarkan kecurigaannya bahwa sikap masyarakat yang mengejek dan pandangan pesimistis yang datang punya dorongan dari luar.
Presiden Prabowo menaruh curiga, kalau sifat yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa saja didanai oleh kekuatan asing.
Sebelumnya, pada Juli 2025 lalu, Prabowo juga pernah menyinggung atau menaruh kecurigaan mengenai penggunaan teknologi dan uang untuk membayar pakar guna menciptakan pesimisme dan menyebarkan tagar negatif (seperti #KaburAjaDulu) di media sosial.
Semua bentuk kecurigaan yang disampaikan seorang presiden bisa jadi adalah sesuatu yang mencerminkan atau merefleksikan kewaspadaan, kehati-hatian, dan intuisi politik dalam merespon realitas.
Namun, ketika diucapkan oleh seorang presiden, bahasa tidak lagi berdiri sebagai ekspresi personal. Ia telah berubah menjadi bahasa negara, membawa bobot institusional, simbolik, dan psikologis yang jauh lebih besar pada khalayak.
Dalam teori pemerintahan modern, bahasa pemimpin adalah bagian dari arsitektur kekuasaan. Presiden tidak hanya berbicara sebagai individu, melainkan sebagai representasi cara negara membaca situasi, mengelola ancaman, dan mengambil keputusan.
Karena itu kemudian, setiap kata presiden tentu bukan sekadar sikap, tetapi sinyal tentang apakah negara bekerja dengan sistem atau bergantung pada intuisi.
Rasa curiga merupakan mekanisme alamiah dalam kondisi ketidakpastian. Rakyat wajar curiga karena akses informasinya terbatas, atau media, misalnya, menaruh curiga karena bekerja di wilayah dugaan dan verifikasi terbuka.
Namun, presiden berada pada posisi yang berbeda sama sekali. Jabatan atau posisi yang menjadi titik temu atau muara dari seluruh informasi negara.
Dalam kerangka negara rasional sebagaimana dirumuskan Max Weber, kekuasaan modern bekerja melalui rasionalitas hukum dan birokrasi. Negara dijalankan bukan oleh firasat personal, melainkan oleh prosedur, verifikasi, dan otoritas yang terlembaga.
Presiden, dalam sistem ini, bukan aktor yang hidup dalam kekurangan data, melainkan figur yang justru dirancang untuk mengakhiri ketidakpastian lewat berbagai data atau informasi yang diterima.
Indonesia memiliki instrumen keamanan dan intelijen yang boleh dinilai sangat lengkap. Mulai dari Badan Intelijen Negara, intelijen TNI dan Polri, serta laporan berlapis dari kementerian dan lembaga.
Dalam teori security state, apparatus ini dibangun agar ancaman yang samar dapat diolah menjadi pengetahuan yang terang sehingga dapat ditindaklanjuti, bukan berhenti sebagai persepsi.
Di titik inilah diksi “curiga” menjadi problematis. Bukan karena keliru secara moral atau politis, tetapi karena itu menunjukkan seolah negara masih berada pada fase dugaan, bukan kepastian.
Publik wajar bertanya atau bahkan ‘menggugat’: jika presiden masih terus menyampaikan kecurigaan, di mana posisi institusi yang seharusnya memverifikasi dan memastikan satu fenomena tidak hanya berhenti pada curiga, tapi kesimpulan?
Bahasa “curiga” berada di wilayah antara. Diksi yang bukan tuduhan, tapi bukan pula satu kesimpulan. Karena tidak menyebut aktor, tidak menjelaskan skala masalah, dan tidak menguraikan langkah-langkah penyelesaian.
Dalam teori komunikasi politik, bahasa semacam ini menciptakan ruang kosong informasi. Dan dalam politik, ruang kosong hampir selalu diisi oleh spekulasi atau memunculkan kecurigaan di masyarakat.
Francis Fukuyama dalam sejumlah karyanya—terutama State-Building dan Political Order and Political Decay menekankan bahwa negara yang efektif bukan hanya negara yang kuat secara koersif, tetapi negara yang dapat diprediksi.
Menurutnya, kepastian arah, konsistensi kebijakan, dan kejelasan komunikasi merupakan fondasi bagi lahirnya kepercayaan publik.
Sehingga rakyat tidak selalu menuntut situasi ideal, tetapi mereka membutuhkan keyakinan bahwa negara memahami masalah dan mampu mengendalikan keadaan.
Ketika presiden berbicara dalam bahasa kecurigaan, publik tidak mendapatkan kepastian, melainkan rasa siaga tanpa peta. Negara seolah mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi berhenti sebelum menjelaskan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya.
Dalam jangka pendek, bahasa ini mungkin efektif sebagai peringatan. Namun, dalam jangka panjang, hal ini berisiko memproduksi kecemasan kolektif.
Dalam studi keamanan Copenhagen School (Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde) diperkenalkan konsep sekuritisasi, yakni bagaimana isu diubah menjadi ancaman melalui bahasa.
Ketika pemimpin negara menyampaikan kecurigaan, ia sedang melakukan proses sekuritisasi simbolik.
Masalahnya, sekuritisasi tanpa kejelasan kebijakan oleh negara, justru akan makin memperlebar jarak antara negara, dalam hal ini pemerintah dan warga.
Namun, membaca pernyataan presiden semata sebagai ekspresi ketidakpastian juga terlalu sederhana. Ada kemungkinan bahwa kata “curiga” juga digunakan sebagai strategi komunikasi.
Dalam literatur politik keamanan dikenal konsep strategic ambiguity, yakni ketidakjelasan yang disengaja untuk mengirim sinyal kepada aktor tertentu tanpa eskalasi terbuka.
Dalam tradisi militer dan intelijen, sinyal sering kali lebih penting daripada pernyataan eksplisit. Pesan tidak langsung dapat lebih efektif daripada tudingan yang dilakukan secara terbuka.
Dalam konteks ini, “saya curiga” bisa dibaca sebagai peringatan halus bahwa negara sedang mengamati, tanpa harus membuka konflik atau kepanikan publik.
Namun, simbol dan isyarat memiliki batas dalam negara demokratis modern. Simbolisme mungkin efektif dalam budaya feodal atau militeristik. Namun, dalam negara konstitusional, legitimasi bertumpu pada akuntabilitas dan kejelasan arah.
Negara tidak cukup hanya memberi sinyal, tetapi harus menunjukkan mekanisme kerja. Perlu pula adanya rasionalisasi yang memadai, terutama dari otoritas terkait.
Douglass North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990) menegaskan bahwa institusi adalah “rules of the game” yang diciptakan manusia untuk mengurangi ketidakpastian (uncertainty) dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Ketidakpastian inilah musuh utama kerja sama, investasi, dan kepercayaan.
Ia pun mengingatkan bahwa institusi dibangun untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi manusia. Tata kelola yang baik bukan hanya menghasilkan keputusan yang benar, tetapi juga menciptakan rasa aman melalui kejelasan prosedur dan komunikasi.
Jika bahasa negara justru memproduksi atau memperpanjang ketidakpastian, maka terdapat paradoks institusional yang tentu saja kontraproduktif dengan kepentingan negara.
Curiga boleh menjadi tahap awal. Bahkan kewaspadaan adalah keharusan dalam dunia yang penuh risiko dan ketidakpastian.
Namun, negara tidak boleh berhenti pada kecurigaan. Ia harus bergerak dari dugaan menuju verifikasi, dari sinyal menuju kebijakan, dari peringatan menuju tindakan yang terukur.
Presiden tentu tidak dituntut membuka seluruh data intelijen kepada publik. Negara keamanan memang bekerja dengan kerahasiaan. Namun, kerahasiaan berbeda dengan ketidakjelasan.
Publik tidak selalu membutuhkan detail, tetapi selalu membutuhkan rasa bahwa negara sesungguhnya sedang atau terus mengendalikan situasi.
Negara modern hidup dari keseimbangan antara kewaspadaan dan kepastian. Terlalu percaya diri berbahaya, tetapi terlalu sering menyatakan kecurigaan juga berisiko. Kondisi pertama dapat melahirkan kelengahan, yang kedua melahirkan kecemasan kolektif.
Jika bahasa negara terlalu lama berhenti di “curiga”, atau presiden kerap kali mengatakan ‘saya curiga’ maka yang tumbuh bukan kewaspadaan nasional, melainkan spekulasi nasional.
Dan spekulasi adalah musuh utama kepercayaan publik. Bukan karena rakyat tidak memahami ancaman, tetapi karena kepastian terlalu lama ditangguhkan.
Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan apakah presiden boleh curiga, melainkan kapan negara harus bisa bergerak melampaui kecurigaan.
Karena dalam politik, ancaman yang paling merusak sering kali bukan ancaman itu sendiri, melainkan ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut.
Negara yang terus berbicara dengan bahasa kecurigaan perlahan kehilangan modal terpentingnya. Yaitu keyakinan publik bahwa kekuasaan dijalankan dengan sistem, bukan sekadar firasat.
Sekalipun kewaspadaan adalah keharusan dalam kepemimpinan, tetapi kepastian adalah kebutuhan dalam kenegaraan.
Negara boleh berjaga, bahkan harus selalu siaga. Namun, ia tidak boleh terlalu lama berbicara dalam bahasa dugaan. Karena di tangan pemimpin kecurigaan seharusnya berakhir, bukan diwariskan kepada publik.
Ketika negara mampu mengubah rasa waspada menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipahami warga, di situlah kepercayaan tumbuh.
Sebab kekuasaan yang kuat bukanlah yang paling sering memberi peringatan, melainkan yang paling mampu menenangkan warganya dengan kepastian, bukan sebaliknya: keraguan dan kekhawatiran.
Tag: #bahasa #kecurigaan #presiden