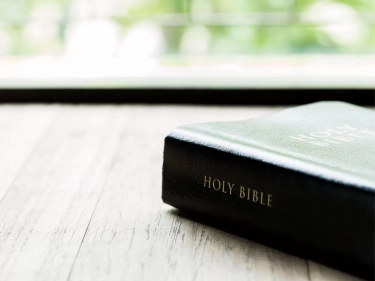Negara Membayar, Hukum Menegaskan
REL baja itu lurus. Hukum keuangan negara tidak selalu demikian. Di atas kertas, garisnya tegas: mana yang menjadi kewajiban publik, mana yang tanggung jawab privat.
Namun, di stasiun kebijakan, kereta argumentasi sering berpindah jalur.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC) yang dulu digadang sebagai simbol kemajuan kini menguji nalar dasar hukum fiskal: siapa yang berutang, siapa yang membayar, dan siapa yang bertanggung jawab.
Proyek ini dilahirkan dengan semangat “tanpa dana APBN”, tetapi dalam operasionalnya mulai menuntut keterlibatan negara untuk menanggung beban bunga dan risiko finansial.
Ketika negara harus menambal lubang korporasi, yang dipertaruhkan bukan sekadar uang, tetapi juga disiplin fiskal dan kepercayaan publik.
Hukum Keuangan Negara berakar pada asas-asas yang ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Asas ini mengikat semua entitas yang mengelola dana publik, baik melalui APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan.
Pemisahan ini penting. Ketika kekayaan negara disetorkan ke BUMN, statusnya berubah menjadi “kekayaan negara yang dipisahkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Artinya, risiko dan tanggung jawab berpindah ke ranah korporasi. Negara berperan sebagai pemegang saham, bukan penjamin utang.
Namun, prinsip hukum yang lurus itu sering kali berbelok ketika politik dan kebanggaan nasional ikut campur. Dalam konteks KCIC, garis pemisah antara uang publik dan risiko privat mulai kabur.
Secara hukum, PT KCIC adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas — hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia (60 persen) dan China Railway International Co. Ltd (40 persen).
Pinjaman besar dari China Development Bank (CDB) bukanlah utang negara, tetapi utang korporasi.
Konsekuensinya jelas: menurut Pasal 11 ayat (1) UU 19/2003, BUMN berbentuk Persero tunduk pada prinsip hukum perusahaan.
Negara tidak bertanggung jawab atas kewajiban hukum yang timbul dari tindakan korporasi, kecuali ada jaminan pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 12 ayat (1) UU 17/2003).
Dan hingga kini, tidak ada jaminan pemerintah (sovereign guarantee) untuk proyek KCIC. Dengan demikian, beban bunga dan risiko pembayaran utang KCIC bukan tanggungan negara, melainkan tanggung jawab korporasi dan pemegang sahamnya.
Namun dalam praktik, ketika BUMN strategis menghadapi tekanan gagal bayar, pemerintah sering terseret sebagai penanggung moral.
Padahal, dalam kerangka hukum, tidak ada dasar bagi negara untuk menanggung kesalahan manajemen korporasi.
Hukum keuangan negara mengenal konsep liabilitas kontinjensi (contingent liability): kewajiban potensial yang bisa menjadi tanggung jawab negara jika entitas milik negara gagal memenuhi kewajibannya.
Konsep ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2011, yang menyebut bahwa pinjaman luar negeri BUMN tidak menimbulkan kewajiban langsung bagi pemerintah pusat.
Namun, di sisi lain, pemerintah dapat memberikan jaminan terbatas jika dianggap perlu untuk mendukung proyek strategis nasional. Celah inilah yang sering menjadi pintu masuk “tanggung jawab moral” negara.
Dari sini muncul dilema klasik: menjaga kredibilitas proyek di mata internasional atau menegakkan disiplin fiskal di dalam negeri.
Ketika negara memilih opsi pertama, hukum kehilangan daya cegahnya. Negara yang seharusnya menjadi pengawas justru berubah menjadi penolong.
Prinsip “no bailout rule” lahir dari pelajaran krisis ekonomi 1998. Negara dilarang menanggung kewajiban pihak lain tanpa dasar hukum dan tanpa kepentingan publik yang sah.
Prinsip ini tersirat dalam Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003, yang mengatur bahwa pengelolaan utang dan pinjaman negara harus berdasarkan tujuan kebijakan fiskal dan persetujuan DPR.
Dalam praktiknya, “no bailout” berarti dua hal:
Pertama, Negara tidak boleh menanggung risiko korporasi tanpa persetujuan politik dan dasar hukum eksplisit.
Kedua, setiap bentuk dukungan fiskal kepada BUMN harus melalui mekanisme penugasan khusus (Pasal 66 UU 19/2003), bukan bantuan terselubung atau lembaga investasi negara yang tidak transparan.
Jika negara tetap menanggung beban utang korporasi di luar mekanisme ini, maka prinsip hukum keuangan negara berubah dari guardrail menjadi decoration — indah di teks, tapi rapuh di praktik.
Danantara
Keterlibatan lembaga seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang populer disebut Danantara menambah lapisan kompleksitas.
Secara formil, LPI memang mengelola kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN. Namun, dalam doktrin hukum keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara secara substantif, karena sumbernya berasal dari dana publik.
Hal ini ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 2 UU 17/2003, yang menyebutkan bahwa keuangan negara mencakup juga kekayaan negara yang dikelola oleh entitas lain, seperti BUMN dan badan hukum negara lainnya.
Artinya, jika Danantara menggunakan dana publik untuk menutupi bunga utang KCIC, maka secara formil boleh diklaim bukan APBN, tapi secara substantif tetap berstatus uang negara.
Maka, intervensi semacam itu—jika tanpa dasar hukum investasi yang sah—dapat dikategorikan sebagai bailout terselubung. Negara membayar, korporasi melenggang.
Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan bahwa BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.
Itu berarti, walaupun KCIC adalah badan privat, bila di dalamnya terdapat penyertaan modal negara, maka seluruh aktivitasnya dapat diaudit oleh BPK.
Audit bukan sekadar urusan angka, tetapi pengujian etika fiskal: apakah tindakan pemerintah mengandung dasar hukum, tujuan publik, dan manfaat ekonomis yang nyata?
BPK, DPR, dan publik berhak tahu apakah intervensi negara adalah investasi strategis atau justru penyelamatan politis.
Di sinilah hukum keuangan negara diuji oleh politik fiskal. Proyek seperti KCIC membawa muatan simbolik: kecepatan, kemajuan, dan kebanggaan nasional.
Namun, di balik kebanggaan itu, hukum fiskal sering dilupakan. Ketika biaya membengkak dan pendapatan tak menutup bunga, argumen “kepentingan nasional” menjadi dalih untuk membuka dompet negara.
Padahal Pasal 34 UU 17/2003 dengan jelas mewajibkan pemerintah meminta persetujuan DPR untuk setiap tambahan penyertaan modal negara atau jaminan fiskal baru.
Jika prinsip ini dikesampingkan, maka keputusan fiskal berubah menjadi keputusan politis yang berpotensi melanggar asas akuntabilitas publik.
Transparansi
Tidak ada kepercayaan tanpa keterbukaan. Empat hal harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan DPR.
Pertama, posisi utang KCIC secara riil (pokok, bunga, tenor, mata uang). Kedua, kemampuan bayar berbasis proyeksi pendapatan operasional.
Ketiga, skema restrukturisasi yang jelas—siapa menanggung apa. Keempat, dampak fiskal terhadap APBN dan BUMN induk.
Transparansi bukan sekadar laporan formal, tetapi bentuk tanggung jawab moral.
Negara harus jujur menjawab: apakah benar proyek ini tidak membebani APBN, ataukah sekadar mengganti jalur beban melalui lembaga yang tetap bersumber dari uang publik?
Etika keuangan publik mengajarkan satu hal: negara boleh membantu rakyat, tapi tidak seharusnya menolong korporasi yang salah hitung.
Dalam hukum, ini disebut moral hazard: ketika entitas privat mengambil risiko berlebihan karena yakin akan diselamatkan oleh negara.
Setiap kali pemerintah membayar bunga atau menalangi proyek tanpa dasar hukum yang jelas, pesan yang tersirat ke dunia usaha adalah sederhana: “Bila gagal, negara akan datang.” Pesan semacam itu berbahaya. Ia membunuh akuntabilitas dan mematikan disiplin fiskal.
Untuk mencegah pengulangan, ada tiga rambu yang harus ditegakkan:
Pertama, pemerintah wajib memasukkan seluruh risiko proyek BUMN strategis ke dalam Laporan Risiko Fiskal tahunan, sebagaimana praktik transparansi fiskal internasional.
Kedua, semua intervensi fiskal non-APBN terhadap BUMN harus memiliki dasar hukum eksplisit—baik dalam bentuk penugasan melalui PP maupun persetujuan DPR.
Ketiga, pembentukan dan penggunaan lembaga investasi negara harus berada dalam sistem pengawasan yang sama ketatnya dengan APBN, termasuk audit BPK dan keterbukaan publik.
Kereta cepat mungkin melaju di rel modernitas, tetapi hukum keuangan negara tetap harus menjadi remnya.
Jika negara mulai membayar utang yang bukan miliknya, maka yang melaju bukan lagi pembangunan, melainkan pelonggaran prinsip hukum publik.
Negara bisa bangga dengan infrastruktur megah, tetapi kebanggaan itu akan kehilangan makna jika dibangun dengan mengorbankan disiplin fiskal dan supremasi hukum.
Hukum keuangan negara menegaskan satu hal sederhana: yang berutang harus membayar.
Negara hadir untuk rakyat, bukan untuk menanggung kesalahan korporasi.
Dan ketika negara mulai membayar demi menjaga citra, maka yang benar-benar tertinggal bukanlah kereta cepat, melainkan kesadaran kita tentang keadilan fiskal.