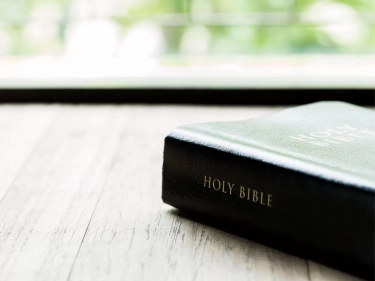Keluhan Anak Muda dan Sistem yang Tak Adil
BEBERAPA hari ini media sosial ramai, setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyoroti generasi muda Indonesia yang dianggap terlalu mudah menyerah dan gemar mengeluh di media sosial.
Ia menyayangkan sikap anak muda yang menurutnya kurang tangguh dibanding generasinya sendiri yang “berjuang keras mencari beasiswa dan kuliah di luar negeri”.
Ia menilai Gen Z mudah menyerah dan lebih memilih mengeluh di media sosial ketimbang bekerja keras saat menghadapi tantangan.
Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan motivasi di acara Sekolah Unggulan MH Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Kritik seperti ini sekilas terdengar membangun, seolah mendorong etos kerja dan semangat pantang menyerah.
Namun, di baliknya tersimpan pandangan yang bermasalah, bagaimana gagasan bahwa keberhasilan atau kemiskinan seseorang hanyalah urusan mentalitas pribadi.
Pandangan semacam ini menutupi kenyataan bahwa ketimpangan sosial bukan lahir dari kelemahan moral, tetapi dari struktur ekonomi dan kebijakan publik yang timpang.
Narasi “kemiskinan karena malas” sudah lama hidup dalam imajinasi pembangunan Indonesia. Ia menjadi alat yang ampuh untuk menenangkan nurani kelas menengah dan elite politik, karena dengan cara itu kemiskinan tampak sebagai kesalahan individu, bukan akibat sistem yang gagal.
Padahal di balik statistik ekonomi, ada jutaan orang yang bekerja keras setiap hari, tapi tetap tak beranjak dari kemiskinan.
Mereka bukan tidak berjuang, melainkan berjuang dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk menang.
Dalam banyak kasus, kerja keras justru menjadi prasyarat bertahan hidup di tengah struktur ekonomi yang menindas.
Maka kemiskinan seharusnya dilihat bukan sebagai aib pribadi, melainkan sebagai gejala dari tata kelola sumber daya dan kekuasaan yang tidak adil.
Kita bisa melihatnya dari kehidupan nelayan, petani, dan generasi muda pekerja, tiga kelompok yang menggambarkan bagaimana ketimpangan struktural bekerja dalam ruang yang berbeda, yakni laut, darat, dan kota.
Ketiganya menghadapi situasi yang membuat kerja keras saja tidak cukup untuk menjamin kehidupan yang layak.
Nelayan adalah contoh paling ironis dari paradoks pembangunan Indonesia. Negara kepulauan ini hidup dari laut, tetapi masyarakat pesisir justru menjadi kelompok paling miskin.
Mereka bangun sebelum fajar, melaut berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun, laut yang dulu memberi kehidupan kini kian sakit.
Sejak masa kolonial, sumber daya laut dieksploitasi tanpa pemulihan yang memadai. Kini hasil tangkapan menurun drastis karena overfishing, pencemaran industri, dan kebijakan yang lebih memihak kapal besar serta perusahaan eksportir daripada nelayan kecil.
Sementara biaya operasional meningkat—bahan bakar, es, peralatan, hingga logistik—harga jual ikan di tingkat nelayan justru stagnan.
Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan ekologis, di mana alam yang rusak memiskinkan masyarakat yang bergantung padanya, sementara kebijakan negara gagal menjadi pelindung.
Banyak nelayan terpaksa berlayar jauh ke perairan internasional, bekerja di kapal asing dalam kondisi yang nyaris seperti perbudakan modern.
Mereka tidak dilindungi hukum, tidak memiliki jaminan sosial, dan sering kali tidak dibayar dengan layak.
Ketika seorang pejabat menuduh anak muda kurang berjuang, barangkali ia lupa bahwa di laut ribuan kilometer dari rumah, ada orang Indonesia yang mempertaruhkan nyawanya bukan untuk kaya, melainkan sekadar untuk hidup.
Situasi serupa terjadi di daratan. Petani, yang selama berabad-abad menjadi tulang punggung pangan nasional, kini semakin terpinggirkan.
Sejak awal 2000-an, gelombang besar pengambilalihan tanah untuk perkebunan, tambang, dan proyek infrastruktur membuat jutaan petani kehilangan akses terhadap lahan.
Jika kita melihat laporan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan ribuan konflik agraria terjadi dalam dua dekade terakhir, mayoritas melibatkan perebutan tanah antara warga dan korporasi.
Banyak petani yang dulunya pemilik tanah kini berubah menjadi buruh di atas tanah yang dulu mereka garap sendiri.
Mereka menyebut diri “hantu di kampung sendiri”—masih tinggal di sana secara administratif, tetapi kehilangan kendali atas sumber kehidupannya.
Hilangnya tanah bukan sekadar kehilangan aset ekonomi, melainkan juga kehilangan kedaulatan.
Tanpa tanah, petani tak mampu menentukan nasibnya sendiri. Mereka menjadi buruh musiman dengan upah rendah, bergantung pada harga pasar yang dikendalikan tengkulak dan perusahaan besar.
Dalam sistem seperti ini, kerja keras tidak menjamin apa pun. Setiap kali panen, sebagian besar hasil tetap mengalir ke pemilik modal.
Maka ketika orang berkata bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya semangat berusaha, ia sesungguhnya menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak orang telah berusaha sekuat tenaga di atas tanah yang tidak lagi mereka miliki.
Sementara di kota, generasi muda menghadapi bentuk baru ketimpangan, ketidakpastian kerja dan masa depan yang suram.
Selama dua dekade terakhir, pendidikan tinggi sering dijanjikan sebagai tiket keluar dari kemiskinan. Namun, kini semakin banyak lulusan universitas yang mendapati bahwa ijazah tidak lagi menjamin apa pun.
Pekerjaan layak semakin langka, upah minimum sulit menutupi biaya hidup, sementara sistem kontrak dan outsourcing menjadikan tenaga kerja muda mudah diganti.
Mereka bekerja tanpa jaminan kesehatan, tanpa cuti, tanpa kepastian masa depan. Inilah yang disebut kelas prekariat—generasi yang hidup dalam ketidakpastian permanen.
Fenomena ini menemukan gaungnya dalam ruang digital. Awal 2025, tagar #KaburAjaDulu viral di berbagai platform media sosial.
Ungkapan itu menjadi semacam satire kolektif terhadap realitas ekonomi yang membuat banyak anak muda merasa tidak punya masa depan di Tanah Air.
Di balik nada bercandanya, tersimpan rasa frustrasi yang dalam, sulitnya mencari kerja layak, biaya hidup yang terus naik, dan ketiadaan jaminan sosial yang memadai.
Tagar ini bukan sekadar ajakan “kabur”, melainkan bentuk kritik sosial terhadap negara yang gagal menyediakan ruang hidup yang manusiawi bagi generasi penerusnya. Ia menunjukkan bahwa kelelahan bukan sekadar emosional, tetapi struktural.
Reaksi terhadap tagar itu justru memperjelas jurang persepsi antara elite dan rakyat. Sebagian pejabat menilai gerakan tersebut sebagai bukti “kurangnya nasionalisme”, sementara para pengamat melihatnya sebagai refleksi kegagalan sistemik.
Ketika lapangan kerja makin sempit dan ketimpangan makin lebar, pilihan “kabur” bukan karena malas, tetapi karena negara gagal memberi alasan yang cukup untuk bertahan.
Dalam konteks ini, #KaburAjaDulu dapat dibaca sebagai bentuk digital dari migrasi ekonomi, protes senyap terhadap tatanan sosial yang memaksa warga muda untuk mencari makna dan kelayakan hidup di luar negeri.
Gerakan ini menegaskan bahwa generasi muda bukan tidak mau berjuang, mereka hanya muak berjuang dalam sistem yang tidak adil.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan konsekuensi langsung dari arah kebijakan ekonomi yang menempatkan fleksibilitas pasar di atas kesejahteraan manusia.
Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, secara eksplisit memperluas ruang outsourcing dan menghapus banyak perlindungan tenaga kerja. Bagi perusahaan, ini berarti efisiensi. Namun bagi pekerja, ini berarti ketidakpastian.
Maka ketika anak muda menulis keluh kesah tentang lelah bekerja, sulit membeli rumah, atau cemas menghadapi masa depan, itu bukan tanda kemanjaan, melainkan gejala dari sistem yang gagal menjamin keadilan sosial.
Mereka bukan lemah, mereka lelah—dan keluh kesah mereka adalah bentuk kesadaran baru tentang struktur ketidakadilan yang menjerat.
Dari laut hingga kampus, pola yang sama terlihat, kerja keras rakyat tidak diimbangi dengan struktur ekonomi yang adil.
Ketimpangan di Indonesia bukanlah hasil dari pilihan individu, melainkan dari tata kelola sumber daya yang dikuasai segelintir pihak.
Narasi “kemiskinan akibat malas” menjadi berguna bagi mereka yang diuntungkan oleh sistem ini, karena ia mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan yang sebenarnya—distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata.
Dengan menggeser tanggung jawab dari struktur ke individu, elite ekonomi dan politik berhasil mempertahankan status quo tanpa harus melakukan perubahan mendasar.
Untuk mengatasi kemiskinan, kita harus berani membalik cara pandang. Solusi tidak terletak pada ceramah moral atau motivasi kerja keras, tetapi pada pembenahan struktur sosial yang selama ini menindas.
Nelayan membutuhkan tata kelola laut yang adil, bukan sekadar bantuan sosial. Petani membutuhkan reforma agraria sejati, bukan sekadar subsidi pupuk.
Anak muda membutuhkan jaminan kerja, perlindungan sosial universal, dan kebijakan ekonomi yang menempatkan manusia di atas pasar. Ketiganya membutuhkan negara yang berpihak pada rakyat, bukan pada logika akumulasi modal.
Kritik terhadap mentalitas generasi muda hanya masuk akal bila kita hidup dalam sistem yang adil. Namun ketika ketimpangan begitu nyata—nelayan kehilangan laut, petani kehilangan tanah, pekerja muda kehilangan kepastian—maka menuduh mereka lemah adalah bentuk ketidakadilan baru.
Kemiskinan bukan aib pribadi. Ia adalah cermin dari bagaimana negara memperlakukan warganya, siapa yang diberi ruang untuk berkembang, dan siapa yang dibiarkan terpinggirkan.
Jika Indonesia sungguh ingin keluar dari jerat kemiskinan, langkah pertama bukanlah menyuruh rakyat “bermental baja”, melainkan memastikan struktur sosial dan ekonomi kita benar-benar berpihak pada manusia.