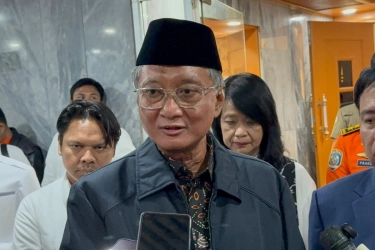RUU KUHAP dan Reformasi Penyidikan di Kepolisian
DPR dan pemerintah segera memulai pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Setelah lebih dari empat dekade, Indonesia berada di titik balik: apakah kita mau membuat RKUHAP sekadar “revisi teks” dari KUHAP yang telah berlaku sejak 1981, atau menjadikannya momentum untuk meletakkan fondasi kerja peradilan pidana yang sepenuhnya menjunjung tinggi integritas dan nilai hak asasi manusia (HAM)?
Saat ini, struktur hukum acara pidana memberi tempat yang terlalu dominan bagi polisi sebagai pihak yang memegang kendali penuh atas kerja penyidikan.
Dominasi itu bukan hanya soal teknis semata, tetapi soal pola kerja yang memberi ruang bagi pelanggaran HAM dari dalam sistem itu sendiri.
Berbagai laporan, misalnya, Komnas HAM maupun LSM pemerhati penegakan hukum terus memberi alarm bahwa pola kerja ini belum berubah dari tahun ke tahun.
Sebagaimana diungkapkan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berbagai kasus penyiksaan oleh polisi dalam proses penyidikan terus terjadi secara berulang.
Misalnya, kasus Sarpan di Polsek Percut Sei Tuan, Sumatera Utara, yang disiksa dan dianiaya pada Juni 2020, hanyalah salah satu contoh dari pola itu.
Berstatus sebagai saksi, bukan tersangka, Sarpan keluar dari kantor polisi dengan tubuh penuh lebam dan luka. Tidak pernah ia bayangkan bahwa datang memberi keterangan justru membuatnya menjadi korban dari sistem itu sendiri.
ICJR mengungkapkan bahwa kasus semacam itu bukan anomali. Ada pola yang berulang dari tahun ke tahun.
Seperti yang dialami RF, seorang terduga pelaku pencurian dari Ketapang, Kalimantan Barat. Pada 25 Januari 2024, RF diantar pulang oleh polisi ke rumah orangtuanya dalam keadaan tak bernyawa.
Sehari sebelumnya, RF dijemput dari rumah tanpa sepengetahuan orangtua maupun kerabat. Jenazah RF penuh dengan luka lebam dan tanda-tanda penganiayaan, termasuk luka mirip tembakan peluru di kening kanan atas dan lebam membiru di lengan kirinya.
Pamannya menduga RF dianiaya untuk memaksa pengakuan atas tindak pidana yang belum tentu dilakukannya. Pola tersebut terus berulang.
Pertengahan Juli 2023, seorang warga Banyumas berinisial OK juga dikembalikan ke rumah keluarganya dalam keadaan tak bernyawa, setelah sebelumnya dituduh melakukan tindak pidana pencurian.
Beruntung, dalam kasus ini, empat anggota Polri yang terbukti melakukan penganiayaan dijatuhi vonis 7–8 tahun penjara oleh majelis hakim.
Vonis itu bahkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa, dengan pertimbangan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP. Namun, vonis itu hanya satu dari sedikit contoh bagaimana sistem dapat memberi efek jera bagi pelaku.
Data dari berbagai pihak memberi gambaran yang belum juga berubah dari waktu ke waktu. Selama tahun 2023, Komnas HAM mencatat Polri sebagai pihak yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran HAM, bahkan lebih tinggi dibandingkan korporasi maupun pemerintah daerah.
Pengaduan ini tidak hanya soal tindak kekerasan, tetapi juga terkait rendahnya profesionalisme kerja penyidikan oleh korps Bhayangkara.
Sementara itu, data dari KontraS (Juni 2022–Mei 2023) juga memberi alarm: dari 54 kasus penyiksaan yang teridentifikasi, 34 kasus di antaranya dilakukan oleh anggota Polri. Namun dari jumlah itu, 19 kasus tidak pernah mendapat tindak lanjut atau pertanggungjawaban dari pelakunya.
Amnesty International juga mencatat pola yang sama. Selama tiga tahun terakhir, dari Juli 2019 hingga Juni 2024, terdapat sedikitnya 226 korban penyiksaan di Indonesia.
Angka ini terus naik dari tahun ke tahun: dari 15 kasus dengan 25 korban (2021–2022), menjadi 16 kasus dengan 26 korban (2022–2023), dan melonjak hingga 30 kasus dengan 49 korban (2023–2024).
Sekitar 75 persen pelaku dari tindak penyiksaan ini adalah personel Polri, 19 persen TNI, 5 persen gabungan Polri-TNI, dan 1 persen pihak lembaga pemasyarakatan.
Angka ini bukan hanya statistik biasa, tetapi alarm bahaya bagi masa depan sistem penegakan hukum Indonesia.
Terbaru dan paling memprihatinkan adalah peristiwa pada 9 Juni 2024 di Kota Padang, Sumatera Barat. Publik dikejutkan dengan dugaan penganiayaan oleh polisi terhadap beberapa anak dengan dalih penertiban dari aksi tawuran.
Salah satu dari mereka, remaja berinisial AM yang baru berusia 13 tahun, meninggal dunia.
Kasus ini kembali memberi pesan bahwa pola kerja penyidikan yang belum diawasi dengan mekanisme kuat dapat membawa risiko pelanggaran HAM yang tak dapat diterima oleh negara demokrasi mana pun.
Contoh-contoh ini bukan soal pelanggaran dari individu semata, tetapi soal struktur kerja yang belum memberi ruang kontrol dan pengawasan memadai bagi kerja penyidikan.
RKUHAP yang tengah berada di meja legislatif harus menjawab kebutuhan itu. Reformasi ini tidak bisa hanya soal memperbarui nomor pasal atau memberi judul bab yang lebih relevan, tetapi juga soal memberi landasan kerja bagi sistem peradilan pidana untuk tumbuh sebagai mekanisme yang transparan, dapat diaudit, dan menghormati nilai-nilai HAM sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Salah satu titik krusial dari RKUHAP adalah kebutuhan untuk memberi warna baru bagi pola kerja penegakan hukum, khususnya di tingkat penyidikan.
RKUHAP harus memberi ruang bagi mekanisme kontrol dan pengawasan yang dapat dijalankan dari berbagai pihak.
Kontrol ini bisa datang dari berbagai institusi, entah dari badan independen yang dibentuk khusus, dari internal Polri dengan mekanisme yang dapat diaudit, atau dari pihak-pihak lain yang dapat memberi jaminan bahwa kerja penyidikan tidak berdiri sendiri sebagai domain absolut yang sulit dijamah.
Yang terpenting, kontrol itu memang harus eksis, dapat dijalankan dengan transparansi penuh, dan memberi ruang bagi pengawasan dari luar agar setiap langkah kerja pemeriksaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Reformasi ini juga harus menyentuh mekanisme praperadilan. Selama ini, praperadilan lebih digunakan untuk memeriksa aspek formal dari suatu penahanan atau status tersangka.
Padahal, kebutuhan untuk menjamin nilai-nilai substantif dari proses pemeriksaan tidak dapat diabaikan.
Mekanisme ini harus dapat digunakan untuk memeriksa integritas bukti, termasuk memeriksa dugaan tindak penyiksaan, pemaksaan pengakuan, atau pelanggaran HAM lainnya.
Dengan begitu, praperadilan tidak hanya soal siapa yang ditahan, tetapi juga soal bagaimana penahanan itu dijalankan.
Selain itu, teknologi juga perlu dijadikan instrumen untuk membuat kerja pemeriksaan dapat diawasi dan diaudit.
Model pemeriksaan dengan perekaman elektronik dan kehadiran penasihat hukum dapat memangkas risiko tindak kekerasan, intimidasi, atau manipulasi pemeriksaan.
Bukti yang dihasilkan dari pemeriksaan juga harus diuji dengan standar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin bahwa tidak ada pihak yang dikorbankan oleh bukti-bukti yang direkayasa atau diperoleh dari proses yang melanggar HAM.
Pada akhirnya, RUU KUHAP bukan soal siapa yang memegang kendali penuh atas kerja penyidikan, tetapi soal bagaimana kerja itu dapat dijalankan dengan mekanisme kontrol yang kuat, dapat diawasi dari berbagai sisi.
Selain itu, memberi jaminan bahwa nilai-nilai negara hukum tidak hanya berada di atas kertas, tetapi juga terlihat nyata dalam kerja sehari-hari aparat penegak hukum.
Sekarang atau tidak sama sekali, RUU KUHAP harus memberi jawaban itu bagi Indonesia. Kesempatan ini belum tentu datang dua kali.
Jika digunakan dengan kesungguhan dan keberanian, RUU KUHAP dapat membawa Indonesia keluar dari pola kerja yang penuh pelanggaran dan memberi harapan bagi tumbuhnya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan manusiawi.