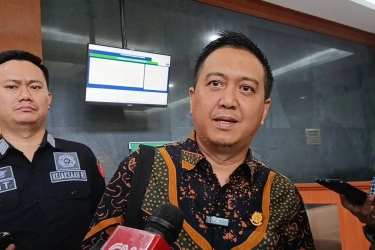Bersaudara dengan Papua secara Utuh dan Komprehensif
PADA 2023 lalu, Lachlan McNamee akhirnya membukukan disertasinya di Standford University yang kemudian diterbitkan oleh Princeton University Press, berjudul “Settling for less. Why States colonize and why they stop”.
McNamee berangkat dengan teori “settler colonialism”, yang kerap disematkan kepada negara-negara seperti Inggris dan negara Eropa lainnya akibat ulah mereka di tanah Amerika, Kanada, Australia, atau New Zealand.
Inggris dan negara-negara Eropa lainnya tersebut tidak saja menjajah (mengeksploitasi) daerah jajahannya, tapi juga memigrasikan sebagian penduduknya di daerah-daerah koloni tersebut.
Walhasil, terjadi perubahan komposisi penduduk antara pendatang dan penduduk asli. Nahasnya, yang akhirnya memproklamirkan kemerdekaan dari Inggris atau negara Eropa lainnya adalah penduduk pendatang.
Sementara penduduk asli cenderung terpinggirkan, baik karena jumlahnya berkurang drastis karena supresi dan bahkan genosida yang dilakukan penjajah maupun karena membesarnya jumlah penduduk pendatang, yang secara nominal jauh lebih representatif ketimbang penduduk asli.
Dalam kajiannya yang menjadi disertasi itu, terutama kajian demografis, McNamee menyimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya mempraktikkan konsep “settler colonialism” di Papua.
Berdasarkan data demografi di Papua Barat, terutama dari tahun 1970-an sampai pada 1999 (di mana program transmigrasi dinyatakan berhenti secara resmi), terjadi pertambahan drastis jumlah penduduk transmigran di Papua hampir 300.000 orang.
Sementara itu, akibat pemberontakan yang kata beberapa pengamat politik nyaris berhasil oleh OPM di awal tahun 1980-an, pemerintah pusat menyupresi penduduk asli Papua Barat secara tanpa pandang bulu, karena kesulitan untuk membedakan mana pemberontak dan mana bukan pemberontak. Secara fisik semuanya sama.
Selain operasi militer, kebijakan transmigrasi dianggap sebagai salah satu bentuk supresi demografis untuk menekan pemberontakan OPM, hampir mirip dengan apa yang dilakukan Beijing di Xinjiang sebelum reformasi ekonomi 1978 sebagai akibat dari seteru geopolitik antara China dan Uni Soviet, lalu berlanjut setelah kemunculan gerakan separatis teroris di sana pada 1990-an awal.
Awalnya, Beijing memobilisasi migrasi suku Han (suku mayoritas China sampai hari ini) ke daerah-daerah perbatasan dengan Soviet yang banyak terdapat penduduk keturunan Rusia.
Secara drastis dari tahun 1960-an hingga awal 1980-an, terjadi pergeseran komposisi penduduk di daerah-daerah perbatasan China dan Rusia. Jumlah penduduk China dari suku Han mendadak membesar menggantikan penduduk China keturunan Rusia yang mengalami hal sebaliknya.
Lalu awal 1990-an, setelah muncul gerakan teroris pertama di Xinjiang akibat pengaruh dari gerakan Mujahidin di Afghanistan (Mujahidin di Afghanistan adalah pejuang gerilya Islam yang menentang pendudukan Soviet dan Taliban), Beijing mulai menjalankan kebijakan serupa untuk menekan suku Uighur.
Sehingga sampai tahun 2000-an, komposisi penduduk di Xinjiang juga akhirnya berubah secara drastis. Penduduk Xinjiang dari suku Han meningkat sampai hampir 40 persen. Lalu mulai “stuck”, bahkan cenderung menurun.
Setelah itu, terutama setelah kawasan China bagian pantai (coastal) mulai mengalami industrialisasi masif yang menarik sangat banyak migran dari kawasan China Utara dan Selatan.
Bahkan sejak proyek Belt and Road Initiative diluncurkan, migrasi ke Xinjiang terbilang menurun.
Sekalipun pemerintah China bersedia menanggung kerugian atas proyek-proyek masif di Xinjiang untuk menarik minat migrasi suku Han, justru yang terjadi adalah pembesaran jumlah suku Han yang hanya memilih menjadi pekerja musiman di Xinjiang alias menolak untuk menetap.
Mereka mengetahui bahwa proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah China di Xinjiang sebenarnya tidak memiliki masa depan komersial. Proyek bisa berjalan hanya karena dukungan subsidi dari pemerintah pusat.
Menurut McNamee, settler colonialism di Xinjiang akhirnya terbilang gagal, sama dengan upaya Australia di Papua dan New Guinea (yang akhirnya berubah menjadi Papua New Guinea/PNG), meskipun kebijakan-kebijakan supresif dan diskriminatif masih terjadi di Xinjiang sampai hari ini.
New Guinea diserahkan kepada Australia setelah Jerman kalah dalam perang dunia pertama, layaknya sebagian jajahan Jerman di China yang diserahkan kepada Jepang kala itu.
Sebagian Papua yang masuk ke dalam PNG hari ini pada awalnya adalah koloni Australia, lalu ditambah dengan New Guinea (menjadi PNG hari ini).
Pada akhirnya Australia gagal mewujudkan ambisinya untuk merelokasi sebagian penduduknya ke Papua karena alasan topografi dan biaya transportasi yang memang mahal.
Awalnya, Australia melihat PNG sebagai daerah strategis secara geopolitik dan pertahanan, karena di kawasan tersebut Jepang tertahan untuk meneruskan ekspansinya di era perang dunia kedua.
Terbukti akhirnya Australia memang gagal dijajah oleh Jepang. Karena itulah mengapa Australia sangat ingin menjadikan PNG sebagai salah satu negara bagian Australia.
Namun setelah melakukan berbagai upaya, termasuk pemberian konsesi untuk jangka waktu 99 tahun kepada sektor bisnis, semuanya terbilang gagal memobilisasi penduduk Australia untuk pindah ke PNG.
Sehingga opsi terakhir yang tersisa adalah membiarkan PNG menjadi negara independen di tahun 1970-an.
Nah, setelah itu justru menyuluk atau tepatnya memotivasi sebagian pihak di Papua Barat untuk mengikuti langkah PNG, dengan menguatkan gerakan prokemerdekaan, yang ternyata berujung ‘tragis’ untuk penduduk asli Papua sendiri, terutama Papua Barat.
Indonesia terjebak ke dalam aksi “settler colonialism” di Papua Barat, kata McNamee, karena beberapa hal.
Pertama, tentu karena ingin menyupresi Papua Barat secara demografis untuk menekan pemberontakan.
Kedua, karena upaya konsolidasi teritorial. Ketiga, karena keinginan untuk mengekstraksi sumber daya alam Papua Barat yang sangat banyak.
Lucunya, kata McNamee, saat memulai bukunya, bahwa semua itu bermula dari pidato Sukarno yang sangat anti-imperialis di KTT Asia Afrika.
Sukarno berkoar-koar tentang betapa jahatnya imperialisme dan kolonialisme baru (new colonialism) dari dunia Barat di dalam pidatonya.
Namun, pidato tersebut memiliki tujuan lain, yakni untuk memperjuangkan Papua Barat agar segera masuk ke NKRI yang didukung oleh negara-negara dari dunia ketiga.
Pada saat bersamaan, Belanda sedang mempersiapkan Papua Barat untuk merdeka. Bagi Belanda kala itu, selain telah kehilangan dukungan geopolitis dari negara-negara besar, juga merasa bahwa mempertahankan Papua Barat sebagai jajahan tidak lagi affordable secara fiskal.
Dan buah dari pidato tersebut hari ini, tulis McNamee, yang terjadi kemudian adalah Indonesia berubah dari negara yang menolak keras kolonialisme menjadi negara yang justru mempraktikkan kolonialisme itu sendiri di Papua Barat.
Saya agak kaget juga saat pertama kali melihat judul bab yang dipakai oleh McNamee untuk menjelaskan pengalaman Indonesia di Papua Barat.
Judul babnya cukup provokatif, berbunyi “Hit the Road, Jakarta: Indonesia’s Colonisation of West Papua”.
Sementara itu, saya dipertemukan dengan buku ini oleh buku sebelumnya yang saya baca, yakni buku Michael Albertus, “Land Power”, yang baru saja terbit di Januari 2025 lalu.
Dalam bukunya, Michael Albertus memasukkan Indonesia, China, dan Israel ke dalam kategori setller colonialism yang masih berjalan hingga hari ini.
Ketika saya periksa referensinya, ternyata adalah buku dari Lachlan McNamee itu. Saat itulah saya akhirnya mencari buku Settling for Less dan syukurnya saya mendapatkannya.
Saya katakan agak kaget karena sebenarnya jauh hari sebelum membaca kedua buku ini, saya juga sudah mendapatkan beberapa referensi dan pandangan-pandangan lain dari pihak luar tentang apa yang dilakukan Indonesia di Papua Barat menurut pandangan internasional.
Namun kedua buku ini justru menguatkan pandangan tersebut, yang secara pribadi sebenarnya membuat saya bertambah sedih.
Pasalnya, pertama, meskipun kebijakan transmigrasi telah berhenti secara resmi, tapi pertumbuhan dan perkembangan demografis di Papua Barat, diakui atau tidak, tentu sangat dipengaruhi oleh perubahan komposisi penduduk selama masa transmigrasi terjadi, yang secara matematis merugikan penduduk asli Papua.
Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sampai hari ini tak menunjukkan perubahan signifikan untuk memperbaiki benih-benih persoalan yang kini telah tumbuh besar di Papua Barat.
Sebagaimana beberapa kali telah saya sampaikan di dalam opini-opini saya sebelumnya, bahwa penduduk asli Papua justru semakin tertinggal oleh penduduk pendatang di dalam segala hal.
Hal itu membuat seolah-olah memang pemerintah belum berbuat apa-apa di sana untuk rakyat Papua sendiri. Meskipun secara matematis dan fiskal berkali-kali diumumkan bahwa telah terjadi pergeseran fiskal ke Indonesia Timur, terutama Papua, dalam jumlah yang sangat signifikan.
Dalam hemat saya, hari ini, sebelum terjadi pergeseran geopolitik dunia di satu sisi, yang secara historis telah membuat Belanda hengkang dari Papua di satu sisi dan telah mempermudah jalan Indonesia menjadi merdeka di sisi lain (lihat tulisan saya sebelumnya tentang bagaimana peran diplomasi dan geopolitik dunia menguntungkan Indonesia di akhir tahun 1040-an), pemerintah harus berani untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki pendekatannya hari ini di Papua.
Pendekatan keamanan (security approach) harus diimbangi dengan pendekatan pembangunan berbasiskan kepada kemajuan rakyat Papua sebagai prioritas.
Dalam sepuluh tahun ke depan, SDM rakyat Papua, misalnya, harus mampu mengimbangi SDM non-Papua yang ada di dalam pemerintahan dan dunia usaha di Papua.
Sehingga Papua pada akhirnya benar-benar merasa beruntung menjadi bagian dari Indonesia, bukan malah merasa buntung dan menjadi korban “ambisi eksploitatif” para elite di Jakarta.
Program makan siang gratis kebanggaan Presiden Prabowo Subianto, misalnya, harus mulai di Papua secara masif dan berkelanjutan. Kalau bisa di semua sekolah di Bumi Cenderawasih.
Sekolah-sekolah unggulan dan beberapa universitas harus mulai dibangun dan dikembangkan di sana. Investasi-investasi yang memakan lahan luas harus dialihkan dari model HGU kepada model kemitraan, dengan program-program pemberian keterampilan baru yang diutamakan untuk rakyat Papua, agar segera terjadi pergeseran penguasaan lahan produktif di satu sisi dan pemerataan kue ekonomi di Papua di sisi lain.
Komunikasi intensif harus mulai digalakkan dengan rakyat Papua di semua lapisan atas nama pemerintah Indonesia.
Bahkan tak menutup kemungkinan, dialog dan komunikasi menuju rekonsiliasi harus mulai dicarikan celahnya dengan pihak yang selama ini dianggap pemberontak dan teroris.
Celah untuk pihak-pihak asing memanfaatkan situasi di Papua harus ditutup dengan cara yang elegan, bukan dengan cara supresi militer secara membabi buta.
Tujuannya sangat jelas, yakni untuk mengintegrasikan Papua ke dalam NKRI secara menyeluruh dan komprehensif, menjadikan Papua benar-benar sebagai saudara kandung, tidak hanya secara administratif dan teritorial, tapi juga secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sekaligus geopolitik.
Pendeknya, semestinya bukan hanya Indonesia yang merasa beruntung memiliki Papua, Orang Papua pun semestinya juga berhak merasakan hal sama. Semoga bisa demikian.