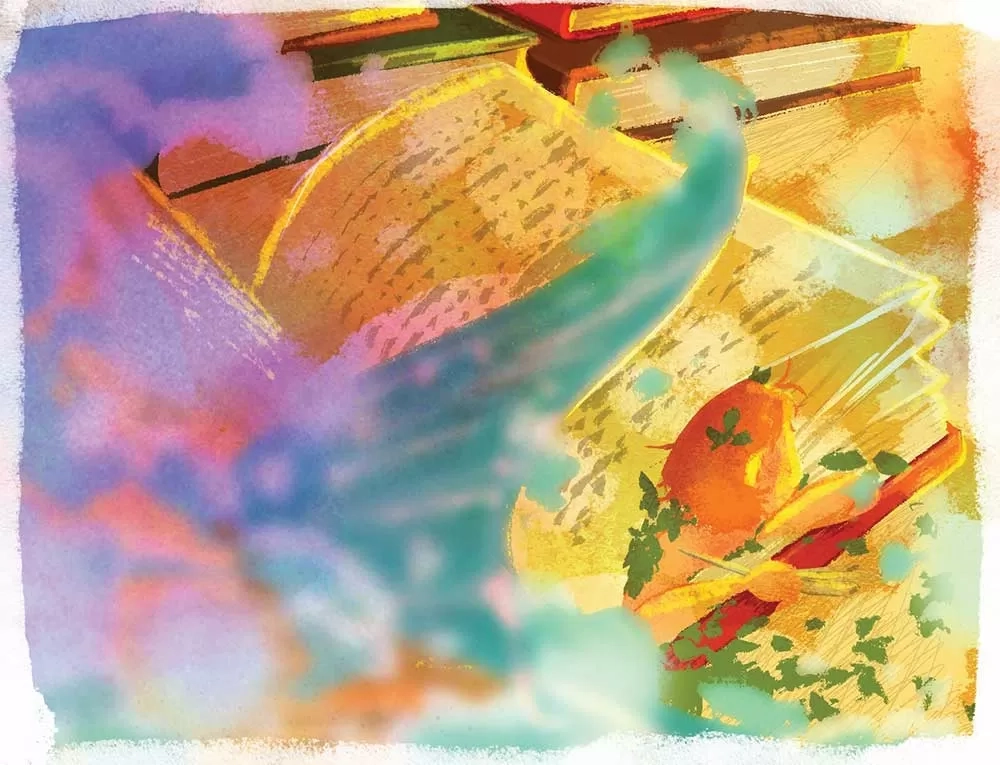
Anak, Membaca Sastra, dan Berlatih Sepi
Oleh: BRAMANTIO
Tulisan ini dengan berat hati saya akui adalah sebuah klise atas Hari Anak Nasional beberapa saat lalu. Bagaimanapun, ada yang berbeda pada tahun ini dengan hadirnya peristiwa monumental Sastra Masuk Kurikulum. Terlepas dari silang sengkarut di balik peristiwa tersebut yang hingga hari ini masih menjadi bahan jagongan di sana-sini meskipun sekadar sambil lalu, hal ini mau tidak mau membuat saya mengingat kembali pengalaman tidak kurang dari tiga dasawarsa lalu.
Membaca Sastra
Akhir 1980-an tentulah seruang waktu yang seolah berada di sisi lain dari sekeping koin yang kita pijak hari ini. Hari-hari yang terkesan melaju lebih lambat tidak kemudian menjadikan siapa pun yang berada di dalamnya berfokus melakukan seni tidak melakukan apa apa (the art of doing nothing), melainkan menyerap sebanyak-banyak yang bisa dilakukan dalam diam, sendiri, dan sepi. Pada masa inilah saya berkenalan dengan bacaan sastra –selain buku Kumpulan Dongeng Sedunia dan Burung Emas dan Cerita-Cerita Lainnya– yang pada waktu itu tentu saja belum saya kenali sebagai sastra, melalui Intisari yang dibeli oleh bapak saya sebulan sekali, saya mulai membaca cerita-cerita kriminal yang beberapa di antaranya disertai label berdasarkan peristiwa nyata tanpa satu kali pun saya buktikan kebenarannya. Lagi-lagi pengalaman berharga ini tentulah bukan hal yang dapat saya namai pada waktu itu dan sekadar menjadi laku otomatis bulanan.
Belasan tahun terakhir seiring semakin gegasnya laju hari-hari, dalam katakanlah evaluasi suka-suka ihwal yang terjadi pada masa kanak-kanak, yang terjadi pada diri bocah saya adalah sebuah peristiwa menyerap informasi tanpa disertai syak wasangka. Tidak ada pula kekhawatiran yang begini-begitu dari orang tua saya ketika melihat saya terpapar bacaan dewasa semacam itu alih-alih buku anak dengan narasi dan ilustrasi inosens. Bahkan, segala yang bisa jadi terasa vulgar dalam sejumlah cerita kriminal tersebut tidak lantas membuat saya bocah merasakan sensasi yang membuat jengah, memekakkan, atau memuakkan, dan itu semua karena bahasa. Dalam realismenya yang ketat, cerita-cerita tersebut hadir dengan bahasa yang dapat dikatakan asing –bukan keseharian meskipun tidak lantas berbunga-bunga– sehingga dengan sendirinya menjadi filter yang menjauhkan saya dari pukulan godamiah peristiwa tragis dan kelam yang disampaikannya.
Dari yang demikian, meskipun tentu saya tidak berhak membanding-bandingkan masa itu dengan segala yang kekinian karena setiap zaman memiliki jiwanya masing-masing, melihat banyak bocah hari ini yang keluangannya terisi oleh hiruk pikuk audiovisual gawai tentu bukanlah pemandangan yang elok bagi saya. Bahkan, entah disadari atau tidak, suasana hati sebagian dari mereka sedikit banyak ternyata juga ditentukan oleh gawai. Bocah-bocah ini tampak semakin jarang merasakan momen membosankan atau bahkan mandek semandek-mandeknya karena senantiasa ada gawai dalam genggaman. Realitas inilah yang mungkin turut berkontribusi menghadirkan keengganan mereka menaut tangan dengan buku-buku yang cenderung menuntut mandek secara ragawi dan berserah kepada sepi.
Di sisi lain, akses ke bacaan dalam satu dasawarsa terakhir semakin baik karena meskipun tetap memiliki keterbatasannya masing-masing, sejumlah taman bacaan masyarakat hadir di sejumlah titik, juga perpustakaan keliling yang digagas baik oleh lembaga pemerintah maupun komunitas literasi. Belum lagi situs-situs daring yang memberikan akses seluas-luasnya pada bacaan-bacaan pendek seperti cerpen dan puisi, baik yang mereka kompilasi dari media massa maupun yang mereka kurasi sendiri secara berkala. Artinya, meskipun harga buku-buku fisik terbilang masih mahal, minim bahan bacaan tentu tidak lagi sepenuhnya dapat dijadikan alasan untuk jarang atau bahkan tidak membaca sastra.
Berlatih Sepi
Telah banyak yang menulis ihwal manfaat membaca sastra, mulai yang berkaitan dengan nilai (value), perluasan cakrawala pengetahuan, hingga mengalami kehidupan melalui ”mata yang lain”. Karena itu pula tulisan ini tidak hendak saya arahkan ke sana, melainkan ke jalur lain yang bukan berarti menjadi kurang bermakna: membaca (sastra) adalah berlatih sepi. Yang demikian lagi-lagi tidak terlepas dari saya bocah yang mengalami berada di ruang tunggu dokter umum dan dokter gigi yang di meja utamanya selalu ada koran atau majalah, meskipun tidak jarang sebagian terbit berbulan-bulan sebelumnya. Dalam beberapa belas hingga puluh menit di sepetak ruang publik itu, siapa pun yang membaca dapat dikatakan menjadikan dirinya berada dalam sepi. Ada peristiwa menjedakan diri dari semesta sosial dan hiruk pikuk, lalu bertamasya ke semesta bacaan yang dihamparkan oleh koran dan majalah lawas itu. Peristiwa yang demikian tentu semakin pekat ketika yang dibaca adalah sastra karena membaca sebait puisi adalah laku meniti kata demi kata yang sering kali tidak taat asas, bahkan mendadak bermain sirkus. Begitu pula membaca fiksi, baik cerpen maupun novel, yang serealis apa pun tetap tidak hadir apa adanya, dan menurut Wolfgang Iser (1980) menyediakan ”ruang-ruang kosong” untuk ”diisi, dimaknai” oleh pembacanya. Bahkan, fiksi fantasi pun sejatinya adalah pohon besar yang menetas dan tumbuh dari sebiji realitas yang sedang berkaca pada cermin.
Dalam satu halaman yang mungkin mengabadi, sastra mengingatkan kita untuk ”mengunyah lamat-lamat”: menandai bagian-bagian paling mengesankan atau paling problematis, kembali ke halaman sebelumnya sekiranya ada yang kurang terpahami, membuka kamus ketika terganjal oleh kata-kata arkais atau dari tradisi kebahasaan lain, dan menahan diri agar tidak membuka halaman terakhir demi mengetahui nasib tokoh pujaan meskipun tetap memiliki kuasa sepenuhnya untuk melakukannya. Membaca sastra adalah dialektika internal terus-menerus selama prosesnya sekaligus berlatih tahan berlama-lama dengan diri sendiri. Hal yang demikian menjadi terasa semakin krusial bagi generasi hari ini yang hidup dalam masyarakat komunal –nyata dan maya– dengan hasrat dan kebebasan lantang bertutur luar biasa semacam hampir latah, agar tidak mudah larut, menyaru, lalu menjelma ini-itu tanpa terlebih dulu bercakap-cakap panjang dengan dirinya sendiri. (*)
Bramantio, Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga







