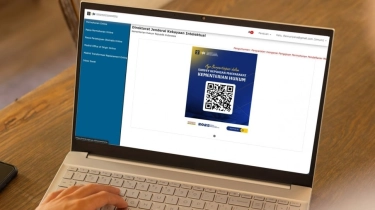Potret ''Bekerja tapi Tetap Miskin'' di Indonesia
SETIAP pagi, jutaan orang Indonesia berangkat bekerja dengan harapan yang sama, yaitu hari ini harus lebih baik dari kemarin.
Mereka mengendarai motor di tengah macet, memanggul barang di pasar, berdiri berjam-jam di pabrik, atau mengejar order di aplikasi.
Mereka sejatinya bukanlah pengangguran karena mereka bekerja. Namun, seringkali penghasilan habis untuk makan seadanya, sewa kontrakan, dan ongkos transportasi, serta tabungan nihil.
Sakit sedikit saja bisa mengguncang ekonomi keluarga. Inilah potret getir pembangunan kita hari ini yaitu bekerja, tapi tetap miskin (working poor).
Fenomena working poor kian menguat di Indonesia. Ia hidup di balik euforia pertumbuhan ekonomi dan jargon “pemulihan”.
Angka-angka makro memang terlihat sehat. Namun, di level rumah tangga pekerja, ekonomi terasa kering. Pertumbuhan ada, kesejahteraan tertahan.
Di sini, ada jurang antara apa yang dirayakan di podium dan apa yang dirasakan di lapangan. Dan jurang itulah yang seharusnya menjadi bahan koreksi serius bagi arah pembangunan kita.
Dalam persepsi lama tentang mobilitas sosial, kerja keras adalah tangga naik kelas. Orang bekerja, menabung, menyekolahkan anak, lalu pelan-pelan keluar dari kemiskinan.
Namun, bagi banyak pekerja hari ini, tangga itu seolah dicabut anak-anaknya. Mereka bekerja penuh waktu, bahkan lembur, tetapi tetap hidup pas-pasan.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, tapi Kesenjangan Melebar
Setiap kenaikan harga adalah ancaman. Setiap pengeluaran tak terduga adalah krisis kecil. Kerja berubah menjadi rutinitas bertahan hidup, bukan jalan pembebasan.
Di titik ini, kita perlu jujur mengakui bahwa masalahnya bukan pada etos kerja individu. Banyak working poor justru bekerja lebih keras daripada kelas menengah.
Masalahnya ada pada struktur ekonomi yang membuat kerja menjadi murah, sementara hidup semakin mahal. Ketika upah tertinggal dari biaya hidup, kerja kehilangan daya penariknya.
Kondisi ini menampar amanat konstitusi. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Layak” berarti cukup untuk hidup bermartabat seperti makan bergizi, tempat tinggal layak, akses kesehatan, dan sedikit ruang untuk merencanakan masa depan.
Jika jutaan pekerja bekerja tanpa mampu mencapai standar layak itu, maka ada jarak serius antara teks konstitusi dan praktik kebijakan.
Akar persoalan working poor salah satunya terletak pada jurang antara upah dan biaya hidup. Di kota-kota besar, biaya sewa, pangan, dan transportasi meningkat lebih cepat daripada upah.
Pekerja berupah minimum hidup di tepi rapuh. Mereka mungkin tidak jatuh di bawah garis kemiskinan resmi, tetapi hidup di “zona abu-abu” yang mudah terjerumus ketika terjadi guncangan kecil seperti anak sakit, motor rusak, pekerjaan sepi.
Pasar kerja yang kelebihan pasokan tenaga kerja memperlemah posisi tawar pekerja. Di banyak sektor, pekerja dihadapkan pada pilihan pahit, yaitu terima upah rendah atau menganggur.
Negara sering berdiri “netral”, menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha. Namun, netralitas dalam struktur yang timpang bukanlah keadilan, karena justru mengukuhkan ketimpangan.
Pancasila berbicara tentang keadilan sosial, bukan keseimbangan dingin antara yang kuat dan yang lemah.
Mayoritas working poor bertahan hidup di sektor informal. Mereka berdagang kecil, menjadi buruh harian, pekerja rumah tangga, tukang bangunan, atau pengemudi aplikasi.
Kerja ada, tetapi perlindungan nyaris tidak. Tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan kecelakaan, tanpa kepastian pendapatan, hidup mereka seperti berjalan di atas tali tipis.
Satu hari sepi berarti satu hari tanpa pemasukan. Satu kecelakaan kerja bisa menghapus tabungan bertahun-tahun jika tabungan itu pernah ada.
Sektor informal sering dipuji sebagai “penyangga ekonomi” yang fleksibel. Namun, memuji tanpa melindungi adalah bentuk pengabaian.
Pembiaran sektor informal tumbuh tanpa agenda formalisasi yang serius berarti membiarkan jutaan warga hidup tanpa hak-hak dasar ketenagakerjaan.
Padahal Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa. Perlindungan itu seharusnya hadir juga dalam bentuk perlindungan sosial-ekonomi, bukan hanya retorika.
Ekonomi digital hadir dengan janji fleksibilitas dan peluang. Namun, bagi banyak pekerja platform, fleksibilitas berarti pendapatan tidak pasti.
Baca juga: Negara Tak Berkutik untuk Sebatang Pena
Algoritma menentukan order, insentif bisa berubah sewaktu-waktu, dan status kerja sering kabur. Mereka bekerja mengikuti ritme aplikasi, tetapi sulit merencanakan hidup. Modernitas teknologi tidak otomatis berarti kemajuan sosial.
Tanpa regulasi yang berpihak pada pekerja, ekonomi digital berpotensi memperluas barisan working poor dalam wajah baru, yaitu lebih modern, tetapi tetap rentan.
 Foto udara ratusan pengemudi ojek online ante untuk menerima bantuan beras seusai doa bersama di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membagikan bantuan beras untuk membantu perekonomian pengemudi ojek online dan mempererat jalinan silaturahmi. Negara diuji di sini apakah hanya menjadi fasilitator inovasi, atau juga penjaga keadilan bagi mereka yang hidup dari inovasi tersebut?
Foto udara ratusan pengemudi ojek online ante untuk menerima bantuan beras seusai doa bersama di parkir timur GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo membagikan bantuan beras untuk membantu perekonomian pengemudi ojek online dan mempererat jalinan silaturahmi. Negara diuji di sini apakah hanya menjadi fasilitator inovasi, atau juga penjaga keadilan bagi mereka yang hidup dari inovasi tersebut?
Working poor tidak berdiri sendiri karena terhubung dengan kemiskinan antar-generasi. Anak-anak dari keluarga pekerja miskin memulai hidup dengan modal sosial yang minim seperti gizi kurang, akses pendidikan berkualitas terbatas, lingkungan belajar yang tidak kondusif.
Ketika dewasa, mereka cenderung masuk ke pekerjaan berupah rendah. Siklus berulang, yaitu bekerja keras, tetapi tetap miskin.
Program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat merupakan salah satu upaya yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus kemiskinan antar-generasi ini.
Pendidikan sering dipromosikan sebagai kunci mobilitas sosial. Namun, tanpa pasar kerja yang menyediakan pekerjaan berkualitas, pendidikan kehilangan daya ungkitnya.
Banyak lulusan terjebak di pekerjaan yang tidak sesuai kompetensi. Industrialisasi yang tidak padat karya terampil membuat peluang naik kelas makin sempit.
Di sini, kita melihat kegagalan pembangunan dalam membangun tangga sosial yang adil.
Sering terdengar kabar bahwa angka kemiskinan menurun. Namun, bagi pekerja berupah rendah, hidup terasa makin sempit. Mereka mungkin tidak tercatat miskin secara statistik, tetapi hidup di ambang rapuh.
Garis kemiskinan yang rendah membuat banyak keluarga “tidak miskin” di atas kertas, tetapi miskin dalam pengalaman hidup.
Baca juga: Saatnya Negara Berpihak pada Gig Economy
Ini menciptakan ilusi keberhasilan kebijakan, sementara kerentanan sosial tetap menganga. BPS membuat klasifikasi kelompok mulai dari miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas termasuk memberikan kontribusi ilusi kemiskinan ini.
Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan di bawah garis tertentu, melainkan juga soal rasa aman, kemampuan merencanakan masa depan, dan akses terhadap layanan dasar.
Jika bekerja penuh waktu tidak memberi rasa aman, maka kita sedang mengelola kemiskinan, bukan mengentaskannya.
Pancasila menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa. UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan layak.
Kondisi ini bukan jargon moral melainkan mandat politik. Ketika working poor menjadi fenomena luas, hal tersebut menunjukkan bahwa janji konstitusi belum sepenuhnya ditepati.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaan tajamnya ialah kemakmuran siapa yang sedang dibesarkan?
Jika pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh dapur pekerja, maka arah pembangunan patut dikoreksi. Negara tidak boleh puas dengan grafik naik jika kualitas hidup pekerja stagnan.
Mengatasi working poor menuntut keberanian menggeser fokus pembangunan, yaitu dari sekadar menciptakan pekerjaan ke menciptakan pekerjaan layak.
Upah harus lebih dekat dengan kebutuhan hidup riil. Perlindungan sosial perlu menjangkau pekerja informal dan pekerja platform. Industrialisasi harus diukur dari kualitas pekerjaan yang tercipta, bukan hanya nilai investasi.
Negara juga perlu tegas berpihak. Dalam struktur yang timpang, keberpihakan pada yang lemah bukanlah bias ideologis, melainkan kewajiban konstitusional.
Pancasila bukan pajangan melainkan harus menjadi kompas moral. UUD 1945 bukan sekadar teks melainkan suatu kontrak sosial.
Bekerja seharusnya membebaskan manusia dari kemiskinan, bukan mengurungnya dalam lingkaran pas-pasan.
Working poor adalah alarm keras bahwa pembangunan kita terlalu lama memuja pertumbuhan, tetapi kurang memuliakan kerja. Jika kerja tidak memberi kehidupan layak, maka ada yang salah dengan arah kebijakan.
Meluruskan arah pembangunan berarti mengembalikan martabat kerja sebagai hak konstitusional.
Ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan seberapa banyak pekerja yang benar-benar bisa hidup layak dari keringatnya sendiri.
Di situlah Pancasila dan UUD 1945 menemukan maknanya yang paling konkret, yaitu hadir di meja makan keluarga pekerja, bukan hanya di lembaran dokumen negara.