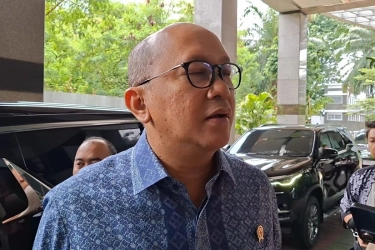Membangun Resiliensi Ekonomi Indonesia di Tengah Badai Global
DALAM beberapa tahun terakhir, ekonomi global dilanda ketidakpastian. Dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berlalu, dunia kembali diguncang oleh perang Rusia–Ukraina yang mengguncang rantai pasok energi dan pangan.
Ketika inflasi mulai mereda, muncul lagi konflik baru di Timur Tengah yang menekan harga minyak dunia.
Di saat yang sama, rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan China kian mengeras, memunculkan ketidakpastian dalam perdagangan global dan arus investasi.
Bagi negara seperti Indonesia, yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas dan impor bahan baku, gejolak eksternal ini bisa menyeret ekonomi domestik dalam pusaran yang sulit dikendalikan.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, fluktuasi harga pangan, hingga potensi perlambatan pertumbuhan menjadi ancaman nyata.
Namun di sisi lain, krisis juga selalu membawa pelajaran penting bahwa ketahanan sejati bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan luar, melainkan kemampuan membangun resiliensi ekonomi domestik.
Resiliensi ekonomi bukan sekadar kemampuan bertahan di tengah badai, tetapi juga kecerdasan beradaptasi, memanfaatkan peluang, dan bangkit lebih kuat.
Di tengah gejolak dunia yang tak pasti, membangun resiliensi ekonomi domestik menjadi strategi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat.
Tulisan ini akan mengulas secara reflektif bagaimana kondisi ekonomi global saat ini memengaruhi Indonesia, apa saja fondasi resiliensi yang telah dimiliki, serta strategi apa yang perlu diperkuat agar Indonesia benar-benar tahan guncangan dan mampu berdiri tegak dalam menghadapi badai ekonomi global.
Dunia ekonomi global kini hidup dalam era di mana krisis yang saling bertaut, memperkuat, dan menciptakan ketidakpastian berlapis. Terdapat lima arus besar yang paling berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dunia dan Indonesia.
Pertama, krisis geopolitik dan keamanan global. Konflik di Ukraina, Palestina, dan ketegangan di Laut Cina Selatan menyebabkan disrupsi pada rantai pasok energi dan pangan global. Harga minyak, gas, dan gandum naik-turun tajam, menekan inflasi di banyak negara.
Kedua, fragmentasi perdagangan global. Dunia yang dulu mengandalkan perdagangan bebas kini bergerak menuju proteksionisme baru.
Negara-negara besar lebih fokus pada kemandirian strategis mulai dari semikonduktor hingga bahan baku penting seperti nikel dan litium.
Ketiga, perubahan iklim dan krisis pangan. Fenomena El Niño menyebabkan kekeringan panjang, mengganggu produksi pangan di Asia dan Amerika Latin. Indonesia pun tidak lepas dari ancaman gagal panen dan kenaikan harga beras.
Keempat, perlambatan ekonomi China. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, pelemahan ekonomi China berdampak langsung terhadap permintaan komoditas ekspor seperti batu bara, sawit, dan nikel.
Kelima, ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan suku bunga tinggi di AS membuat arus modal keluar dari negara berkembang, melemahkan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya impor serta utang luar negeri.
Semua faktor ini saling terkait dalam menciptakan tekanan berlapis pada ekonomi domestik. Maka, resiliensi ekonomi menjadi keharusan strategis, bukan pilihan.
Sejarah mencatat, ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang relatif kuat. Krisis moneter 1997–1998 menjadi pelajaran berharga ketika ketergantungan berlebihan pada utang luar negeri dan lemahnya sistem perbankan menjerumuskan ekonomi nasional.
Namun, dari krisis itu pula lahir reformasi struktural yang memperkuat sistem keuangan, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat fondasi fiskal.
Ketika krisis global 2008 melanda, Indonesia termasuk sedikit negara yang mampu tetap tumbuh positif. Hal ini karena kebijakan moneter yang hati-hati, sistem perbankan sehat, dan peran konsumsi domestik yang besar.
Pandemi COVID-19 menjadi ujian berikutnya. Ekonomi Indonesia sempat mengalami pertumbuhan negatif, namun kita mampu melakukan pemulihan relatif cepat.
Kebijakan fiskal ekspansif yang fleksibel melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dukungan UMKM, dan percepatan vaksinasi menjadi penopang utama.
Kondisi ini menunjukkan bahwa resiliensi ekonomi Indonesia tidak muncul tiba-tiba, melainkan dibangun melalui pengalaman krisis dan reformasi berkelanjutan.
Namun, menghadapi tantangan global baru, fondasi yang ada perlu diperkuat dengan orientasi baru, yaitu transformasi ekonomi domestik inklusif, produktif, dan berdaya saing.
Untuk menghadapi badai global, setidaknya terdapat empat pilar utama yang menjadi penopang ketahanan ekonomi domestik Indonesia.
Pertama, membangun ketahanan pangan dan energi. Kemandirian pangan dan energi adalah basis resiliensi ekonomi.
Pandemi dan konflik global menunjukkan betapa rentannya negara yang bergantung pada impor bahan pangan dan energi.
Indonesia telah menempuh langkah strategis, seperti program Food Estate, penguatan cadangan beras pemerintah, serta hilirisasi energi melalui biodiesel B35 dan pengembangan energi baru terbarukan.
Namun, tantangan masih besar. Produktivitas pertanian stagnan, lahan semakin sempit, dan regenerasi petani lambat.
Di sisi energi, transisi menuju energi bersih masih terkendala investasi dan teknologi. Karena itu, pembangunan ketahanan pangan dan energi perlu dilanjutkan dengan pendekatan ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan bukan sekadar produksi masif, tetapi juga efisiensi sumber daya dan pemberdayaan petani milenial.
Kedua, mendorong hilirisasi industri dan kemandirian manufaktur. Selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh ekspor bahan mentah. Ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
Hilirisasi industri, seperti pada sektor nikel, menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan impor barang jadi.
Namun, hilirisasi tidak boleh hanya fokus pada satu komoditas. Indonesia perlu memperluas ke sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang berbasis inovasi dan digitalisasi.
Dengan begitu, ekonomi domestik tidak hanya tangguh menghadapi krisis, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan baru.
Pilar ketiga ialah ketahanan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin adalah fondasi utama resiliensi.
Pemerintah perlu menjaga defisit dan rasio utang tetap sehat, tanpa mengorbankan stimulus untuk pertumbuhan.
Sementara itu, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah tekanan eksternal.
Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah contoh adaptasi yang efektif. Ke depan, fleksibilitas dan koordinasi kebijakan semacam ini perlu dijaga, terutama menghadapi potensi capital outflow akibat kebijakan suku bunga global.
Pilar terakhir ialah ketahanan sosial dan UMKM. Resiliensi ekonomi tidak hanya soal angka makro, tetapi juga soal daya tahan masyarakat. UMKM yang menyerap 97 persen tenaga kerja menjadi benteng sosial-ekonomi terpenting Indonesia.
Saat pandemi, banyak UMKM yang terpukul. Namun digitalisasi dan dukungan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan platform digital membantu mereka bangkit.
Ke depan, penguatan UMKM melalui akses pembiayaan syariah, digitalisasi, dan integrasi dengan rantai pasok industri besar akan menentukan kekuatan ekonomi nasional menghadapi krisis.
Untuk mewujudkan agar ekonomi Indonesia benar-benar tangguh menghadapi guncangan global, diperlukan strategi menyeluruh yang menggabungkan pendekatan makro, sektoral, dan sosial. Setidaknya terdapat lima strategi utama yang bisa menjadi panduan.
Strategi pertama ialah dengan diversifikasi ekonomi dan pasar ekspor. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah dan pasar tertentu (seperti China) perlu dikurangi.
Diversifikasi produk ekspor berbasis manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif harus diperluas ke pasar Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Indonesia juga harus memperkuat kerja sama regional seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) untuk memperluas akses pasar dan rantai pasok.
Kemandirian teknologi dan inovasi merupakan strategi kedua yang dapat dilakukan. Resiliensi ekonomi tak bisa dilepaskan dari kemampuan teknologi nasional.
Investasi riset, pengembangan industri berbasis teknologi lokal, dan pendidikan vokasi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen teknologi.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah harus menjadi ekosistem inovasi yang nyata.
Strategi ketiga ialah penguatan ekonomi syariah dan keuangan inklusif. Sektor keuangan syariah yang tumbuh pesat dapat menjadi instrumen stabilitas baru.
Zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara berpotensi menjadi sumber pembiayaan domestik alternatif yang berkelanjutan. Dengan mendorong inklusi keuangan syariah, masyarakat lapisan bawah dapat lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi.
Transformasi digital dan ekonomi sirkular menjadi strategi berikutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Digitalisasi ekonomi terbukti mempercepat adaptasi selama pandemi. Namun agar inklusif, digitalisasi harus menjangkau UMKM di daerah dan sektor informal.
Ekonomi digital juga perlu diarahkan ke ekonomi sirkular seperti yang mengurangi limbah, mengoptimalkan sumber daya, dan menciptakan nilai ekonomi baru dari daur ulang.
Strategi terakhir ialah reformasi struktural dan tata kelola. Resiliensi ekonomi akan rapuh tanpa tata kelola yang transparan dan efisien.
Reformasi birokrasi, simplifikasi regulasi, dan kepastian hukum menjadi fondasi agar investasi produktif tumbuh. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu diberdayakan agar kebijakan ekonomi lebih responsif terhadap potensi lokal.
Resiliensi ekonomi nasional sejatinya bermula dari ekonomi lokal yang kuat. Desa-desa dengan basis pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif adalah fondasi nyata kemandirian nasional.
Program Desa Wisata, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih dan kampung nelayan merah putih dapat menjadi katalis jika didukung akses modal dan pasar.
Ketahanan ekonomi juga harus dibangun dengan memperkuat rantai nilai domestik mulai dari produksi bahan baku hingga konsumsi akhir agar nilai tambah tidak bocor keluar negeri.
Pendekatan “from local to global” menjadikan ekonomi desa sebagai fondasi bagi kekuatan ekonomi nasional.
Membangun resiliensi ekonomi bukan tanpa hambatan. Setidaknya ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi.
Pertama, kesenjangan struktural. Ketimpangan wilayah dan pendapatan masih tinggi. Pembangunan ekonomi masih terpusat di Jawa, sementara potensi luar Jawa belum tergarap optimal.
Kedua, keterbatasan fiskal dan investasi. Anggaran negara terbatas untuk membiayai semua program strategis. Ketergantungan pada investasi asing masih tinggi, sementara iklim investasi domestik perlu terus diperbaiki.
Ketiga, perubahan iklim dan transisi hijau. Indonesia menghadapi dilema antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi karbon. Diperlukan kebijakan transisi energi yang adil dan bertahap agar tidak mengorbankan sektor riil.
Namun di balik tantangan itu, Indonesia memiliki modal besar seperti populasi muda produktif, kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar, serta stabilitas politik yang relatif terjaga.
Dengan tata kelola yang baik, modal ini bisa menjadi kekuatan untuk menembus badai global.
Pada akhirnya, resiliensi ekonomi domestik bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk melangkah lebih maju menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
Indonesia harus berani menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan sosial.
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan visi “Indonesia Emas 2045” dengan fokus pada kemandirian pangan, energi, dan industrialisasi nasional.
Visi ini sejalan dengan semangat membangun resiliensi ekonomi domestik yang berpijak pada kekuatan sendiri, namun tetap terbuka pada kerja sama global yang saling menguntungkan.
Sejarah mengajarkan, bangsa yang bertahan bukanlah yang paling kuat atau paling kaya, melainkan yang paling adaptif.
Indonesia telah berkali-kali diuji oleh krisis, dan setiap kali, kita bangkit dengan pelajaran baru.
Kini, saat dunia kembali bergejolak, pilihan kita hanya dua yaitu terombang-ambing oleh badai, atau memperkuat fondasi agar menjadi benteng yang kokoh.
Resiliensi ekonomi domestik bukanlah proyek sesaat, melainkan perjalanan panjang membangun kemandirian, keadilan, dan kemakmuran bersama. Aksi ini menuntut sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
Dengan demikian, membangun resiliensi ekonomi domestik sejatinya adalah membangun ketahanan bangsa. Sebuah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemain utama di dunia global.
Tag: #membangun #resiliensi #ekonomi #indonesia #tengah #badai #global