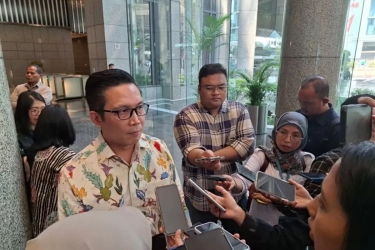Whoosh Bukan Investasi Sosial
DI TENGAH hangatnya perdebatan publik soal utang dan pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 Joko Widodo muncul dengan pembelaan yang menarik untuk bahas.
Ia menyebut proyek tersebut bukan beban keuangan negara, melainkan “investasi sosial” yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Klaimnya seperti sangat meyakinkan, tetapi benarkah logika tersebut?
Dari sudut pandang teori inovasi sosial seperti dikemukakan Geoff Mulgan (The Process of Social Innovation, 2007) dan Alex Nicholls serta Alex Murdock (Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets, 2012), klaim Presiden Jokowi bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial justru menunjukkan logika terbalik.
Inovasi sosial menilai sebuah inisiatif bukan dari besarnya skala proyek, tetapi dari sejauh mana ia mampu memperkuat partisipasi masyarakat dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Dalam kerangka itu, klaim Jokowi mengasumsikan bahwa nilai sosial dapat dihasilkan secara otomatis melalui pembangunan infrastruktur besar. Padahal inovasi sosial sejati menolak logika top-down semacam itu.
Alih-alih memperluas akses dan memberdayakan warga, Whoosh justru menegaskan ketimpangan dengan manfaat terbatas, minim partisipasi publik, dan bergantung pada utang serta subsidi.
Proyek Whoosh gagal memenuhi semua unsur itu. Dari sisi kebaruan, Whoosh bukan terobosan sosial, melainkan substitusi atau komplementer teknologi yang mempercepat perjalanan antarkota tanpa memperbaiki struktur mobilitas sosial.
Masalah kemacetan di Jakarta dan Bandung bukan karena lambatnya moda antar-kota, melainkan karena sistem transportasi di dalam kota yang timpang dan belum terintegrasi.
Inovasi sosial sejatinya menekankan perubahan yang menghubungkan transportasi, perumahan, dan lapangan kerja agar jarak sosial-ekonomi dapat dipersempit.
Whoosh tidak menyentuh akar masalah itu dan lebih menonjolkan simbol modernitas daripada pemerataan akses mobilitas.
Dari sisi partisipasi, proyek ini mencerminkan dominasi teknokratik (technocratic capture). Semua keputusan diambil secara tertutup oleh pemerintah pusat, BUMN, dan investor China tanpa melibatkan masyarakat sekitar atau pemerintah daerah.
Padahal, dalam konsep open innovation for social impact yang dijelaskan oleh Henry Chesbrough dalam Open Innovation Results (2020), nilai sosial hanya tercipta jika masyarakat ikut dalam proses perencanaan dan evaluasi.
Tanpa partisipasi publik, yang lahir bukan inovasi sosial, melainkan proyek elitis berbiaya tinggi dengan manfaat yang terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Klaim keuntungan sosial yang didasarkan pada efisiensi waktu dan penurunan emisi juga lemah secara metodologis.
Dalam pengukuran social return on investment (SROI), terdapat prinsip additionality, yakni dampak sosial baru yang tidak akan muncul tanpa proyek tersebut.
Dalam kasus Whoosh, manfaat semacam itu sulit dibuktikan. Justru terjadi peningkatan emisi selama konstruksi akibat penggunaan beton, baja, dan pembukaan lahan.
Kajian life-cycle assessment terhadap proyek kereta cepat di China yang dilakukan oleh Zhao dkk. dalam jurnal Transportation Research Part D: Transport and Environment (2022) menunjukkan bahwa manfaat pengurangan emisi baru terasa setelah sekitar empat dekade operasi, sedangkan beban sosial dan fiskal muncul sejak tahun pertama.
Secara empiris, efektivitas Whoosh pun belum terbukti. Sejak mulai beroperasi pada Oktober 2023, jumlah penumpang hingga Februari 2025 baru mencapai sekitar delapan juta orang, dengan rata-rata harian 16.000–21.000 penumpang.
Angka ini jauh di bawah target studi kelayakan yang memproyeksikan 50.000–76.000 penumpang per hari.
Harga tiket yang berkisar Rp 150.000 hingga Rp 600.000 jelas belum terjangkau mayoritas masyarakat.
Dengan biaya proyek mencapai sekitar Rp 110 triliun, rasio biaya terhadap manfaat sosial tampak tidak seimbang dan memperlihatkan jurang antara narasi efisiensi dan realitas keterjangkauan publik.
Jika dari sudut inovasi sosial, Whoosh gagal menciptakan nilai baru, dari perspektif investasi sosial kesalahannya bahkan lebih mendasar.
Dari sisi investasi sosial, kesalahannya juga jelas. Dalam teori social investment yang dikembangkan oleh Nathalie Morel, Bruno Palier, dan Joakim Palme dalam Towards a Social Investment Welfare State? (2012), investasi sosial berbeda dari investasi fisik.
Ia fokus pada manusia, mencakup pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas produktif masyarakat.
OECD melalui laporan Social Expenditure Update (2020) menegaskan bahwa investasi sosial harus bersifat redistributif, berkelanjutan secara fiskal, dan memberi manfaat jangka panjang bagi kelompok rentan. Whoosh gagal dalam ketiganya.
Ia tidak memperluas akses kelompok miskin terhadap layanan dasar, tidak mengurangi ketimpangan wilayah, dan justru menambah beban fiskal melalui subsidi serta bunga utang jangka panjang yang diwariskan lintas generasi.
Jokowi berasumsi bahwa manfaat sosial eksternal seperti efisiensi waktu dapat membenarkan ketidakefisienan keuangan internal.
Padahal, dalam kerangka blended value creation, keberlanjutan sosial hanya tercapai jika keadilan dan efisiensi berjalan beriringan.
Ketika kerugian negara dibenarkan dengan alasan moral, pemerintah kehilangan insentif untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi fiskal.
Inilah yang dalam literatur ekonomi publik sering disebut state loss under moral disguise, kerugian publik yang disamarkan dengan narasi kebajikan.
Secara makroekonomi, proyek seperti Whoosh memperlihatkan gejala yang dikenal sebagai pergeseran misi (mission drift).
Negara mengklaim sedang mendorong inovasi publik, tetapi kenyataannya memperluas intervensi fiskal demi menopang kepentingan modal besar di bawah bendera nasionalisme teknologi.
Dalam logika ini, Whoosh bukan simbol inovasi sosial, melainkan bentuk nasionalisme teknologi yang dibiayai utang, kemajuan yang dibangun di atas subsidi tanpa mekanisme pembelajaran sosial.
Ia menjadi monumen politik tentang bagaimana kemajuan dipentaskan, bukan bagaimana keadilan diwujudkan.
Jika ditinjau dari dua kerangka teori sekaligus, inovasi sosial dan investasi sosial, klaim bahwa Whoosh adalah investasi sosial tidak dapat dibenarkan.
Dari sisi inovasi sosial, ia gagal menciptakan kebaruan struktural, gagal melibatkan masyarakat, dan gagal membangun nilai sosial baru.
Dari sisi investasi sosial, ia tidak memperkuat kapasitas manusia, tidak inklusif, dan tidak berkelanjutan secara fiskal.
Yang tersisa hanyalah proyek infrastruktur mahal yang dibungkus dengan retorika sosial agar tampak bermoral dan progresif di mata publik.
Investasi sosial jelas tidak diukur dari kecepatan kereta, tetapi dari kemampuan negara membuat seluruh warganya bergerak bersama.
Pendidikan, kesehatan, transportasi publik yang terjangkau, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan adalah bentuk nyata investasi sosial yang sesungguhnya.
Sebab kemajuan bangsa bukan diukur dari berapa cepat kereta tiba di Bandung, melainkan dari seberapa jauh keadilan bisa dirasakan oleh semua penumpang dalam perjalanan panjang bernama pembangunan, perjalanan yang seharusnya tidak hanya membawa mereka yang berdaya, tetapi juga mengangkat mereka yang tertinggal agar ikut tiba di tujuan yang sama.
Tag: #whoosh #bukan #investasi #sosial