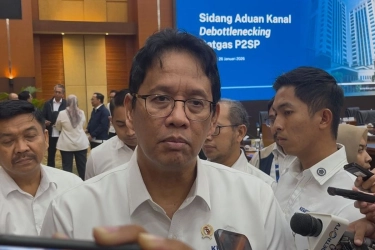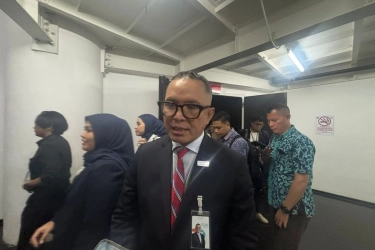Pelajaran dari China: Kereta Cepat Laju Tinggi, Beban Berat
CHINA sering dijadikan panutan ketika membahas kemajuan infrastruktur dan transportasi modern.
Negara itu berhasil membangun jaringan kereta cepat terpanjang di dunia—lebih dari 45.000 kilometer hingga 2025—pencapaian yang mengundang kekaguman banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Namun di balik kilau kemajuan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan: utang besar yang menopang lajunya pembangunan.
Menurut South China Morning Post edisi 7 Januari 2025, China State Railway Group kini menanggung utang sebesar 6,2 triliun yuan atau sekitar 863 miliar dollar AS.
Profesor Zhao Jian dari Beijing Jiaotong University menilai bahwa banyak jalur berkecepatan tinggi dibangun tanpa dasar kelayakan ekonomi yang kuat.
Hanya segelintir rute, seperti Beijing–Shanghai, yang benar-benar menghasilkan keuntungan.
Bahkan, biaya pemeliharaan tahunan dapat mencapai 20 persen dari total investasi awal—beban yang sulit ditutup dengan pendapatan tiket.
Laporan Asia Times (Juni 2025) memperkuat temuan itu. Ekspansi infrastruktur berbasis utang, menurut laporan tersebut, mulai menekan stabilitas fiskal BUMN transportasi China.
Beberapa proyek bahkan terpaksa ditunda karena tidak lagi mampu menutup biaya operasional.
Ironinya, kemajuan yang dibangun atas nama efisiensi justru melahirkan ketidakseimbangan baru: rel terus bertambah, tapi daya pulih ekonomi melemah.
Pelajaran dari China jelas—pembangunan megastruktur tidak otomatis membawa keberlanjutan fiskal.
Bila negara dengan kapasitas fiskal dan industri raksasa seperti China saja terbebani oleh utang infrastruktur, Indonesia perlu lebih waspada agar tidak terperosok ke rel yang sama.
Ambisi dan Realitas
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diresmikan pada Oktober 2023, memang menjadi simbol kebanggaan nasional. Waktu tempuh hanya 46 menit dianggap lompatan besar menuju modernitas.
Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan ambisi memperpanjang jalur hingga Surabaya agar konektivitas Jawa makin efisien. Namun, di balik semangat itu, masalah keuangan yang menumpuk mulai sulit diabaikan.
Data keuangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menunjukkan kerugian Rp 4,195 triliun sepanjang 2024 dan kembali minus Rp 1,625 triliun pada paruh pertama 2025, sebagaimana dikutip dari Kompas.id (11 Oktober 2025).
Biaya proyek yang semula diperkirakan 5,5 miliar dollar AS kini membengkak menjadi 7,27 miliar dollar AS, dan sekitar 75 persennya ditutup dengan pinjaman dari China Development Bank.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan pembiayaan tidak bersumber dari APBN, tapi beban investasi tetap menekan neraca BUMN yang terlibat.
Masalahnya bukan pada besaran utang semata, tetapi pada tata kelola fiskal yang belum transparan.
Seperti diingatkan peraih Nobel Ekonomi Joseph E. Stiglitz, utang dapat menjadi alat pembangunan. Namun, tanpa pengawasan publik dan disiplin fiskal, ia akan berubah menjadi beban antargenerasi.
Pernyataan itu menemukan konteksnya di Indonesia: proyek infrastruktur yang dijanjikan berbasis business to business justru perlahan merembes ke ranah tanggungan publik.
Rencana memperpanjang jalur cepat hingga Surabaya memperbesar taruhannya. Kementerian Perhubungan memperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 113 triliun.
Padahal, rute Jakarta–Surabaya sudah dilayani oleh kereta reguler dan penerbangan dengan waktu tempuh kompetitif. Efisiensi waktu dua atau tiga jam belum tentu mampu menarik penumpang jika harga tiket tinggi dan integrasi antarmoda belum optimal.
Menurut World Bank Infrastructure Outlook 2024, keberlanjutan proyek infrastruktur bergantung pada rasio utang terhadap pendapatan yang terkendali, idealnya di bawah 40 persen.
Indonesia dengan rasio utang publik sekitar 38 persen PDB berada di batas aman yang tipis. Sedikit saja salah perhitungan, utang infrastruktur bisa menumpuk menjadi beban fiskal jangka panjang.
Negara maju telah lebih realistis. Jepang memadukan layanan penumpang dan logistik barang untuk menekan biaya operasional.
Jerman menyiapkan exit strategy bagi jalur tak menguntungkan dengan mengalihfungsikannya menjadi layanan regional berbiaya rendah.
Langkah semacam ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti menambah rel baru, tetapi memaksimalkan fungsi dari yang sudah ada.
Keseimbangan dan arah
Pembangunan modern tidak cukup diukur dari kecepatan atau panjangnya rel yang terpasang. Seperti diingatkan sosiolog Anthony Giddens dari London School of Economics, modernisasi sejati adalah keseimbangan antara kemajuan material dan kesejahteraan sosial.
Jika simbol kemajuan hanya melayani ambisi elite tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat, proyek besar kehilangan nilai kemanusiaannya.
Karena itu, proyek kereta cepat seharusnya tidak sekadar menjadi ajang unjuk kemampuan teknologi, melainkan sarana memperkuat efisiensi ekonomi dan konektivitas sosial.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kilometer rel menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biayanya. Penekanan harus bergeser dari “cepat membangun” menjadi “tepat mengelola”.
Solusinya bukan semata menambah jalur baru, melainkan membenahi integrasi transportasi lokal dan manajemen fiskal. Dari stasiun akhir, penumpang harus dapat berpindah cepat ke moda lain tanpa hambatan.
Pemerintah juga perlu menyiapkan rencana keluar bagi proyek yang tidak layak secara ekonomi, sehingga tidak menjadi beban jangka panjang bagi generasi berikutnya.
Seorang ekonom dalam diskusi publik yang disitat Kompas.id mengingatkan, “kita tidak boleh membangun rel hanya untuk kehilangan masa depan.”
Kalimat itu menegaskan bahwa kemajuan sejati bukan soal seberapa cepat kita bergerak, melainkan seberapa lama kita bisa bertahan di tujuan yang dicapai dengan bijak.
Tag: #pelajaran #dari #china #kereta #cepat #laju #tinggi #beban #berat