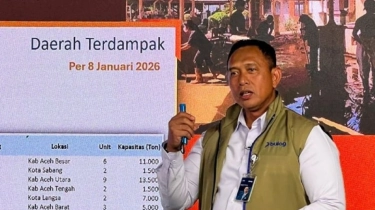Tidak Perlu Tersinggung jika Dibandingkan dengan Afrika
SEBENARNYA, kita tidak perlu alergi dengan komparasi. Dalam kebijakan publik, perbandingan antarnegara adalah praktik lazim untuk memahami posisi relatif kita dalam dinamika global. \
Sayangnya, di Indonesia, komparasi masih sering disalahartikan sebagai penghinaan, terutama jika objek perbandingannya adalah negara-negara Afrika.
Padahal, justru dari komparasi itulah kita bisa menemukan pelajaran berharga dan arah perbaikan.
Bahkan dalam isu-isu kemanusiaan sekalipun, kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara Afrika.
Belajar itu bukan soal melihat ke atas atau ke bawah, tetapi soal kesiapan untuk mengambil pelajaran—baik yang bisa diadopsi, maupun yang perlu dihindari sebagai cermin.
Merunut sejarah, Indonesia justru pernah menjadi pelopor dalam membangun solidaritas Global South bersama negara-negara Afrika melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.
Dalam forum itulah semangat kesetaraan, kemandirian, dan pembelajaran antarbangsa berkembang, jauh dari kompleks inferioritas atau superioritas.
Maka membandingkan diri dengan Afrika bukanlah hal baru atau tabu, tetapi kelanjutan dari semangat yang dulu pernah kita pelopori sendiri: belajar dan tumbuh bersama dalam solidaritas postkolonial.
Dalam beberapa hari terakhir, publik nasional dibuat gaduh oleh kabar pencopotan Olvy Andrianita dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.
Isu yang mencuat adalah bahwa pencopotan ini diduga berkaitan dengan pernyataannya dalam forum peluncuran laporan di CSIS Jakarta, di mana ia menyatakan bahwa Indonesia tertinggal dari beberapa negara Afrika dalam merespons dinamika global.
Bila benar demikian, maka ini bukan hanya mengkhawatirkan dari sisi kebebasan akademik dan diskursus kebijakan, tetapi juga menunjukkan rendahnya ketahanan emosional dan intelektual sebagian pengambil kebijakan terhadap kritik berbasis komparasi.
Indonesia adalah negara dengan banyak keunggulan, tetapi juga tidak luput dari berbagai kelemahan struktural dan kebijakan yang menghambat kemajuan.
Dalam situasi seperti ini, membandingkan—secara objektif dan berimbang, dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di Afrika, adalah metode yang sah dan perlu dalam proses evaluasi kebijakan.
Tidak semua negara Afrika tertinggal dari Indonesia, dan dalam beberapa aspek, beberapa negara Afrika justru sudah lebih progresif dan responsif dalam menjawab tantangan global.
Salah satu area di mana beberapa negara Afrika menunjukkan keunggulan adalah dalam pemanfaatan teknologi digital untuk inklusi keuangan.
Kenya, misalnya, melalui platform M-Pesa, telah merevolusi layanan keuangan digital sejak 2007. Platform ini memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil tanpa akses ke bank, untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan ponsel fitur dasar.
Hingga saat ini, M-Pesa telah diadopsi oleh lebih dari 30 juta pengguna aktif dan menyumbang lebih dari 40 persen PDB Kenya dalam bentuk transaksi digital.
Bandingkan dengan Indonesia, di mana tingkat inklusi keuangan memang meningkat signifikan dalam dekade terakhir, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam literasi keuangan digital, penetrasi layanan keuangan formal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta integrasi antara lembaga keuangan dan platform digital.
Inovasi fintech Indonesia masih terfokus pada konsumen urban dan kelas menengah, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan segmen informal dan rural yang justru paling membutuhkan akses inklusif.
Dalam sektor energi terbarukan, Maroko layak dijadikan referensi. Negara ini membangun salah satu kompleks tenaga surya terbesar di dunia, Noor Solar Complex, yang mampu menghasilkan lebih dari 500 MW energi bersih.
Investasi besar ini dilakukan dengan visi strategis jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menjadikan Maroko sebagai eksportir energi hijau ke Eropa.
Sementara itu, Indonesia—meski telah menyatakan komitmen transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP), masih menghadapi kendala besar dalam implementasi.
Dominasi batu bara sebagai sumber energi utama, ketergantungan fiskal terhadap pendapatan dari industri ekstraktif, serta lemahnya political will dalam membatalkan proyek PLTU baru, menunjukkan bahwa transisi energi Indonesia masih setengah hati.
Dalam konteks ini, menyebut Maroko atau Afrika Selatan sebagai lebih maju dalam komitmen energi bersih bukanlah hinaan, melainkan fakta yang dapat diverifikasi.
Rwanda adalah contoh menarik lainnya. Setelah mengalami tragedi genosida pada 1994, negara ini melakukan reformasi birokrasi secara radikal.
Pemerintah Rwanda mengadopsi sistem pemerintahan berbasis data, mengintegrasikan pelayanan publik melalui sistem digital, dan menekan korupsi melalui mekanisme transparansi yang terstruktur.
Hasilnya, dalam laporan Ease of Doing Business versi Bank Dunia (edisi terakhir 2020 sebelum dihentikan), Rwanda menempati peringkat 38 dari 190 negara. Ini menjadikannya negara dengan iklim bisnis terbaik di Afrika dan salah satu terbaik di dunia berkembang.
Indonesia, dalam laporan yang sama, berada di peringkat 73. Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, seperti pembentukan OSS (Online Single Submission) dan Undang-Undang Cipta Kerja, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan kompleksitas perizinan, tumpang tindih regulasi daerah, dan ketidakkonsistenan dalam implementasi.
Ini bukan soal pesimisme, tapi kenyataan yang terus diangkat oleh pelaku usaha dan pengamat kebijakan.
Komparasi berikutnya adalah terkait adaptasi terhadap standar perdagangan global, terutama dalam isu traceability, keberlanjutan (sustainability), dan non-tariff measures seperti standar lingkungan dan sosial.
Negara-negara Afrika Barat seperti Ghana dan Pantai Gading telah mulai menerapkan sistem traceability pada ekspor kakao mereka, mengikuti tuntutan Uni Eropa dalam regulasi Deforestation-Free Products (EUDR).
Ghana bahkan melakukan digitalisasi data petani dan kebun untuk memastikan keterlacakan produk dari hulu ke hilir.
Indonesia masih berdebat soal urgensi kebijakan serupa. Di saat dunia bergerak cepat menuju transparansi rantai pasok, banyak eksportir Indonesia—terutama di sektor sawit dan kehutanan—masih bersandar pada pendekatan defensif dan lobi politik, alih-alih melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk menjaga daya saing jangka panjang.
Ketika pejabat atau pengamat menyampaikan bahwa Indonesia bisa belajar dari Afrika, reaksi yang muncul kerap emosional, bahkan defensif.
Ini mengungkapkan dua hal sekaligus: adanya mitos tentang superioritas Indonesia atas Afrika, dan sekaligus kompleks inferioritas yang belum terselesaikan.
Kenyataannya, Indonesia dan negara-negara Afrika adalah bagian dari Global South yang sama-sama menghadapi tantangan besar: ketimpangan ekonomi global, krisis iklim, dan tekanan geopolitik.
Namun dalam beberapa hal, negara-negara Afrika lebih berani mengambil keputusan strategis dan menunjukkan ketegasan dalam reformasi domestik.
Indonesia sering kali terjebak dalam birokrasi yang lamban dan kebijakan yang bersifat tambal sulam. Padahal, Indonesia memiliki semua modal untuk melompat lebih jauh: skala ekonomi besar, populasi muda, potensi sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geopolitik yang strategis.
Komparasi yang dilakukan, jika memang itu menjadi sebab pencopotannya, tentu tidak lebih dari analisis berbasis data dan pengalaman lintas negara.
Komparasi bukan penghinaan. Justru, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berkaca dan belajar, tak peduli dari mana sumber pelajarannya berasal. Bahkan negara kecil pun bisa memberikan pelajaran besar jika kita mau membuka diri.
Dalam perspektif kebijakan publik, benchmarking adalah metode utama untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu program. Tanpa perbandingan, kita hanya berkutat dalam asumsi internal yang berisiko bias.
Maka jika ada pejabat yang menyampaikan bahwa negara lain, termasuk negara Afrika, lebih cepat dalam beberapa hal, maka reaksi seharusnya adalah: "apa yang bisa kita pelajari dari itu?", bukan "mengapa kita dibandingkan dengan mereka?"
Indonesia punya banyak alasan untuk optimistis. Namun optimisme yang sehat harus disertai keberanian untuk menerima kritik dan melakukan introspeksi.
Membandingkan Indonesia dengan negara-negara Afrika bukanlah bentuk merendahkan, tetapi justru pengakuan bahwa kita berada dalam komunitas global yang saling belajar dan saling menantang untuk lebih baik.
Jika negara-negara Afrika bisa menunjukkan lompatan kemajuan di tengah keterbatasan, maka Indonesia pun seharusnya bisa, bahkan lebih dari itu.
Syaratnya satu: jangan alergi terhadap komparasi, apalagi jika niatnya adalah untuk memperbaiki negeri.
Tag: #tidak #perlu #tersinggung #jika #dibandingkan #dengan #afrika