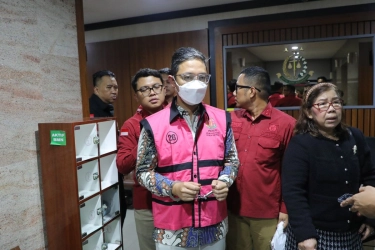Mengembalikan Ruh Kehalalan: Antara Regulasi dan Kesadaran Moral
SERTIFIKASI halal pada dasarnya lahir dari semangat luhur: memberikan kepastian bagi umat Islam agar terhindar dari yang haram.
Namun, belakangan, semangat ini seolah bergeser menjadi instrumen administratif dan ekonomi yang tak selalu sejalan dengan maqashid syariah, tujuan pembentukan hukum syariah.
Belum lama, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan “barang yang tidak bersertifikasi halal adalah barang ilegal”.
Menghubungkan legalitas barang dengan kehalalan jelas satu hal yang problematik. Mencampur-adukkan keduanya bukan hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi menimbulkan overreach regulasi.
Sertifikasi halal seharusnya hanyalah alat bantu administratif, bukan dasar ontologis dari kehalalan itu sendiri, apalagi menentukan legalitas.
Dalam epistemologi hukum Islam, kaidah fiqh yang menjadi fondasi adalah “Al-ashlu fil asy-ya’ al-ibahah, hatta yadulla ad-dalilu ‘ala tahrimihi” hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil/petunjuk tentang keharamannya.
Sesuatu yang tidak terdapat bukti keharamannya adalah halal dan boleh dikonsumsi. Kekeliruan berpikir terjadi ketika hukum “boleh” diubah menjadi “tidak boleh”, hanya karena tidak ada sertifikat halal.
Lebih dari sekadar kekeliruan epistemologis, ini adalah bentuk ta’assub birokratis: nilai agama dilembagakan sebagai administrasi birokrasi. Akibatnya, standar halal bergeser dari makna moral menuju legalitas formal.
Kehalalan tak lagi dijalankan sebagai ekspresi nilai, kebersihan proses, dan keterjagaan dari unsur haram, melainkan sebagai kepemilikan dokumen dan label.
Paradigma ini mengubah nilai spiritual menjadi prosedur birokrasi: selama ada cap dan sertifikat, sesuatu dianggap halal dan legal.
Ketika sertifikat menjadi ukuran kehalalan formal dan menjelma menjadi alat penentu legalitas, elan vital agama kehilangan denyutnya.
Halal/haram tereduksi menjadi dokumen administrasi. Di titik inilah agama tereduksi menjadi sistem simbol, bukan sistem nilai.
Stempel menggantikan dalil, dokumen menggantikan keyakinan, dan proses administratif menggantikan tanggung jawab moral. Lahirlah kondisi di mana sesuatu boleh jadi “halal secara administratif”, tetapi belum tentu “halal secara etis”.
Pajak agama
Kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semula dimaksudkan untuk melindungi konsumen Muslim. Namun dalam praktiknya, regulasi itu menciptakan ekosistem baru: industri sertifikasi.
Ketika sertifikat halal menjadi syarat peredaran barang, logika pasar ikut bermain. Sertifikasi menjadi komoditas ekonomi: siapa yang ingin “diakui halal”, harus menempuh serangkaian prosedur administratif yang tentu saja megandung biaya.
Dalam konteks ini, kehalalan berubah menjadi produk ekonomi. Lembaga sertifikasi, auditor halal, hingga konsultan halal tumbuh subur, bukan semata karena kesadaran agama, tetapi karena permintaan administratif.
Lebih jauh, ketika sertifikasi dijadikan penentu legalitas, logika keagamaan berubah menjadi logika fiskal.
Dalam situasi seperti ini, sertifikasi halal perlahan menyerupai “pajak agama”. Pelaku usaha seolah diwajibkan “membayar” untuk memperoleh pengakuan kehalalan negara, sebagaimana pengusaha rokok harus membayar cukai agar rokonya legal untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat.
Yang semula dimaksudkan sebagai upaya melindungi konsumen dan menjaga kesucian produk, kini berpotensi bergeser menjadi mekanisme penarikan biaya atas nama agama.
Kehalalan yang sejatinya bersifat spiritual dan berbasis kejujuran pribadi, berubah menjadi kontrak administratif antara pengusaha dan lembaga sertifikasi.
Dalam konteks negara modern, tentu ada logika birokrasi yang tak bisa dihindari. Namun, ketika logika itu bersinggungan dengan ranah agama, harus ada batas etis yang jelas.
Menghalalkan pungutan atas nama agama tanpa landasan keharaman yang nyata justru berpotensi menciptakan bentuk baru dari monopoli moral yang bisa mengaburkan esensi tanggung jawab pribadi dalam beriman.
Tentu saja, negara harus hadir untuk melindungi warganya. Namun, upaya perlindungan melalui jaminan produk halal tidak semestinya justru menimbulkan serangkaian persoalan baru.
Dalam konteks ini, kaidah fiqh memberikan pedoman yang sangat jelas: “Adh-dhararu la yuzâlu bidhararin âkhar”, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang lain.
Kebijakan sertifikasi halal yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang haram tidak seharusnya melahirkan masalah baru bagi pelaku usaha maupun konsumen.
Dalam praktiknya, beban administrasi dan biaya sertifikasi sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Bagi banyak UMK, terutama di sektor pangan tradisional, biaya untuk memperoleh sertifikat halal bisa menjadi beban nyata bagi usaha meraka.
Di sisi lain, jika tidak mengurus sertifikasi, mereka bisa tersingkir dari pasar yang menuntut legalitas formal.
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan struktural: perusahaan besar dengan sumber daya memadai dapat dengan mudah memenuhi seluruh prosedur dan memasarkan produknya sebagai “halal bersertifikat”.
Sementara usaha kecil, yang produknya mungkin lebih sederhana, jelas bahan dan cara mengolahnya, kehilangan akses pasar hanya karena kendala administratif.
Pada titik ini, kebijakan yang semula dimaksudkan untuk melindungi umat justru berpotensi menciptakan madharat sosial-ekonomi.
Lebih berbahaya lagi, masyarakat bisa kehilangan kemampuan kritisnya dalam menilai halal-haram. Mereka menjadi bergantung pada logo, bukan pada ilmu.
Padahal, Islam menuntut setiap individu untuk berpikir, memahami, dan meneliti bukan sekadar mengikuti simbol.
Mengembalikan ruh kehalalan
Tentu, sertifikasi halal tetap memiliki manfaat. Dalam dunia industri modern yang kompleks, sulit bagi masyarakat untuk menelusuri asal bahan dan proses produksi. Di sinilah fungsi sertifikasi menjadi penting: memberikan jaminan dan ketenangan bagi konsumen.
Namun, penting diingat bahwa sertifikasi adalah instrumen ihtiyath (kehati-hatian), bukan instrumen tahrim (pengharaman). Ia membantu, bukan menentukan.
Ketika alat bantu dijadikan sumber hukum, lahirlah penyimpangan epistemologis yang berbahaya.
Karenanya, para ulama dan intelektual Muslim perlu kembali menegaskan garis pemisah antara kehalalan substantif dan kehalalan administratif.
Yang pertama bersifat teologis, yang kedua bersifat teknokratis. Ketika dua ranah ini tumpang tindih, agama kehilangan ruhnya dan mewujud menjadi alat regulasi.
Sertifikasi halal semestinya dikelola dengan semangat tahsin (penyempurnaan), bukan tajir (komersialisasi).
Negara boleh berperan, tetapi peran itu harus proporsional: memfasilitasi, bukan memonopoli. Lembaga sertifikasi seharusnya menjadi penjaga etika, bukan pencipta biaya.
Dalam kerangka itu, beberapa langkah dapat ditempuh. Pertama, dekonsentrasi lembaga sertifikasi agar tidak terpusat dan memberi ruang bagi ormas, pesantren, serta universitas untuk turut berperan melalui sistem akreditasi terbuka yang tetap terjamin integritasnya.
Kedua, pemberian subsidi sertifikasi halal bagi UMKM, agar regulasi tidak justru menambah beban ekonomi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Terakhir dan tidak kalah pentingnya, Pendidikan publik tentang fiqh halal-haram perlu diperkuat, agar masyarakat tidak kehilangan kemampuan berpikir kritis di balik simbol dan logo.
Dengan demikian, kehalalan dapat kembali dimaknai sebagai kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar urusan administratif yang berbiaya.
Dengan cara ini, sertifikasi halal tidak akan jatuh menjadi alat ekonomi, melainkan tetap menjadi ekspresi nilai agama dalam tata niaga modern.
Tag: #mengembalikan #kehalalan #antara #regulasi #kesadaran #moral