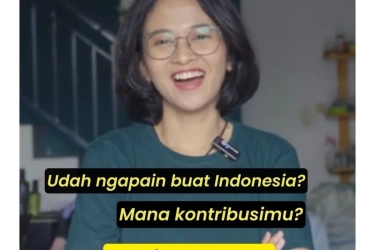Evaluasi Kritis Evakuasi WNI dari Iran dan Israel
PADA Jumat, 20 Juni 2025, pemerintah Indonesia secara resmi memulai operasi evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari dua kawasan konflik paling genting saat ini: Iran dan Israel.
Operasi ini dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Crisis Response Team (CRT) yang terdiri atas 34 personel gabungan.
Jalur evakuasi telah ditetapkan: WNI dari Iran akan dibawa ke Baku, Azerbaijan, melalui jalur darat, sementara WNI dari Israel akan dievakuasi melalui Amman, Yordania, sebelum diterbangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat komersial.
Secara substansi, langkah ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara di saat rakyatnya berada dalam ancaman bahaya.
Namun, jika ditinjau lebih dalam melalui kerangka teoritis hubungan internasional dan perlindungan warga negara, kebijakan ini menyisakan sejumlah catatan kritis yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan ke depan.
Dalam literatur hubungan internasional kontemporer, perlindungan warga negara di luar negeri merupakan bagian dari citizen protection abroad, konsep yang berkembang kuat sejak pasca-Perang Dingin.
Negara tidak hanya menjadi pelindung batas wilayah, tetapi juga penjaga keselamatan setiap warga negaranya, di manapun mereka berada.
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara eksplisit menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan konsuler terhadap warganya.
Bagi Indonesia, kebijakan evakuasi ini merupakan wujud dari politik luar negeri bebas aktif. Artinya, meskipun Indonesia tidak memihak dalam konflik antara Israel dan Iran, pemerintah tetap aktif melindungi warga negaranya yang terdampak.
Namun, perlindungan itu menjadi kurang efektif jika baru dilakukan setelah situasi memburuk. Keaktifan semacam ini bersifat reaktif, bukan antisipatif, sehingga tidak mencerminkan semangat sejati dari prinsip bebas aktif.
Mengapa terlambat?
Fakta menunjukkan bahwa intensitas konflik di Iran dan Israel meningkat tajam sejak awal Juni. Laporan Institute for the Study of War (12 Juni 2025) mengungkap peningkatan serangan drone dan rudal yang menargetkan wilayah sipil di Teheran dan Qom.
Data ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) menunjukkan peningkatan 43 persen insiden bersenjata di Iran dalam dua pekan pertama bulan Juni. Namun, keputusan evakuasi baru diambil pada 19 Juni dan dilaksanakan keesokan harinya.
Keterlambatan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki sistem deteksi dini yang terintegrasi untuk membaca dan memprediksi ancaman terhadap WNI secara real-time.
Ketergantungan pada kanal diplomatik konvensional tidak lagi cukup di tengah lanskap konflik modern yang sangat dinamis dan sulit diprediksi.
Menurut Kementerian Luar Negeri, terdapat 578 WNI di Iran dan Israel. Namun, hanya 115 WNI di Iran dan 11 WNI di Israel yang menyatakan bersedia dievakuasi.
Artinya, hanya 21,8 persen WNI yang ikut dalam evakuasi. Rendahnya angka ini memunculkan pertanyaan penting: apakah komunikasi pemerintah selama krisis cukup efektif? Apakah WNI telah mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai?
Mayoritas WNI yang berada di Iran dan Israel adalah pelajar dan mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan di kota-kota seperti Qom, Teheran, dan Yerusalem. Kelompok ini seharusnya menjadi prioritas dalam perlindungan negara saat situasi keamanan memburuk.
Namun, berdasarkan pernyataan dari Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) di Iran, banyak mahasiswa yang merasa belum mendapat informasi yang cukup jelas mengenai skema evakuasi, serta hanya bergantung pada komunikasi informal melalui grup WhatsApp. (edukasi.okezone.com)
Minimnya edukasi risiko yang terstruktur dan ketiadaan sistem peringatan dini berbasis teknologi memperkuat kesan bahwa kehadiran negara dalam krisis ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Evakuasi dari Iran hanya bisa dilakukan melalui darat karena tidak ada pesawat yang diizinkan memasuki wilayah udara negara tersebut.
Rute darat dari Teheran ke Baku menempuh jarak lebih dari 1.800 km dengan estimasi waktu 30 jam. Rute ini bukan hanya panjang, tetapi juga berisiko tinggi secara keamanan.
Ketergantungan pada negara ketiga sebagai titik transit (seperti Azerbaijan dan Yordania) menunjukkan belum adanya skema evakuasi regional atau multinasional yang bisa diandalkan saat situasi darurat muncul.
Ini berbeda dengan negara-negara seperti Jepang atau Perancis yang telah membangun permanent evacuation protocols di kawasan-kawasan rawan konflik, termasuk melalui kerja sama trilateral atau regional. Tampaknya Indonesia belum sampai ke titik itu.
Jalan kedepan
Pertama, pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini berbasis teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi seluler, lokasi GPS, dan kanal informasi resmi di semua perwakilan RI di luar negeri.
Sistem ini memungkinkan peringatan real-time, koordinasi evakuasi, serta asesmen risiko secara individual terhadap WNI.
Kedua, Kementerian Luar Negeri dan KBRI harus mulai menyusun protokol evakuasi permanen di kawasan rawan, bekerja sama dengan ASEAN, OKI, atau bahkan PBB. Protokol ini harus mencakup rute darurat, pengamanan militer, logistik medis, dan pendampingan psikososial.
Ketiga, pemerintah perlu menggandeng organisasi-organisasi diaspora, seperti PPI dan komunitas profesional Indonesia di luar negeri, sebagai mitra aktif dalam merancang dan mensosialisasikan skema perlindungan WNI.
Keempat, perlu ada laporan publik tahunan mengenai upaya perlindungan WNI, termasuk simulasi, pelatihan, dan capaian program.
Ini penting agar masyarakat tahu bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak berhenti pada diplomasi formal, tetapi juga menyentuh aspek paling personal: keselamatan warga.
Evakuasi WNI dari Iran dan Israel adalah cerminan nyata bahwa negara mampu hadir saat dibutuhkan. Namun kehadiran itu tidak boleh hanya bersifat administratif dan reaktif.
Krisis global hari ini menuntut negara untuk bergerak dari reaksi ke antisipasi, dari operasional ke strategis, dan dari sekadar prosedur ke perlindungan yang visioner.
Kebijakan evakuasi yang baru berjalan setelah risiko meningkat menunjukkan perlunya transformasi mendasar dalam arsitektur perlindungan WNI di luar negeri.
Ini bukan hanya soal jalur darat atau udara, bukan soal jumlah personel TNI atau anggaran logistik, melainkan soal bagaimana Indonesia mendefinisikan kembali politik luar negeri bebas aktif sebagai politik yang berpihak pada keselamatan warga, berbasis data, dan mampu merespons dunia yang tidak stabil secara cepat dan tepat.
Dan yang harus diingat, ini baru Iran dan Israel. Kita memiliki ratusan ribu WNI di berbagai kawasan berpotensi konflik lainnya.
Salah satu yang paling rawan adalah Taiwan, tempat tinggal lebih dari 300.000 WNI, dan mayoritas pekerja migran.
Taiwan adalah kawasan strategis yang berada dalam bayang-bayang konflik militer antara China dan Amerika Serikat, dua kekuatan besar dunia.
Ironisnya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Taiwan, sehingga tidak memiliki akses resmi dan instrumen perlindungan formal jika krisis tiba-tiba meletus.
Fakta ini menegaskan satu hal: kita butuh kebijakan perlindungan global yang terstruktur, sistematis, dan lintas batas diplomatik.
Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak lagi cukup diukur dari berapa WNI yang berhasil diselamatkan setelah krisis terjadi, tetapi dari seberapa siap dan tanggap negara dalam mencegah risiko sebelum nyawa terancam.
Inilah tantangan besar politik luar negeri Indonesia ke depan: menjadikan perlindungan WNI sebagai prioritas strategis nasional, bukan sekadar urusan kemanusiaan, tetapi bagian dari posisi dan peran Indonesia dalam percaturan global yang makin tidak pasti.
Dalam dunia multipolar yang penuh ketegangan, politik luar negeri yang baik adalah yang mampu menyelamatkan rakyatnya—di manapun mereka berada.