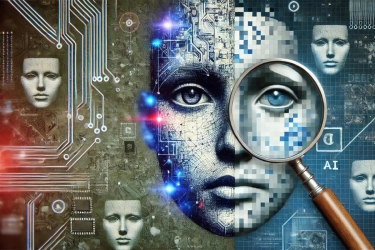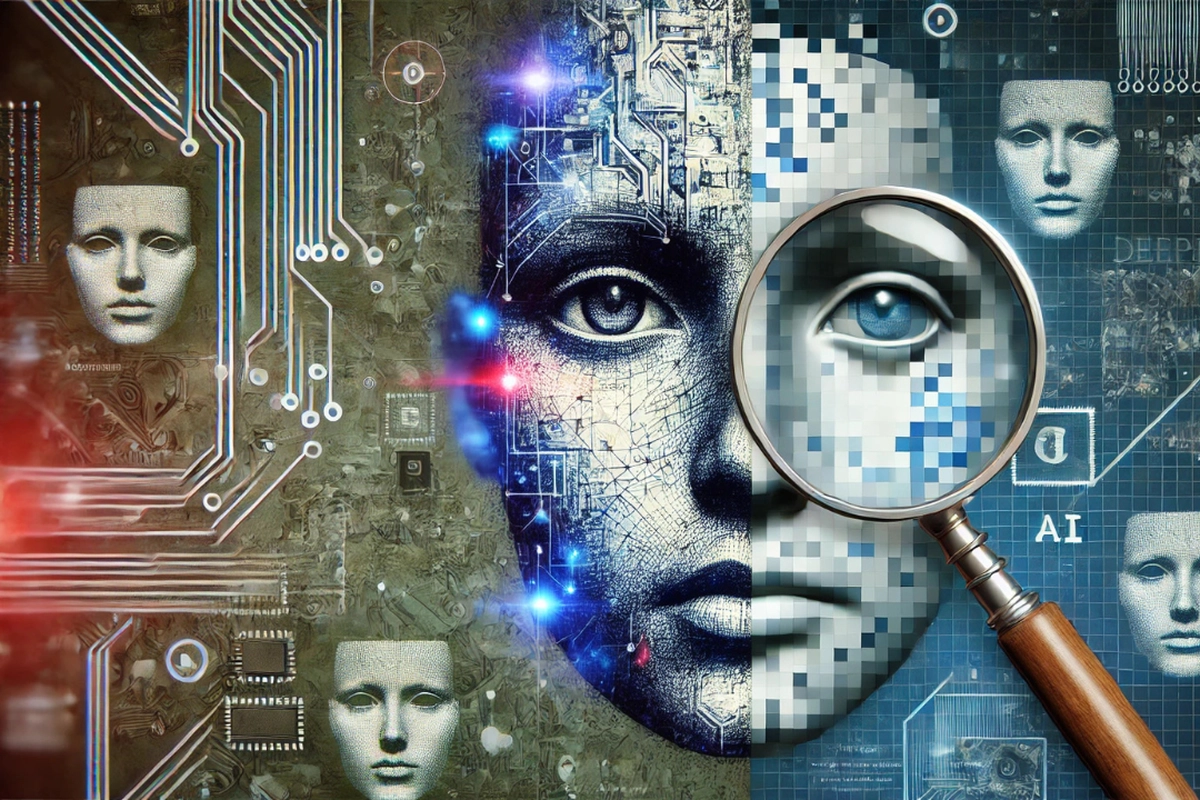
Siapkah Kita Memasuki Era Deepfake AI 2026?
PADA Januari 2026, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menangguhkan akses Grok AI —chatbot canggih dari xAI milik Elon Musk— karena disalahgunakan untuk menghasilkan deepfake pornografi non-konsensual.
Ribuan gambar sintetis yang memalsukan wajah perempuan dan anak Indonesia beredar di platform digital, meninggalkan trauma yang dalam.
Kasus ini bukan sekadar "penyalahgunaan teknologi", melainkan sinyal kuat: kita sedang memasuki era Deepfake AI 2026, di mana batas antara asli dan palsu semakin kabur. Konsekuensinya bisa fatal bagi individu, industri, bahkan stabilitas nasional.
Pertanyaan mendasar kini bukan lagi apakah AI berbahaya?, tapi: Siapkah Indonesia menghadapinya?
Deepfake bukan lagi fantasi sci-fi. Teknologi generatif AI kini mampu menciptakan video, suara, dan gambar yang hampir tak terbedakan dari asli hanya dalam hitungan detik.
Di Indonesia, penyalahgunaannya sudah meluas: dari penipuan suara (voice cloning) hingga hoaks politik yang berpotensi memicu kerusuhan.
Dalam workshop Cybersecurity #13 di Yogyakarta (31 Januari 2026), CEO Cyberkarta Ismail Hakim menyampaikan data mengejutkan: serangan deepfake melonjak 1.400 persen secara year-on-year dari 2024 ke 2025, dengan korban terbanyak perempuan dan anak.
Kekhawatiran ini sejalan hasil survei Sharing Vision, Desember 2025, yang melibatkan 2.442 responden.
Survei tersebut menunjukkan, 39 persen responden mengkhawatirkan AI digunakan untuk cybercrime, manipulasi opini, dan penipuan.
Sementara itu, 38 persen responden mengatakan sulit mengetahui apakah konten dibuat oleh manusia atau AI—sebuah indikasi nyata bahwa masyarakat mulai menyadari ancaman deepfake di kehidupan sehari-hari.
Namun, respons kita masih reaktif. Pemblokiran Grok adalah langkah cepat, tapi sementara. Pelaku mudah berpindah ke model open-source lain yang tak terawasi.
Ini mengingatkan kita pada peringatan yang saya sampaikan dalam tulisan di kolom Kompas.com berjudul "Sudahkah Butuh Babak Revolusi Keamanan Siber Indonesia?" (3 Februari 2026):
“Ancaman siber berkembang eksponensial dengan hadirnya AI generatif yang mampu membuat deepfake untuk penipuan, quantum computing yang akan membuat enkripsi kita usang dalam 5-10 tahun, dan jutaan perangkat IoT yang menjadi bom waktu keamanan.”
Penulis menegaskan, kita tidak hanya kalah dalam teknologi, tapi juga dalam kesadaran kolektif. Analisis mendalam menunjukkan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara yang lebih matang dalam mengantisipasi era ini.
Gap Regulasi dan Hukum: Dari Reaktif ke Proaktif
Indonesia saat ini belum ada undang-undang AI yang komprehensif. Yang ada hanyalah rencana dua Perpres (Roadmap Nasional AI dan Etika AI) yang ditargetkan awal 2026, draft regulasi wajib watermark/label untuk konten AI-generated (sedang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital), dan pemanfaatan UU ITE serta UU PDP untuk kasus deepfake (tapi tanpa definisi khusus AI).
Aksi cepat seperti blokir Grok menunjukkan niat baik, tapi bersifat ad hoc. Tidak ada sanksi spesifik untuk penyedia AI, tidak ada kewajiban deteksi otomatis, dan belum ada badan pengawas independen.
Hasilnya: pelaku deepfake bisa berpindah platform dengan mudah, sementara korban (terutama perempuan dan anak) sulit mendapat keadilan cepat.
Hasil survei Sharing Vision menguatkan urgensi ini: 92 persen responden menilai perlunya regulasi untuk mengatur penggunaan AI secara tepat.
Angka yang sangat tinggi ini mencerminkan kesadaran publik bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, teknologi AI, termasuk deepfake, akan terus disalahgunakan tanpa konsekuensi memadai.
Uni Eropa sudah punya kerangka risk-based yang melarang praktik berbahaya dan mewajibkan transparansi.
Singapura punya toolkit konkret (AI Verify) yang menjadi bahan masukan bagi kita. Jepang menunjukkan bahwa soft law bisa efektif jika didukung kolaborasi pemerintah-swasta yang kuat, dan ini sesuatu yang belum kita miliki.
Fondasi yang Rapuh
Ada tiga faktor yang menunjukkan kerapuhan fondasi di Indonesia. Pertama, People (Manusia). Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang risiko AI masih rendah.
Edukasi digital minim, terutama di kalangan orang tua dan anak. Guru dan orang tua sering tidak tahu cara mendeteksi deepfake.
Sementara itu, Uni Eropa mewajibkan "AI literacy" untuk semua pengguna high-risk AI, Singapura punya program nasional "AI literacy" sejak 2019 termasuk untuk sekolah, dan Jepang punya guidelines yang mewajibkan pejabat pemerintah mengawasi risiko AI. Kita kekurangan tenaga ahli.
Jumlah pakar AI governance di Indonesia diperkirakan kurang dari 500 orang, sementara Singapura sudah punya ribuan melalui program pelatihan IMDA.
Kedua, Process (Proses). Proses penanganan kasus deepfake masih manual dan lambat (laporan ke polisi → investigasi → takedown). Tidak ada SOP nasional untuk pelaporan cepat atau kerja sama antar-platform.
Berbeda dengan Uni Eropa yang punya proses otomatis via Code of Practice dengan timeline 48 jam takedown. Singapura dengan sandbox untuk uji coba proses governance sebelum deploy, dan Jepang dengan task force di bawah PM untuk koordinasi cepat.
Penegakan hukum kita masih bergantung pada keluhan korban, bukan pencegahan sistemik.
Ketiga, Technology (Teknologi). Kita belum punya infrastruktur deteksi deepfake nasional. Alat seperti watermarking masih dalam tahap wajib, bukan otomatis.
Sementara itu, Singapura punya AI Verify—toolkit open-source untuk tes bias, deepfake, dan keamanan.
Uni Eropa mewajibkan machine-readable marking yang bisa dideteksi secara otomatis. Jepang mendorong R&D untuk deteksi sintetis content.
Teknologi kita masih bergantung impor, tanpa standar nasional. Akibatnya, deepfake menyebar sebelum terdeteksi.
Dalam kolom lain, "Menyambut Musim Semi AI di Indonesia" (30 Juni 2025), penulis sudah memperingatkan: "Potensi penyalahgunaan AI untuk kejahatan, seperti deepfake, disinformasi atau amplifikasi konten negatif, juga menjadi ancaman... pemerintah perlu segera merampungkan regulasi AI berbasis nilai-nilai Pancasila."
Sayangnya, hingga Februari 2026, kita masih dalam "perdebatan regulasi yang berkepanjangan", seperti yang saya kritik dalam tulisan terbaru.
Prof. Dr. Ahmad M Ramli, Guru Besar Cyber Law dan Regulasi Digital Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, juga menyoroti isu serupa dalam tulisannya di Kompas.com.
Dalam artikel "Ketiadaan Regulasi Picu Kejahatan Berbasis AI" ia menyatakan: "Ketiadaan regulasi yang komprehensif memicu maraknya kejahatan berbasis AI, termasuk deepfake dan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat."
Selain itu, dalam konteks regulasi digital yang lebih luas, Prof. Ramli pernah menekankan pentingnya kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana tercermin dalam diskusi tentang cyber law dan digital policy di kolomnya.
Rekomendasi
Bagi pelaku industri (terutama keuangan dan strategis). Sektor keuangan adalah target empuk deepfake: penipuan identitas sintetis, manipulasi transaksi, hingga serangan deepfake pada video conference direksi.
Dalam "Cyber Alarm: Tiga Prioritas Mendesak ICT Perbankan Indonesia 2026" (2 Januari 2026), saya menyerukan tiga langkah mendesak:
- Adopsi AI untuk pertahanan, bukan hanya serangan: Gunakan model deteksi deepfake real-time pada sistem KYC dan video verification.
- Mandatory cybersecurity insurance: Seperti yang dilakukan Korea Selatan untuk fintech, agar kerugian tidak hanya ditanggung nasabah.
- Kolaborasi antar-bank: Bangun shared threat intelligence platform berbasis AI untuk mendeteksi pola deepfake secara kolektif.
Bagi industri strategis (energi, pertahanan, infrastruktur kritis), saatnya menerapkan "zero-trust architecture" yang memverifikasi setiap input digital—termasuk suara dan video—dengan biometrik multi-faktor dan watermarking internal.
Selain itu, perlu langkah cepat secara nasional periode 2026-2027.
Pertama, regulasi:
- Percepat Perpres AI menjadi undang-undang pada pertengahan 2026.
- Bangun kerangka tata kelola AI nasional yang wajib diikuti BUMN dan platform besar, dengan pendekatan yang praktis dan operasional.
- Masukkan klausul sanksi progresif (denda + blokir permanen) untuk penyedia AI yang lalai.
Kedua, People:
- Kampanye nasional "Kenali Deepfake" via Kemendikdasmen serta Komdigi, mulai dari SD.
- Pelatihan wajib untuk 10.000 guru dan aparat desa dalam 12 bulan.
Ketiga, Process:
- Bentuk National AI Safety Task Force di bawah Kemenkomdigi dengan wewenang koordinasi lintas kementerian.
- Buat portal pelaporan deepfake 24/7 dengan SLA 24 jam takedown.
Keempat, Technologi:
- Kembangkan toolkit nasional berbasis open-source untuk menguji bias, deepfake, dan keamanan AI.
- Wajibkan semua platform besar terapkan watermark otomatis mulai 2027.
Bagi pengguna individual, Anda tak perlu ahli untuk melindungi diri, cukup lakukan ini:
- Selalu verifikasi sumber: Jika ada video atau suara yang mencurigakan, cross-check dengan minimal dua platform independen.
- Aktifkan pengaturan privasi ketat di aplikasi AI dan medsos: Jangan pernah bagikan foto atau rekaman suara berkualitas tinggi yang bisa digunakan untuk training model.
- Gunakan tools deteksi gratis: Contohnya Hive Moderation atau Microsoft Video Authenticator.
- Laporkan segera: Aduankonten.komdigi.go.id atau polisi siber jika menjadi korban.
Pada akhirnya, Indonesia bukan negara lemah. Indonesia pernah memimpin ASEAN dalam regulasi data pribadi (UU PDP).
Namun, era "Deepfake AI 2026" menuntut lebih: bukan hanya regulasi, melainkan revolusi kesadaran digital yang saya sebut sebagai "keberanian politik untuk transformasi total".
Menariknya, survei Sharing Vision juga menunjukkan optimisme: lebih dari 60 persen responden meyakini bahwa teknologi AI akan digunakan secara luas di berbagai bidang dalam tiga tahun ke depan.
Ini adalah peluang sekaligus tantangan. Jika kita gagal mengatur dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI, maka 2026 bisa menjadi tahun di mana kepercayaan publik runtuh—bukan karena virus, tapi karena gambar dan suara yang tak lagi bisa dipercaya.
Namun, jika kita berhasil, maka Indonesia bisa menjadi teladan Asia Tenggara: negara yang tak hanya mengadopsi AI, tapi juga menjinakkannya dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapkah kita?, melainkan kapan kita mulai?
(Artikel ini disusun berdasarkan analisis terkini hingga 16 Februari 2026, termasuk kasus Grok AI, regulasi global, survei Sharing Vision Desember 2025 (2.442 responden), dan kolom-kolom penulis serta Prof. Dr. Ahmad M Ramli di Kompas.com. Terima kasih terkhusus pada Prof. Dr. Ahmad Ramli (Fakultas Hukum, UNPAD) dan Prof. Dr. Topo Santoso (Fakultas Hukum, UI) dan Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto (Fakultas Hukum, UNPAD), serta Ir. Budi Rahardjo, Ph. Dn (Dosen STEI ITB) yang banyak menginspirasi penulis)