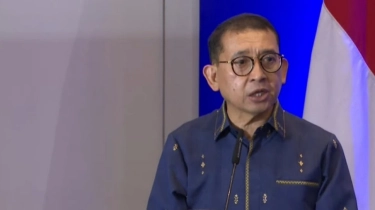Puasa dan Katarsis Politik
PUASA pada hakikatnya bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan latihan spiritual untuk menata kembali relasi manusia dengan dirinya sendiri.
Al-Qur’an menegaskan: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 183).
Kata kunci dari ayat ini adalah takwa: kemampuan mengendalikan diri di hadapan godaan, kepentingan, dan hasrat berlebihan.
Puasa melatih manusia untuk tidak tunduk pada dorongan instingtif yang jika dibiarkan akan berkembang menjadi kerakusan, keserakahan, dan dominasi atas yang lain.
Ayat lain menegaskan dimensi moral puasa: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan” (QS. Al-A’raf: 31). Spirit anti-ekses ini mengandung pesan sosial-politik yang kuat.
Dalam kehidupan publik, kerusakan sering lahir bukan karena kebutuhan, melainkan karena ketamakan. Kekuasaan yang awalnya instrumen pelayanan berubah menjadi alat akumulasi.
Jabatan yang seharusnya amanah berubah menjadi sarana memperkaya diri dan kelompok. Puasa, dalam makna terdalamnya, adalah terapi terhadap mentalitas berlebih itu.
Karena itu, puasa sejatinya adalah proses katarsis—pembersihan batin dari ego, ambisi tak terkendali, dan rasa memiliki yang berlebihan terhadap kekuasaan.
Ia mengembalikan manusia pada kesadaran dasar: bahwa semua yang dimiliki bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Heroisme Jokowi dan Teka-teki Gibran
Tanpa dimensi spiritual seperti ini, politik mudah terperosok menjadi arena kompetisi nafsu. Dengan puasa, manusia diajak keluar dari logika “menguasai” menuju etika “mengabdi”.
Korupsi, Oligarki, dan Krisis Moral Politik
Realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa krisis utama bukan semata kelemahan sistem, melainkan krisis pengendalian diri para pelaku kekuasaan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2025. Angka ini turun 3 poin dari tahun lalu, yaitu di angka 37, menempati peringkat 109 dari 180 negara.
Angka tersebut menunjukkan satu fakta: masalah struktural masih kuat. Bahkan laporan terbaru menunjukkan kecenderungan melemahnya pengawasan publik, meningkatnya praktik suap dan nepotisme, serta kekhawatiran terhadap menurunnya efektivitas mekanisme pencegahan korupsi.
Korupsi hari ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai kejahatan individual. Ia terhubung dengan fenomena yang lebih luas: oligarki.
Konsentrasi kekayaan dan pengaruh ekonomi pada segelintir kelompok telah mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat.
Relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan modal menciptakan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan negara berisiko lebih mencerminkan kepentingan elite dibanding kepentingan rakyat luas.
Secara ekonomi-politik, oligarki bekerja melalui tiga mekanisme utama: pembiayaan politik yang mahal, kontrol terhadap sumber daya strategis, dan pengaruh terhadap regulasi.
Biaya kontestasi yang tinggi mendorong ketergantungan kandidat pada pemodal besar. Ketika kekuasaan diperoleh, politik balas budi menjadi sulit dihindari.
Di sinilah puasa menemukan relevansinya sebagai metafora politik: kemampuan menahan diri dari godaan timbal balik antara kekuasaan dan uang.
Tanpa disiplin moral, demokrasi dapat berubah menjadi prosedur formal yang dikendalikan oleh kepentingan sempit.
Baca juga: Saatnya Memuliakan Pokok, Bukan Tokoh
Korupsi merusak kepercayaan publik, sementara oligarki menggerus kesetaraan kesempatan. Keduanya bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan etika kekuasaan—persoalan tentang kemampuan menahan diri, yang justru menjadi inti dari ibadah puasa.
Hukum, Etika Kekuasaan, dan Puasa
Secara normatif, Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk membersihkan politik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar pidana yang tegas terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen untuk penindakan dan pencegahan.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan larangan konflik kepentingan.
Di bidang politik, regulasi pembiayaan partai dan kampanye dimaksudkan untuk mengurangi dominasi modal besar dalam proses demokrasi.
Namun, pengalaman menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup. Penegakan hukum membutuhkan integritas aparat, sementara integritas membutuhkan fondasi etika.
Tanpa transformasi moral, regulasi mudah dilemahkan melalui kompromi politik, revisi normatif, atau praktik informal.
Di sinilah puasa menjadi relevan bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi sebagai etos kebangsaan.
Puasa mengajarkan tiga nilai yang penting bagi politik bersih. Pertama, pengendalian diri terhadap godaan materi.
Kedua, empati sosial terhadap penderitaan rakyat, karena rasa lapar membuka kesadaran tentang ketimpangan.
Ketiga, kesadaran akuntabilitas transenden—bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi moral yang melampaui pengawasan manusia.
Baca juga: Paspor, Amanah Publik, dan Sensitivitas Awardee
Jika nilai-nilai ini diinternalisasi oleh para pemegang kekuasaan, maka politik tidak lagi sekadar kompetisi kepentingan, tetapi menjadi ruang pelayanan publik.
Katarsis yang dihasilkan puasa dapat menjadi energi moral untuk memperkuat gerakan antikorupsi, mempersempit ruang oligarki, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
Pada akhirnya, bangsa tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga manusia yang mampu menahan diri.
Puasa mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh moral akan berubah menjadi alat penindasan. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan dengan kesadaran spiritual dapat menjadi sarana keadilan.
Karena itu, puasa harus dimaknai lebih luas sebagai gerakan pembersihan: membersihkan hati dari keserakahan, membersihkan politik dari korupsi, dan membersihkan negara dari dominasi kepentingan sempit.
Katarsis spiritual yang lahir dari puasa semestinya mengalir menjadi katarsis sosial—mendorong lahirnya kepemimpinan yang sederhana, kebijakan yang adil, dan tata kelola transparan.
Bangsa ini tidak kekurangan hukum, tetapi sering kekurangan pengendalian diri. Di tengah godaan kekuasaan dan kekayaan yang semakin besar, puasa menjadi pengingat paling mendasar: bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah kemampuan menguasai, melainkan kemampuan menahan diri.
Maka berpuasalah—bukan hanya dari makan dan minum, tetapi dari keserakahan, dari penyalahgunaan kewenangan, dan dari hasrat menguasai tanpa batas.
Dengan puasa seperti itu, kita tidak hanya membersihkan diri, tetapi juga membersihkan politik, merawat demokrasi, dan menegakkan martabat bangsa serta negara.