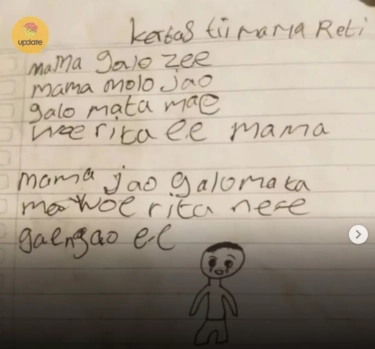Board of Peace: Antara Mimbar Ulama dan Meja Diplomasi (Bagian I)
SUASANA Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa itu, terasa berbeda dari biasanya karena dipenuhi oleh wajah-wajah yang merepresentasikan kekuatan moral bangsa ini.
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan mengundang pimpinan ormas Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia untuk duduk satu meja membicarakan isu yang sangat sensitif.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan upaya komunikasi politik tingkat tinggi terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Kita melihat sosok-sosok penting seperti Kiai Cholil Nafis hingga Gus Ipul hadir mendengarkan paparan langsung dari Kepala Negara mengenai strategi di Gaza.
Langkah ini jelas menunjukkan bahwa Presiden sangat memahami betapa isu Palestina bukan lagi sekadar isu luar negeri semata bagi publik Indonesia.
Kehadiran para tokoh agama ini memberikan sinyal bahwa pemerintah membutuhkan legitimasi moral sebelum melangkah lebih jauh ke dalam lumpur panas geopolitik Timur Tengah.
Ini adalah manajemen persepsi yang rapi untuk memastikan bahwa langkah kaki Indonesia di panggung dunia tidak tersandung oleh kerikil di halaman rumah sendiri.
Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden
Keputusan untuk merangkul para ulama di tahap awal ini memang cerdas jika dilihat dari kacamata stabilitas politik domestik yang seringkali mudah bergejolak.
Kita harus mengakui bahwa isu Palestina memiliki daya ledak emosional yang luar biasa di kalangan akar rumput sehingga setiap kebijakan yang menyentuhnya harus dikelola dengan kehati-hatian tingkat tinggi.
Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa narasi "bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat" bisa menjadi bola liar yang digoreng menjadi tuduhan lunaknya sikap kita terhadap Barat.
Penjelasan langsung kepada para pemimpin umat bertujuan membangun benteng pertahanan narasi sebelum kritik-kritik tajam bermunculan dari mimbar-mimbar masjid.
Dengan mendapatkan anggukan kepala atau setidaknya pemahaman dari para kiai, pemerintah merasa memiliki tiket emas untuk melaju di jalur diplomasi yang diinisiasi di Davos tersebut.
Strategi merangkul key opinion leaders ini efektif untuk meredam potensi kegaduhan yang bisa mengganggu konsentrasi pemerintah.
Namun, ada satu pertanyaan besar yang tersisa di benak saya ketika melihat komposisi tamu yang hadir di ruangan itu.
Apakah forum tersebut sudah cukup untuk membedah kompleksitas jebakan dan peluang yang ada di dalam Board of Peace secara komprehensif?
Diplomasi bukan sekadar niat baik
 Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026)Kita sering lupa bahwa diplomasi modern tidak bisa hanya dijalankan dengan bermodalkan semangat persaudaraan atau dukungan moral semata tanpa hitungan matematis yang dingin.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah petinggi organisasi masyarakat (ormas) Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026)Kita sering lupa bahwa diplomasi modern tidak bisa hanya dijalankan dengan bermodalkan semangat persaudaraan atau dukungan moral semata tanpa hitungan matematis yang dingin.
Isu Palestina adalah contoh klasik dari isu yang memiliki dua wajah sekaligus, yaitu wajah domestik yang penuh emosi dan wajah internasional yang penuh kalkulasi.
Baca juga: Menyoal Dukungan PBNU pada Board of Peace
Pemerintah tampaknya sedang berupaya menyeimbangkan neraca politik di mana negosiasi terjadi di dua meja sekaligus, yaitu meja perundingan global dan meja konstituen domestik.
Langkah mengundang ormas Islam jelas merupakan upaya memenangkan pertarungan di level domestik untuk mengamankan dukungan publik agar satu suara dengan pemerintah.
Padahal, tantangan sesungguhnya yang jauh lebih buas dan tidak kenal ampun ada di arena global yang anarkis dan transaksional.
Di sanalah nasib kredibilitas Indonesia dipertaruhkan di hadapan kekuatan-kekuatan besar yang memiliki agenda tersembunyi di balik jubah perdamaian.
Tanpa persiapan teknis yang matang, dukungan domestik sekuat apapun tidak akan mampu menolong kita jika kita salah langkah dalam manuver diplomatik yang rumit.
Fenomena yang terjadi di Istana kemarin, menunjukkan gejala di mana pendekatan komunikatif lebih diutamakan daripada pendekatan substansial dalam merumuskan kebijakan luar negeri.
Publik disuguhi pemandangan yang menyejukkan hati di mana umara dan ulama bersatu. Namun, kerangka kerja dari Board of Peace itu sendiri belum terbedah secara detail dan mendalam.
Kita perlu ingat bahwa Board of Peace adalah inisiatif yang lahir dari rahim pemerintahan Donald Trump yang dikenal sangat pragmatis dan seringkali bias dalam memandang konflik Timur Tengah.
Mengandalkan restu ulama saja tidak akan cukup untuk membekali para negosiator kita dalam menghadapi tekanan lobi asing atau manuver negara-negara adidaya.
Diperlukan lebih dari sekadar husnuzan atau prasangka baik untuk terjun ke dalam kawah candradimuka diplomasi global yang penuh dengan tipu daya dan kepentingan.
Seharusnya, euforia dukungan ormas ini tidak membuat kita terlena dan melupakan kewajiban untuk melakukan uji tuntas atau due diligence yang ketat terhadap proposal ini.
Saya melihat adanya ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan antara bobot politis dan bobot teknis dalam langkah awal pemerintah menyikapi inisiatif global ini.
Para tokoh agama yang hadir tentu memiliki kapasitas mumpuni dalam membimbing umat dan menjaga moral bangsa, tapi mereka bukanlah perancang strategi negara.
Mereka mungkin tidak terbiasa membaca yang tersirat dari draf resolusi atau memahami implikasi hukum dari tanda tangan di atas kertas perjanjian internasional.
Dukungan mereka bersifat normatif dan didasarkan pada harapan tulus agar penderitaan saudara kita di Gaza segera berakhir dan perdamaian terwujud.
Namun, harapan tulus itu bisa dimanfaatkan oleh aktor global lain jika Indonesia tidak memiliki "gigi" dan kecerdikan dalam bernegosiasi di dalam dewan tersebut.
Kita membutuhkan pisau analisis yang jauh lebih tajam daripada sekadar himbauan moral untuk membedah anatomi konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun ini.
Absennya para teknokrat dan pemikir strategis dalam pertemuan awal ini menyisakan celah yang bisa menjadi titik lemah diplomasi kita.
Membutuhkan "Brain Trust" yang solid
Di sinilah letak urgensi untuk melibatkan kalangan profesional yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami dinamika hubungan antarnegara dan keamanan global.
Seharusnya, sebelum atau setidaknya bersamaan dengan penggalangan dukungan ormas, Presiden mengajak duduk para pemikir strategis yang paham betul peta lapangan.
Indonesia memiliki gudang pemikir yang luar biasa, mulai dari diplomat senior yang kenyang pengalaman, pengamat pertahanan, hingga ahli hukum internasional.
Baca juga: Board of Peace dan Dilema Diplomasi Indonesia
Merekalah yang seharusnya diajak berdebat keras di ruang tertutup untuk membedah naskah dan roadmap dari Board of Peace tersebut secara brutal dan jujur.
Kelompok ahli atau yang sering disebut sebagai brain trust ini memiliki peran krusial untuk memberikan pandangan pembanding yang objektif.
Mereka bisa memberikan simulasi skenario terburuk atau worst-case scenario yang mungkin tidak terpikirkan oleh para politisi maupun para ulama yang hadir di Istana.
Bayangkan jika Indonesia masuk ke dalam dewan tersebut tanpa bekal analisis mendalam mengenai pergeseran aliansi keamanan di Timur Tengah pasca-konflik Gaza terbaru.
Para pemikir strategis akan mempertanyakan sejauh mana independensi Board of Peace ini dari pengaruh hegemoni satu pihak yang kini kembali berkuasa.
Mereka akan menelisik apakah keterlibatan kita justru akan melegitimasi status quo pendudukan dengan bungkus rekonstruksi yang terlihat manis di permukaan.
Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini jarang muncul dalam forum silaturahmi dengan ormas karena memang bukan di sana letak fokus pembicaraan para kiai kita.
Profesional di bidang ini dilatih untuk menjadi skeptis demi menjaga kepentingan nasional dari potensi kerugian jangka panjang yang tidak terlihat mata telanjang.
Mengabaikan suara kaum intelektual ini sama saja dengan mengirim pasukan ke medan perang tanpa peta intelijen yang akurat.
Keberanian Presiden Prabowo harus diimbangi dengan kalkulasi yang presisi agar kita tidak sekadar menjadi penggembira.
Kebijakan luar negeri yang sound dan prudent haruslah merupakan hasil perkawinan antara visi politik pemimpin dan analisis teknokratis para ahlinya.
Jika pemerintah hanya berhenti pada konsolidasi ormas Islam, maka kita sedang terjebak dalam diplomasi simbolik yang mengutamakan kemasan daripada isi.
Publik mungkin akan tenang sesaat. Namun sejarah akan mencatat apakah langkah kita benar-benar membawa dampak konkret bagi perdamaian atau hanya menjadi catatan kaki yang terlupakan.
Kita tidak boleh lupa pengalaman masa lalu di mana niat baik Indonesia seringkali kandas karena kurangnya pemahaman terhadap detail teknis negosiasi di lapangan.
Diplomasi adalah seni dari segala kemungkinan yang membutuhkan penguasaan detail yang sangat rinci dan seringkali melelahkan.
Para praktisi dan pemikir ini adalah orang-orang yang siap memberikan masukan kritis itu untuk negara.
Mengapa sumber daya intelektual yang begitu berharga ini tidak diletakkan di barisan depan dalam proses pengambilan keputusan?
Penting untuk dipahami bahwa kritik ini bukan berarti menafikan peran penting ormas Islam dalam ekosistem diplomasi Indonesia.
Ormas Islam adalah aset soft power terbesar kita yang menjadi bukti bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan di negara ini.
Namun, menempatkan mereka sebagai pilar utama dalam analisis strategi geopolitik adalah kesalahan penempatan sumber daya atau misplacement of resources.
Peran ormas seharusnya berada di hilir sebagai penyambung lidah pemerintah dan pengawal moral, bukan di hulu sebagai penentu kelayakan strategi internasional.
Ketika batas kompetensi ini dikaburkan demi kepentingan optik politik, maka kualitas kebijakan luar negeri kita yang menjadi taruhannya.
Kita membutuhkan arsitektur diplomasi yang kokoh di mana setiap elemen bangsa memainkan peran sesuai dengan kapasitas terbaiknya masing-masing.
Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace membawa konsekuensi bahwa kita akan berinteraksi intensif dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bertolak belakang.
Ini adalah medan ranjau yang sangat licin bagi wakil kita yang selama ini memegang teguh prinsip anti-penjajahan sesuai amanat konstitusi.
Baca juga: Board of Peace dan Ujian Konstitusional Politik Luar Negeri
Para ahli strategi pasti akan langsung menyoroti bagaimana kita menjaga postur diplomasi agar tidak terseret arus normalisasi terselubung yang mungkin menjadi agenda tersembunyi.
Diplomat senior akan mengingatkan tentang preseden-preseden sebelumnya di mana forum multilateral sering digunakan untuk menekan negara berkembang agar melunakkan sikap prinsipilnya.
Diskusi semacam ini membutuhkan kedalaman literasi sejarah dan kepekaan terhadap nuansa bahasa diplomatik yang seringkali manipulatif.
Hal-hal subtil seperti ini tidak akan tertangkap radar jika diskusi di Istana hanya berkutat pada dukungan moral semata. Oleh karena itu, pintu Istana harus segera dibuka untuk para teknokrat.
Kita harus jujur mengakui bahwa diplomasi di era disrupsi global saat ini tidak bisa lagi dijalankan dengan gaya konvensional atau business as usual.
Kompleksitas konflik di Gaza melibatkan proksi perang, perang siber, hingga pertarungan narasi di media global yang sangat canggih dan multidimensi.
Mengandalkan intuisi politik semata tanpa didukung data riset yang valid dari para pakar adalah kecerobohan yang mahal harganya.
Para pemikir kita memiliki jejaring internasional yang bisa dimanfaatkan untuk menggali informasi yang tidak tersedia di saluran resmi pemerintah atau media massa.
Mereka bisa menjadi mitra berpikir atau sparring partner yang tangguh bagi Presiden untuk menguji seberapa kuat argumen dan posisi tawar Indonesia.
Sinergi antara otoritas politik dan otoritas keilmuan inilah yang akan melahirkan kebijakan yang tidak hanya populer, tetapi juga efektif.
Tag: #board #peace #antara #mimbar #ulama #meja #diplomasi #bagian