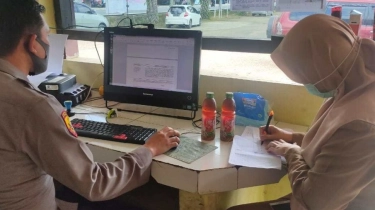Board of Peace dan Ujian Konstitusional Politik Luar Negeri
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu dibaca pertama-tama bukan dari sudut diplomasi global atau euforia peran internasional, melainkan dari kacamata konstitusi.
Dalam negara hukum, terutama negara yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi, setiap langkah politik luar negeri yang strategis tidak boleh dilepaskan dari fondasi yuridis yang jelas.
Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan secara eksplisit: “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”
Frasa membuat perdamaian bukanlah istilah simbolik, melainkan norma konstitusional yang bersifat operasional.
Artinya, setiap tindakan Presiden yang secara substantif masuk dalam kategori pembuatan perdamaian—baik bilateral maupun multilateral—wajib memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu.
Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 mempertegas bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, menyangkut beban keuangan negara, serta memengaruhi arah politik luar negeri Indonesia, harus mendapat persetujuan DPR.
Norma ini tidak memberi ruang interpretasi longgar. Ia dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances agar kebijakan luar negeri strategis tidak menjadi domain eksklusif kekuasaan eksekutif.
Baca juga: Dewan Narsisme Trump, Asa Indonesia
Isu Palestina—yang menjadi salah satu justifikasi utama keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace—jelas memenuhi seluruh kriteria Pasal 11 ayat (2).
Ia berdampak luas secara politik, moral, dan geopolitik; memengaruhi posisi Indonesia di dunia internasional; dan berpotensi menimbulkan konsekuensi anggaran serta komitmen diplomatik jangka panjang.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam forum perdamaian apa pun yang berkaitan langsung dengan isu Palestina tidak dapat ditempuh hanya melalui keputusan sepihak Presiden.
Dalam konteks ini, persoalannya bukan soal niat baik atau buruk Presiden, melainkan ketaatan pada konstitusi.
Negara hukum tidak menilai kebijakan dari niat, tetapi dari prosedur dan dasar kewenangan. Ketika prosedur konstitusional dilewati, bahkan dengan alasan kemanusiaan, maka preseden yang tercipta justru melemahkan sendi negara hukum itu sendiri.
Kelemahan "Board of Peace"
Board of Peace yang digagas Donald Trump bukan lembaga internasional formal yang dibentuk melalui perjanjian antarnegara yang diratifikasi secara konstitusional.
Ia lebih menyerupai forum politik ad hoc, dengan struktur kekuasaan terpusat, di mana otoritas agenda, keputusan, dan arah kebijakan berada pada satu figur sentral.
Dalam piagamnya, posisi ketua memegang hak veto penuh, termasuk dalam menentukan keanggotaan dan arah program.
Dari sudut pandang UUD NRI 1945, ini menimbulkan problem serius. Ketika Presiden Indonesia bergabung dalam forum semacam itu, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta dialog, tetapi secara implisit ikut mengafirmasi struktur dan logika kekuasaan forum tersebut.
Padahal, konsekuensi politik dan simbolik dari keikutsertaan itu tidak kecil. Indonesia dapat dianggap menyetujui model perdamaian yang bersifat elitis, transaksional, dan sangat bergantung pada kepentingan satu negara besar.
Yang menjadi persoalan konstitusional bukan semata keanggotaan itu sendiri, melainkan mekanisme pengambilannya.
Hingga saat ini, tidak terdapat persetujuan DPR yang secara eksplisit menyetujui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
Tidak pula terdapat undang-undang ratifikasi atau pernyataan resmi DPR yang memberikan mandat politik kepada Presiden untuk masuk ke dalam forum tersebut.
Ini berpotensi bertentangan langsung dengan semangat Pasal 11 UUD 1945. Dalam konstruksi konstitusi Indonesia, Presiden bukan pemegang kedaulatan tunggal dalam urusan perang dan perdamaian.
Baca juga: Soekarno, Dasasila Bandung, dan Anomali Board of Peace
Ia adalah pelaksana mandat konstitusional yang harus bekerja bersama DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.
Apabila praktik semacam ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan pergeseran diam-diam dari "constitutional foreign policy" menuju "executive-driven diplomacy".
Presiden dapat dengan mudah bergabung dalam forum internasional apa pun atas nama perdamaian, tanpa mekanisme akuntabilitas parlementer.
Dalam jangka panjang, ini berbahaya, karena mengaburkan batas antara kebijakan negara dan preferensi politik pribadi seorang Presiden atau rezim.
Masa depan politik luar negeri
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace Trump seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya secara tegas.
Pasal 11 UUD 1945 bukan sekadar norma pasif, melainkan instrumen aktif untuk menjaga agar politik luar negeri tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat.
DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk mempertanyakan dasar hukum, implikasi politik, dan konsekuensi strategis dari keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Bukan untuk menghambat diplomasi, melainkan untuk memastikan bahwa diplomasi dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi.
Tanpa sikap DPR, kebijakan luar negeri Indonesia berisiko terjebak dalam logika personalisasi kekuasaan global, di mana hubungan antarnegara direduksi menjadi hubungan antarfigur.
Lebih jauh, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas Indonesia juga berpotensi tereduksi.
Bebas aktif bukan berarti bebas dari konstitusi. Justru kebebasan diplomasi Indonesia harus dibingkai oleh hukum dasar negara, agar tidak berubah menjadi fleksibilitas tanpa arah dan tanpa legitimasi.
Baca juga: Mengoreksi Darah Penghabisan Kapolri, Siapa Sanggup?
Isu Palestina, yang menjadi alasan moral utama keikutsertaan Indonesia, sejatinya justru menuntut kehati-hatian konstitusional yang lebih tinggi.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina selama ini kuat karena konsistensi Indonesia pada prinsip hukum, keadilan, dan multilateralisme.
Jika dukungan itu kini ditempuh melalui forum yang tidak jelas mandat konstitusionalnya, maka posisi moral Indonesia justru bisa melemah.
Pada titik inilah, Board of Peace Trump menjadi ujian bagi keteguhan Indonesia sebagai negara hukum.
Apakah kita akan menempatkan konstitusi sebagai panglima dalam politik luar negeri, atau membiarkan kebijakan strategis ditentukan oleh kalkulasi jangka pendek dan simbolisme global?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya berada di tangan Presiden, tetapi juga di DPR sebagai penjaga kedaulatan rakyat.
Diamnya DPR dalam isu ini bukan netralitas, melainkan pengabaian terhadap mandat konstitusional.
Dan dalam negara hukum, pengabaian konstitusi—dalam bentuk apa pun—selalu memiliki harga politik dan sejarah yang mahal.
Tag: #board #peace #ujian #konstitusional #politik #luar #negeri