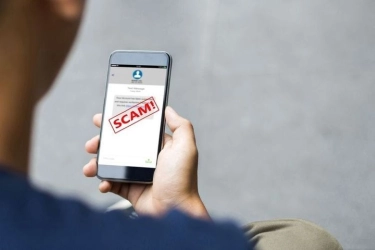Presidential Threshold Nol Persen dan Demokrasi yang Diuji dari Awal
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menjadikan presidential threshold (PT) nol persen adalah koreksi struktural penting dalam arsitektur demokrasi elektoral Indonesia.
Ia bukan sekadar perubahan teknis aturan main, melainkan pergeseran filosofi mendasar tentang siapa yang berhak menawarkan kepemimpinan nasional.
Dari demokrasi yang disaring ketat oleh elite partai besar, menuju demokrasi yang membuka peluang lebih luas bagi aktor politik lain.
Dalam konteks Pilpres, keputusan ini membuka ruang bagi lahirnya calon-calon alternatif, sekaligus menguji kedewasaan partai politik, parlemen, dan publik secara bersamaan.
Demokrasi diuji bukan hanya pada hari pemungutan suara, tetapi sejak desain awal kompetisinya.
Dengan PT nol persen, setiap partai politik yang lolos verifikasi pemilu pada prinsipnya memiliki hak konstitusional untuk mempersiapkan dan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Tidak lagi ada pagar tinggi yang hanya bisa dilompati oleh segelintir partai besar melalui akumulasi kursi parlemen.
Logika “besar dulu baru boleh mencalonkan” digeser menjadi “lolos verifikasi pemilu dulu, lalu berkompetisi secara terbuka”.
Dari putusan MK ke medan politik nyata
Namun, justru di sinilah babak paling krusial dimulai. Putusan MK adalah teks hukum, tetapi terjemahan operasionalnya sangat ditentukan oleh pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR.
Mekanisme pencalonan, syarat administratif, hingga desain tahapan seleksi akan menentukan apakah PT nol persen benar-benar menjadi pintu masuk demokrasi, atau sekadar jendela sempit yang tampak terbuka, tapi sulit dilewati.
Karena itu, pengawalan publik terhadap revisi UU Pemilu menjadi keharusan, bukan pilihan.
Dalam teori constitutional politics, sebagaimana dikemukakan oleh Giovanni Sartori, aturan main pemilu sering kali lebih menentukan kualitas demokrasi dibanding hasil pemilunya sendiri.
Demokrasi bisa tampak prosedural, tetapi cacat secara substansi bila desainnya dikunci sejak awal.
Secara politik, sulit dibantah bahwa putusan ini berpotensi merugikan partai-partai besar. Daya tawar mereka dalam kontestasi Pilpres menjadi lebih lemah karena tidak lagi memegang kunci tunggal pencalonan.
Dalam kajian politik, ini dapat dibaca sebagai pelemahan gatekeeping power—kekuasaan untuk menyaring siapa yang boleh dan tidak boleh masuk gelanggang.
Selama ini, partai besar berfungsi seperti operator bandara, yaitu hanya pesawat tertentu yang diizinkan mendarat. Kini, landasan dibuka untuk lebih banyak penerbangan. Konsekuensinya, lalu lintas politik menjadi lebih ramai, lebih berisik, tetapi juga lebih kompetitif.
Dari sinilah kita bisa memahami kemunculan partai-partai baru seperti Gerakan Rakyat, Gema Bangsa, serta partai-partai kecil yang gagal lolos Pemilu 2024. Mereka melihat peluang yang lebih cerah menuju Pemilu 2029.
Kehadiran mereka bukan anomali, melainkan respons rasional terhadap struktur peluang yang berubah.
Jika sebelumnya peluang mengusulkan calon presiden nyaris mustahil bagi partai kecil, kini peluang itu—meski tetap berat—setidaknya eksis.
Dalam istilah ilmu politik, ini dikenal sebagai political opportunity structure. Ketika aturan berubah, aktor baru akan muncul untuk menguji celah yang tersedia. Politik, dalam pengertian ini, selalu adaptif terhadap struktur.
Idealnya, PT nol persen menjadi ruang bagi masyarakat untuk disuguhi alternatif calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam.
Demokrasi tidak hanya soal memilih, tetapi soal memiliki pilihan yang bermakna. Robert A. Dahl menyebut pluralitas pilihan sebagai syarat minimal demokrasi yang inklusif.
Pilihan yang terlalu sempit justru mereduksi esensi kompetisi. Dalam analogi sederhana, pemilu tanpa alternatif yang cukup ibarat pasar yang hanya menjual satu merek beras: rakyat tetap bisa membeli, tetapi tidak pernah benar-benar memilih.
Tentu, keterbukaan ini tidak berarti kebebasan tanpa batas. Mekanisme pencalonan tetap perlu dirancang agar tidak liar dan serampangan.
Ada kebutuhan untuk menjaga kualitas kandidat, kapasitas kepemimpinan, dan rasionalitas jumlah pasangan calon.
Namun, batasan itu seharusnya bersifat administratif dan substantif, bukan politis. Intinya jelas, yaitu partai besar tidak lagi boleh “mengunci” calon potensial hanya karena mereka didukung partai kecil.
Dalam konteks ini, wacana koalisi permanen yang digulirkan oleh partai-partai koalisi pemerintah patut dicermati secara kritis.
Argumen ini muncul bersamaan dengan lemparan wacana Pilkada tidak langsung, sehingga sulit dilepaskan dari kepentingan jangka panjang elite.
Koalisi permanen berpotensi menyempitkan ruang lahirnya figur alternatif capres dan cawapres. Jika logika ini diterapkan, Pilpres berisiko mengembalikan pola lama melalui pintu belakang dengan kompetisi dipersempit bukan oleh aturan formal, tetapi oleh kesepakatan elite.
Pilpres 2029 dan politik yang dimulai lebih awal
Karena model PT nol persen ini baru akan diterapkan pada Pilpres 2029, wajar jika kontestasi dan seleksi calon dimulai sejak sekarang. Ini bukan politik terlalu dini, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang lebih terbuka.
Artinya, semakin panjang waktu pengenalan kandidat, semakin besar peluang publik untuk menilai kapasitas, rekam jejak, dan gagasan secara rasional.
Dalam posisi ini, petahana—Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—memiliki peran strategis.
Mereka bekerja maksimal, menjalankan mandat pemerintahan, dan memberikan hasil terbaik bagi rakyat.
Sementara itu, calon-calon penantang seharusnya hadir sebagai pengoreksi yang fair dan adil, bukan sekadar oposisi emosional. Kritik programatik dan adu gagasan menjadi menu utama demokrasi.
Menariknya, lemahnya oposisi di parlemen justru bisa membuka ruang oposisi alternatif di luar parlemen. Dalam ilmu politik, ini dikenal sebagai extra-parliamentary opposition.
Selama dilakukan dalam koridor hukum dan etika demokrasi, kehadiran kandidat di luar parlemen dapat memperkaya wacana dan menyeimbangkan kekuasaan. Arena kompetisi tidak lagi tunggal, tetapi menyebar ke ruang publik yang lebih luas.
Harapannya sederhana, tapi fundamental. Sejak awal, publik ditawarkan nama-nama alternatif calon presiden dan wakil presiden. Bukan untuk memilih secara instan, melainkan untuk mengamati, menguji, dan menilai melalui maraton kelayakan.
Dalam analogi olahraga, Pilpres 2029 bukan sprint 100 meter, melainkan lomba lari jarak jauh.
PT nol persen, pada akhirnya, adalah ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Ia membuka pintu, tetapi tidak menjamin siapa yang layak masuk.
Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana DPR menyusun UU Pemilu, bagaimana partai politik bersikap, dan bagaimana publik menjaga nalar kritisnya.
Demokrasi tidak pernah selesai; ia hanya terus diuji oleh keberanian membuka pilihan dan kebijaksanaan mengelolanya.
Tag: #presidential #threshold #persen #demokrasi #yang #diuji #dari #awal