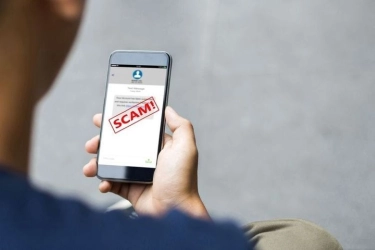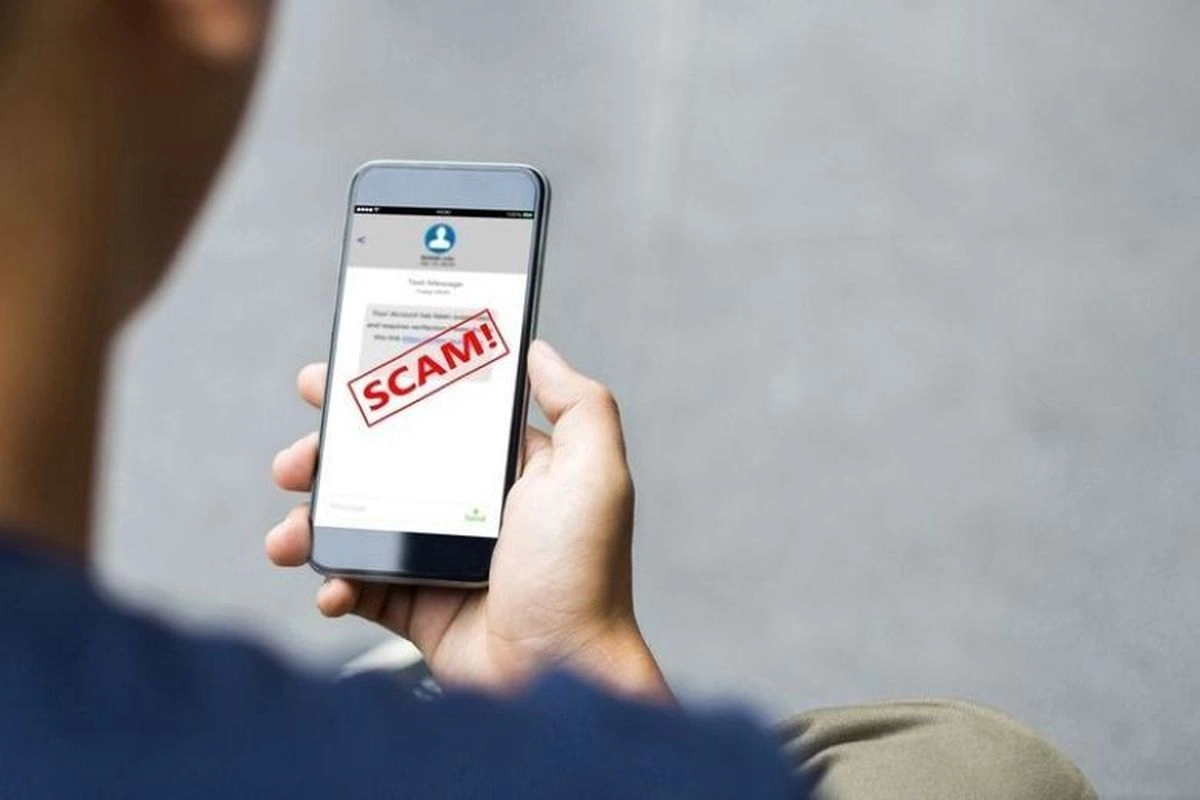
Rp 9,1 Triliun yang Hilang, Negara Terlambat Sadar
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap angka yang mencengangkan, kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai Rp 9,1 triliun hanya dalam rentang sekitar satu tahun. Angka itu belum termasuk kerugian fraud di ekosistem pembayaran yang mencapai Rp 4,6 triliun hingga Agustus 2025.
Namun, sesungguhnya yang lebih mengkhawatirkan bukanlah besarnya angka kerugian itu. Melainkan satu pertanyaan, ke mana negara selama ini? Sebab penipuan digital bukanlah fenomena baru. Ia bukan muncul kemarin sore. Ia tumbuh, membesar, dan beranak pinak di ruang digital Indonesia selama bertahun-tahun, nyaris tanpa kendali yang serius, tanpa pengawasan yang memadai, dan tanpa sistem perlindungan yang berpihak kepada masyarakat sebagai pengguna layanan digital.
Angka Rp 9,1 triliun itu bukan sekadar statistik. Ia adalah akumulasi dari kegagalan tata kelola ruang digital. Ironisnya, negara selama ini terlihat sangat aktif membuat aturan di ruang digital: mulai dari regulasi konten, pembatasan media sosial, pengawasan ekspresi warga, hingga rencana-rencana registrasi yang semakin ketat. Namun ketika ruang digital menjadi ladang kejahatan yang merugikan rakyat triliunan rupiah, negara tampak gagap.
Masyarakat dipaksa melek digital. Dipaksa bertransaksi secara elektronik. Dipaksa masuk ke ekosistem pembayaran digital. Dipaksa mendaftar kartu SIM dengan NIK. Dipaksa menyerahkan data pribadi ke berbagai platform. Tetapi ketika data itu bocor, disalahgunakan, atau menjadi pintu masuk penipuan, negara justru lambat bertindak. Di sinilah letak persoalan seriusnya, regulasi lebih berorientasi pada kontrol, bukan perlindungan.
Terkait pernyataan Menkomdigi yang disampaikan dalam peluncuran Peraturan Menteri tentang Registrasi Biometrik. Apakah benar akar persoalan penipuan digital ada pada kurangnya biometrik? Ataukah ini sekadar respons administratif yang terlambat terhadap kegagalan pengawasan bertahun-tahun?
Sebab praktik penipuan digital yang marak hari ini bukan terjadi karena pelaku tidak bisa diidentifikasi. Banyak kasus justru menggunakan rekening bank resmi, nomor telepon yang terdaftar, akun pembayaran yang tervalidasi, bahkan memanfaatkan celah di sistem perbankan dan fintech itu sendiri. Masalah utamanya bukan identitas. Masalah utamanya adalah pengawasan ekosistem digital yang longgar dan lemahnya tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.
Narasi yang sering muncul setiap ada penipuan digital selalu sama, masyarakat harus hati-hati, jangan mudah percaya, tingkatkan literasi digital. Padahal, dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum siber modern, beban utama perlindungan tidak boleh diletakkan di pundak pengguna, tetapi pada penyelenggara sistem dan negara sebagai regulator.
Jika penipuan bisa berlangsung masif di ekosistem pembayaran digital, berarti ada celah sistemik. Jika rekening penampung dana kejahatan bisa aktif berhari-hari tanpa diblokir, berarti ada kelalaian pengawasan. Jika nomor telepon penipu bisa bertahan lama, berarti ada kegagalan verifikasi. Ini bukan lagi soal kelengahan individu. Ini adalah kelengahan sistem.
Baca juga: Menkomdigi: Kerugian Masyarakat akibat Penipuan Digital Rp 9,1 Triliun
Negara Baru Bereaksi
Angka Rp 9,1 triliun itu seperti alarm keras yang baru membangunkan negara dari tidur panjangnya di ruang digital. Namun alarm ini berbunyi setelah kerugian terjadi, bukan sebelum. Artinya, pendekatan negara selama ini lebih reaktif daripada preventif. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, regulasi fintech, regulasi perbankan digital semuanya sudah ada. Yang tidak ada adalah keseriusan implementasi dan koordinasi antar lembaga.
Ruang digital Indonesia terlalu lama dibiarkan tumbuh liar, tanpa pagar pengaman yang kuat. Tidak mungkin penipuan digital sebesar ini terjadi tanpa kebocoran dan peredaran data pribadi secara masif. Nama, nomor telepon, NIK, alamat, bahkan pola transaksi, semuanya menjadi amunisi bagi pelaku kejahatan. Dan ini terjadi di negara yang sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi.
Pertanyaannya, berapa banyak sanksi tegas yang sudah dijatuhkan kepada penyelenggara sistem yang lalai menjaga data? Hampir tidak terdengar. Yang terdengar justru rencana pengetatan registrasi bagi masyarakat. Registrasi biometrik mungkin terdengar canggih. Namun jika kultur pengawasan, penegakan hukum, dan tanggung jawab penyelenggara sistem tidak dibenahi, maka biometrik hanya akan menambah tumpukan data baru yang suatu hari berpotensi bocor lagi.
Masyarakat kembali diminta menyerahkan lebih banyak data. Sementara negara belum menunjukkan bahwa data yang lama sudah mampu dijaga dengan baik. Kerugian itu bukan semata-mata ulah penipu. Itu adalah harga dari kelalaian tata kelola digital yang terlalu lama dibiarkan longgar. Ruang digital diperlakukan sebagai ruang ekonomi, tetapi tidak diperlakukan sebagai ruang hukum yang harus dijaga dengan ketat.
Negara terlalu cepat mendorong digitalisasi, tetapi terlalu lambat menyiapkan sistem perlindungannya. Dan kini, setelah triliunan rupiah hilang, barulah regulasi baru diperkenalkan. mengapa harus menunggu sampai Rp 9,1 triliun melayang? Karena yang hilang bukan hanya uang masyarakat. Yang hilang adalah kepercayaan publik pada keamanan ruang digital yang selama ini dipromosikan negara sendiri.
Baca juga: Mayoritas Penipuan Digital Bermula dari Lemahnya Verifikasi Identitas