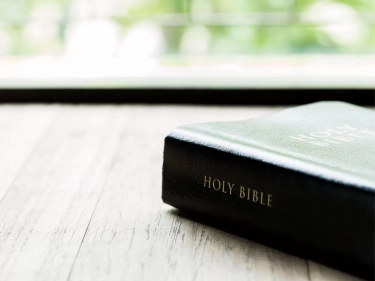Bencana Sumatera dan Paradoks Diplomasi
BENCANA Sumatera pada akhir November 2025, akibat hujan ekstrem yang dipicu anomali iklim global menelan lebih dari seribu korban jiwa, ratusan ribu orang mengungsi dan infrastruktur publik lumpuh.
Ketika air bah meluap dan ribuan warga Sumatera kehilangan rumah, pertanyaan yang segera muncul bukan hanya tentang berapa besar kerusakan dan berapa banyak korban jiwa.
Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mengatasi bencana itu. Tatkala para korban butuh bantuan, para petinggi negeri mementingkan kedaulatan.
Tak pelak lagi, bencana Sumatera segera mengundang perhatian dunia internasional. Bantuan negara sahabat ditolak, kecuali melalui lembaga internasional.
Bencana Sumatera ternyata menampakkan sikap bagaimana negara memaknai kedaulatannya di hadapan penderitaan manusia.
Di titik inilah bencana tidak lagi sekadar peristiwa alam, tetapi berubah menjadi arena perjumpaan, bahkan ketegangan, antara dua narasi besar dalam hubungan internasional: kedaulatan negara dan imperatif kemanusiaan.
Media global dan komunitas internasional menyoroti bencana ini. Bukan hanya karena skalanya, tetapi lebih karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam penanggulangan bencana.
Di sinilah paradoks mulai muncul: ketika solidaritas kemanusiaan dunia mengalir, negara justru menggariskan batas-batasnya.
Sesuai fatsun diplomasi, respons komunitas internasional berupa ucapan belasungkawa sebagai wujud solidaritas.
Negara sahabat menawarkan bantuan. Badan-badan PBB dan organisasi non-pemerintah internasional menyalurkan dukungan logistik, pendanaan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Dalam bahasa Hedley Bull, inilah ekspresi international society: kesadaran kolektif terhadap penderitaan manusia melampaui batas teritorial dan memanggil tanggung jawab bersama (The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 1977)
Namun, ungkapan solidaritas ini tak semua disambut dengan tangan terbuka. Pemerintah Indonesia menolak bantuan bilateral dari negara sahabat dan hanya menerima bantuan melalui lembaga internasional-multilateral.
Keputusan ini menyiratkan pemerintah menarik garis batas yang jelas antara solidaritas dan
derajat keterlibatan negara lain dalam penanganan bencana.
Indonesia melihat kehadiran negara adalah niscaya, terutama sebagai penjaga otoritas, memastikan bahwa kendali atas wilayah dan proses penanganan bencana tetap berada di tangan nasional.
Dalam kaidah hubungan internasional, sikap ini mencerminkan cara pandang klasik tentang kedaulatan sebagai prinsip tertinggi dalam hubungan internasional.
Stephen Krasner berkata kedaulatan bukan hanya soal kontrol teritorial, tetapi juga soal pengakuan atas otoritas politik negara (Sovereignty: Organized Hypocrisy, 1999).
Dalam konteks bencana, kedaulatan sering kali diuji: apakah negara bersedia membuka diri demi kemanusiaan, atau justru menegaskan batas demi menjaga otoritas?
Indonesia, dalam kasus ini, tampaknya secara hati-hati memilih jalan tengah: menerima bantuan, tetapi melalui saluran yang dianggap netral dan tidak mengganggu simbol kedaulatan. Itulah bantuan kemanusiaan multilateral, bukan bilateral.
Lembaga internasional-multilateral dan organisasi kemanusiaan beroperasi dengan logika berbeda. Tidak melulu berpijak pada logika kekuasaan seperti laiknya politik bilateral.
Prinsip humanity dalam bantuan internasional-multilateral menempatkan penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai prioritas utama, meski harus melangkahi batas negara.
Michael Barnett menyebut legitimasi kemanusiaan ini sebagai “otoritas moral” yang memungkinkan aktor non-negara beroperasi di ruang yang secara tradisional dikuasai negara
(Empire of Humanity: A History of Humanitarianism, 2011).
Karena itulah, bantuan multilateral sering lebih mudah diterima: ia hadir bukan sebagai simbol
kekuasaan negara lain, melainkan sebagai perpanjangan dari nurani global.
Bagaimana dengan bantuan bilateral? Bantuan kemanusiaan, betapapun mulianya, tidak pernah sepenuhnya steril dari kepentingan politik.
Joseph Nye mengingatkan, tindakan solidaritas internasional juga membangun soft power—citra, pengaruh, dan kepercayaan.
Tawaran bantuan bilateral dari negara lain, meskipun dibingkai sebagai empati, tetap saja membawa simbol kehadiran dan relasi kekuasaan.
Di sinilah kecurigaan negara penerima sering muncul: apakah bantuan ini murni kemanusiaan, atau juga bagian dari diplomasi politik kekuasaan?
Keputusan Indonesia menolak bantuan bilateral karenanya dapat dibaca sebagai upaya
mengelola dilema tersebut.
Dengan membatasi pintu masuk bantuan, negara berusaha memastikan bahwa tragedi kemanusiaan tidak membuka ruang penetrasi politik.
Sikap ini sekaligus menyampaikan pesan bahwa Indonesia memiliki kapasitas nasional dan tidak berada dalam posisi ketergantungan.
Dalam konteks Global South, pesan ini memiliki bobot simbolik yang kuat, mengingat sejarah panjang intervensi Global North yang sering dijustifikasi atas nama kemanusiaan.
Meski demikian, sikap Indonesia menolak bantuan kemanusiaan bilateral ini menghadirkan paradoks lain.
Pembatasan sumber bantuan berpotensi memengaruhi kecepatan tanggap darurat, terutama ketika bencana terjadi serentak di banyak wilayah.
Ketika sumber daya domestik terbatas, keterbukaan terhadap bantuan eksternal – utamanya dalam konteks bilaeral - dapat menjadi faktor penyelamat.
Di sini paradoks kembali muncul: sampai sejauh mana sabda kedaulatan negara harus dipertahankan ketika nyawa manusia menjadi taruhannya?
Sikap menolak bantuan bilateral ini juga berimplikasi diplomatik. Joseph S. Nye menasihati, daya tarik suatu negara dalam politik internasional tidak hanya bergantung pada apa yang dilakukannya, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai dan tindakannya dipersepsikan, diinterpretasikan, dan diterima oleh negara lain (Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004).
Dipindai dari potensi soft power, Indonesia telah lama dipandang sebagai negara mayoritas Muslim moderat dan toleran yang menghargai keberagaman, kemanusiaan, dan jiwa gotong royong.
Dengan reputasi ini, bagaimana dunia akan menilai Indonesia jika tampak ragu-ragu untuk menerima bantuan kemanusiaan internasional?
Bagi negara-negara sahabat - yang terbiasa melihat Indonesia aktif terlibat dalam diplomasi kemanusiaan - tidak mudah bagi mereka untuk memahami mengapa Indonesia menolak bantuan kemanusiaan bilateral.
Di sini kembali kebijakan Indonesia menolak bantuan kemanusiaan untuk bencana Sumatera menghadirkan paradoks.
Bencana Sumatera memperlihatkan bahwa kedaulatan dan kemanusiaan bukanlah dua nilai yang selalu sejalan, tetapi juga tidak harus saling meniadakan. Atau malah mempertontonkan paradoks.
Penyelarasan sikap terhadap kedua narasi besar itu – kedaulatan dan kemanusiaan - justru menjadi ruang refleksi tentang bagaimana negara menempatkan diri dalam pergaulan dunia.
Manakala air surut dan perhatian dunia beralih, yang tersisa bukan hanya pertanyaan tentang bantuan apa yang diterima atau ditolak, melainkan tentang bagaimana negara memaknai kedaulatannya: apakah sebagai tembok yang membatasi empati dan solidaritas, atau sebagai landasan moral dan etika yang justru memungkinkan kemanusiaan dijalankan secara bermartabat.