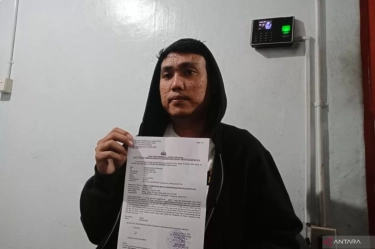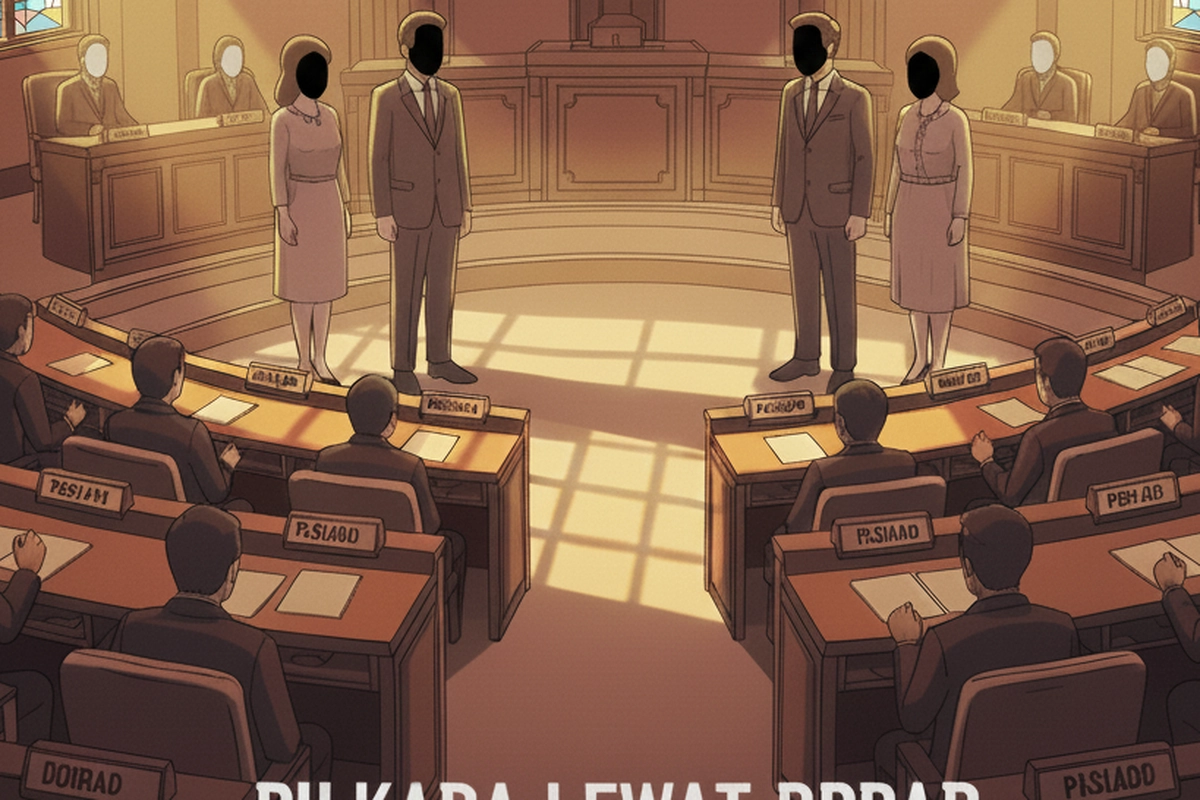
Wacana Pilkada Melalui DPRD, Cabut Mandat Rakyat Secara Paksa?
- Direktur Eksekutif Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah "pencabutan mandat rakyat secara paksa.
Dia beralasan, pilkada langsung adalah instrumen utama rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya.
"Mengembalikan pemilihan ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen, DEEP Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik," ucap Neni, dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).
Selain menyebut wacana ini merampas mandat rakyat secara paksa, alasan politik berbiaya mahal juga turut disorot Neni.
Dia mengatakan, keluhan biaya politik dengan pemilhan langsung sangat mahal justru tidak pernah tecermin dalam laporan dana kampanye.
"Kandidat hanya melaporkan dana kampanye asal-asalan dan prosedural untuk menggugurkan kewajiban," tutur dia.
Hal ini terlihat dari temuan DEEP Indonesia pada pemilu serentak 2024.
Dari 13 temuan kandidat kepala daerah yang melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), memilih angka minimum.
Padahal, baliho dan spanduk atau alat peraga kampanye kandidat tersebut terpasang cukup masif.
Oleh sebab itu, Neni meyakini jika alasannya benar terkait politik berbiaya mahal, solusinya bukan mengalihkan hak pilih masyarakat pada DPRD, tetapi memperbaiki transparansi dan kampanye.
"Agar publik dapat melihat secara komprehensif termasuk menjawab dan membongkar apakah benar atau tidak ada mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai," ucap dia.
Membonsai hak rakyat
Kritik tajam atas wacana ini juga disampaikan oleh Pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini.
Dia mengatakan, argumen pemerintah dan partai politik yang menyebut biaya pemilihan langsung sangat mahal sehingga perlu ada efisiensi sangat mudah dipatahkan.
Karena pemerintah saat ini harus berkaca bahwa membentuk puluhan kementerian baru dalam rangka bagi-bagi jabatan politik adalah pemborosan yang sesungguhnya.
"Padahal, membandingkan jumlah kementerian (awalnya) yang 34 versus kementerian dan badan yang hampir sudah 50 (jumlahnya) dengan lebih 100 menteri dan wakil menteri. Kalau kembali pada model penyederhanaan sebelumnya, biaya pilkada yang tadi disebutkan (mahal) itu tidak seberapa," ucap Titi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Titi mengatakan, biaya pilkada yang disebut mahal itu juga bisa dihemat jika bisa menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran dengan cara yang tepat.
"Tanpa membonsai hak rakyat," tutur dia.
Titi mengatakan, muasal pilkada dipilih langsung oleh rakyat dikarenakan pilkada dipilih DPRD tak ubahnya politik transaksional para elite.
Peristiwa seperti politik uang untuk setiap kursi dukungan calon kepala daerah.
Hal ini tak ubahnya memindahkan politik uang dari eceran ke grosiran semata.
Jejak politik uang saat pilkada dipilih DPRD
Merujuk dua artikel Kompas berjudul ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke” (14 Maret 2000) dan ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap” (15 Maret 2000), yang diulas kembali dalam liputan bertajuk "Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD" politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD.
Praktik "biaya lain-lain yang merusak moral bangsa" itu digambarkan secara gamblang dalam pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000.
Saat itu, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi.
Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.
Fenomena serupa muncul di Boyolali pada Februari 2000 ketika suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara.
Rumor yang beredar saat itu menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik ”karantina” anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.
Praktik transaksi politik lebih vulgar di Lampung Selatan, dalam proses pemilihan bupati periode 2000–2005, tim sukses calon bupati mendatangi rumah anggota DPRD, menginapkan mereka di hotel, dan memberikan uang tunai dengan nilai bervariasi.
Sejumlah anggota DPRD mengaku menerima uang antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, bergantung pada posisi mereka sebagai anggota atau pimpinan fraksi.
Praktik politik uang tersebut merebak di berbagai daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dukungan partai kian bertambah
Kendati telah menjadi catatan merah sejarah demokrasi di Indonesia, wacana yang pernah ditolak Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini justru terus mendapatkan dukungan baru dari partai politik.
Termasuk partai politik yang membesarkan nama SBY, Partai Demokrat.
Setidaknya, ada empat partai politik yang telah menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Demokrat.
Meski tidak secara eksplisit menyatakan dukungan pada pilkada oleh DPRD, partai berlambang bintang mercy itu sudah meneguhkan, sikap mereka mengekor dengan sikap penguasa, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).
“Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” sambung Herman.
Sikap penguasa tentunya telah diwakilkan oleh Partai Gerindra, karena partai tersebut bersikap sesuai dengan ketua umumnya, Prabowo Subianto.
Tag: #wacana #pilkada #melalui #dprd #cabut #mandat #rakyat #secara #paksa