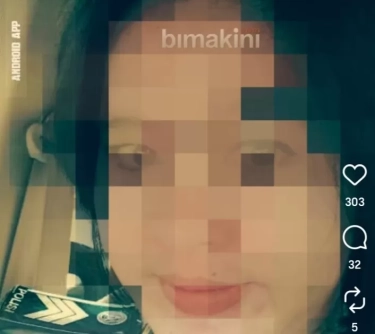Republik Alergi Diskusi
SABTU malam di Pasar Pundensari, Madiun, suasana sudah hampir matang: kursi tertata, peserta berdatangan, diskusi bedah buku "Reset Indonesia" bersiap dibuka pukul 19.00 WIB.
Mengutip dari siaran persnya, beberapa sosok beratribut kekuasaan datang—camat, perangkat desa, Babinsa, Polsek—membawa satu kalimat yang sering terdengar di republik ini, “tidak ada izin.”
Padahal surat pemberitahuan sudah disampaikan ke Polsek. Ruang yang diniatkan sebagai tukar gagasan—tanpa agenda politik praktis, tanpa provokasi—mendadak diperlakukan seolah ancaman.
Pembubaran itu bukan hanya menutup acara, tetapi juga membuka pola. Di Madiun, panitia menyebut tekanan langsung, peserta diminta pulang, bahkan ada larangan khusus terkait kehadiran Dandhy Laksono sebagai narasumber.
Di versi pemberitaan lain, sekelompok pria mengaku polisi membentak penyelenggara dan “membubarkan paksa”.
Lalu muncul detail yang membuat tengkuk terasa dingin: setelah acara dipindahkan dan selesai mendekati tengah malam, dini hari sekitar pukul 03.00, terjadi pelemparan telur ke kendaraan tim.
Peristiwa terasa seperti pesan tak tertulis—diskusi boleh selesai, tetapi rasa aman belum tentu kembali.
Setahun sebelumnya, di Kemang, Jakarta Selatan, diskusi Forum Tanah Air mengalami resep serupa dengan bumbu yang lebih kasar: kelompok massa masuk ruangan, mengobrak-abrik perlengkapan, berteriak “bubar-bubar!”, sementara aparat disebut tak sigap menghentikan.
Sesudahnya, narasi “tak berizin” kembali dipakai sebagai alasan, seakan kebebasan berkumpul dan bertukar pikiran perlu stempel sebelum boleh hidup.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) membaca rangkaian pembubaran diskusi dan aksi damai dengan pola yang berulang: dimulai oleh kelompok pro-kekerasan, berakhir pada intimidasi atau kekerasan, lalu negara tampak terlambat—atau terlalu tenang.
Republik ini bukan kekurangan bahan bacaan, melainkan terlalu sering “alergi” pada forum yang membuat warga berpikir bersama.
Jaminan hukum yang sering macet di lapangan
Di atas kertas, republik ini sebetulnya tidak pernah kekurangan jaminan hukum. Konstitusi secara eksplisit menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berkumpul sebagai hak dasar warga negara.
Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menyebutkan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta berkumpul dan berserikat.
Pasal 28F menambahkan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala saluran yang tersedia.
Jaminan ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai sebagai hak yang wajib dihormati dan dilindungi negara.
Dalam kerangka hukum internasional, posisi itu bahkan lebih jelas. Indonesia telah mengaksesi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Kovenan ini menjamin kebebasan berekspresi (Pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21), dan kebebasan berserikat (Pasal 22).
Pembatasan hanya boleh dilakukan secara ketat, berdasarkan hukum, untuk tujuan yang sah, dan harus proporsional—bukan karena ketidaknyamanan terhadap isi diskusi atau siapa yang berbicara.
Bedah buku, diskusi publik, dan forum dialog jelas masuk dalam kategori penggunaan hak-hak sipil dan politik yang dilindungi.
Masalahnya, jaminan normatif itu kerap berhenti sebagai teks. Di lapangan, hak-hak tersebut dengan mudah dikalahkan oleh frasa administratif seperti “tidak ada izin”, seolah kebebasan sipil adalah fasilitas yang menunggu persetujuan.
Padahal, dalam rezim hukum nasional—termasuk UU Nomor 9 Tahun 1998—yang dikenal hanyalah pemberitahuan, bukan perizinan, dan itu pun terutama untuk aksi di ruang terbuka.
Kala diskusi intelektual di ruang publik atau ruang tertutup diperlakukan sebagai gangguan keamanan, yang terjadi bukan sekadar salah tafsir hukum, melainkan pengosongan makna hak asasi manusia itu sendiri. Jaminan tetap tercetak rapi, tetapi perlindungannya macet begitu diuji oleh praktik.
Alergi diskusi
Alergi ini bukan muncul karena bahaya nyata, melainkan karena tubuh politik bereaksi berlebihan terhadap hal yang seharusnya biasa.
Begitu muncul ruang diskusi, republik ini seperti langsung bersin: refleks, tergesa, dan sering tanpa diagnosa. Pikiran kritis diperlakukan layaknya alergen—harus dijauhkan sebelum memicu reaksi lanjutan.
Yang dianggap berisiko bukan keributan atau kekerasan, melainkan orang-orang yang duduk rapi, membaca buku, lalu bertanya.
Gejala alergi diskusi terlihat dari perubahan cara memandang masalah. Percakapan dianggap potensi gangguan, dialog dicurigai sebagai ancaman, dan perbedaan pendapat disalahpahami sebagai bibit kekacauan.
Dalam kondisi seperti ini, negara tidak perlu membungkam secara kasar; cukup membuat suasana tidak nyaman.
Sedikit tekanan, sedikit alasan administratif, sedikit pembiaran terhadap intimidasi, lalu ruang diskusi mengempis dengan sendirinya. Efeknya halus, tapi dalam: rasa takut bekerja lebih efektif daripada larangan terbuka.
Jika alergi ini dibiarkan, maka dampaknya menyerupai penyakit kronis. Publik belajar menahan diri sebelum berbicara, menyederhanakan pikiran agar aman, dan menghindari forum yang berpotensi “sensitif”.
Diskusi bukan lagi ruang bersama untuk mencari makna, tetapi kegiatan berisiko yang harus dihitung untung-ruginya.
Maka, republik ini tidak sedang kekurangan undang-undang atau jargon demokrasi—republik sedang sakit pada satu hal mendasar, yakni ketakutan terhadap warganya sendiri yang berani berpikir keras dan berbicara terbuka.
Jika republik benar-benar ingin sembuh dari “alergi” ini, resepnya bukan menutup ruang diskusi, melainkan menguatkan pelindungan terhadap ruang itu.
Diskusi publik yang damai semestinya diperlakukan sebagai kegiatan normal dalam negara hukum: dijaga keamanan penyelenggara dan peserta, bukan dihentikan atas alasan administratif yang lentur.
Kala ada intimidasi, pembentakan, perusakan, atau ancaman—yang pertama bekerja seharusnya kewajiban negara: mencegah kekerasan, mengusut pelaku, memastikan rasa aman pulih.
Negara tidak boleh tampil seperti petugas yang hanya rajin memeriksa label, tetapi abai ketika warga butuh pelindung.
Poinnya sederhana, hak-hak konstitusional dan instrumen HAM bukan pajangan untuk pidato resmi. Jaminan itu harus terasa di lapangan—dalam bentuk standar pengamanan yang menghormati kebebasan sipil, prosedur yang jelas, dan keberanian menindak kelompok yang menggunakan kekerasan atau intimidasi sebagai cara “mengatur” ruang publik.
Kala aparat lebih cepat mematikan acara ketimbang menghentikan ancaman, yang diproduksi bukan ketertiban, melainkan ketakutan. Pun, ketakutan, dalam jangka panjang, selalu lebih merusak daripada kritik.
Jadi, yang perlu “di-reset” bukan forum diskusinya, melainkan cara pandang negara terhadap warganya.
Demokrasi yang sehat tidak alergi terhadap pertanyaan; demokrasi yang sehat justru membutuhkan pertanyaan sebagai sistem imunnya.
Jika diskusi damai terus dianggap masalah, republik ini sedang memilih menjadi tubuh yang menolak antibodi—lalu heran mengapa penyakit otoritarianisme gampang kambuh.