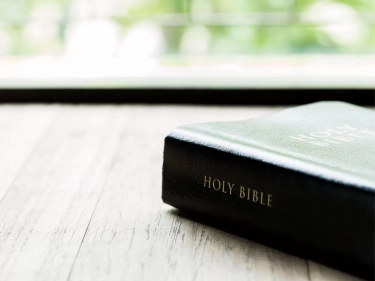PPPK: Janji yang Tak Setara
KETIKA pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, publik birokrasi menyambutnya dengan harapan baru.
Undang-undang itu menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri atas dua kelompok: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di atas kertas, keduanya setara dalam prinsip dan penghargaan.
Namun, sebagaimana banyak janji negara lainnya, kesetaraan itu berhenti di atas kertas. Dalam praktik birokrasi, PPPK masih menjadi warga kelas dua.
Mereka direkrut melalui seleksi nasional yang ketat, bekerja di posisi strategis yang sama dengan PNS, tetapi tidak menikmati kepastian karier, mobilitas jabatan, atau jaminan pensiun yang memadai.
Revisi UU ASN yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional 2025 sejatinya diharapkan menuntaskan ironi tersebut.
Namun, proses pembahasan justru memperlihatkan wajah lama birokrasi: lamban, politis, dan terbelenggu kalkulasi fiskal. Janji kesetaraan yang diucapkan dengan lantang kembali terperangkap dalam bahasa rapat dan perhitungan anggaran.
Realitas
Sebagian besar PPPK adalah mereka yang telah lama mengabdi: guru, tenaga kesehatan, dan staf teknis di daerah.
Mereka dulunya berstatus honorer, digaji seadanya, lalu dijanjikan kepastian hukum melalui formasi PPPK.
Namun kini, setelah diangkat, mereka justru terjebak dalam sistem yang belum siap memberikan perlakuan setara.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 memang memperbarui struktur gaji dan tunjangan PPPK. Namun, di banyak daerah implementasinya tersendat karena keterbatasan fiskal.
Pemerintah daerah kesulitan membayar gaji PPPK dari belanja pegawai yang sudah melampaui batas 30 persen APBD.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020, yang mengatur tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, hanya menjelaskan mekanisme teknis—tanpa solusi atas kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.
Perbedaan perlakuan juga tampak dalam jenjang karier. PNS dapat berpindah antarinstansi, naik pangkat, dan menduduki jabatan struktural.
PPPK sebaliknya, terikat kontrak dan lokasi kerja, dengan masa kerja yang bergantung pada perpanjangan tahunan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sudah membuka ruang mutasi antarinstansi dengan syarat persetujuan kedua PPK.
Namun, dalam praktiknya, sistem birokrasi belum siap. Banyak instansi tidak memiliki mekanisme mutasi PPPK, sehingga mereka tetap terkungkung dalam lingkaran administrasi yang sempit.
Ironinya, dalam banyak kasus, PPPK justru menanggung beban kerja yang sama—bahkan lebih berat—daripada PNS, karena di banyak sekolah dan puskesmas hanya ada satu tenaga fungsional yang harus melayani ribuan warga.
Negara menuntut kesetiaan dan profesionalisme, tetapi kepastian hidup masih menjadi kemewahan.
Memang benar, sebagian hak dasar seperti perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian sudah diatur dalam PP 49/2018 Pasal 99. Namun, jaminan pensiun dan karier yang setara masih belum nyata. Di sinilah rasa keadilan birokrasi diuji.
Revisi
Revisi UU ASN yang sedang digodok DPR menjadi ujian keseriusan negara menegakkan prinsip meritokrasi.
DPR mendorong beberapa gagasan besar: menyetarakan hak pensiun PPPK dengan PNS, memperpanjang masa kontrak agar tidak bergantung pada evaluasi tahunan, dan membuka peluang alih status bagi PPPK berprestasi.
Namun, pemerintah menanggapinya dengan hati-hati. Kekhawatiran terhadap beban fiskal menjadi alasan klasik yang berulang.
Dalam rapat Komisi II DPR (Maret 2025), pemerintah memperkirakan tambahan beban keuangan negara sekitar Rp 18 triliun per tahun jika hak pensiun PPPK disetarakan penuh dengan PNS.
Solusi yang kini dibahas adalah skema pensiun berbasis iuran bersama, di mana negara dan pegawai sama-sama menanggung kontribusi.
Padahal, masalah kesetaraan bukan sekadar soal angka. Ini soal penghargaan atas pengabdian.
Bila negara bisa menanggung ratusan triliun rupiah untuk proyek-proyek ambisius dan subsidi politik, mengapa jaminan masa depan bagi aparatur yang melayani rakyat dianggap beban?
Revisi UU ASN juga harus berhati-hati terhadap jebakan baru: kebijakan PPPK paruh waktu yang diatur dalam Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Kebijakan ini memang ditujukan untuk menata tenaga non-ASN. Namun jika tidak diatur dalam undang-undang, status paruh waktu justru bisa menjadi “honorer gaya baru”—bekerja untuk negara tanpa kepastian karier yang layak.
Ketimpangan antara PNS dan PPPK bukan sekadar administratif, melainkan struktural. Ia menggambarkan wajah ganda birokrasi Indonesia: di satu sisi berbicara tentang meritokrasi, di sisi lain masih memelihara sistem hierarkis yang menilai pegawai dari status, bukan prestasi.
Bagi sebagian kepala daerah, PPPK bukan mitra profesional, tetapi sekadar tenaga kontrak yang bisa digerakkan sesuai kebutuhan politik lokal.
Laporan Ombudsman RI tahun 2024 bahkan mencatat adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam perpanjangan kontrak PPPK di sejumlah daerah, terutama bagi pegawai yang kritis terhadap kebijakan pimpinan.
Kesenjangan ini tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga merusak semangat reformasi birokrasi.
PNS mendapat penghargaan simbolik sebagai “abdi negara”, sedangkan PPPK sering dianggap “pekerja kontrak pemerintah”. Padahal, keduanya sama-sama melayani publik, terikat pada sumpah jabatan, dan tunduk pada sistem merit yang sama.
Reformasi ASN tidak akan berarti bila negara masih memandang aparatur dari status hukum, bukan dari kontribusi terhadap pelayanan publik.
Keadilan birokrasi bukan sekadar tabel gaji atau angka tunjangan. Ia diukur dari bagaimana negara memperlakukan setiap pegawai sebagai manusia yang bermartabat.
Dalam konteks PPPK, keadilan berarti memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan ruang karier yang adil.
Negara perlu membangun sistem jaminan pensiun dan hari tua yang modern dan berkelanjutan.
Skema pensiun berbasis iuran—di mana PPPK dan pemerintah sama-sama berkontribusi—bisa menjadi jalan tengah antara kemampuan fiskal dan kewajiban moral.
Selain itu, fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus diperkuat, bukan dilemahkan. Pengawasan merit perlu dijaga agar pengangkatan, promosi, dan mutasi PPPK tidak terjebak dalam politik patronase.
Revisi UU ASN semestinya menjadi momentum koreksi moral terhadap sistem kepegawaian yang masih elitis. Setiap aparatur, apa pun status hukumnya, layak mendapat perlakuan yang adil.
Harapan PPPK kini bertumpu pada keberanian politik pemerintah dan DPR. Setelah satu tahun penerapan UU ASN baru dan kebijakan gaji yang diperbarui, publik birokrasi menunggu bukti, bukan lagi janji.
Di sekolah, rumah sakit, dan kantor pelayanan publik, rakyat tidak peduli siapa yang melayani mereka—PNS atau PPPK. Yang mereka harapkan hanyalah pelayanan yang cepat, jujur, dan manusiawi. Negara seharusnya menjawab dengan kebijakan yang adil, bukan diskriminatif.
Jika PPPK terus dibiarkan menunggu di ruang kebijakan yang tak kunjung pasti, maka reformasi birokrasi hanya akan menjadi mitos. Janji kesetaraan akan tinggal kenangan, seperti banyak janji lain yang tak pernah ditepati.
Negara harus menepati janjinya bukan karena tekanan politik, tetapi karena panggilan moral: menghormati setiap pengabdian yang telah diberikan warganya kepada republik.
Reformasi birokrasi sejati bukan sekadar efisiensi, melainkan keberanian untuk menegakkan keadilan di dalam tubuh negara sendiri. PPPK telah menunjukkan loyalitas tanpa jaminan; kini giliran negara menepati janji tanpa alasan.
Revisi UU ASN menjadi cermin bagi arah moral birokrasi kita. Bila kesetaraan hanya menjadi retorika, dan nasib PPPK tetap di ruang tunggu, maka yang gagal bukan undang-undangnya, melainkan nurani negara yang kehilangan rasa adilnya.