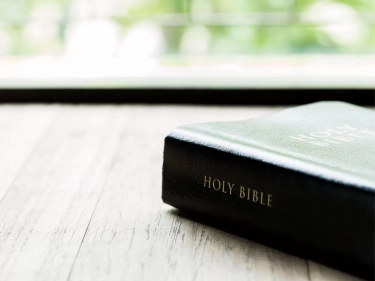Buku, Imajinasi, dan Demonstrasi
ADA yang menarik di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin (6/10/2025). Bersamaan dengan aksi Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan gedung wakil rakyat itu, sejumlah peserta aksi juga menggelar lapak baca buku (Kompas.com, 06/10/2025).
Tentu saja para mahasiswa itu bukan hendak jualan buku. Ada kritik simbolik seiring dengan aktivitas utama mereka, yakni aksi atau demonstrasi dalam bentuk RDPW.
Meski tak seorang pun anggota DPR hadir, sebagai peristiwa politik dan kebudayaan, aksi BEM UI itu bisa disebut berhasil.
Peristiwa itu diliput media massa, juga viral media sosial. Dan, tak kalah penting dari sisi kebudayaan, aksi para mahasiswa itu menjadi bagian dialektika kebudayaan.
Di mata saya, sebagai kritik simbolik, sangatlah cerdas mereka membuka lapak baca buku bersamaan dengan demonstrasi. Mendasar sekali substansi kritiknya.
Bukan sekadar kritik kepada polisi yang beberapa waktu lalu menyita buku-buku yang diduga berkaitan erat dengan kerusuhan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo.
Beberapa buku yang disita polisi berjudul Apa itu Anarkisme Komunis? karya Alexander Berkman; Strategi Perang Gerilya Che Guevara, Kisah Para Diktator karya Jules Archer, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya Franz Magnis-Suseno, dan Anarkisme: Apa yang Sesungguhnya Diperjuangkan karya Emma Goldman.
Pihak kepolisian menyebut buku-buku yang disita itu berisi paham soal anarkisme dan komunisme.
Kepolisian akhirnya memang mengembalikan buku-buku milik para tersangka kasus kerusuhan di Jawa Timur itu pada akhir September lalu, setelah menyimpulkan tidak ada kaitan antara buku tersebut dan tindak pidana yang disidik (Kompas.id, 30/09/2025).
Namun, publik bertanya-tanya, jangan-jangan polisi memang miskin literasi. Pengembalian buku-buku itu bukan karena penyidik tak menemukan kaitan antara buku tersebut dan tindak pidana yang disidik, melainkan desakan reformasi kepolisian yang berhembus kencang hari-hari ini.
Kita tahu bahwa desakan reformasi kepolisian itu direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menjanjikan hendak membentuk Komite Reformasi Polri.
Publik juga tahu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahkan mendahuluinya dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisi 52 perwira polisi.
Karena itu, masuk akal bila ada tafsir bahwa pengembalian buku-buku itu bagaikan “pemerah bibir” belaka. Publik belum melihat sebagai refleksi reformasi kepolisian, yang sepenuhnya didasari perubahan cara pandang dan perilaku sebagai produk kematangan literasi.
Buat saya, aksi mahasiswa membuka lapak baca buku bersamaan dengan demonstrasi di depan Gedung DPR itu menghujam dasar kebudayaan.
Secara khusus mereka mengritik tradisi politik bernegara modern Indonesia yang menjauh dari pelahirannya.
Tradisi bernegara Indonesia dikritik tak lagi dituntun oleh kematangan intelektual yang disimbolisasi melalui buku. Para elite politik dan penyelenggara negara dinilai tunarungu-tunawicara-tunatindakan, karena miskin imajinasi dan pemikiran akibat miskin literasi.
Padahal, Indonesia adalah negara modern produk literasi yang sangat kuat dari para pendiri. Indonesia bukan pemberian penguasa kolonial. Indonesia dirajut dengan kekuatan dan kematangan intelektual para pendiri.
Mereka, para pendiri bangsa, adalah generasi yang sukses merayakan literasi dalam situasi yang serba terbatas.
Mereka membaca, menulis dan berdebat melalui surat kabar dan karya sastra tentang zamannya dengan penuh gairah.
Literasi yang sungguh-sungguh terbukti membuahkan tradisi kritik, keterbukaan pikiran, dan imajinasi yang melampaui zamannya.
Hasilnya sungguh hebat, luar biasa, out of the box. Literasi mereka menandai “kebangkitan”, menuntun “pergerakan” rakyat jajahan, fajar kebudayaan masyarakat Nusantara.
Literasi tersebut membuahkan komunitas baru yang menyebut dan disebut “bangsa Indonesia”, mahakarya reflektif dan visioner, yang kelak memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk negara dengan segenap piranti ketatanegaraan negara demokrasi modern.
Kita ambil satu aspek dari mahakarya itu, yakni Pancasila, yang disepakati sebagai dasar negara melalui perdebatan tajam yang menunjukkan kematangan intelektual.
Pancasila mustahil lahir tanpa kematangan intelektual, tanpa literasi sungguh-sungguh. Bung Karno menyebut “digali” dari bumi Indonesia.
Tanpa kuatnya literasi dengan tradisi kritik yang juga kuat mustahil pemikiran-pemikiran besar di bumi Indonesia bisa diketahui, baik kekuatan maupun keburukannya.
Pancasila berhasil disepakati, baik substansi maupun teksnya, melalui perdebatan tajam. Hal itu hanya dimungkinkan oleh manusia-manusia yang tumbuh di dalam literasi yang baik dan sungguh-sungguh.
Tradisi kritik adalah anak kandung tradisi literasi. Literasi tanpa kritik tak akan menjumpai refleksi, tak akan menemukan sintesis-sintesis yang dibutuhkan bagi pembaruan peradaban.
Tradisi kritik yang tumbuh dari tradisi literasi yang baik dan sungguh-sungguh itulah yang menghilang di negeri ini justru saat bangsa ini harus mengisi kemerdekaan.
Kebudayaan dan peradaban bukan bergerak maju, tapi jalan di tempat, bahkan mundur kembali pada zaman kegelapan kolonial.
Penyitaan buku-buku menandai zaman gelap itu. Negeri ini memiliki jejak literasi yang penuh ironi, dampaknya masih sangat terasa hingga kini.
Saya ambil contoh satu saja, terhadap karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Apakah bawah sadar kita sudah sepenuhnya pulih dan jernih melihat karya-karya Pram?
Sudahkah kita (negara) menghargai karya-karya bermutu Pram dan merawatnya untuk pengayaan literasi Indonesia?
Sejarah literasi Indonesia menyedihkan dan payah. Karya tulis Pram dikagumi dunia, dicetak-ulang berkali-kali, dan diterjemahkan ke banyak bahasa asing, tapi dilarang, dibuang, dan dikecam di negeri sendiri.
Alih-alih dijadikan bacaan wajib anak-anak sekolah, karya-karya Pram disingkirkan dari jangkauan publik, terutama generasi muda.
Semestinya generasi muda diminta melahap habis bacaan bermutu itu sebagai sumber pembangunan karakter, tapi malah dijauhkan dari karya-karya itu.
Ketakutan publik terhadap karya Pram sengaja diciptakan. Melalui ketakutan itulah pikiran publik dikontrol, dikendalikan. Tak boleh ada pikiran lain. Pada saat yang sama pikiran penguasa ditanamkan sedalam-dalamnya.
Penguasa Orde Baru tak peduli bahwa Tetralogi Pulau Buru karangan Pram adalah karya sastra bermutu dengan latar zaman kolonial yang sesungguhnya bagus sebagai sumber literasi kebangsaan.
Orde Baru juga tak ambil pusing bahwa dunia mengapresiasi Pramoedya karena kualitas pemikiran kemanusiaannya.
Sedemikian mendalam ketakutan publik, sehingga ketakutan itu dengan sendirinya menyeleksi pilihan-pilihan publik. Cara pandang polisi yang menyita buku-buku, saya kira, merefleksikan soal ini.
Sungguh aneh, buku Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya Franz Magnis-Suseno yang terbit setelah Orde Baru runtuh turut disita.
Di mata saya, buku tersebut sangat membantu publik Indonesia memahami pemikiran Karl Marx yang menguncang dunia.
Menyita buku tersebut bagaikan menutup jalan kebudayaan dan peradaban Indonesia, bahkan merendahkan para pendiri bangsa yang mustahil punya imajinasi Indonesia Raya tanpa membaca karya-karya Karl Marx.
Dampaknya sangat mendasar dan terasa hingga kini. Perubahan yang digerakkan reformasi pada 1998 terbukti jalan di tempat (involusi).
Banyak problem warisan Orde Baru tak menemukan solusi. Konsolidasi demokrasi lamban dan tak menemukan wujud yang didambakan. Perubahan kelembagaan politik tak diikuti penguatan nilai-nilai demokrasi, tak membuat rakyat berdaya secara politik.
Sebaliknya, kesewenang-wenangan penguasa (elite) terkesan dibiarkan, dilindungi, dibenar-benarkan.
Hasilnya, korupsi merajalela, distribusi kesejahteraan dan keadilan tak merata, cita-cita kemerdekaan menjauh dari kenyataan.
Tak seperti masa lampau sebelum penjajahan yang mampu bikin Borobudur dan mahakarya lain serta awal-awal kemerdekaan yang mampu bikin Pancasila, UUD 1945, memimpin Asia-Afrika, kini Indonesia miskin karya yang dikagumi dunia.
Sebaliknya, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) malah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Meskipun juaranya Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, keputusan OCCRP menampar muka kita dan patut direnungkan secara sungguh-sungguh.
Para mahasiswa di depan Gedung DPR kemarin mengingatkan kita, terutama mereka yang berada di Gedung DPR dan para elite pemimpin negeri ini.
Eksistensi Indonesia dan masa depan yang diimajinasikan para pendiri bangsa terancam, karena mereka meninggalkan dasar peradaban modern, yakni buku dengan anak kandungnya berupa tradisi kritik.
Tag: #buku #imajinasi #demonstrasi