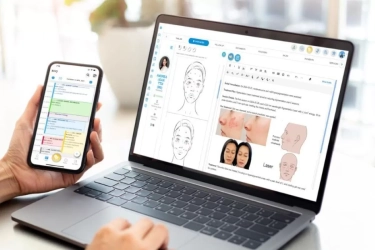Pasar Estetika, Kekuatan Digital, dan Krisis Etik Kedokteran
INDUSTRI estetika di Indonesia sedang tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Klinik-klinik bermunculan dengan janji kulit sempurna, membungkus promosi dengan bahasa ilmiah yang tampak meyakinkan. Kredensial medis berpadu dengan algoritma digital, menciptakan ilusi bahwa keindahan bisa dibeli dan keamanan bisa diasumsikan.
Di balik gemerlap itu, ada hal yang tak bisa diabaikan, yaitu bergesernya layanan medis dari ruang etik ke ruang komersial. Fenomena ini melahirkan ekonomi baru yang bertumpu pada simbol profesi. Gelar dokter yang semestinya merepresentasikan tanggung jawab kini sering berubah menjadi alat jualan.
Produk berlabel “racikan dokter” beredar tanpa izin edar BPOM, diklaim sebagai terapi padahal sejatinya kosmetik bebas kontrol. Publik percaya karena figur yang tampil bukan hanya penjual, tetapi seseorang dengan jas putih dan gelar medis. Di sinilah letak persoalannya, ilmu yang seharusnya menjadi pagar keselamatan berubah menjadi dekorasi pemasaran.
Data BPOM tahun 2024 menunjukkan hampir delapan dari sepuluh produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, hingga kortikosteroid poten. Bahan tersebut tidak sekadar memberikan efek samping ringan, melainkan konsekuensi medis yang serius seperti atrofi kulit, gangguan ginjal, dan hiperpigmentasi kronis akibat paparan jangka panjang.
Dalam istilah kedokteran, ini disebut iatrogenic harm by negligence of oversight, kerusakan yang muncul bukan karena penyakit, tetapi karena pengawasan yang absen. Ironisnya, banyak pengguna tetap percaya bahwa gejala yang mereka alami adalah “tanda adaptasi”, bukan tanda bahaya.
Pengetahuan ilmiah tereduksi menjadi mitos kecantikan yang menenangkan, tapi menyesatkan. Kekuatan digital mempercepat distorsi itu. Di ruang media sosial, kredibilitas tak lagi ditentukan oleh publikasi ilmiah, melainkan oleh jumlah pengikut dan impresi visual. Konten tentang estetika menjadi standar baru otoritas. Algoritma bekerja seperti dopamin sosial, memperkuat rasa percaya tanpa memberi ruang pada keraguan.
Dokter-dokter yang viral di dunia maya seringkali menjadi panutan, meski isi komunikasinya lebih dekat ke promosi ketimbang edukasi. Fenomena ini bisa disebut neurokomersialisasi estetika, situasi di mana sistem penghargaan otak masyarakat diprogram untuk mengaitkan kecantikan dengan kepercayaan, tanpa memeriksa dasar ilmiahnya.
Dalam konteks ini, vonis empat tahun penjara terhadap individu yang disebut menggunakan kekuatan digital untuk memeras pihak klinik hanya satu potongan kecil dari lanskap yang lebih luas. Hukum pidana menegur perilaku individu, tetapi belum menyentuh akar dari patologi sosialnya.
Kombinasi antara celah regulasi, tekanan pasar, dan banalitas promosi menciptakan lingkungan yang patologis secara struktural. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, kondisi seperti ini dikenal sebagai regulatory failure with iatrogenic consequences, kegagalan pengawasan yang justru melahirkan dampak buatan sistem itu sendiri.
Krisis etik kedokteran modern tidak terjadi dalam sekejap. Tumbuh perlahan, disuburkan oleh normalisasi perilaku yang salah. Sumpah profesi kehilangan bobot ketika dijadikan jaminan merek dagang.
Kode Etik Kedokteran Indonesia sebenarnya tegas, profesi medis tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau promosi menyesatkan. Namun di lapangan, implementasinya sering berhenti di administratif. Di dunia digital yang bergerak cepat, batas etik menjadi porus. Setiap klik yang dibiarkan tanpa klarifikasi mengikis integritas ilmu sedikit demi sedikit.
Akibatnya, bukan hanya reputasi profesi yang terkikis, tetapi juga ecology of trust, ekosistem kepercayaan yang menopang seluruh sistem kesehatan. Yang dibutuhkan kini bukan pembelaan terhadap individu, tetapi rekonstruksi terhadap nilai-nilai profesi.
Regulasi estetika seharusnya diperlakukan seketat regulasi farmasi. Berbasis bukti, transparan, dan diawasi secara independen. Kolaborasi antara BPOM, Kemenkes, IDI, dan Kominfo tidak boleh berhenti pada penandatanganan MoU, melainkan diwujudkan dalam pengawasan digital yang terintegrasi, real-time, dan dapat diaudit publik.
Dokter yang berpraktik di ranah komersial perlu tunduk pada mekanisme conflict of interest disclosure yang terbuka dan dapat diverifikasi. Tanpa itu, industri ini akan terus bekerja seperti jaringan limfatik sosial, mengalir di seluruh tubuh masyarakat tanpa disadari, hingga efeknya meluas dan sulit dikendalikan.
Dalam situasi seperti ini, tugas profesi medis jauh melampaui ruang praktik. Tugas utamanya kini adalah menjaga rasionalitas publik. Pasar boleh tumbuh, tapi tidak boleh mengambil alih fungsi etik. Teknologi digital boleh memperluas akses, tapi tidak boleh menggantikan verifikasi ilmiah. Keindahan boleh menjadi aspirasi, tetapi keselamatan harus tetap menjadi norma.
Kepercayaan terhadap profesi medis tidak dibangun oleh solidaritas sejawat, melainkan oleh konsistensi terhadap prinsip non-maleficence atau jangan mencederai. Dan mungkin, di tengah derasnya kekuatan digital, kejujuran ilmiah adalah bentuk keberanian paling tinggi yang masih tersisa dalam profesi ini.
Tag: #pasar #estetika #kekuatan #digital #krisis #etik #kedokteran