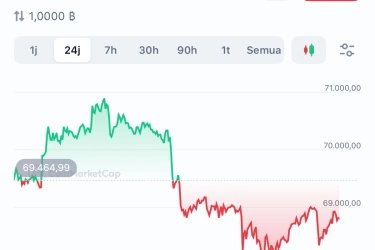Stagnasi Gaji Aparatur Negara
DI TENGAH wacana efisiensi anggaran dan disiplin fiskal, dan paradoks anggaran besar-besaran untuk makan bergizi gratis (MBG), ada satu kelompok yang kerap luput dari perhatian, yakni aparatur negara.
Mereka adalah ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara yang setiap hari menjadi wajah negara di mata rakyat.
Namun, dalam satu dekade terakhir, kesejahteraan mereka relatif berjalan di tempat. Bahkan pensiunan atau purnawirawan ASN, TNI, dan Polri pun tidak luput dari dampak ditahannya kenaikan kesejahteraan aparatur (gaji dan tunjangan).
Gaji yang diterima pensiunan dan purnawirawan sebagai gaji pensiun juga mengacu pada gaji pokok yang ditetapkan pemerintah.
Pada era pemerintahan Joko Widodo, kenaikan gaji pokok aparatur negara tidak berlangsung setiap tahun. Tercatat hanya tiga kali kenaikan gaji pokok sepanjang periode tersebut.
Itu pun bersifat sporadis, bukan kebijakan rutin tahunan sebagaimana pernah terjadi pada periode sebelumnya.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan bahwa penurunan kesejahteraan aparatur akan berdampak luas terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, juga pada kinerja birokrasi.
Pada masanya, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan/purnawirawan menikmati kenaikan gaji hampir setiap tahun. Kebijakan tersebut bukan semata populisme, tetapi bagian dari strategi menjaga daya beli dan stabilitas nasional.
Baca juga: Korupsi Pajak dan Bea Cukai: Memutus “Clique”, Mengganti Seluruh Pejabat
Kesejahteraan aparatur bukan isu sektoral. Namun, berkaitan dengan daya beli, stabilitas ekonomi keluarga, moral birokrasi, dan pada akhirnya kualitas pelayanan publik.
Negara tidak boleh terus-menerus menahan napas aparaturnya sambil berharap pelayanan tetap prima dan integritas tetap terjaga.
Masalahnya bukan hanya pada gaji pokok. Tunjangan kinerja, yang dalam banyak kasus nilainya jauh lebih besar daripada gaji pokok, praktis tidak pernah mengalami kenaikan nominal sejak tahun 2014.
Patokan 100 persen tunjangan kinerja merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 yang menjadi basis tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.
Selama 12 tahun, angka dasar itu tidak berubah. Kementerian/lembaga lain memang mengalami “kenaikan”, tetapi sebatas kenaikan persentase menuju angka 100 persen tersebut.
Kini hampir seluruh kementerian/lembaga telah mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi perbedaan tunjangan kinerja antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai kementerian/lembaga lain termasuk TNI dan Polri.
Di luar itu, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh pengaturan khusus melalui Perpres Nomor 37 Tahun 2015.
Tunjangan kinerja pegawai DJP selama ini dikenal sebagai yang tertinggi di antara ASN, TNI, dan Polri, bahkan dibandingkan pegawai non-pajak di Kementerian Keuangan.
Namun, jika ditarik lebih luas, tunjangan tersebut bukanlah yang paling tinggi secara absolut.
Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ASN menerima tunjangan kinerja yang selevel dengan DJP, diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.
Fenomena ini menunjukkan satu hal, yakni terjadi disparitas kesejahteraan aparatur, yang tidak lagi semata disparitas antara pusat dan daerah, tetapi juga antarinstansi.
Beberapa kepala daerah menetapkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
Di sejumlah daerah dengan PAD kuat, TPP bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan tunjangan kinerja ASN, TNI, atau Polri di kementerian/lembaga pusat.
Bandingkan dengan sektor swasta. Karyawan swasta lazim menerima kenaikan gaji dan tunjangan hampir setiap tahun mengikuti pertumbuhan usaha dan inflasi.
Selain itu, di sektor swasta diatur kenaikan upah minimum setiap daerah, yang menjadi batas bawah pengupahan, dan setiap tahun dinaikkan menyesuikan dengan inflasi yang terjadi.
Sementara selama 12 tahun terakhir, ASN, TNI, dan Polri hanya tiga kali menerima kenaikan gaji pokok dan bahkan kenaikan tunjangan tidak pernah terjadi selama 12 tahun.
Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan gaji hakim melalui peraturan presiden.
Kebijakan itu tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari penguatan integritas lembaga peradilan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan ASN, TNI, dan Polri lainnya?
Baca juga: Niat Baik Presiden dan OTT Hakim Depok
Di sisi lain, pemerintah pusat melakukan penyesuaian dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Konsekuensinya, ASN daerah semakin sulit berharap kenaikan TPP. Ruang fiskal daerah menyempit, sementara kebutuhan hidup terus meningkat.
Secara makro, jumlah ASN, TNI, dan Polri diperkirakan sekitar 6 juta orang, sekitar 2 persen dari total penduduk Indonesia.
Jika setiap aparatur menanggung rata-rata tiga anggota keluarga, maka sekitar 8 persen penduduk Indonesia menggantungkan kesejahteraan pada stabilitas pendapatan aparatur negara.
Jika ditambahkan dengan jumlah pensiunan dan purnawirawan serta keluarganya, mungkin mencapai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Ketika gaji dan tunjangan stagnan, di sisi lain inflasi secara perlahan menggerus daya beli mereka. Penurunan daya beli dalam skala jutaan keluarga bukan sekadar isu kesejahteraan individu, tetapi juga persoalan ekonomi nasional.
Ironisnya, kasus-kasus korupsi tetap terjadi, bahkan pada kelompok dengan penghasilan tertinggi, seperti hakim yang baru saja mendapat kenaikan signifikan maupun pegawai pajak yang selama ini bertunjangan besar.
Fakta ini tentu membuat miris ASN, TNI, dan Polri lain yang pendapatannya jauh lebih rendah, tapi tetap dituntut menjaga integritas.
Kesejahteraan memang bukan satu-satunya faktor pencegah korupsi, tetapi ketimpangan dan stagnasi pendapatan jelas bukan resep yang sehat bagi moral birokrasi.
Pertanyaan serupa layak diajukan terkait kesejahteraan aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan institusi penegakan hukum lainnya. Apakah kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian serius pemerintah?
Negara menuntut profesionalisme, integritas, dan keberanian moral. Namun, negara juga memiliki kewajiban menjaga martabat hidup mereka yang menjalankan mandat konstitusi.
Sehingga sampai kapankah aparatur negara diminta bertahan dengan pendapatan yang secara riil terus menyusut?
Jika negara menginginkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berwibawa, maka kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat.
Dalam literatur administrasi publik dan ekonomi kelembagaan, kesejahteraan aparatur negara bukan sekadar isu moral, tetapi bagian dari desain institusional.
Baca juga: MBG, Guru Honorer, dan Ironi Kesejahteraan Pendidik
Teori efficiency wage menjelaskan bahwa organisasi, termasuk negara, sering kali perlu membayar pegawai di atas tingkat upah minimum pasar untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan menekan perilaku menyimpang.
Upah yang memadai menciptakan “biaya kehilangan” yang tinggi jika seseorang melanggar aturan. Dalam konteks birokrasi, gaji dan tunjangan yang kompetitif menjadi instrumen pencegah korupsi yang rasional, bukan sekadar insentif material.
Gary Becker dalam teori ekonomi kejahatan menegaskan bahwa individu mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum melakukan pelanggaran.
Jika penghasilan legal rendah dan risiko kehilangan pekerjaan kecil secara relatif, maka insentif untuk menyimpang meningkat.
Sebaliknya, ketika aparatur menikmati pendapatan yang layak dan berkelanjutan, maka kehilangan jabatan akibat korupsi menjadi kerugian besar secara ekonomi dan sosial.
Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji bukanlah pemborosan, melainkan investasi dalam tata kelola.
Teori motivasi seperti two-factor theory dari Herzberg juga membedakan antara faktor pemeliharaan (hygiene factors) dan faktor motivator.
Gaji dan tunjangan termasuk faktor pemeliharaan yang jika tidak memadai akan menimbulkan ketidakpuasan dan demoralisasi.
Tanpa fondasi kesejahteraan yang cukup, sulit mengharapkan aparatur menunjukkan kinerja optimal, apalagi inovasi pelayanan publik.
Dalam kerangka public service motivation, aparatur memang digerakkan oleh idealisme melayani publik.
Namun, idealisme tidak dapat berdiri di atas tekanan ekonomi yang terus-menerus. Inflasi yang menggerus daya beli selama lebih dari satu dekade tanpa penyesuaian tunjangan riil berarti penurunan kesejahteraan secara sistematis.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong talenta terbaik memilih sektor swasta dengan kompensasi lebih tinggi, menciptakan distorsi distribusi sumber daya manusia di birokrasi nasional.
Jika gaji dan tunjangan tidak segera dinaikkan, maka bukan tidak mungkin, Gen Z dan sebagian Milenial muda, yang saat ini menjadi ASN, TNI, atau Polri akan mengajukan pengunduran diri dan memilih bekerja di sektor swasta.
Padahal di antara mereka adalah pegawai-pegawai bertalenta terbaik yang diterima dengan sistem seleksi yang ketat.
Dari perspektif makroekonomi, kenaikan gaji aparatur juga memiliki efek pengganda (multiplier effect).
Baca juga: Salah Kaprah Kenaikan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah
Dengan jumlah sekitar 6 juta aparatur dan jutaan anggota keluarga yang bergantung pada mereka, peningkatan daya beli kelompok ini akan menggerakkan konsumsi domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Artinya, kebijakan penyesuaian gaji dan tunjangan bukan hanya belanja rutin, melainkan stimulus ekonomi yang terarah.
Last but not least, dalil normatif dan empiris bertemu pada satu titik, yaitu negara yang menuntut integritas tinggi dan pelayanan publik berkualitas harus menjamin kesejahteraan aparaturnya secara rasional dan berkelanjutan.
Kenaikan gaji dan tunjangan bukanlah hadiah, tetapi bagian dari kontrak sosial antara negara dan mereka yang mengabdi kepadanya.
Tanpa itu, kita mempertaruhkan kualitas birokrasi, dan pada akhirnya, kualitas negara itu sendiri.