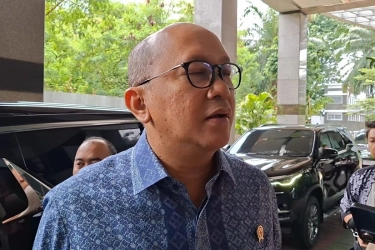Sertifikasi BNSP: Ketika Standar Nasional Ditinggalkan Pasar Kerja
SERTIFIKASI kompetensi nasional sejatinya dirancang sebagai penanda mutu. Ia diharapkan menjadi bahasa bersama antara negara, dunia pendidikan, dan dunia kerja: siapa yang tersertifikasi berarti kompeten.
Namun di Indonesia, sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) justru kian sering dipertanyakan relevansinya. Bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga oleh publik yang melihat jarak semakin lebar antara sertifikat dan kesiapan kerja nyata.
Pertanyaannya sederhana, tapi mendasar: mengapa standar nasional yang seharusnya menjadi rujukan justru ditinggalkan oleh pasar kerja?
Sertifikat ada, kepercayaan tidak selalu menyertai
Dalam praktik rekrutmen, banyak perusahaan terutama sektor swasta tidak lagi menjadikan sertifikat kompetensi nasional sebagai penentu utama penerimaan kerja.
Sertifikat sering diperlakukan sebagai pelengkap administrasi, sementara keputusan akhir ditentukan oleh tes internal, studi kasus, wawancara berbasis masalah nyata, dan masa percobaan kerja.
Logika perusahaan jelas, biaya salah rekrut sangat mahal. Karena itu, perusahaan lebih percaya pada mekanisme seleksi yang mereka rancang sendiri, sesuai kebutuhan spesifik pekerjaan dan budaya organisasi. Sertifikat eksternal dianggap belum cukup menjamin job readiness.
Fenomena ini bukan penolakan terhadap konsep sertifikasi, melainkan cerminan ketidakpercayaan terhadap kualitas sinyal yang dihasilkan.
Krisis kepercayaan tersebut tidak berhenti pada keluhan informal. Ia berubah menjadi sorotan nasional ketika sejumlah kasus hukum menyeret aktor dalam ekosistem sertifikasi.
Misalnya, berdasarkan pemberitaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perkara korupsi penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi kerja sektor prioritas yang melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Bali.
Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyeret pengelola LSP, tetapi juga mantan Ketua BNSP, yang oleh pengadilan dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan ratusan juta rupiah yang disebut sebagai fee dalam proses sertifikasi.
Kasus ini penting bukan karena jumlah uangnya semata, tetapi karena melibatkan puncak otoritas sistem sertifikasi nasional.
Dampaknya bersifat sistemik. Sekali legitimasi runtuh, publik dan industri sulit membedakan mana LSP yang kredibel dan mana yang sekadar menjalankan rutinitas administratif.
Perlu ditegaskan, tidak semua LSP bermasalah. Banyak LSP dan asesor bekerja dengan integritas.
Namun dalam kebijakan publik, satu kasus saja cukup untuk merusak kepercayaan terhadap seluruh sistem, terutama ketika sistem tersebut bertumpu pada legitimasi moral dan profesional.
Kesalahan terbesar dalam membaca persoalan sertifikasi adalah menganggapnya sekadar masalah moral individu. Padahal, akar persoalan terletak pada desain insentif dan tata kelola.
Mayoritas LSP di Indonesia beroperasi dengan pembiayaan mandiri. Biaya uji kompetensi menjadi sumber pendapatan utama. Dalam desain seperti ini, keberlanjutan lembaga sangat bergantung pada volume peserta dan tingkat kelulusan.
Secara teori pengendalian manajemen, ini adalah situasi berisiko tinggi. Ketika pendapatan bergantung pada kelulusan, sementara kualitas sulit diukur dan jarang dievaluasi berbasis hasil kerja nyata, maka standar akan cenderung melunak.
Asesmen mudah berubah menjadi formalitas: dokumen lengkap, simulasi minimal, wawancara normatif, lalu sertifikat terbit.
Pengawasan memang ada seperti witness dan monitoring, tapi sebagian besar masih berfokus pada kepatuhan prosedural, bukan pada dampak riil di pasar kerja.
Pertanyaan kuncinya jarang diajukan: apakah lulusan sertifikasi benar-benar bekerja, bertahan, dan berkinerja baik?
Belajar dari negara maju
Jika menoleh ke negara maju, perbedaannya sangat mencolok. Di Jerman, sertifikasi vokasi tidak terpisah dari dunia kerja.
Sistem dual vocational training memastikan asesmen kompetensi dilakukan di lingkungan kerja nyata, dengan keterlibatan langsung kamar dagang dan industri. Sertifikat hanya terbit jika peserta lulus uji di konteks kerja riil.
Di Australia, lembaga sertifikasi diawasi ketat oleh regulator independen. Tingkat kelulusan yang terlalu tinggi tanpa korelasi dengan penempatan kerja justru menjadi sinyal risiko. Lembaga yang tidak kredibel bisa kehilangan akreditasi.
Di Inggris dan Kanada, banyak sertifikasi profesional dikelola oleh professional bodies. Sertifikat tidak bernilai jika tidak diakui oleh pemberi kerja. Reputasi lembaga menjadi mata uang utama bukan volume peserta.
Benang merahnya jelas, di negara maju, sertifikasi hidup atau mati oleh kepercayaan industri, bukan oleh banyaknya sertifikat yang dicetak.
Mengapa Indonesia tertinggal?
Indonesia masih cenderung memosisikan sertifikasi sebagai target program, bukan sebagai alat seleksi pasar kerja yang diuji oleh kebutuhan nyata industri.
Gejalanya terlihat dari cara kinerja sering dibaca: berapa banyak asesi yang tersertifikasi, berapa sertifikat terbit, berapa LSP/TUK bergerak, dan seberapa tinggi realisasi kegiatan.
Dalam Laporan Kinerja BNSP 2023, misalnya, capaian “asesi yang berhasil tersertifikasi” disebut mencapai sekitar 1,23 juta orang pada tahun tersebut—angka yang menunjukkan skala output yang besar, tetapi belum otomatis menjawab pertanyaan kunci: apakah mereka bekerja, bertahan, dan produktif setelah tersertifikasi?
Pola “output-driven” ini membuat sertifikasi mudah menjadi indikator administratif: semakin tinggi volume asesmen dan kelulusan, semakin terlihat “berhasil”.
Namun, pasar kerja tidak menilai keberhasilan dari volume sertifikat; pasar kerja menilai dari risk of hiring dan performance on the job.
Itulah sebabnya banyak perusahaan tetap mengandalkan mekanisme seleksi yang mereka percayai: tes internal, studi kasus, work sample test, probation, dan evaluasi supervisor karena biaya salah rekrut jauh lebih mahal daripada biaya mengabaikan sertifikat.
Masalahnya bukan sekadar persepsi. Berbagai kajian tentang sistem keterampilan Indonesia menekankan bahwa yang menentukan dampak pelatihan/sertifikasi adalah keterhubungan yang nyata dengan permintaan kerja dan kemampuan sistem untuk membaca kebutuhan keterampilan secara granular.
World Bank, misalnya, menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis permintaan (demand-side) dan penggunaan data kebutuhan kerja (termasuk data lowongan) agar pasokan keterampilan tidak berjalan sendiri tanpa “pembeli” yang jelas.
Jika sistem informasi pasar kerja (LMIS) dan umpan balik industri lemah, program keterampilan cenderung menghasilkan output (pelatihan/sertifikat) tanpa jaminan outcome (pekerjaan/produktivitas).
Karena itu, selama kelulusan masih menjadi KPI yang paling “terlihat”, sementara outcome kerja tidak diukur sistematis (placement rate 6–12 bulan, retensi, peningkatan produktivitas/upah, kepuasan pengguna), sertifikasi akan terus rentan menjadi “ritual kelulusan”.
Dan selama industri hanya dilibatkan secara simbolik—misalnya, sebatas seremonial kemitraan atau konsultasi awal—maka standar sertifikasi akan sulit menjadi standar rekrutmen.
Pasar kerja akan memilih jalannya sendiri: sertifikat nasional tetap ada, tetapi ditinggalkan dalam praktik.
Koreksinya jelas: negara perlu menggeser akuntabilitas dari berapa banyak yang lulus menjadi berapa banyak yang benar-benar bekerja dan berkinerja.
Negara-negara OECD telah lama menekankan pentingnya kebijakan keterampilan yang berorientasi hasil dan insentif yang mengarahkan sistem pendidikan/pelatihan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja—bukan sekadar mengejar output program.
Reformasi yang tidak bisa ditunda
Jika sertifikasi BNSP ingin kembali relevan dan dipercaya, reformasi harus bersifat struktural.
Pertama, ubah indikator keberhasilan LSP. Bukan jumlah peserta dan tingkat kelulusan, tetapi tingkat penempatan kerja, retensi 12 bulan, dan kepuasan pengguna tenaga kerja.
Kedua, wajibkan keterlibatan industri dalam asesmen, bukan sekadar dalam MoU atau seminar.
Untuk skema kerja, kelulusan harus melibatkan penilai dari dunia usaha. Para asesor wajib memiliki pengalaman kerja atau magang minimum 1 tahun di industri yang relevan sehingga eligible menilai kompetensi peserta sertifikasi bukan sekedar faham teori.
Ketiga, tegakkan pemisahan peran secara nyata antara lembaga pelatihan, LSP, dan asesor. Semakin terpisah rantai kepentingan, semakin kecil konflik kepentingan.
Keempat, publikasikan reputasi LSP secara transparan. Di negara maju, reputasi adalah sanksi paling efektif. Lembaga dengan kualitas rendah akan ditinggalkan pasar tanpa perlu kriminalisasi.
Sertifikasi BNSP kini benar-benar berada di persimpangan jalan kebijakan publik. Di satu sisi, ia memiliki peluang besar untuk berbenah dan kembali memainkan peran strategis sebagai instrumen peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional—terutama di tengah tekanan bonus demografi dan kompetisi tenaga kerja regional.
Namun di sisi lain, tanpa koreksi mendasar, sertifikasi berisiko terus berjalan sebagai formalitas administratif: sertifikat terbit, laporan kinerja terpenuhi, tetapi dunia kerja tetap mencari mekanisme seleksi alternatif yang mereka anggap lebih dapat dipercaya.
Realitas ini penting dicatat: dunia kerja tidak anti-sertifikasi. Yang ditolak bukan gagasan standarisasi, melainkan sertifikasi yang tidak menghadirkan nilai tambah nyata dalam menurunkan risiko rekrutmen dan meningkatkan produktivitas.
Kepercayaan tidak lahir dari regulasi, logo, atau label nasional, melainkan dari konsistensi antara kompetensi yang dijanjikan oleh sertifikat dan kemampuan nyata pemegangnya saat diuji di tempat kerja.
Karena itu, jika sertifikasi ingin kembali dihormati, ia harus menundukkan diri pada logika pasar kerja, bukan sebaliknya.
Artinya, standar, skema, dan proses asesmen harus diuji oleh kebutuhan riil industri; kelulusan harus bermakna kesiapan kerja; dan keberhasilan sistem harus diukur dari outcome, bukan sekadar output.
Pasar kerja akan selalu rasional: ia memilih sinyal yang paling akurat dan paling mengurangi risiko.
Jika sertifikasi mampu menyediakan sinyal tersebut secara konsisten, industri akan menggunakannya tanpa paksaan. Namun jika tidak, sertifikasi akan terus ada secara formal tetapi ditinggalkan secara praktis.
Tag: #sertifikasi #bnsp #ketika #standar #nasional #ditinggalkan #pasar #kerja