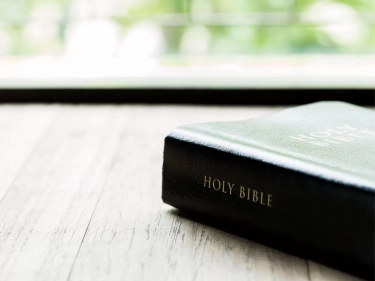Menyoal Co-Payment Asuransi Kesehatan ala OJK
BEBERAPA minggu terakhir, konsumen jasa asuransi, khususnya asuransi dibuat resah dan gelisah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK mengeluarkan surat edaran SE OJK No. 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Produk Asuransi Kesehatan.
Inti sari dari SE OJK No. 7/2025 adalah konsumen dibebani 10 persen biaya, jika akan melakukan klaim asuransinya, misalnya untuk rawat jalan. Jadi konsumen harus membayar 10 persen dari total biaya, tapi maksimal Rp 3.000.000.
Surat edaran ini tentu membuat heboh dan banyak penolakan, baik dari konsumen, pemerhati asuransi dan lembaga konsumen, seperti FKBI (Forum Konsumen Berdaya Indonesia) dan YLKI.
Tampaknya DPR, khususnya Komisi XI, mendengarkan kegelisahan publik sebagai konsumen jasa asuransi.
Klimaksnya Komisi XI DPR meminta OJK untuk menunda atau menangguhkan SE OJK No.7 Tahun 2025. Dan OJK menyepakati rekomendasi Komisi XI DPR tersebut.
Namun jika ditelisik, rekomendasi Komisi XI DPR tidak serta merta memuaskan publik sebagai konsumen jasa asuransi. Bahkan pada titik tertentu hanya "omon omon" saja.
Terhadap rekomendasi Komisi XI atas SE OJK No. 07/2025, berikut beberapa catatan kritisnya.
Pertama, rekomendasi tersebut bersifat ambigu karena hanya menangguhkan/menunda saja. Dengan kata lain, Komisi XI DPR tidak serius menyerap aspirasi publik, bahkan hanya setengah hati saja.
Pasalnya, kalau hanya menunda/menangguhkan, maka suatu saat OJK akan memberlakukan SE OJK tersebut.
Kedua, bahkan rekomendasi Komisi XI DPR justru akan makin menguatkan SE OJK tersebut dan akan ditingkatkan menjadi produk hukum yang lebih kuat, yakni "Peraturan OJK". Lah, ini malah makin berpotensi merugikan kepentingan konsumen.
Seharusnya jika memang berpihak pada kepentingan publik, maka DPR meminta OJK untuk membatalkan SE OJK No.7/2025, dan meminta tidak mengulanginya lagi dengan membuat SEOJK/POJK serupa.
Kenapa mesti dibatalkan? Sebab filosofi SEOJK No.7/2025 terkandung spirit yang sesat pikir, sebab sangat melemahkan dan menjadikan konsumen asuransi produk kesehatan sebagai "kambing hitam". Lah, kok bisa?
Spirit SEOJK No.7/2025 disahkan dengan alasan untuk mengurangi praktik "fraud" yang dilakukan konsumen, over utilitas, dan bahkan tingginya inflasi di sektor kesehatan. Ketiga alasan itu sangat tidak adil.
Misalnya, dugaan praktik fraud di sektor pelayanan kesehatan pelakunya multi stakeholders, bukan hanya konsumen. Namun, kenapa hanya konsumen yang dijadikan tertuduh, dan kemudian dibebani co-payment sebesar 10 persen?
Dugaan over utilitas oleh konsumen juga bisa dimitigasi dengan membuat prasyarat yang lebih ketat. Misalnya, harus disertai data riwayat kesehatan yang detail via hasil medical check up; sehingga nantinya tak akan terjadi over utilitas oleh konsumen.
Atau, OJK bisa membuat aturan bahwa premi untuk perokok aktif bisa lebih tinggi dibanding nonperokok. Sebab seorang perokok aktif punya risiko kesehatan lebih tinggi.
Jadi over utilitas justru dipicu terlalu longgarnya aturan saat konsumen akan menjadi peserta asuransi kesehatan.
Dan terkait tingginya inflasi di sektor kesehatan, yang katanya mencapai 12,5 persen, itu tugas dan tanggung jawab regulator, bahkan pemerintah untuk mengintervensi. Jangan konsumen dijadikan tameng untuk menurunkan tingginya inflasi tersebut.
Pemerintah dan OJK harus mengulik dari sisi hulu hingga hilir, agar tingginya inflasi di sektor kesehatan bisa diturunkan, sebagaimana inflasi secara keseluruhan.
Di sisi lain, dalam kasus yang lebih sistemik, dugaan moral hazard bukan hanya dilakukan oleh konsumen atau pelayanan kesehatan saja, tetapi juga oleh pelaku usaha asuransi itu sendiri. Yakni dengan menyelundupkan klausula baku dalam perjanjian standarnya (di dalam polisnya).
Klausula baku inilah yang sangat merugikan konsumen, dan hal ini terlarang menurut UU Perlindungan Konsumen.
Justru OJK kita minta untuk menjadi pengawas yang adil terhadap praktik klausula baku, atau bahkan menyeragamkan perjanjian standar.
Jadi seharusnya OJK tidak menghidupkan lagi SE OJK atau bahkan POJK, untuk membenani konsumen dengan co-payment ini.
Praktik co-payment justru akan makin menurunkan inklusivitas berasuransi masyarakat Indonesia yang terbilang masih rendah, hanya 13,5 persen saja.
Lagi pula, tidak semua perusahaan asuransi butuh co-payment, tergantung kemampuan cash flow masing-masing perusahaan asuransi.