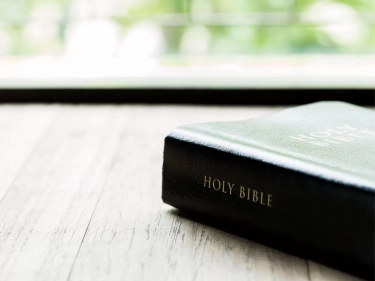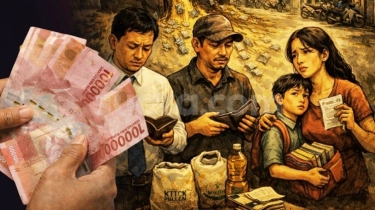Coretax dan Karut Marut Penerimaan Negara
CORETAX, sistem baru administrasi perpajakan, diperkenalkan dengan harapan mempercepat digitalisasi dan efisiensi pemungutan pajak.
Namun, seperti kebanyakan ambisi besar yang tidak disertai kesiapan teknis, ia justru menjadi penghambat.
Lebih dari sekadar ketidaksiapan teknis, ada kemungkinan lain yang turut menjadi faktor penghambat: masih adanya pihak-pihak yang resisten terhadap sistem perpajakan yang lebih canggih.
Sistem ini berpotensi membongkar praktik-praktik lama, membuat perpajakan lebih transparan, dan mengungkap apa yang selama ini mereka sembunyikan.
Resistensi ini dapat berasal dari berbagai pihak yang selama ini diuntungkan oleh celah sistem yang lama, baik dari dalam birokrasi maupun dari wajib pajak besar yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo.
Penerapan sistem yang tergesa-gesa ditambah komitmen setengah hati, membuat sistem ini tidak siap dijalankan sepenuhnya, memaksa pemerintah untuk tetap menggunakan sistem lama.
Sistem perpajakan tidak stabil, yang justru memperburuk penerimaan negara yang sudah menghadapi tantangan berat. Akibatnya, kita kini memiliki dua sistem yang berjalan bersamaan— ironi dalam upaya modernisasi.
Seorang penguasa yang baik, kata Adam Smith dalam The Wealth of Nations, harus tahu dari mana uangnya berasal dan ke mana ia pergi.
Namun, di negeri ini, uang yang seharusnya menjadi hak negara sering kali memiliki cara sendiri untuk menguap sebelum sampai ke kas negara.
Pajak, yang seharusnya menjadi tulang punggung penerimaan negara, kini menghadapi hambatan yang tidak sepele: peraturan yang menguntungkan segelintir orang, serta kebocoran anggaran yang tak kunjung tersumbat.
Tak hanya itu, revisi kebijakan perpajakan yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan malah menambah ketidakpastian.
Formula baru tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 21, yang berlaku sejak tahun lalu, justru mengoreksi setoran pajak.
Sementara rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang batal diterapkan secara menyeluruh semakin mempersempit ruang fiskal.
Dengan segala kerumitan ini, target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun terlihat seperti puncak gunung yang semakin menjulang, sementara pemerintah hanya punya seutas tali rapuh untuk mendakinya.
Bercermin kepada negara-negara maju seperti Jerman dan Kanada, mereka telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajaknya dengan sistem digitalisasi yang lebih matang.
Jerman, misalnya, dengan sistem Elster yang telah diterapkan sejak 1996, berhasil meningkatkan kepatuhan pajak hingga 95 persen.
Sementara itu, Kanada melalui Canada Revenue Agency (CRA) mampu mengurangi celah penghindaran pajak hingga 10 persen dengan pendekatan berbasis data dan pengawasan ketat.
Sebaliknya, Indonesia masih berkutat dengan tingkat kepatuhan pajak yang rendah, hanya sekitar 70 persen wajib pajak terdaftar yang benar-benar membayar pajak.
Namun, permasalahan uang negara tentu bukan hanya tentang pajak. Di sisi lain, pemborosan anggaran dan korupsi masih menjadi luka yang menganga.
Anggaran kementerian dan lembaga dipangkas demi menyeimbangkan keuangan negara. Namun di saat yang sama, kebocoran anggaran terjadi dalam skala besar.
Tahun 2023, Indonesia mengalami kebocoran keuangan negara akibat korupsi sebesar Rp 81 triliun, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Skandal demi skandal meledak seperti bom waktu: korupsi di proyek infrastruktur, pertambangan, penyalahgunaan dana sosial, hingga permainan anggaran di tubuh BUMN yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, justru menggerogoti negara.
Kita pun bertanya: berapa banyak lagi yang harus dikorbankan sebelum uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat?
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah sering kali mengulang pola yang sama: menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi—tahun ini, targetnya 8 persen, tetapi kurang terlihat komitmen nyata.
Kita memang memiliki pepatah yang mengatakan "gantungkan cita-citamu setinggi langit", tetapi harusnya juga realistis.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina hanya ditargetkan 6-7 persen dengan strategi yang lebih realistis, yakni penguatan industri ekspor dan peningkatan investasi langsung.
Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan belanja negara yang tidak efisien dan bergantung pada sumber daya alam yang semakin terbatas.
Lebih ironis, negara ini kerap kali kehilangan haknya sendiri karena aturan yang dibuatnya sendiri.
Revisi Undang-undang BUMN yang disahkan pada 4 Februari lalu, misalnya, menggeser kewenangan negara dalam mengatur dan mengawasi perusahaan pelat merah.
Ditambah dengan penegasan dalam klausul bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara.
Ini mengindikasikan bahwa segala bentuk penyertaan modal negara dalam BUMN akan dianggap sebagai investasi belaka, terlepas dari sumber dananya yang berasal dari pajak rakyat.
Bahkan, ketika terjadi kerugian, pemerintah dapat berdalih bahwa itu adalah risiko bisnis semata, bukan kerugian keuangan negara.
Revisi ini lebih banyak memberikan celah bagi kepentingan-kepentingan yang lebih lihai dalam memainkan regulasi penerimaan negara.
Padahal tanpa celah yang lebih dibuka lebar saja, korupsi di BUMN sudah demikian besar. Pada tahun 2023, total kerugian negara akibat korupsi di BUMN mencapai Rp 42 triliun, sebagian besar berasal dari sektor energi dan infrastruktur.
Di hadapan semua ini, kita tidak bisa tidak mengingat kembali peringatan Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel: "Masalah dengan ekonomi bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi distribusinya yang tidak adil."
Dalam kasus Indonesia, ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh kebijakan yang setengah matang dan pengawasan yang lemah.
Sementara rakyat kecil dipaksa membayar pajak hingga rupiah terakhir, para pemilik modal besar memiliki seribu cara untuk menghindari kewajiban mereka.
Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah pertama, memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan memastikan Coretax dapat berjalan optimal sebelum diterapkan secara penuh.
Pemerintah harus menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan sistem digital pajak yang aman dan andal, serta memberikan pelatihan kepada petugas pajak untuk memastikan kelancaran implementasi.
Kedua, memperketat pengawasan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan besar dan individu kaya melalui reformasi aturan perpajakan yang lebih transparan dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
Pembentukan lembaga independen yang bertugas mengaudit pajak perusahaan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Ketiga, mencegah kebocoran keuangan negara dengan meningkatkan transparansi anggaran dan sistem pengadaan barang dan jasa yang berbasis digital untuk mengurangi potensi korupsi.
Penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus penyalahgunaan anggaran harus didukung dengan kebijakan yang tidak melemahkan kewenangannya.
Keempat, menyeimbangkan kembali strategi fiskal dengan tidak hanya mengandalkan pajak, tetapi juga memperluas basis penerimaan negara melalui sektor non-pajak seperti optimalisasi BUMN yang dikelola dengan baik, peningkatan investasi yang berkualitas, dan pengembangan industri kreatif yang memiliki potensi besar.
Dengan langkah-langkah ini, penerimaan negara tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga dari sumber daya yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Apabila pembenahan sistem dan penguatan antikorupsi tidak dilaksanakan sepenuh hati, kembali, rakyat lah yang harus menanggung akibat dari semua ini.
Mereka lah yang selalu menjadi objek penderitaan dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik, layanan publik yang kian terpangkas, dan janji pertumbuhan ekonomi yang selalu terdengar indah, tapi tak pernah benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari.
Mungkin, inilah saatnya kita bertanya: sampai kapan negara ini terus berharap tanpa komitmen yang konkret?
Sebab, di balik setiap revisi kebijakan, setiap target yang dicanangkan, dan setiap angka dalam laporan keuangan negara, ada kehidupan nyata yang terus menunggu kepastian. Dan pertanyaan itu, hingga kini, belum menemukan jawaban.