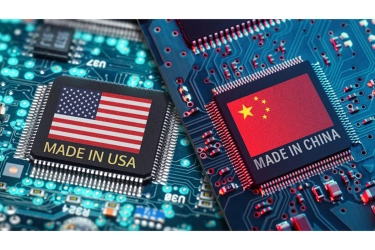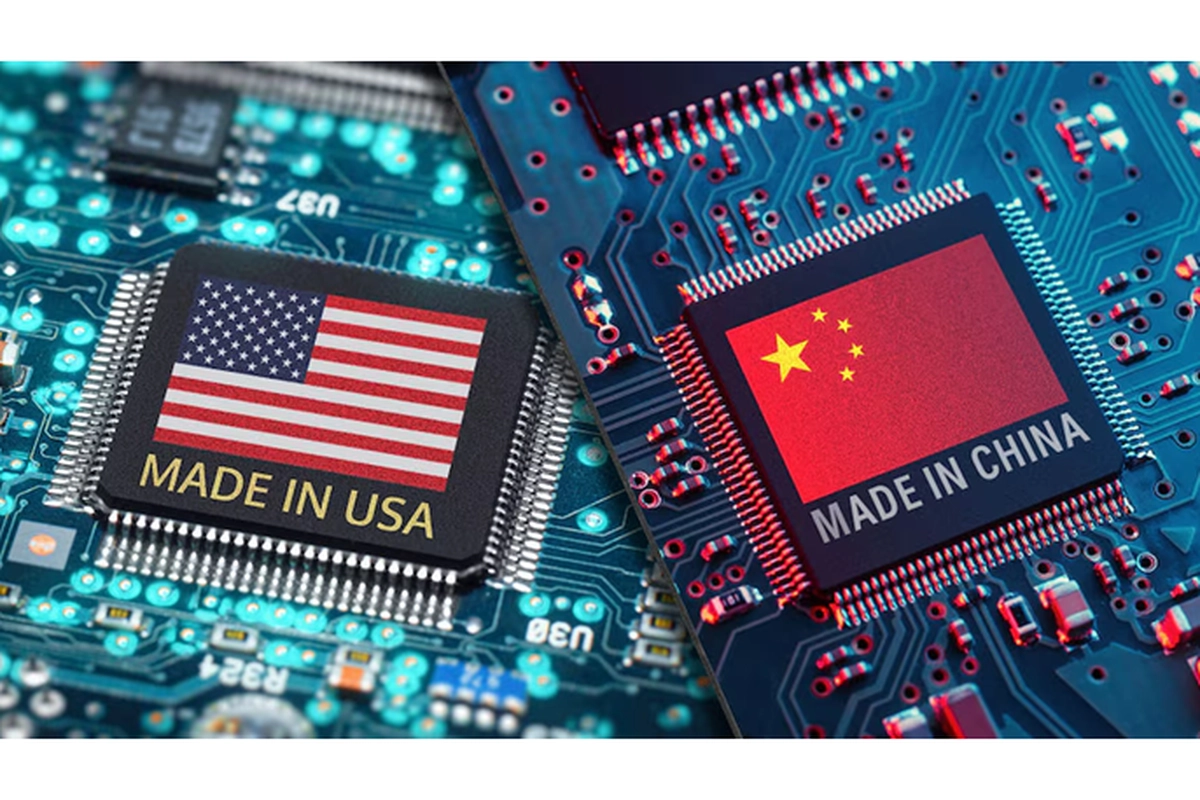
Persaingan AI Global, China Ungguli AS dalam Hal Ini
Ringkasan berita:
- Persaingan AI AS vs China kini ditentukan pasokan listrik, bukan hanya model dan chip AI, karena kebutuhan energi pusat data melonjak tajam seiring ekspansi kecerdasan buatan.
- China dinilai lebih unggul dalam "AI race" berkat kesiapan infrastruktur energi dan investasi besar-besaran di listrik terbarukan, sementara AS mulai kewalahan menghadapi keterbatasan pasokan listrik data center.
- China juga mengembangkan chip AI analog super efisien, diklaim 1.000 kali lebih cepat dan hanya memakai 1 persen energi GPU digital, berpotensi mengubah peta persaingan AI global ke depan.
- Persaingan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI race) antara Amerika Serikat dan China kian memanas. Namun, di balik adu kecanggihan model dan chip AI, muncul satu faktor krusial yang mulai dianggap menentukan arah perlombaan AI ini, yakni pasokan listrik.
Sejumlah pengamat menilai China kini berada di posisi lebih unggul dibanding AS dalam mendukung ekspansi industri AI. Bukan karena algoritma atau semikonduktor semata, melainkan kesiapan infrastruktur energi.
Laporan Fortune menyebutkan bahwa listrik telah menjadi “bottleneck” atau titik lemah utama dalam pengembangan AI di AS. Hal ini membuat Negeri Paman Sam cukup keteteran dalam persiapan perlombaan AI.
Sebab, model AI modern dan canggih membutuhkan daya komputasi sangat besar. Ini berarti konsumsi listrik dan air dalam jumlah masif di pusat data (data center).
Sementara itu, China dinilai sudah lebih dulu mengantisipasi kebutuhan tersebut dengan investasi agresif pada jaringan listrik nasionalnya.
Editor Tech Buzz China, Rui Ma, yang sempat melihat langsung perkembangan teknologi AI di China, menggambarkan perbedaan kedua negara dengan cukup kontras.
“Energi dianggap sebagai masalah yang sudah selesai di China. Ke mana pun kami pergi, ketersediaan listrik dianggap sebagai hal yang pasti tersedia,” tulis Ma.
Menurut Ma, kondisi ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat, di mana pertumbuhan AI kini justru sering tersendat oleh perdebatan soal kapasitas listrik, konsumsi energi pusat data, hingga keterbatasan jaringan.
 Ilustrasi data center AI. Permintaan tinggi terhadap aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan cloud computing mendorong transaksi data center senilai setidaknya 5,6 miliar dolar AS (sekitar Rp 91,9 triliun) di kawasan Asia-Pasifik pekan ini.
Ilustrasi data center AI. Permintaan tinggi terhadap aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan cloud computing mendorong transaksi data center senilai setidaknya 5,6 miliar dolar AS (sekitar Rp 91,9 triliun) di kawasan Asia-Pasifik pekan ini.
AI memang dikenal sebagai teknologi yang rakus energi. Data center yang menopang model bahasa besar (large language model/LLM) seperti ChatGPT berisi ribuan hingga jutaan chip yang harus bekerja tanpa henti, sekaligus membutuhkan sistem pendingin intensif agar tetap stabil.
Alhasil tak heran, ketersediaan listrik menjadi faktor penentu seberapa cepat sebuah negara bisa memperluas infrastruktur AI.
Di Amerika Serikat, keterbatasan energi mulai memunculkan solusi ekstrem. Salah satu contohnya datang dari perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, yang dilaporkan menggunakan sekitar 35 generator gas metana portabel di area parkir pusat datanya di Memphis.
Langkah ini menuai kritik karena menimbulkan polusi udara dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar.
Di sisi lain, China relatif tidak menghadapi masalah serupa. Sepanjang 2024, China menyumbang hampir 65 persen dari total pembangunan energi terbarukan global.
Negari Tirai Bambu memasang panel surya dan turbin angin dalam skala besar, bahkan hingga disebut menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2) nasionalnya turun untuk pertama kalinya. Ini terjadi meski permintaan energi terus mencetak rekor.
Keunggulan ini membuat China mampu mengembangkan pusat data dan sistem AI tanpa harus terhambat isu pasokan listrik.
Sementara Amerika Serikat masih mencari jalan keluar, termasuk wacana kontroversial dari Presiden AS Donald Trump yang sempat melontarkan ide menghubungkan langsung pusat data AI dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.
Di tengah lonjakan kebutuhan energi nasional yang belum pernah setinggi ini, AS kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi ingin memimpin perlombaan AI global, di sisi lain infrastruktur energinya belum siap mengimbangi laju konsumsi teknologi tersebut.
Sebaliknya, China tampak melaju stabil, nyaris tanpa hambatan energi. Namun, di sisi chip AI, China sebenarnya bisa dibilang masih bergantung pada GPU dari Nvidia untuk model-model AI canggih dan populernya, termasuk DeepSeek R1.
Namun, penggunaan chip GPU tercanggih dari Nvidia (chip seri Blackwell) tampaknya belum bisa leluasa, lantaran rentan menjadi alat politik AS,
Seperti diketahui, AS sempat membatasi pengiriman chip GPU tercanggih Nvidia (chip seri Blackwell) ke China dengan dalih keamanan nasional. Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump mulai memberikan lampu hijau, asalkan mendapat kompensasi 25 persen.
China bikin chip AI analog
 Ilustrasi chip AI buatan China.China dilaporkan terus berupaya mengembangkan chip AI canggihnya sendiri. Beberapa waktu lalu eneliti di China dilaporkan berhasil mengembangkan chip AI analog yang dapat bekerja hingga 1.000 kali lebih cepat dibanding GPU kelas atas saat ini, termasuk produk keluaran Nvidia dan AMD.
Ilustrasi chip AI buatan China.China dilaporkan terus berupaya mengembangkan chip AI canggihnya sendiri. Beberapa waktu lalu eneliti di China dilaporkan berhasil mengembangkan chip AI analog yang dapat bekerja hingga 1.000 kali lebih cepat dibanding GPU kelas atas saat ini, termasuk produk keluaran Nvidia dan AMD.
Chip analog di sini adalah chip yang mampu melakukan proses komputasi langsung melalui rangkaian fisiknya, tanpa mengandalkan sistem pemrosesan digital biner seperti prosesor dan GPU modern.
Penelitian terkait chip tersebut dipublikasikan dalam jurnal Nature Electronics, dan menyebut bahwa teknologi baru ini juga mampu mengatasi masalah “turun-temurun” dalam sistem komputasi analog, seperti akurasi rendah dan masalah implementasi praktis selama lebih dari satu abad.
Selain unggul dalam kecepatan, chip AI analog buatan ilmuwan China ini juga disebut sangat efisien.
Dalam risetnya, para peneliti menjelaskan bahwa perangkat tersebut dapat mencapai presisi setara prosesor digital, namun hanya menggunakan 1 persen energi dari konsumsi daya chip digital konvensional, seperti Nvidia H100.
Peningkatan efisiensi energi ini diperoleh karena chip memproses data langsung di dalam perangkat kerasnya, sehingga mengurangi kebutuhan transfer data dan konsumsi daya secara signifikan.
Chip ini dirancang menggunakan arsitektur baru dan memanfaatkan sel memori RRAM (Resistive Random-Access Memory) sebagai bagian dari sistem komputasinya.
Para ilmuwan menilai chip analog ini sangat relevan dengan tantangan teknologi masa depan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar, seperti kecerdasan buatan dan teknologi 6G.
Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal produksi komersial atau rencana implementasi industri dari teknologi chip analog buatan China ini.