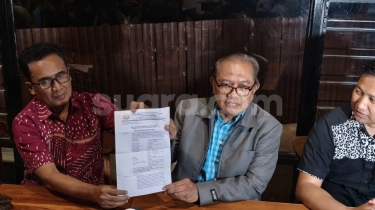Mengapa Ambang Batas Parlemen Jadi Isu Sensitif Parpol-parpol di DPR?
- Isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hampir selalu menjadi sorotan setiap kali pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu digulirkan DPR.
Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa ambang batas menyentuh langsung kepentingan elektoral partai politik.
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, ambang batas parlemen bukan sekadar persoalan desain demokrasi, melainkan juga berkaitan erat dengan untung-rugi politik bagi partai peserta pemilu.
“Isu ambang batas parlemen selalu menjadi sorotan setiap revisi UU Pemilu karena ambang batas menyangkut langsung kepentingan elektoral partai politik,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/1/2026).
Baca juga: Pakar Usul Parliamentary Threshold Diganti Ambang Batas Pembentukan Fraksi DPR RI
Menurut Titi, ambang batas parlemen pada akhirnya menentukan partai mana yang dapat masuk parlemen dan partai mana yang harus tersingkir dari kompetisi politik nasional.
“Jadinya, isu ambang batas bukan sekadar soal desain demokrasi, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersingkir dalam kompetisi politik,” kata dia.
Oleh karena itu, Titi menilai wajar apabila isu ambang batas selalu menjadi salah satu topik paling sensitif dan paling diperebutkan dalam setiap agenda perubahan UU Pemilu.
“Maka wajar jika ambang batas selalu menjadi salah satu isu paling sensitif dan paling ‘diperebutkan’ dalam setiap agenda perubahan UU Pemilu,” jelasnya.
Baca juga: PKS: Ambang Batas Parlemen Masih Diperlukan untuk Jaga Stabilitas Politik
Titi menjelaskan, secara prinsip ambang batas parlemen memang dapat dipahami sebagai instrumen untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen sekaligus mencegah fragmentasi yang berlebihan.
Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kebijakan tersebut kerap menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis karena berdampak langsung pada hilangnya suara sah pemilih.
“Dalam praktiknya di Indonesia, ambang batas ini juga selalu menimbulkan dilema konstitusional dan demokratis, karena secara langsung berimplikasi pada hilangnya suara sah pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi atau fenomena suara terbuang,” ujar Titi.
Baca juga: PDI-P Usul RUU Pemilu Pertahankan Ambang Batas Parlemen Tanpa Nominal Persentase
Atas dasar itu, lanjut Titi, perdebatan mengenai ambang batas parlemen seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan perlu atau tidak, melainkan menyentuh aspek rasionalitas dan proporsionalitas kebijakan tersebut.
Dia mengingatkan, ambang batas yang ditetapkan terlalu tinggi berpotensi menjadi mekanisme eksklusi politik yang menguntungkan partai-partai besar dan mempersempit ruang representasi.
Sebaliknya, penghapusan ambang batas tanpa disertai desain kelembagaan alternatif juga dinilai berisiko terhadap efektivitas kinerja parlemen.
“Sebaliknya, jika dihapus tanpa desain kelembagaan lain, perlu juga dipikirkan dampaknya terhadap efektivitas parlemen,” kata dia.
Baca juga: Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen di RUU Pemilu
Titi pun menegaskan bahwa revisi UU Pemilu seharusnya tidak lagi dijadikan arena transaksi politik jangka pendek antar-elite, melainkan diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan.
“Pada titik ini, yang lebih penting adalah memastikan revisi UU Pemilu tidak lagi menjadi arena transaksi aturan main, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat representasi, keadilan suara, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan,” tutur Titi.
 Pakar hukum tata negara sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam diskusi daring, Minggu (27/7/2025).
Pakar hukum tata negara sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam diskusi daring, Minggu (27/7/2025).
Dia menilai, pengaturan ambang batas parlemen semestinya disusun melalui kajian terbuka berbasis data, evaluasi empiris pemilu sebelumnya, serta perdebatan publik yang partisipatif.
Titi juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Baca juga: PAN Usul Revisi UU Pemilu Hapus Ambang Batas Pilpres dan Pileg
Namun, MK memberikan sejumlah rambu agar perumusan ambang batas tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
“MK memberi rambu bahwa besaran threshold harus tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat agar tidak terlalu banyak suara pemilih terbuang, ditetapkan secara rasional dan proporsional, serta didasarkan pada evaluasi empiris pemilu sebelumnya,” ungkap Titi.
MK juga menekankan pentingnya proses pembahasan yang terbuka dan partisipatif serta perlunya keseimbangan antara tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dan keadilan representasi politik.
Baca juga: Tak Ada Oposisi di Era Prabowo-Gibran, Cukupkah dengan “Penyeimbang”?
Perdebatan Ambang Batas Jelang RUU Pemilu
Untuk diketahui, isu mengenai aturan ambang batas parlemen menjadi perdebatan menjelang dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu.
Sebelumnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengusulkan penurunan ambang batas parlemen secara bertahap dalam dua siklus pemilu.
Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandez mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2029 dan 3 persen pada pemilu berikutnya.
Baca juga: MK Diminta Tetapkan Ambang Batas Parlemen Maksimal 2,5 Persen
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai, ambang batas menyia-nyiakan aspirasi jutaan pemilih karena suara partai yang tidak lolos ambang batas tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
Di sisi lain, sejumlah partai politik seperti PDI-P, PKS, dan Partai Nasdem berpandangan bahwa ambang batas parlemen tetap diperlukan.
Bahkan, Nasdem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 6 hingga 7 persen.
Partai-partai tersebut menilai ambang batas parlemen dibutuhkan untuk mendorong institusionalisasi partai politik dan menciptakan pemerintahan yang efektif, meskipun memiliki konsekuensi berupa hilangnya sebagian suara pemilih.
Tag: #mengapa #ambang #batas #parlemen #jadi #sensitif #parpol #parpol