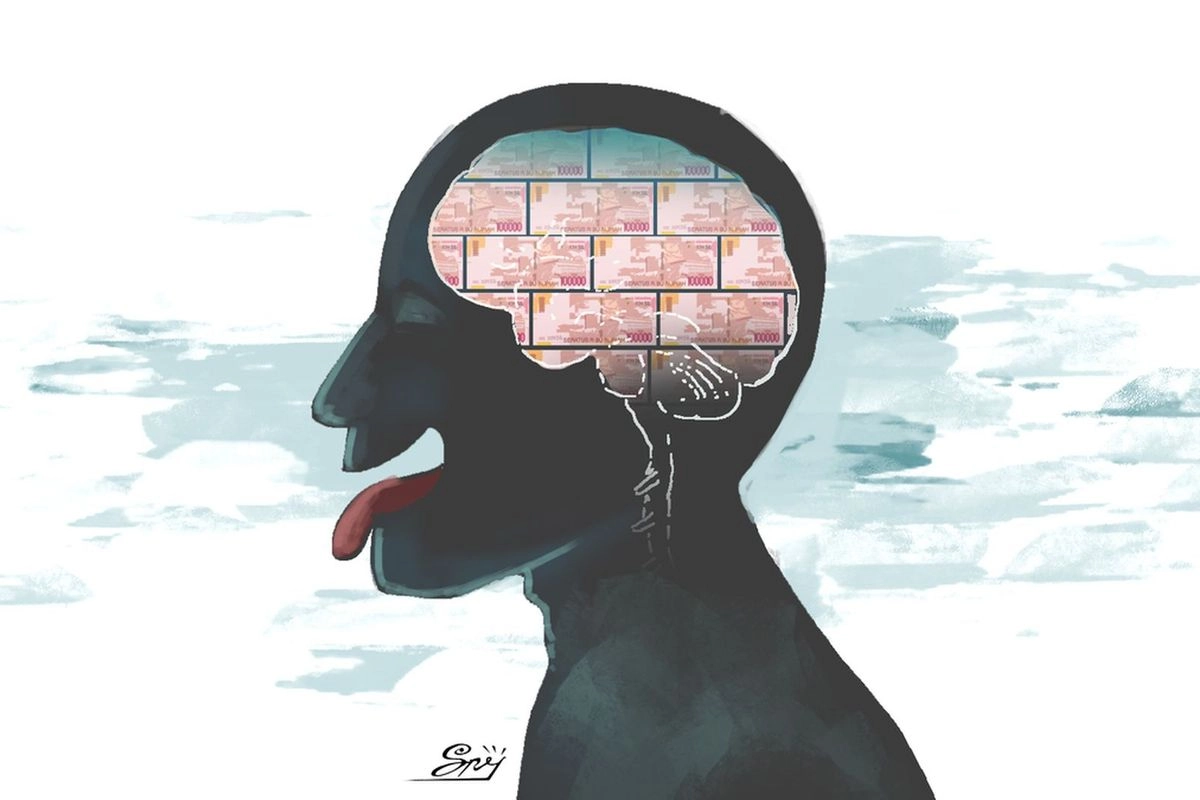
Negara Mengejar Aset, Bukan Sekadar Pelaku Korupsi
KORUPSI selalu meninggalkan dua jejak. Pertama adalah pelaku: nama, wajah, jabatan, dan perkara yang disidangkan.
Kedua—yang kerap lebih sunyi—adalah aset: uang, tanah, properti, saham, rekening, yang berpindah tangan cepat, melampaui prosedur hukum, bahkan melintasi batas negara.
Selama bertahun-tahun, negara kita lebih tekun mengejar jejak pertama. Kita sibuk memburu orangnya, menunggu vonisnya, menghitung lamanya hukuman. Sementara jejak kedua sering dibiarkan memudar.
Padahal, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan ekonomi. Motifnya sederhana dan keras: keuntungan.
Jika motif itu tidak diputus, jika hasil kejahatan tetap bisa dinikmati, maka penjara hanya menjadi jeda. Vonis menjadi simbol. Negara bisa menang di ruang sidang, tetapi kalah di balik pintu bank.
Kesadaran inilah yang mulai menguat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada 15 Januari 2026, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, memaparkan draf RUU Perampasan Aset yang disusun dalam delapan bab dengan kerangka pengaturan yang secara sadar menggeser fokus: dari semata menghukum pelaku, menuju mengambil kembali hasil kejahatan.
Ini bukan sekadar perubahan teknis legislasi. Ia adalah perubahan cara negara membaca kejahatan.
Paparan Badan Keahlian DPR memberi penegasan penting: perampasan aset ditempatkan sebagai instrumen pemulihan.
Negara tidak hanya ingin memenjarakan, tetapi juga memulihkan apa yang telah dirampas dari kepentingan publik.
Uang hasil korupsi bukan angka abstrak. Ia adalah sekolah yang tak dibangun, rumah sakit yang tertunda, layanan publik yang memburuk.
Dalam kerangka itu, RUU Perampasan Aset dibangun di atas dua mekanisme: perampasan berbasis putusan pidana dan perampasan tanpa putusan pidana pada kondisi tertentu.
Pembedaan ini krusial. Negara tidak sedang menghapus prinsip penghukuman, tetapi menyediakan jalan hukum ketika proses pidana tidak lagi efektif dijalankan.
Makna yang hendak ditegaskan sederhana, tetapi tegas: kejahatan tidak boleh tetap menguntungkan. Negara yang membiarkan hasil kejahatan aman dan diwariskan sesungguhnya sedang memelihara ketidakadilan.
Karena itu, perampasan aset tidak boleh dibaca sebagai ekspresi kekuasaan yang represif, melainkan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh penyalahgunaan wewenang.
Salah satu kekuatan paparan Badan Keahlian DPR terletak pada upaya konsolidasi. Selama ini, pengaturan perampasan aset tersebar di berbagai undang-undang dengan standar dan mekanisme yang tidak seragam.
Akibatnya, penegakan hukum kerap berjalan timpang: tegas di satu perkara, ragu di perkara lain.
RUU Perampasan Aset berusaha merapikan lanskap itu. Ia menyusun satu payung hukum yang memuat jenis aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan, hukum acara, pengelolaan aset, hingga kerja sama internasional.
Dengan desain ini, perampasan aset tidak lagi bergantung pada kreativitas penegak hukum semata, tetapi berada dalam kerangka normatif yang jelas.
Namun, desain hukum selalu mengandung konsekuensi. Karena itu, Badan Keahlian DPR menempatkan perampasan aset dalam relasi yang tidak saling meniadakan dengan hukum pidana.
Ia bukan pengganti proses pidana, melainkan pelengkap yang bekerja dalam kondisi tertentu dan melalui mekanisme yang dapat diuji di hadapan hakim.
Di sinilah negara hukum diuji: berani mengambil kembali aset kejahatan, tetapi juga berani memastikan bahwa prosesnya tunduk pada prinsip kehati-hatian dan pengawasan peradilan.
Risiko
Setiap terobosan hukum membawa risiko. RUU Perampasan Aset pun tidak kebal dari kekhawatiran.
Dalam pembahasan di Komisi III, muncul pengingat penting bahwa perampasan aset tidak boleh menjadi jalan pintas ketika proses pidana masih dapat berjalan normal.
Perampasan—terutama yang tidak berbasis putusan pidana—harus ditempatkan sebagai alternatif ketika pidana pokok menghadapi hambatan serius.
Peringatan ini patut dicatat, bukan untuk melemahkan gagasan, melainkan untuk menguncinya agar tidak disalahgunakan.
Risiko terbesar bukan terletak pada keberanian negara mengambil aset, melainkan pada kelengahan dalam mengawasinya.
Namun, risiko juga tidak boleh dijadikan dalih untuk menunda. Sejarah pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa ketakutan sering kali lebih melumpuhkan daripada kesalahan.
Sementara hukum ragu-ragu, kejahatan bergerak lincah, memanfaatkan celah dan waktu.
Karena itu, dukungan terhadap paparan Badan Keahlian DPR justru harus dibarengi dengan penguatan kontrol, bukan pembatalan arah.
Negara yang mengejar aset, bukan sekadar pelaku, sedang menentukan arah baru. Dari hukum yang reaktif menuju hukum yang korektif. Dari penghukuman simbolik menuju pemulihan substantif. Dari sekadar vonis menuju keadilan yang dirasakan.
RUU Perampasan Aset memang bukan obat mujarab. Ia tidak akan menghapus korupsi dalam semalam. Namun, ia adalah pernyataan sikap: bahwa republik ini tidak lagi rela hasil kejahatan hidup nyaman di balik prosedur.
Paparan Kepala Badan Keahlian DPR patut dibaca sebagai undangan untuk melampaui kebiasaan lama. Kita diajak melihat bahwa inti kejahatan ekonomi bukan hanya pada siapa yang bersalah, tetapi pada apa yang dirampas dari publik.
Negara yang berhenti pada penjara sering kali kehabisan daya. Negara yang berani mengejar aset sedang berusaha memulihkan martabatnya.
Dalam korupsi, keadilan bukan hanya soal menghukum orangnya, tetapi memastikan bahwa hasil kejahatan benar-benar kembali kepada republik.
Tag: #negara #mengejar #aset #bukan #sekadar #pelaku #korupsi










