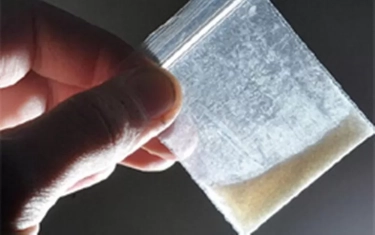Melawan Syahwat Oligarki di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD
BAYANGKAN sebuah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bukanlah beras atau daging, tapi nasib dan masa depan sebuah kabupaten atau provinsi.
Di pasar tersebut, pembelinya hanya segelintir orang yang duduk di kursi empuk parlemen daerah atau DPRD dan penjualnya adalah mereka yang memiliki modal tak berseri di daerah atau bahkan justru dari Jakarta.
Inilah potret muram yang ingin dilukis oleh para penganjur wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD.
Dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas, mereka sebenarnya bukan sedang ingin memperbaiki keadaan, tapi sedang mengusulkan sistem yang layak disebut sebagai "grosir kekuasaan terpusat di daerah".
Sistem di mana rakyat hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, sementara nasib mereka ditentukan melalui "logika dagang sapi" yang ingin dilembagakan secara resmi.
Pilkada langsung, dengan segala keriuhan dan biaya mahalnya, diakui atau tidak, sebenarnya adalah satu-satunya momen di mana seorang petani, buruh, peternak maupun guru honorer di seluruh Indonesia memiliki kekuatan tawar yang setara dengan seorang menteri atau pengusaha besar.
Karena di depan kotak suara, satu suara bernilai sama dan satu suara sangatlah menentukan.
Oleh karena itu, wacana mengembalikan pemilihan ke DPRD merupakan upaya sistematis untuk mencabut "senjata" terakhir rakyat di daerah.
Jika ini terjadi, Indonesia tidak lagi bicara tentang kedaulatan rakyat, tapi tentang “elite capture”, istilah di dalam ilmu politik yang terkait dengan penyanderaan kekuasaan oleh segelintir orang.
Artinya, di ruang-ruang gedung DPRD, boleh jadi argumen programatik dan visi-misi brilian akan kalah oleh tebalnya amplop, dan rencana strategis pembangunan daerah akan tunduk pada logika bagi-bagi jatah proyek.
Tentu ini bukanlah efisiensi, tapi diskon besar-besaran bagi para oligarki untuk membeli kepatuhan penguasa daerah tanpa perlu repot-repot menyapa rakyat di pasar-pasar becek dan pelosok-pelosok desa.
Secara akademis, sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya, argumen "politik uang" yang sering dipakai oleh pendukung Pilkada DPRD adalah argumen yang menyesatkan.
Para pendukung Pilkada tak langsung ini seolah berkata, "karena rakyat bisa disuap, maka hak pilihnya dicabut saja."
Bukankah logika tersebut seperti membakar lumbung padi hanya karena ada beberapa tikus di dalamnya?
Masalah korupsi kepala daerah pasca-terpilih bukan disebabkan oleh rakyat di daerah melakukan pemilihan secara langsung, tapi karena biaya "mahar" ke partai politik yang sangat mahal di satu sisi dan sistem pendanaan kampanye yang tidak transparan di sisi lain.
Jika pemilihan dipindah ke DPRD, apakah politik uang hilang? Tentu tidak. Yang terjadi adalah "efisiensi pasar politik" secara teknis, tapi sangat cacat secara moral.
Untuk mudahnya, mari kembali pada ilustrasi saya tempo hari. Jika dulu seorang kandidat harus menyebar uang ke sejuta orang, lalu saat Pilkada dialihkan ke DPRD, maka ia cukup menyuap 50 anggota Dewan.
Bagi para cukong, jelas-jelas perubahan tersebut berarti penghematan luar biasa. Namun, bagi demokrasi, perubahan tersebut adalah lonceng kematian.
Kondisi ini mengingatkan saya pada kegelisahan intelektual dua orang penulis buku "Tyranny of the Minority" (2024), Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.
Dua profesor dari Harvard ini mengingatkan bahwa ancaman terbesar demokrasi modern bukan lagi kudeta militer, melainkan penghancuran institusi demokrasi dari dalam oleh para elite yang terpilih secara sah.
Kedua guru besar Harvard yag juga penulis buku How Democracies Die itu menyoroti bagaimana aturan-aturan yang terlihat teknis dan sepele, seperti perubahan dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung alias penguatan peran lembaga perwakilan atas hak pilih populer rakyat, seringkali digunakan untuk memastikan bahwa minoritas elite tetap berkuasa di atas mayoritas rakyat.
Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, pesan buku ini sangat jelas dan terang. Sekali kita memberikan ruang bagi elite untuk memonopoli pilihan politik publik, maka kita sedang membuka pintu lebar-lebar pada “otoritarianisme baru”.
Dalam buku "Democracy's Discontent: A New Edition for Our Perilous Times" (2023), filsuf politik Michael J. Sandel juga pernah memberikan peringatan yang sangat keras bahwa demokrasi akan kehilangan “daya hidupnya” jika rakyat merasa tidak lagi memiliki peran dalam menentukan siapa pemimpinnya dan tidak punya kuasa untuk ikut memengaruhi arah kebijakan publik.
Menurut Sandel, ketika keputusan-keputusan krusial, seperti memilih pemimpin daerah, dipindahkan dari tangan publik ke tangan elite atau teknokrat, maka dalam konteks filsafat politik, yang terjadi sebenarnya adalah pengikisan martabat warga negara.
Artinya, di negara seperti Indonesia, Pilkada secara langsung bukan sekadar urusan teknis tentang coblos-mencoblos, tapi ritus pengakuan negara bahwa rakyat di pelosok daerah sekalipun memiliki kedaulatan yang sama dengan orang-orang besar yang berada di pusat-pusat kekuasaan atau para pemilik modal raksasa yang tak pernah mengetahui bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil.
Mencabut hak pilih rakyat di daerah berarti memperlebar jurang keterasingan politik: rakyat jadi orang asing di rumahnya sendiri. Bahkan, hilangnya rasa memiliki rakyat terhadap negara.
Dari sisi ekonomi politik, Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku fenomenal mereka, "The Narrow Corridor" (2019) juga cukup berhasil menjelaskan bahwa kemakmuran dan stabilitas bangsa hanya bisa dicapai melalui "lorong sempit" di mana terdapat keseimbangan yang sangat kuat antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat.
Jadi jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD, Indonesia sebenarnya sedang melemahkan masyarakat di satu sisi dan membiarkan "Leviathan" (negara/elite) bergerak liar tanpa kontrol langsung dari rakyat di sisi lain.
Karena itu, Acemoglu dan Robinson yang juga menulis buku Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty menegaskan bahwa bagaimanapun ceritanya, masyarakat harus terus terlibat secara aktif dalam proses politik untuk mencegah negara jatuh ke dalam pola ekstraktif, di mana kekuasaan dan ekonomi hanya dikeruk untuk kepentingan segelintir elite.
Apalagi, kata mereka, di negara berkembang, partisipasi langsung adalah instrumen utama untuk memastikan koridor keseimbangan itu tidak runtuh dan berubah menjadi “kediktatoran” oleh segelintir elite.
Oleh karena itu, sebelum kita terburu-buru mengambil jalan pintas berbahaya dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah korektif yang jauh lebih cerdas dan beradab serta mengedepankan rakyat.
Masalah mahalnya biaya politik dan korupsi pasca-terpilih adalah penyakit yang harus diobati dengan membenahi akarnya, bukan dengan mematikan hak politik rakyat di daerah.
Lebih lanjut, di dalam "Democracy Playbook 2025" yang diterbitkan oleh Brookings Institution juga ditekankan secara tegas bahwa di tengah gelombang kemunduran demokrasi global seperti hari ini, transparansi dan partisipasi langsung warga adalah "obat penawar" paling ampuh untuk melawan korupsi.
Dengan kata lain, solusi atas mahalnya biaya politik Pilkada bukanlah dengan “melenyapkan” hak pilih rakyat di daerah atas calon pemimpinnya, tapi dengan membersihkan saluran-saluran politik elektoral yang masih membuka peluang terjadinya korupsi di daerah.
Sehingga mengalihkan Pilkada ke DPRD justru melanggar prinsip transparansi yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kuasa di negara yang indeks persepsi korupsinya masih melangit seperti Indonesia.
Namun demikian, mengkritik wacana pengembalian Pilkada ke DPRD bukan berarti menutup mata pada berbagai keborokan yang ada pada sistem Pilkada langsung saat ini.
Perlu diakui bahwa biaya politik Pilkada memang “gila-gilaan” dan korupsi kepala daerah pasca-terpilih adalah kenyataan pahit politik di banyak daerah saat ini.
Sudah tidak terhitung cerita yang saya dengar tentang “penyunatan anggaran proyek daerah” sekian persen oleh seorang kepala daerah, yang diakui atau tidak, juga ikut menjadi penyebab utama mengapa daerah menjadi semakin sulit untuk maju.
Namun sekali lagi, solusinya bukanlah dengan membakar lumbung kedaulatan rakyat hanya karena ada tikus korupsi di dalamnya.
Pilkada membutuhkan pembenahan teknis yang radikal dan berani.
Pertama, digitalisasi total proses kampanye. Selama ini, sebagian besar biaya politik di daerah habis untuk baliho, bilboard, panggung hiburan, dan mobilisasi massa yang bersifat fisik.
Untuk itu, negara harus hadir dengan melarang penggunaan alat peraga fisik secara mandiri oleh kandidat.
KPU harus menjadi satu-satunya otoritas yang memfasilitasi iklan dan ruang kampanye digital bagi semua calon secara setara.
Dengan memindahkan arena pertarungan dari lapangan fisik ke ruang gagasan digital yang terverifikasi, dalam hitungan sederhana saya, bisa memangkas biaya logistik 7-10 persen.
Kedua, diperlukan audit forensik yang sangat ketat atas dana kampanye. Selama ini, laporan dana kampanye hanya formalitas administratif yang diakui atau tidak, sebenarnya penuh kepura-puraan dan manipulatif.
Sehingga diperlukan aturan yang memungkinkan diskualifikasi permanen bagi kandidat yang terbukti menerima aliran dana dari pihak ketiga yang melampaui batas, atau yang menggunakan dana tersebut untuk politik uang. Hukumannya harus bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar.
Selain itu, sepaket dengan audit forensik, ada baiknya juga dipertimbangkan kebijakan di mana negara juga harus menaikkan dana subsidi bagi partai politik untuk membiayai operasional mereka, dengan syarat partai tersebut dilarang keras memungut "mahar politik" dari para calon.
Jika ada partai yang tertangkap tangan menjual tiket pencalonan, maka partai tersebut harus dilarang ikut serta dalam pemilu berikutnya di daerah tersebut.
Dalam hemat saya, inilah salah satu cari untuk memotong akar korupsi sejak dari hulu pencalonan, bukan dengan menyerahkan pemilihan kepada mereka yang selama ini justru menjadi bagian dari masalah mahalnya tiket pencalonan tersebut.
Ketiga, penggunaan teknologi rekapitulasi elektronik yang berbasis transparansi “penuh” bisa menekan biaya penyelenggaraan pemilu yang selama ini sangat besar dari sisi honorarium petugas dan logistik berupa kertas.
Biasanya, jika kita berkaca pada negara-negara maju, efisiensi anggaran dilakukan melalui inovasi teknologi, bukan melalui pemangkasan hak konstitusional warga negara.
Sepaket dengan itu, peran pengawasan masyarakat melalui platform pelaporan yang aman dan terintegrasi harus diinstitusionalisasikan secara jelas. Warga yang melaporkan praktik suap dalam Pilkada diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Dengan cara ini, setiap warga negara akan menjadi pengawas demokrasi.
Terakhir, memperkuat demokrasi internal partai politik. Selama partai politik masih dikelola layaknya perusahaan pribadi atau korporasi keluarga oleh ketua umumnya, maka siapa pun yang memilih, baik rakyat maupun DPRD, hasilnya akan tetap transaksional.
Diperlukan undang-undang yang mewajibkan partai politik melakukan pemilihan pendahuluan secara terbuka.
Biarkan kader dan rakyat di tingkat lokal menentukan siapa yang layak dicalonkan, sebelum nama tersebut dibawa ke surat suara.
Dengan cara ini, kedekatan calon dengan konstituennya sudah terbangun sejak awal, dan partai politik dipaksa untuk bekerja keras melahirkan kader berkualitas ketimbang sekadar mencari sosok yang paling tebal dompetnya.
Pendeknya, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah lonceng kematian bagi kedaulatan rakyat di daerah atau upaya "kudeta halus" terhadap hak-hak dasar warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Jangan biarkan privilese politik rakyat ini dirampas dengan alasan-alasan “picik” yang dikemas sedemikian rupa. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus berdiri tegak menolak kemunduran ini.
Demokrasi di daerah mungkin belum sempurna, masih riuh dan masih terdapat kekurangan di sana sini. Namun, eksistensi demokrasi lokal hari ini, masih tetap jauh lebih baik dibanding membawa kembali oligarki ke daerah.
Oligarki? Ah, itu nama lain untuk 'kelompok lama yang ingin kembali berkuasa'. Jangan khawatir, rakyat sudah siap memberikan argumentasi dan menolak bukan lagi sekadar dengan popcorn untuk menyaksikan drama itu.
Tag: #melawan #syahwat #oligarki #balik #wacana #pilkada #lewat #dprd