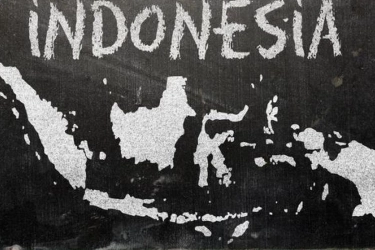Cerlang Nusantara dan Tantangan Indonesia
SEBAGIAN besar warga bangsa Indonesia, saya kira, tak sepenuhnya menyadari atribut “raya” yang dilekatkan WR Soepratman pada kata “Indonesia” di lagu gubahannya, “Indonesia Raya”. Kalaupun menyadari, mungkin sebatas Indonesia memang luas, besar dan kaya.
Ternyata Indonesia bukan cuma luas, besar dan kaya. Yudi Latif dalam karya terbarunya yang berjudul Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia? Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan (Penerbit Buku Kompas, 2025) menunjukkan signifikansi Indonesia pada dunia.
Penulis buku Negara Paripurna itu menyebut Cerlang Nusantara, lompatan-lompatan besar yang memberi arti signifikan bagi dunia, tapi kerap dilupakan, mungkin juga tak disadari oleh bangsa Indonesia sendiri.
Mulai dari geologi, geografi, oseanografi, sumber daya mineral, keanekaragaman hayati hingga hutan tropis dan keindahan alam.
Dari paleoantropologi, arkeologi, peradaban maritim, hingga manusia dengan kerajaan agung dan produk budaya sejak prakolonial hingga zaman kemerdekaan.
Sriwijaya, misalnya, mengajarkan bahwa kejayaan sejati lahir dari kolaborasi, bukan dominasi; kebijaksanaan mengelola keragaman, bukan keseragaman.
Sriwijaya bertahan tujuh abad bukan karena pasukan besar, melainkan kemampuan membaca perubahan.
Kuliner Nusantara yang terkesan remeh-temeh pun menggerakkan dunia. Rempah yang kuat pada kuliner Nusantara terbukti menggerakkan Barat yang berujung penjajahan.
Yudi Latif dengan mengutip Pramoedya Ananta Toer menulis, “Rempah kita mungkin pernah dijajah, tapi rasanya akan selalu merdeka.”
Cerlang Nusantara membuktikan bahwa Indonesia bukanlah pinggiran, melainkan nadi dunia. Tanpa Indonesia, dunia tak akan berdenyut.
Cerlang Nusantara yang ditulis Yudi Latif itu pula, saya kira, basis imajinasi WR Soepratman dan kawan-kawan saat mendeklarasikan “tanah air-bangsa-bahasa Indonesia” dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” pada 1928.
Dan, kini terbukti, bahasa Indonesia yang dulu berfungsi lingua franca akhirnya diterima sebagai bahasa resmi UNESCO sejak 2023.
Di stanza kedua dan ketiga “Indonesia Raya” (stanza yang sangat jarang dinyanyikan dan boleh jadi banyak yang tak mengenalnya), WR Soepratman menulis:
(2)
Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya
Di sanalah aku berdiri untuk s’lama-lamanya
Indonesia tanah pusaka, p’saka kita semuanya
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia
……
(3)
Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti
Di sanalah aku berdiri 'njaga ibu sejati
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji Indonesia abadi
……
Sangat mendalam maknanya, baik secara historis, antropologis, maupun kosmologis. Istilah “tanah pusaka”, misalnya, khas dalam sejarah dan antropologi.
“Tanah pusaka” menandai perikatan yang teramat dalam antara tanah dan orang yang hidup di atas tanah tersebut. Diberi bobot keramat (fetish) yang harus dirawat, diselamatkan, dilestarikan, bila perlu dengan taruhan nyawa.
Di bagian akhir stanza ketiga, WR Soepratman berseru:
S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah Neg'rinya,
Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.
Jelas sekali “Indonesia Raya” bukan imajinasi tanpa dasar. Atribut “raya” layak disandang oleh Indonesia, karena jejak masa lalu Nusantara yang gilang-gemilang.
Tak aneh bila Indonesia yang masih muda belia sukses menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955. KAA merupakan Cerlang Indonesia pada dunia.
Jejak historisnya mengamini Soekarno dan para pemimpin Indonesia saat itu didengar pemimpin dunia, khususnya negara-negara di Asia dan Afrika. Spirit pembebasan Indonesia menginspirasi dunia.
Begitu pula ketika Soekarno berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960. Melalui pidato berjudul "To Build The World Anew", Soekarno menawarkan Pancasila sebagai ideologi universal yang relevan untuk membangun dunia baru yang saat itu bipolar.
Dan, Yudi Latif pun mencatatnya sebagai signifikansi Pancasila bagi dunia, baik masa lalu maupun masa kini.
Peristiwa tersebut bukan datang begitu saja. Bukan tanpa riwayat yang membuat Indonesia pantas disegani.
Ikhtiar membalik arus
Cerlang Nusantara yang diungkap Yudi Latif mengingatkan bangsa Indonesia untuk tak sekadar mendendangkan “Indonesia Raya” pada acara resmi kenegaraan, tapi ikhtiar serius membalik arus, meraih status “raya” betulan.
“Indonesia Raya” bukan sekadar identitas kebangsaan untuk seremoni, melainkan mengantarkan subjek (yang menyanyikan) memasuki – meminjam antropolog Arnold van Gennep – fase liminal.
Dalam perspektif van Gennep, fase liminal adalah fase reflektif yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Meskipun waktu refleksi (durasi menyanyikan 3 stanza) tak sampai 5 menit.
Karya setebal 750 halaman itu oleh penulisnya dibuat bukan sebagai glorifikasi masa lalu, melainkan sebagai ikhtiar menegakkan keadilan.
Menurut Yudi Latif, mustahil “Ibu Semesta” menakdirkan satu belahan bumi saja sebagai pusat kejayaan dan kemakmuran, sementara belahan lain terjerembab dalam kubangan kemiskinan dan kesengsaraan yang tak berakhir.
Sejauh ini, Indonesia sebagai bangsa pascakolonial, selalu menerima pandangan yang bias Barat. Peradaban agung seolah hanya milik Barat, sehingga yang lain harus berguru dan tunduk pada Barat. Sejarah seolah mengalir satu arah, dari Barat ke Timur.
Pandangan bias Barat itu selayaknya dibaca ulang dengan membuka kemungkinan arus balik, dari Timur ke Barat. Ada masa ketika Barat gelap, lalu bangkit dengan nyala obornya. Pun ada masa tatkala Timur berjaya, lalu mundur memasuki kegelapan.
Peradaban bukan gerak linier yang dimonopoli satu kutub. Peradaban, menurut Yudi Latif, sejatinya merupakan proses perjumpaan: saling belajar, saling melengkapi, saling menyempurnakan.
Hal serupa juga pernah diingatkan oleh Pramoedya Ananta Toer melalui karya fiksi yang berjudul Arus Balik. Bila Yudi Latif menggunakan oposisi biner Barat:Timur, Pram memakai Utara:Selatan.
Arus sejarah bergerak dari Nusantara di belahan bumi Selatan ke belahan bumi Utara. Namun, pada masa tertentu arus berbalik. Utara menyerbu Selatan. Utara menguasai jalur rempah, menguasai urat nadi Nusantara.
“Kapal kita makin lama makin kecil. Seperti kerajaannya. Kapal besar hanya bisa dibuat oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara,” seru Wiranggaleng di novel Arus Balik.
Dengan demikian, atribut “raya” yang dilekatkan pada Indonesia merefleksikan kesadaran membalik arus yang dilandasi jiwa merdeka.
Hanya dengan jiwa merdeka, lompatan besar peradaban Nusantara dimungkinkan timbul kembali, tentu dengan format baru Indonesia modern.
Secara metaforis, Yudi Latif menyebut laksana pohon yang berakar dalam tanah leluhurnya, sementara ranting dan daunnya terbuka menyerap cahaya dari segala penjuru langit.
Para pendiri bangsa telah memberikan teladan. Pancasila yang diterima sebagai dasar negara, misalnya, menurut Bung Karno “digali” dari bumi Indonesia.
Cerlang Nusantara dipelajari dengan baik, demikian pula pemikiran lain dari Barat. Pengetahuan dan pemikiran tidak ditelan begitu saja, tapi dikunyah hingga dirasakan kecocokannya.
Selamat atau involusi makin rumit
Jalan membalik arus sejatinya telah dimulai dan makin terbuka pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia berdiri sebagai negara-bangsa yang diakui dunia. Bahkan, spirit pembebasannya berkontribusi besar pada kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.
Namun, secara substantif ternyata tak mudah dijaga dan kini menjadi tantangan serius kita bersama. Kini, kita memasuki labirin yang penuh jebakan pascakolonial. Jebakan itu memang tertanam begitu mendalam tatkala Nusantara dirundung kekalahan demi kekalahan.
Pertanyaannya, apakah Indonesia akan berhasil melewati usia 1 abad pada 2045 dengan selamat? Ataukah, akan terjadi involusi yang makin rumit, yang akan menunda, bahkan mengubur status “raya”?
Tak mudah menjawabnya. Yang pasti, hari ini kita dikelilingi absurditas, paradoks, dan ironi yang makin menjadi-jadi. Ambil beberapa saja.
Korupsi dan beragam underground economy di negeri ini sungguh absurd. Dilakukan secara berjamaah oleh pembesar negeri. Melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kalangan cerdik pandai. Tak peduli wilayah sakral.
Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dalam pidato Dies Natalis ke-61 Fakultas Hukum Universitas Jember, 15 November 2025, angka korupsi dan underground economy (ekspor/impor ilegal, under-invoicing, narkoba, judi online) diperkirakan per tahun mencapai Rp 1.500 triliun – Rp 2.000 triliun. Sungguh absurd.
Juga soal keadilan sosial. Kalangan elite pesta pora kemewahan, sementara banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Tak sedikit pula rakyat terjerat judi online dari bantuan sosial.
Kemuliaan, keutamaan dan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan agama, filsafat, ilmu pengetahuan dan kearifan lokal bagaikan kotbah di tengah keriuhan pasar.
Ia berbenturan dengan perjuangan hidup yang penuh persaingan tak berkeadilan dan mati rasa kemanusiaan.
Suasana sedih menyelimuti bangsa ini. Ternyata, di usia 80 tahun, anak-anak muda malah menginterupsi pemimpinnya dengan teriakan “Indonesia Gelap” dan berseru “Kabur Aja Dulu”.
Kini, yang paling dibutuhkan, saya kira, ekosistem yang menyuburkan pertumbuhan ruang-ruang kreatif yang dilandasi jiwa merdeka. Bagaikan tanaman, bibit yang baik niscaya tumbuh subur di lahan yang subur.
Namun, negeri ini memiliki pengalaman buruk yang membunuh kreativitas, dan terbiasa dengan praktik seperti itu. Di samping hal-hal yang bersifat birokratis, pengalaman buruk itu berupa sistem pemaknaan yang monolitik dan hegemonik oleh penguasa.
Kekuasaan cenderung menutup ruang-ruang kreatif, alergi kritik. Kekuasaan lebih menyukai teks yang monolitik, bukan teks yang bersilangan. Tanpa persilangan teks, tak ada refleksi/sintesis.
Melalui karya magnum opus-nya, Yudi Latif mengingatkan kembali perihal lompatan besar peradaban Nusantara sebagai pandu masa depan. Bukan hanya buat Indonesia, melainkan juga dunia.
Ia mengutip pandangan dekonstruksi dari nelayan Bugis di Wajo, “Laut bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu kita.” Pandangan ini jelas mengoreksi pandangan serakah yang eksploitatif terhadap alam tanpa prinsip keberlanjutan.
Pandangan nelayan Bugis itu kini mulai terdengar sebagai pandangan global. Pandangan semacam itu menguatkan sikap dunia untuk memaksa negara-negara industri maju membayar utang ekologis.
Kini, tinggal bagaimana kita membaca, mengolah, dan memaknai Cerlang Nusantara sebagai “pencerahan” (aufklärung). Barat pun bangkit dan berjaya berkat penemuan kembali khasanah budaya Yunani dan Romawi.
Mampukah bangsa Indonesia? Para pendiri bangsa telah memulai. Dan, kini giliran kita.