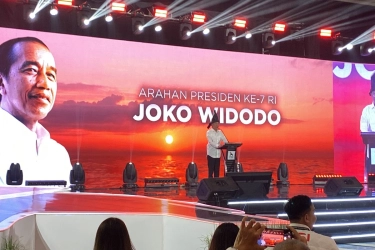Perempuan di Jantung Parlemen
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi representatif Indonesia.
MK secara tegas memerintahkan agar seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR — mulai dari Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan — wajib memuat keterwakilan perempuan secara proporsional.
Tak hanya itu, komposisi pimpinan AKD kini harus menjamin keterlibatan perempuan paling sedikit 30 persen.
Putusan ini sejatinya bukan sekadar koreksi terhadap undang-undang yang abai terhadap kesetaraan, melainkan penegasan bahwa politik hukum Indonesia tidak boleh terus berwajah maskulin.
Selama dua dekade terakhir, keterwakilan perempuan di parlemen sering berhenti pada batas formal: ada kuota dalam daftar calon legislatif, tetapi kuota itu menguap ketika perempuan sudah duduk di kursi kekuasaan. Di balik jargon partisipasi, yang terjadi justru marginalisasi.
Melalui amar putusan ini, MK mengingatkan bahwa keadilan substantif tidak akan lahir dari demokrasi yang timpang gender.
Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik bukanlah kemurahan hati sistem, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
MK bahkan menegaskan kembali prinsip affirmative action sebagai “kesepakatan nasional” — jalan menuju kesetaraan yang nyata, bukan seremonial.
Dari kuota ke keadilan substantif
Selama ini, wacana keterwakilan perempuan dalam politik sering terjebak dalam angka. Kuota 30 persen seolah menjadi garis finis perjuangan, padahal semestinya hal demikian menjadi titik awal menuju keadilan substantif.
Politik kuota tanpa distribusi peran hanyalah kosmetik demokrasi. Dalam banyak kasus, perempuan memang hadir di parlemen, tetapi tidak pada ruang-ruang strategis pengambilan keputusan—tidak di jantung kekuasaan, melainkan di pinggiran simbolik representasi.
Putusan MK kali ini mengubah arah politik hukum tersebut. MK tidak hanya menegaskan hak perempuan untuk duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga mengintervensi struktur internal lembaga legislatif agar ruang pengaruh itu benar-benar terbuka bagi perempuan.
Inilah bentuk konkret dari constitutional feminism—pandangan bahwa Konstitusi harus aktif melindungi dan memberdayakan kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Secara sosiologis, putusan ini menantang budaya politik patriarkal yang telah lama mengakar. DPR selama ini lebih sering dikuasai oleh logika fraksi dan patronase, posisi strategis kerap diberikan berdasarkan loyalitas politik, bukan perspektif kesetaraan.
Padahal, kehadiran perempuan bukan hanya soal keadilan numerik, melainkan soal kualitas kebijakan yang lebih inklusif, empatik, dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.
Dengan membuka ruang perempuan di seluruh AKD, MK sejatinya sedang mendorong redistribusi kekuasaan— langkah penting untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya prosedural, tetapi juga berkeadilan gender.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya menegaskan kembali bahwa demokrasi sejati tidak hanya berbicara tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang diwakili dan didengar.
Demokrasi tanpa keterwakilan perempuan sejatinya adalah demokrasi yang pincang—demokrasi yang gagal menangkap kompleksitas sosial dalam proses pengambilan keputusan publik.
Dalam teori demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, legitimasi politik tidak lahir semata dari hasil pemilihan umum, melainkan dari proses diskursif yang inklusif—yakni keterlibatan semua kelompok yang terdampak oleh kebijakan publik dalam proses pembentukannya.
Dengan demikian, absennya suara perempuan dalam alat kelengkapan Dewan berarti ada separuh warga negara yang tersingkir dari ruang deliberasi kebangsaan.
Dari perspektif teori keadilan ala John Rawls, prinsip fair equality of opportunity menuntut agar semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi keputusan kolektif.
Namun, dalam praktiknya, struktur politik yang maskulin justru menciptakan apa yang disebut Nancy Fraser sebagai “subordinasi sistemik dalam representasi politik”, di mana perempuan hadir sebagai simbol, bukan subjek kekuasaan.
Putusan MK ini mencoba membalik arus tersebut. Dengan mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan Dewan, Mahkamah sejatinya sedang mengubah arsitektur kekuasaan politik agar lebih adil dan reflektif terhadap realitas sosial.
Ini bukan semata langkah hukum, tetapi transformasi budaya politik — dari politics of exclusion menuju politics of inclusion.
Tentu, keberadaan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan bukan hanya memperkaya perspektif, melainkan juga memperkuat kualitas kebijakan publik.
Pelbagai studi, termasuk penelitian World Bank (2020) dan UN Women (2022), menunjukkan bahwa lembaga legislatif yang lebih seimbang secara gender cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan.
Dengan kata lain, keterwakilan perempuan bukan hanya persoalan moral atau etika politik, tetapi juga rasionalitas kebijakan.
Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 dengan demikian harus dibaca sebagai upaya konstitusionalisasi keadilan sosial berbasis gender.
MK mengingatkan bahwa konstitusi bukan teks netral, melainkan instrumen emansipatoris yang harus berpihak pada kelompok termarjinalkan.
Di titik inilah, MK menjalankan fungsinya sebagai penjaga moral konstitusi — memastikan bahwa hukum tidak sekadar mengatur kekuasaan, tetapi juga menata ulang relasi kuasa agar lebih adil.
Meneguhkan politik yang berkeadilan gender
Putusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya tidak berhenti sebagai teks hukum, melainkan menjadi momentum politik untuk menata ulang cara bangsa Indonesia memaknai kekuasaan.
Perintah MK agar keterwakilan perempuan hadir di seluruh alat kelengkapan Dewan menuntut keberanian politik dari partai-partai untuk keluar dari pola lama: politik yang tertutup, hierarkis, dan maskulin.
Tanpa komitmen politik yang nyata, putusan konstitusional ini akan kembali menjadi simbol tanpa roh.
Jika dibaca dengan kacamata politik hukum, langkah MK ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya produk dari kekuasaan, tetapi juga alat korektif terhadap ketimpangan struktural.
MK menggunakan konstitusi sebagai instrumen transformative justice—keadilan yang tidak sekadar menghukum atau mengatur, tetapi mengubah relasi sosial agar lebih setara. Seperti dikatakan oleh jurist feminis, MacKinnon, hukum harus hadir bukan untuk “menyamakan perempuan dengan laki-laki”, melainkan untuk menghapus struktur dominasi yang membuat perempuan selalu berbeda secara sosial dan politis.
Kini, tugas besar ada di tangan DPR dan partai politik. Mereka harus menindaklanjuti putusan ini dengan mekanisme konkret: penataan tata tertib DPR, kebijakan afirmatif dalam fraksi, hingga evaluasi rutin atas komposisi alat kelengkapan Dewan.
Pun, publik sipil dan gerakan perempuan perlu terus mengawal agar prinsip keadilan gender tidak berhenti di ruang sidang MK, tetapi berakar dalam praktik politik keseharian.
Jadi, keterwakilan perempuan di jantung parlemen bukan sekadar tentang menambah kursi, melainkan menambah cara pandang terhadap keadilan.
Demokrasi yang sejati hanya bisa hidup jika seluruh warga negara—tanpa terkecuali—dapat berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan arah bangsa.
Putusan MK ini adalah panggilan konstitusional untuk memastikan bahwa politik Indonesia bukan lagi arena eksklusif “kekuasaan laki-laki”, tetapi ruang bersama untuk keadilan yang setara dan manusiawi.
Tag: #perempuan #jantung #parlemen