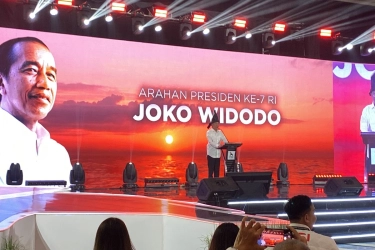Pertarungan di Balik Rencana Kepahlawanan Soeharto
RENCANA pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kembali memunculkan perdebatan publik yang seru.
Isu ini bukan sekadar persoalan historis, tetapi juga menyentuh ranah konstruksi sosial dan politik tentang siapa yang berhak disebut pahlawan.
Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, gelar kepahlawanan selalu menjadi cerminan dari arah politik ingatan dan siapa yang sedang berkuasa.
Bersama dengan Soeharto, ada 39 tokoh lainnya yang dicalonkan untuk mendapatkan gelar serupa. Di antaranya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, aktivis buruh perempuan yang tewas secara tragis pada 1993.
Masuknya kedua tokoh tersebut memunculkan ironi yang tajam. Gus Dur dikenal sebagai tokoh reformis dan demokrat yang secara terbuka mengkritik dan berhadapan dengan Soeharto menjelang kejatuhan Orde Baru.
Sementara Marsinah adalah korban langsung dari represi sistem politik dan ekonomi yang tumbuh di bawah kepemimpinan Soeharto.
Dengan demikian, gagasan menempatkan ketiganya dalam satu daftar calon pahlawan nasional menghadirkan kontradiksi moral dan historis yang sulit diabaikan.
Dalam perspektif sosiologi politik, pahlawan nasional bukan entitas yang objektif atau netral. Penentuannya berasal dari proses simbolisasi politik, di mana negara menentukan nilai, ideologi, dan figur yang layak diwariskan sebagai representasi bangsa.
Sejarawan Benedict Anderson (1983) menyebutnya sebagai bagian dari imagined community, upaya negara membentuk kesadaran kolektif melalui simbol dan narasi sejarah.
Pahlawan, dengan demikian adalah produk dari politics of memory, politik ingatan kolektif yang menentukan siapa yang diingat, siapa yang dilupakan, dan siapa yang diberi tempat terhormat dalam sejarah nasional.
Konsep ini banyak dibahas dalam studi tentang ingatan sosial dan sejarah, misalnya Maurice Halbwachs dalam The Collective Memory (1992) dan Olick & Robbins, Social Memory Studies, (1998), yang menekankan bahwa memori publik selalu dibentuk melalui proses sosial dan kekuasaan.
Setiap rezim memiliki kebutuhan politik untuk menentukan figur mana yang dijadikan teladan moral.
Dalam konteks ini, penetapan pahlawan lebih mencerminkan legitimasi kekuasaan masa kini ketimbang penilaian murni atas jasa masa lalu.
Residu politik Orde Baru dan konsolidasi kekuasaan
Hingga saat ini, Soeharto masih menempati posisi paradoks tertinggi dalam sejarah politik Indonesia modern.
Di satu sisi, ia dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” yang memimpin selama lebih dari tiga dekade dan membawa stabilitas ekonomi pada 1970–1980-an.
Namun di sisi lain, ia juga dipandang sebagai simbol otoritarianisme, pelanggaran HAM, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar selama rezim Orde Baru bahkan hingga sekarang.
Memori sosial terhadap Soeharto tidak pernah tunggal. Sebagian masyarakat mengenangnya sebagai pemimpin kuat yang menegakkan ketertiban dan pembangunan, sementara kelompok lain menilai warisannya sebagai masa kegelapan demokrasi.
Perbedaan pandangan inilah yang menjadikan setiap wacana penghargaan terhadap Soeharto selalu sarat kontradiksi moral dan politik.
Namun menarik untuk dicermati, rencana pemberian gelar tersebut muncul dua dekade setelah kejatuhan Soeharto. Usulan ini menguat dan sepertinya akan mudah terwujud.
Residu politik Orde Baru saat reformasi telah kembali mengonsolidasikan kekuasaan dalam struktur negara.
Sejumlah pengamat menilai bahwa jaringan elite lama, baik dari kalangan partai politik, birokrasi, maupun bisnis, berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika pasca-Reformasi dan kembali memainkan peran penting dalam proses politik nasional.
Dalam konteks ini, rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menormalkan kembali warisan Orde Baru di tengah konsolidasi kekuasaan politik masa kini—sebuah rekontekstualisasi sejarah yang sarat makna ideologis dan simbolik.
Secara simbolik, gelar tersebut bukan hanya penghargaan personal, melainkan juga reproduksi legitimasi kekuasaan lama dalam kemasan moral baru.
Tentang penentuan siapa yang dapat disebut pahlawan, pada dasarnya mencerminkan siapa yang sedang memegang kendali atas narasi sejarah nasional.
Dilema etis dan historis
Kontradiksi rencana ini semakin kuat karena jarak sejarah yang belum cukup memberi ruang refleksi objektif. Masyarakat Indonesia masih hidup dalam warisan struktur politik, ekonomi, dan budaya Orde Baru.
Banyak kasus pelanggaran HAM era 1965–1998 yang belum selesai dituntaskan. Dalam konteks seperti ini, penghargaan kepada Soeharto terasa prematur dan berpotensi melukai memori kolektif korban.
Di banyak media massa dan forum, organisasi HAM seperti KontraS dan Amnesty International Indonesia menilai bahwa langkah tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkuat krisis keteladanan moral.
Mereka menegaskan bahwa negara semestinya terlebih dahulu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan melakukan rekonsiliasi sejarah sebelum mengangkat figur yang masih menyisakan luka kolektif.
Kontroversi tentang Soeharto bukan hanya perdebatan mengenai jasa seorang tokoh, melainkan tentang arah bangsa dalam menulis ulang sejarahnya sendiri.
Apakah Indonesia ingin mengingat masa lalu dengan refleksi kritis, atau menutupnya dengan narasi nostalgia pembangunan?
Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Ricoeur (2004) dalam Memory, History, Forgetting, setiap bangsa menghadapi dilema antara mengingat untuk berdamai dan mengingat untuk menjustifikasi kekuasaan.
Dalam konteks ini, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tampak lebih sebagai upaya normalisasi politik masa lalu ketimbang langkah menuju rekonsiliasi sejati.
Dengan demikian, perdebatan soal gelar pahlawan bagi Soeharto bukan sekadar pro-kontra moral, melainkan cermin dari pertarungan antara memori kritis dan rekonstruksi kekuasaan dalam sejarah Indonesia.