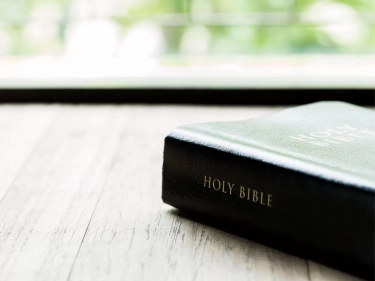Ironi Pemangkasan TKD: Daerah Diminta Hemat, Pusat Justru Boros
RENCANA pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang sangat besar menimbulkan keresahan luas di kalangan kepala daerah.
Sampai-sampai gubernur ramai-ramai menggereduk Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta, yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan kita.
Bagi saya, kebijakan ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut arah besar penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini.
Apakah kita masih punya komitmen pada desentralisasi dan otonomi daerah, atau justru sedang melakukan deotonomisasi alias kembali ke sentralisasi ala Orde Baru?
Sejak Reformasi 1999, otonomi daerah dibangun untuk memberi ruang bagi daerah mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, pemotongan TKD justru menunjukkan arah sebaliknya.
Sekarang saja 80 persen dari 546 daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal — mereka hidup dari dana transfer pusat.
Jika anggaran itu dipangkas hingga Rp 200 triliun, maka akan banyak urusan pemerintahan di daerah yang lumpuh.
Padahal daerah ditugaskan mengurus 32 urusan pemerintahan. UUD 1945, pasal 18 ayat (5) pun mengamanahkan daerah melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya.
Ketimpangan fiskal: Pusat menguasai 80 persen APBN
Keadilan fiskal nasional saat ini sangat timpang. Sekitar 80 persen APBN dikuasai oleh pemerintah pusat, sementara hanya 20 persen dibagi ke 546 daerah otonom.
Padahal, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 jelas menegaskan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus selaras dan adil.
Di negara lain, distribusi keuangan bisa lebih seimbang — bahkan 50:50 antara pusat dan daerah. Namun di Indonesia, kita masih terlalu “Jakarta-sentris”.
Akibatnya, daerah terus menjadi pelaksana, bukan pengambil keputusan, dalam kebijakan pembangunan daerahnya.
Lebih ironis lagi, pemerintah pusat sering menuding rendahnya penyerapan anggaran di daerah sebagai alasan pemangkasan.
Padahal, realisasi belanja kementerian dan lembaga pusat sendiri baru sekitar 55 persen hingga Oktober 2025. Jadi, tidak adil bila daerah dijadikan kambing hitam atas kegagalan efisiensi nasional.
Pemangkasan TKD akan langsung memukul ASN daerah, khususnya melalui pemotongan tunjangan kinerja (TPP).
Gaji pokok ASN di daerah rata-rata hanya Rp 2 juta – Rp 5 juta, sedangkan TPP adalah penopang utama kesejahteraan mereka.
Jika ini dikurangi, bukan hanya daya beli ASN menurun, tetapi juga moral dan produktivitas mereka.
Lebih jauh, pelayanan publik akan tertekan. Urusan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, dan tenaga kerja sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah.
Jika anggaran daerah menyusut, rumah sakit tidak akan bisa diperbaiki, jalan rusak akan terbengkalai, proyek infrastruktur lokal terancam berhenti, obyek pariwisata tak terbenahi, hingga terumbu karang tak bisa dirawat lagi.
Ironisnya, masyarakat tetap akan menyalahkan kepala daerah, padahal sumber masalahnya ada pada kebijakan pusat.
Saya ingin mengingatkan Kementerian Dalam Negeri agar kembali pada fungsinya sebagai pembina dan penjaga otonomi daerah.
Mendagri seharusnya memperjuangkan posisi daerah di hadapan Kementerian Keuangan, bukan hanya menyampaikan pesan politik dari pusat.
Kalau Kemendagri tidak tampil membela daerah, maka kepala daerah akan kehilangan wibawa di mata rakyat. Mereka akan terlihat lemah dan tidak berdaya, padahal tanggung jawab urusan pemerintahan sehari-hari ada di pundak mereka.
Ironi: Daerah diminta hemat, pusat justru boros
Adapun yang paling menggelitik dari kebijakan pemangkasan TKD ini adalah inkonsistensinya. Pemerintah pusat menyerukan efisiensi kepada daerah, tetapi pada saat yang sama justru memperbesar struktur birokrasi.
Lembaga-lembaga baru terus dibentuk, kabinet semakin gemuk, dan beberapa menteri kini memiliki hingga tiga wakil menteri — semuanya digaji dan mendapat insentif dari APBN.
Ini bentuk pemborosan yang nyata. Jika pusat ingin daerah berhemat, maka harus dimulai dengan keteladanan.
Penghematan tidak bisa hanya diwacanakan ke bawah, sementara di atas struktur pemerintahan justru semakin melebar.
Kendatipun demikian, kita tetap mendorong kepala daerah untuk beradaptasi dan melakukan efisiensi cerdas. Ada empat langkah yang bisa ditempuh:
Pertama, kurangi perjalanan dinas dan rapat fisik, manfaatkan teknologi digital.
Kedua, hapus belanja konsumtif, seperti fasilitas berlebih, jamuan, dan atribut seremonial.
Ketiga, tingkatkan transparansi PAD tanpa menambah beban rakyat.
Keempat, bersikap jujur kepada rakyat dan ASN mengenai keterbatasan anggaran.
Kejujuran adalah kunci. Kepala daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat bahwa dana dari pusat berkurang. Dengan komunikasi yang jujur, kepercayaan publik tetap bisa dijaga, bahkan di tengah keterbatasan.
Jika kebijakan ini dibiarkan, saya khawatir otonomi daerah akan tergerus perlahan. Pemerintahan kembali menjadi sentralistik, dan daerah kehilangan daya tawar dalam menentukan arah pembangunan.
Akibatnya, kualitas pelayanan publik akan menurun dan kesenjangan antarwilayah semakin melebar.
Negara ini bukan hanya Jakarta. Indonesia terdiri dari pusat dan 546 daerah otonom yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun bangsa.
Jika daerah terus dilemahkan, maka semangat reformasi dan otonomi yang diperjuangkan sejak 25 tahun lalu akan tinggal sejarah.
Tag: #ironi #pemangkasan #daerah #diminta #hemat #pusat #justru #boros