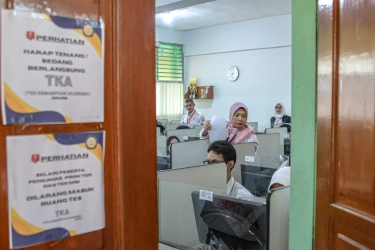Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 1998: Salah, Luka, dan Lupa
PERNYATAAN yang dilontarkan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengenai kerusuhan Mei 1998 baru-baru ini, telah menyulut kembali bara luka lama yang tak kunjung sembuh.
Dalam wawancara pada 9 Juni 2025, Fadli dengan tegas menyangkal terjadinya pemerkosaan massal terhadap perempuan, khususnya keturunan Tionghoa, menyebutnya sekadar "rumor" belaka.
Klaim ini, sayangnya, bukan hanya opini, melainkan dusta publik yang secara keji mengoyak perasaan para korban dan keluarga yang telah bertahun-tahun menanggung trauma.
Koalisi pegiat hak asasi manusia segera mengecam, melihatnya sebagai upaya sistematis untuk menghapus jejak pelanggaran HAM berat yang mencoreng era Orde Baru.
Komnas Perempuan bahkan menegaskan bahwa penyangkalan semacam ini, alih-alih menyembuhkan, justru menambah kepedihan dan melanggengkan impunitas bagi para pelaku.
Ironisnya, sosok Fadli Zon, yang selama ini dikenal sebagai bagian dari aktivis Reformasi 1998, kini justru berbalik mengingkari fakta sejarah kelam yang dulu ia perjuangkan.
Tragedi Mei 1998: Fakta sejarah dalam catatan negara
Tragedi kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar meninggalkan catatan hitam berupa kekerasan berbasis etnis dan gender yang tak terhapuskan.
Sebagai respons terhadap kegelapan itu, pemerintah pada 1998 membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Tim ini, dengan kerja kerasnya, berhasil mencatat setidaknya 85 kasus kekerasan seksual. Angka ini merinci 52 kasus perkosaan massal, 14 perkosaan yang disertai penganiayaan, 10 penyerangan seksual, dan 9 pelecehan seksual.
Fakta-fakta ini, bukan sekadar 'cerita' tanpa dasar, didokumentasikan secara rinci di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Banyak dari korban adalah perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang secara sistematis menjadi target kekerasan rasial.
Laporan TGPF ini kemudian diserahkan langsung kepada Presiden saat itu, B.J. Habibie, yang pada masanya secara terbuka menyesali kekerasan tersebut dan mengesahkan pembentukan Komnas Perempuan sebagai wujud komitmen negara.
Jelaslah, tragedi pemerkosaan massal pada Mei 1998, adalah fakta sejarah yang tercatat resmi, bukan sekadar bisik-bisik tanpa bukti.
Era pasca-Reformasi memang membawa angin segar berupa pengakuan formal negara terhadap pelanggaran HAM berat dalam Tragedi 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun, pengakuan ini sayangnya kerap berhenti di atas kertas.
Lebih dari dua dekade berlalu, ironi keadilan masih nyata: nyaris tak ada satu pun pelaku yang berhasil diseret ke meja hijau, dan para penyintas masih jauh dari kata adil.
Kekosongan penegakan hukum ini, mau tak mau, membuka ruang bagi narasi revisi sejarah yang berani meragukan, bahkan menyangkal kebenaran.
Pernyataan Fadli Zon adalah contoh terbaru dari pola penyangkalan institusional yang sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan bangsa ini.
Pada awal pasca-1998, pernah muncul gelombang penolakan terhadap laporan perkosaan dengan dalih bahwa tak ada korban yang bersedia bersaksi secara terbuka, seolah mengabaikan betapa dalamnya trauma, stigma, dan intimidasi yang membayangi para korban.
Galuh Wandita, seorang pengamat, mencatat adanya ancaman terhadap saksi dan disinformasi yang terorganisir, yang bertujuan mendiskreditkan laporan.
Budaya bungkam inilah yang secara kejam membuat korban enggan muncul ke permukaan, yang kemudian dipelintir seolah ketiadaan kesaksian publik berarti ketiadaan kejadian.
Sebuah paradoks yang menyakitkan dalam penanganan kekerasan seksual: korban terpaksa bungkam demi keamanan, lantas negara seolah-olah berhak untuk abai.
Pernyataan Fadli Zon ini dengan jelas memperlihatkan betapa rapuhnya ingatan kolektif bangsa ini, yang kini terancam oleh mereka yang memiliki kuasa untuk menyusun narasi sejarah.
Ia bahkan disinyalir berencana merevisi narasi sejarah nasional menjelang HUT RI ke-80, untuk menonjolkan sisi 'positif' semata.
Pendekatan semacam ini sangat mengkhawatirkan, karena berpotensi besar menghapus fakta kelam demi narasi yang konon 'menyatukan'.
Namun, Komnas Perempuan telah mengingatkan dengan tegas: laporan TGPF 1998 adalah dokumen resmi negara; menyangkalnya sama saja dengan mengingkari kerja kolektif bangsa dalam mencari kebenaran dan keadilan yang telah susah payah diupayakan.
Kuasa, impunitas, dan bahaya pengingkaran kekerasan seksual
Secara politis dan moral, mengabaikan atau menyangkal kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Ada beberapa alasan mendasar mengapa kebungkaman dan penyangkalan oleh tokoh berkuasa justru berpihak pada ketidakadilan:
Pertama, ini memperkuat ketimpangan kuasa. Membungkam suara korban adalah bentuk kontrol sosial yang keji.
Ketika pejabat menolak mengakui kesaksian korban, itu memperteguh posisi dominan pelaku dan penguasa, sekaligus merampas hak suara korban.
Seperti dicatat Courtney E. Ahrens (2006), "untuk bisa berbicara dan didengar berarti memiliki kuasa atas hidup sendiri; sebaliknya dibungkam berarti kuasa itu dirampas".
Kedua, ini melanggengkan impunitas dan mengirimkan pesan berbahaya kepada pelaku. Ketika pejabat meragukan atau menyangkal kekerasan seksual, pesan yang sampai kepada publik dan, yang lebih berbahaya, kepada para pelaku, adalah bahwa kejahatan mereka tidak serius.
Institusi negara, yang seharusnya menjadi 'gatekeeper' keadilan, justru mengirim sinyal impunitas.
Akibatnya, para penyintas merasa sia-sia untuk melapor, sementara pelaku mendapat lampu hijau untuk terus berbuat kejahatan. Ini melanggengkan impunitas struktural yang telah lama menjadi borok di negara ini.
Ketiga, penyangkalan ini memupuk budaya diam yang menguntungkan pelaku. Korban seringkali enggan melapor karena berbagai alasan: malu, trauma yang mendalam, takut disalahkan, atau ketakutan akan pembalasan. Ini adalah lahan subur bagi para pelaku.
Ketika wakil pemerintah memperkuat budaya diam ini dengan menyangkal peristiwa yang terdokumentasi dengan jelas, ia secara terang-terangan berpihak pada kepentingan pelaku.
Keempat, hambatan terhadap keadilan adalah kekerasan struktural itu sendiri. Berbagai hambatan yang dialami korban dalam mencari keadilan—seperti ketidakpercayaan, stigma sosial, atau proses hukum yang berbelit—adalah bentuk kekerasan struktural.
Kegagalan negara melindungi korban dan memproses pelaku adalah bentuk kekerasan tidak langsung. Pengingkaran yang dilakukan pejabat publik adalah bagian integral dari kekerasan struktural itu sendiri.
Kelima, ini menunjukkan krisis pengakuan dan empati. Teori politik pengakuan menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya pengakuan publik atas penderitaan korban.
Penyangkalan kekerasan seksual adalah penolakan untuk mengakui kemanusiaan dan derita korban, sebuah kegagalan etis yang mendalam dari seorang pejabat publik.
Seorang menteri seharusnya menjadi teladan empati, melindungi warga, bukan justru membuka kembali trauma lama.
Singkatnya, ketidaktahuan yang disengaja atau penyangkalan oleh pejabat mengenai kasus kekerasan seksual adalah tindakan politis yang berdampak sistemik dan merusak tatanan keadilan.
Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madanih menegaskan bahwa penyangkalan semacam itu hanya akan memperpanjang impunitas pelaku dan mengabaikan jeritan korban.
Silence is violence—diamnya korban adalah akibat kekerasan, dan diamnya penguasa terhadap kebenaran adalah bentuk kekerasan baru yang tak kalah menyakitkan.
Ironisnya, pernyataan Fadli Zon muncul di tengah upaya Indonesia membangun pijakan hukum yang lebih progresif dalam menangani kekerasan seksual: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Undang-undang ini mencakup definisi kekerasan seksual yang lebih luas dan mekanisme perlindungan korban yang kuat.
Aparat penegak hukum diwajibkan menangani laporan secara sigap, dengan prosedur yang ramah korban.
UU ini juga menetapkan sanksi pidana tegas dan fokus pada rehabilitasi pelaku. Secara filosofis, UU ini lahir dari pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa yang merendahkan martabat manusia dan harus ditangani secara serius.
Namun, hukum yang tertulis, seprogresif apa pun, bergantung sepenuhnya pada mentalitas aparatur dan elite yang mengimplementasikannya.
Mentalitas lama, yang merupakan warisan era Orde Baru yang menyangkal pelanggaran HAM, masih membayangi.
Penerapan UU TPKS menghadapi berbagai tantangan: mulai dari kendala pelaporan, hambatan birokrasi, hingga resistensi budaya patriarkal yang masih kuat.
Proses hukum yang panjang pun berpotensi kembali menimbulkan trauma bagi korban. Pekerjaan rumah penegakan keadilan masih sangat banyak, dan membutuhkan dukungan penuh dari pejabat publik.
Pernyataan Fadli Zon jelas-jelas bertolak belakang dengan semangat dan jiwa UU TPKS. Alih-alih mendukung langkah maju yang telah diperjuangkan, ia justru memutar balik narasi ke era penyangkalan.
Sikap ini tidak hanya melukai para penyintas, tetapi juga secara fundamental melemahkan semangat penegakan hukum yang progresif.
Efektivitas UU TPKS membutuhkan peningkatan pelatihan aparat, perubahan norma sosial, dan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses.
Dukungan pimpinan politik menjadi sangat krusial; penyangsian yang datang dari seorang menteri berpotensi besar mengendurkan semangat reformasi dan keadilan yang baru tumbuh.
Mengutamakan kebenaran dan empati
Tragedi pemerkosaan massal 1998 bukan hanya sekadar deretan angka statistik; di baliknya ada manusia-manusia yang menanggung trauma mendalam seumur hidup mereka.
Negara, sebagai pelindung rakyat, semestinya hadir untuk mengakui dan menyembuhkan luka itu, bukan malah menuangkan garam dengan menyangkalnya.
Berdamai dengan masa lalu hanya mungkin dicapai dengan keterbukaan, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang nyata. Penolakan Fadli Zon atas fakta sejarah ini patut dikecam dengan keras.
Komnas Perempuan telah mengingatkan, menyangkal temuan TGPF 1998 sama saja dengan mengingkari kerja keras bangsa dalam mengejar kebenaran dan keadilan.
Seluruh upaya advokasi dan pemulihan bagi korban bisa menjadi sia-sia jika ingatan kolektif kita dihapus atau dimanipulasi.
Di era ketika payung hukum sudah jauh lebih baik dan kesadaran publik tentang kekerasan seksual semakin meningkat, tidak ada ruang lagi bagi penyangkalan semacam ini.
Fadli Zon—dan siapa pun pemangku kuasa—seharusnya meminta maaf secara tulus dan belajar dari suara korban serta data faktual yang telah tercatat.
Mengakui kebenaran pahit adalah satu-satunya cara bagi bangsa ini untuk bersatu dan melangkah maju, agar tragedi serupa tak terulang kembali.
Menyusun sejarah yang 'positif' dengan menutupi borok lama hanya akan memperpanjang siklus impunitas dan ketidakpercayaan yang telah lama membelenggu.
Ketidakpedulian terhadap penderitaan korban adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan nilai-nilai reformasi yang dulu diperjuangkan. Suara para penyintas yang sekian lama dibungkam, berhak untuk didengar dan diakui.
Tugas negara dan kita semua adalah memastikan tidak ada lagi penyangkalan atas kekerasan seksual.
Sejarah kelam harus diakui apa adanya, sebagai pengingat abadi bahwa kita memiliki pekerjaan moral yang besar untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Dengan mengutuk tegas pernyataan Fadli Zon, kita menegaskan kembali komitmen bersama: kebenaran dan empati kepada korban harus selalu menjadi arus utama dalam setiap kebijakan dan narasi bangsa.
Negara yang beradab tidak boleh melupakan air mata dan jeritan warganya. Sudah saatnya luka 1998 benar-benar dipulihkan dengan pengungkapan yang jujur, penyesalan tulus, dan tindakan nyata—bukan dengan penyangkalan yang menyesatkan dan melukai.
Tag: #pernyataan #fadli #soal #pemerkosaan #massal #1998 #salah #luka #lupa