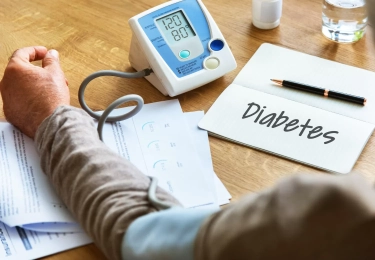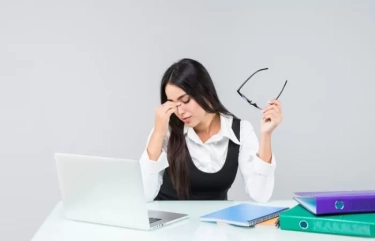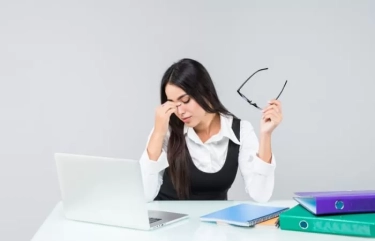Layanan Kesehatan Preventif: Tantangan Retorika
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru mengatakan kalau tugas Kementerian Kesehatan adalah menjaga agar orang sehat tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Arah pembangunan kesehatan Indonesia menitikberatkan pada promotif dan preventif.
Secara normatif memang hampir semua dokumen kebijakan dan program kesehatan nasional telah menyebutkan hal serupa, mencegah lebih murah daripada mengobati.
Namun, mengapa implementasi di lapangan tetap tersendat? Mengapa biaya kesehatan masih didominasi layanan kuratif dan fasilitas kesehatan primer masih terasa seperti ruang tunggu rujukan ketimbang sebagai pusat pencegahan?
Jawabannya terletak pada jurang antara wacana dan budaya. Preventif mudah diucapkan, tetapi kuratif selalu berada di depan mata, nyata dan mendesak.
Dalam masyarakat sosial Indonesia, budaya kuratif bukan sekadar kebiasaan, melainkan refleksi dari sejarah panjang sistem kesehatan dan pola pikir.
Sesungguhnya secara pelaksanaan tindakan preventif jelas lebih mudah dan unggul. Vaksinasi, skrining penyakit, cek kesehatan, edukasi gizi, hingga sanitasi lingkungan terbukti menurunkan morbiditas dan biaya jangka panjang.
Namun, manfaat tindakan preventif bersifat invisible: seseorang yang tidak terkena penyakit karena telah divaksin tidak akan merasakan kesembuhan. Sehingga nilai preventif lebih sulit dirasakan secara personal.
Sebaliknya tindakan kuratif selalu terlihat. Orang sakit, dirawat di rumah sakit, diberikan obat, dan kesembuhan. Ada hubungan sebab-akibat yang konkret.
Dalam psikologi kesehatan, manusia lebih responsif terhadap ancaman yang tampak daripada risiko yang tidak di depan mata.
Masyarakat merasa ancaman yang tampak (illness) lebih dekat daripada risiko abstrak (risk) yang harus dihindari.
Karena itu, sekalipun Menkes menyampaikan seruan promotif-preventif, masyarakat tetap datang ke Puskesmas dan rumah sakit hanya ketika sakit—bukan ketika sehat.
Budaya kuratif bukan hanya budaya masyarakat. Ia diperkuat oleh logika pelayanan kesehatan di Tanah Air selama puluhan tahun.
Sistem kesehatan kita lama bertumpu pada puskesmas dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan.
Investasi kesehatan bangsa sering diukur dari jumlah bangunan rumah sakit baru, alat kedokteran canggih, dan keberadaan dokter spesialis.
Tenaga kesehatan di layanan primer (puskesmas) yang semestinya menjadi ujung tombak layanan promotif dan preventif, lebih banyak terseret ke pekerjaaan administratif dan penanganan kasus daripada murni melakukan edukasi atau penyuluhan.
Dari sinilah maka tidak mengherankan jika masyarakat secara umum memandang puskesmas sebagai tempat pengobatan murah, ditanggung BPJS, dan bukan pusat pencegahan.
Sekarang ditambah lagi dengan fenomena masih rendahnya literasi kesehatan, sebagian masyarakat menjadi takut diperiksa menjalani deteksi dini penyakit karena tidak ingin kabar buruk kondisi kesehatannya diketahui.
Masih terdapat pula penolakan terhadap pelayanan vaksinasi menunjukkan bahwa masyarakat terpengaruh misinformasi dalam masyarakat.
Program preventif dipandang bertabrakan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Pencegahan dianggap tidak mendesak.
Dapat dipahami kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan masih fluktuatif karena semua informasi yang sering juga berbeda.
Terlebih keputusan kesehatan lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga, tokoh masyarakat, dan media sosial daripada tenaga kesehatan.
Dalam ekosistem seperti tersebut, pesan preventif mudah tenggelam di tengah gelombang informasi dan opini yang terus mengisi ruang publik.
Dari sudut pandang industri kesehatan dan profesi, pelayanan kuratif juga lebih produktif dan menghasilkan. Rumah sakit makin berkembang dengan layanan, obat, teknologi dan prosedur.
Dokter dan tenaga medis mendapatkan nilai profesional dari keahlian dalam pengobatan pasien. Sesuatu yang jamak terlihat dan tidak salah, tapi dapat menjelaskan mengapa sistem kesehatan lebih ke layanan kuratif meskipun pemerintah (Kemenkes) ingin bergeser ke promotif dan kuratif.
Pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan juga turut berperan. Skema pembiayaan BPJS Kesehatan masih banyak mengalir ke klaim rumah sakit dan jasa pelayanan, dibanding insentif pencegahan.
Selama pembiayaan terbesar berada di ranah kuratif, layanan preventif akan tetap menjadi retorika kebijakan yang sulit diwujudkan sebagai gerakan semesta.
Memang preventif dan kuratif tidak sedang berhadapan berlawanan. Karena pelayanan kesehatan komprensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam setiap layanan yang dilakukan, semua layanan saling mengisi dan memperkuat.
Kita sependapat dengan Pemerintah (Kemenkes) bahwa sudah waktunya menggeser orientasi pembangunan dengan lebih mengutamakan preventif. Hal ini bisa dilakukan, tapi memerlukan strategi yang lebih realistis dan sederhana.
Seperti menghadirkan program preventif terasa nyata sebagai kebutuhan masyarakat. Program skringing dan cek kesehatan dibuat mudah, dekat dan menyenangkan.
Hal ini dapat dilakukan di lingkungan kerja, sekolah, atau tempat-tempat publik yang tidak memerlukan biaya dan waktu yang panjang.
Ketika orang melihat hasil nyata, misalnya, deteksi dini hipertensi dan diabetes, yang diikuti dengan konseling dan layanan lebih lanjut, maka nilai preventif menjadi lebih dapat dirasakan.
Edukasi kesehatan dilakukan dengan mengubah cara komunikasi sesuai dengan era perkembangan jaman.
Pemanfaatan influencer lokal, micro content di media sosial, dan storytelling harus menjadi prioritas yang terus berkembang. Masyarakat diyakinkan bukan dengan data, tetapi melalui kisah layanan yang telah dilakukan.
Selanjutnya layanan primer Puskesmas dikuatkan bukan sebagai tempat berobat, tetapi pusat edukasi dan komunikasi kesehatan.
Kader kesehatan, posyandu remaja, hingga kegiatan prolanis harus berubah menjadi tempat agen perubahan perilaku.
BPJS Kesehatan juga dapat berperan besar dengan menggeser struktur pembiayaan yang lebih memberikan insentif signifikan untuk pencegahan.
Penyaluran dana kapitasi berbasis kinerja preventif akan dapat menggeser orientasi yang selama ini dijalankan fasyankes yang lebih melihat kebutuhan layanan kuratif.
Pernyataan Menkes dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025 menegaskan kembali arah pembangunan kesehatan yang benar. Namun, agar tidak menjadi retorika belaka, perlu transformasi budaya, sistem dan insentif pada layanan preventif.
Jika Pemerintah ingin membuat layanan preventif tidak sekadar retorika, maka preventif harus dibuat mudah dirasakan, mudah diakses, dan mudah dipercaya.
Ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan sangat diperlukan membuat layanan preventif menjadi nyata.
Pencegahan yang berhasil bukan diukur dari banyaknya frekuensi retorika, slogan dan kampanye pemerintah. Namun, bagaimana masyarakat dapat merasakan bahwa sehat adalah keadaan yang harus dijaga, bukan ditunggu sakit baru berbicara kesehatan.