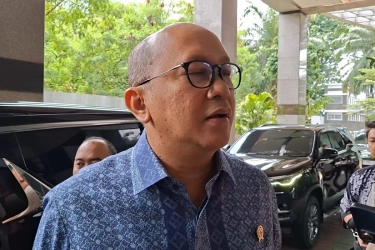Outlook Ekonomi 2026: Di antara Risiko Fiskal dan Iklim
EKONOMI tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia bergerak di atas fondasi kebijakan, tetapi beroperasi di bawah langit yang semakin tidak bisa diprediksi.
Tahun 2026 berdiri di persimpangan itu. Antara konsolidasi fiskal dan tekanan iklim. Antara ambisi pertumbuhan dan realitas risiko.
Bagi pemerintahan baru, 2026 bukan tahun transisi. Mesin kebijakan sudah berjalan penuh. APBN dirancang dan dieksekusi sepenuhnya oleh satu rezim. Tidak ada lagi ruang penyesuaian.
Dalam terminologi kebijakan publik, ini adalah tahun pembuktian kapasitas negara.
Dari sisi eksternal, angin tidak bertiup ke arah Indonesia. Mitra dagang utama mengalami perlambatan. Amerika Serikat stagnan. Korea Selatan naik tipis. CHina, India, Malaysia, dan Thailand melambat.
Volume ekspor sulit melonjak. Harga komoditas utama seperti CPO, batu bara, dan nikel menurun. Indeks harga ekspor berbasis komoditas melemah.
Dampaknya langsung terasa pada sektor eksternal. Surplus perdagangan menipis. Rupiah tertekan. Secara year on year, rupiah melemah terhadap 84,3 persen mata uang dunia. Ini bukan hanya soal dolar. Ini refleksi posisi eksternal yang rapuh.
Neraca pembayaran memperkuat sinyal itu. Dalam 2 kuartal terakhir, defisit tercatat di atas 14 miliar dollar AS. Arus keluar lebih besar dari arus masuk.
Cadangan devisa menurun. Pemerintah merespons dengan kebijakan devisa hasil ekspor. Porsi ditingkatkan dari 30 persen menjadi 100 persen dan ditahan selama 1 tahun.
Secara aritmetika, kebijakan ini menambah pasokan devisa. Secara ekonomi politik, risikonya nyata.
Dalam rezim devisa bebas, perubahan kebijakan yang mendadak sering dibaca pasar sebagai sinyal defensif. Jika ekspektasi memburuk, capital outflow justru dapat terjadi sebelum kebijakan berjalan efektif.
Di dalam negeri, sektor riil menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan kredit turun tajam. Dari di atas 12 persen menjadi sekitar 7,3 persen. Kredit konsumsi hanya tumbuh 4 persen.
Daya beli melemah. Kredit modal kerja tumbuh sekitar 7 persen. Dunia usaha belum melihat prospek permintaan. Kredit investasi tumbuh lebih tinggi, tetapi terkonsentrasi pada sektor berbasis sumber daya alam.
Risiko fiskal
Dari sisi fiskal, masalahnya bersifat struktural. Tax ratio bertahan di kisaran 9,25 persen dan diperkirakan masih di bawah 10 persen pada 2026.
Ini bukan sekadar persoalan kepatuhan. Ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum cukup dalam dan terdiversifikasi.
Tekanan fiskal semakin nyata pada sisi belanja. Sekitar 18 persen belanja negara digunakan untuk membayar bunga utang.
Angka ini lebih besar dari belanja modal dan lebih besar dari transfer ke daerah. Debt service ratio mendekati 43 persen penerimaan negara. Melewati ambang kehati-hatian yang lazim digunakan dalam analisis fiskal.
Dalam konteks ini, target pertumbuhan menjadi isu kredibilitas. Mayoritas lembaga memproyeksikan pertumbuhan sekitar 5 persen.
IMF dan Bank Dunia berada di kisaran 4,9 persen. RPJMN menargetkan 6,3 persen sebagai jalur menuju 8 persen pada 2029.
Masalahnya bukan pada ambisi, tetapi pada lintasan. Jika 2026 berhenti di sekitar 5 persen, maka jarak menuju 8 persen menjadi terlalu curam.
Dalam kerangka ekspektasi rasional ala Thomas Sargent, publik akan mendiskon target yang tidak konsisten dengan kinerja aktual. Investasi menahan diri. Konsumsi menjadi hati-hati.
Risiko fiskal diperberat oleh pemangkasan transfer ke daerah. Porsinya turun hingga sekitar 18 persen dari total belanja negara.
Dalam ekonomi regional, ini signifikan. Belanja daerah adalah motor pertumbuhan lokal. Ketika belanja rutin saja sulit dibiayai, program dihentikan. UMKM tertekan. Kontraktor kecil terpukul. Gaji honorer dipangkas.
Argumen korupsi tidak cukup sebagai pembenaran. Korupsi adalah persoalan tata kelola, bukan alasan mengurangi fungsi stabilisasi fiskal daerah.
Elinor Ostrom menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dapat bekerja efektif jika insentif dan pengawasan dirancang dengan tepat. Mengurangi sumber daya justru melemahkan kapasitas.
Risiko kebijakan juga datang dari desain program nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah contoh penting. Program ini berskala besar. Konsepnya berubah-ubah.
Anggaran signifikan dialokasikan untuk aset fisik. Modal kerja dan skema gaji tidak jelas. Partisipasi masyarakat rendah. Pendekatan top down dominan.
Secara ekonomi, ini berpotensi menjadi zero sum game. Aktivitas baru menggerus usaha yang sudah ada. Pengalaman BUMDes menunjukkan tingkat keberhasilan di bawah 5 persen.
Jika kegagalan terjadi, maka dampaknya tidak berhenti pada ekonomi. Dampak sosial dan politik akan muncul karena dana desa dianggap diambil tanpa keterlibatan.
Dalam kerangka Joseph Stiglitz, ini adalah kegagalan informasi dan insentif. Perancang kebijakan tidak memiliki informasi lokal yang memadai. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien.
Semua risiko tersebut menjadi lebih berat ketika faktor iklim masuk. BMKG memprediksi siklon tropis berlanjut hingga awal tahun.
Pengalaman di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kesiapsiagaan yang rendah. Infrastruktur, logistik, dan birokrasi belum cukup adaptif.
Di sinilah scarring effect bekerja. Bencana iklim tidak hanya merusak aset fisik. Ia meninggalkan luka jangka panjang pada perekonomian. Produksi terganggu.
Basis pajak menyusut. Belanja darurat meningkat. Defisit melebar. Ketika ruang fiskal sempit, respons menjadi lambat. Pemulihan tertunda. Potensi PDB hilang secara permanen.
Ironisnya, anggaran kebencanaan justru dipangkas. Anggaran BNPB turun dari sekitar Rp 1,4 triliun menjadi sekitar Rp 500 miliar.
Dalam ekonomi publik, ini anomali. Risiko meningkat, kapasitas respons menurun. Biaya ekonomi bencana pada akhirnya jauh lebih besar dari penghematan anggaran.
Risiko fiskal dan risiko iklim saling mengunci. Seperti dua arus kuat yang bertemu. Yang satu menekan dari sisi pendapatan dan belanja. Yang lain menggerus basis produksi.
Ketika keduanya bergerak bersamaan, stabilitas makro menjadi rapuh.
Karena itu, solusi harus bersifat teknokratik. Pertama, menyesuaikan target pertumbuhan agar konsisten dengan kapasitas ekonomi. Revisi target bukan tanda kelemahan, melainkan upaya menjaga kredibilitas kebijakan.
Kedua, melindungi belanja daerah yang produktif. Transfer ke daerah harus diposisikan sebagai stabilisator ekonomi lokal.
Pengawasan diperkuat melalui earmarking dan audit berbasis risiko, bukan pemangkasan linear.
Ketiga, melakukan redesain program besar. Koperasi Desa Merah Putih perlu melalui piloting ketat. Partisipasi lokal menjadi prasyarat. Skala dibatasi. Evaluasi berbasis data dilakukan sebelum ekspansi nasional.
Keempat, mereposisi anggaran kebencanaan. Belanja mitigasi iklim harus diperlakukan sebagai investasi fiskal. Setiap rupiah mitigasi mengurangi biaya pemulihan di masa depan.
Kelima, mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka fiskal. Climate stress test pada APBN harus menjadi instrumen rutin, bukan wacana akademik.
Tahun 2026 akan menguji Indonesia bukan oleh satu badai, tetapi oleh perubahan iklim kebijakan dan alam yang bersifat permanen.
Di titik ini, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya tahan guncangan. Ia harus adaptif terhadap iklim. Dan seperti biasa, ekonomi akan mencatat hasilnya dengan jujur. Dalam angka. Dalam fiskal. Dalam pertumbuhan.