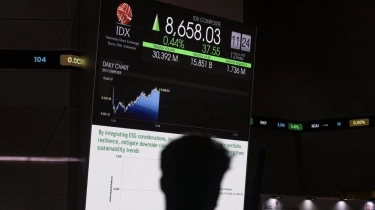Menata Ulang Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Beraca pada Vietnam
SIAPA yang tidak ingin ekonomi Indonesia tumbuh delapan persen? Semua tentu menginginkannya.
Pertumbuhan tinggi bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan strategis agar bangsa ini mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Namun, pertumbuhan semacam itu tidak akan tercapai hanya dengan semangat dan pidato. Sebesar apa pun tekad yang dikumandangkan presiden, tanpa perubahan cara berpikir, sistem kerja, dan pola kebijakan, semuanya hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.
Pertanyaan pentingnya: mengapa keinginan para presiden sebelumnya untuk mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi tidak pernah benar-benar terwujud?
Mengapa ekonomi Indonesia selalu berhenti di kisaran lima persen dan hanya tumbuh tinggi ketika ditopang oleh faktor eksternal — seperti lonjakan harga komoditas atau arus investasi global sesaat?
Jawabannya terletak pada paradigma pembangunan yang belum berubah. Pemerintah boleh berganti, tetapi logika pembangunan nasional tetap sama: bertumpu pada birokrasi administratif, bukan pada produktivitas masyarakat. Kebijakan ekonomi masih lebih sibuk mengatur daripada menumbuhkan.
Pembangunan diukur dari banyaknya program, laporan, dan serapan anggaran, bukan dari seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan rakyat.
Negara tampak sibuk bekerja, tetapi sering kali sibuk pada urusan prosedur, bukan hasil. Akibatnya, energi nasional terserap dalam rutinitas administrasi, sementara daya cipta dan produktivitas masyarakat justru terhambat oleh sistem yang terlalu mengikat.
Presiden Prabowo jika ingin tumbuh ekonomi 8 persen tidak bisa lagi mengandalkan cara pandang lama untuk membawa Indonesia keluar dari kutukan middle income trap. Sistem yang sama tidak akan menghasilkan hasil berbeda. Butuh pendekatan yang berani merubah cara.
Prabowo mesti berani meninjau ulang paradigma pembangunan yang telah usang—menggeser orientasi dari pengelolaan prosedur menuju penciptaan nilai, dari tumpukan laporan menuju pertumbuhan produktivitas nasional.
Tahun 1986, Vietnam adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pendapatan per kapitanya hanya sekitar 231 dollar AS, bahkan lebih rendah dari sebagian besar negara di Afrika kala itu.
Negara itu baru saja keluar dari perang panjang yang meluluhlantakkan segalanya—kelaparan merajalela, pabrik-pabrik hancur, pemerintah kehabisan uang, dan rakyat bekerja keras tanpa pernah melihat hasil. Kemiskinan menjadi wajah keseharian bangsa itu.
Namun tiga puluh tahun kemudian, dunia terperanjat. Ekonomi Vietnam tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan sebagian besar negara Asia Tenggara.
Pendapatan per kapita mereka kini melampaui 4.000 dollar AS, dan tingkat kemiskinan anjlok dari 70 persen menjadi hanya 5 persen. Dunia pun menjulukinya sebagai The Silent Miracle—Keajaiban Asia yang Senyap.
Apa yang sebenarnya mereka lakukan?
Vietnam menyadari satu hal mendasar: tidak ada bangsa yang bisa maju dengan sistem yang tidak efektif.
Pemerintahnya berani melakukan sesuatu yang jarang dilakukan negara berkembang: merombak cara berpikir dan cara bekerja. Mereka menyimpulkan dengan jujur—selama cara lama dipertahankan, hasilnya akan tetap sama.
Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam sistem yang diyakini benar, tetapi justru tidak membawa kemajuan. Sistem itu kaku, tidak efisien, dan gagal menciptakan kesejahteraan.
Namun, yang membedakan Vietnam dari banyak negara lain adalah keberanian untuk mengakui kesalahan. Mereka tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan masa lalu, dan tidak berlindung di balik jargon lama.
Vietnam berani mengucapkan kalimat yang menjadi titik balik sejarah mereka: “Bukan rakyatnya yang malas, melainkan sistemnya yang tidak jalan.”
Dari kesadaran itulah perubahan dimulai. Pemerintah melakukan reformasi total—menyederhanakan birokrasi, menghapus regulasi yang menghambat, dan mengalihkan energi negara ke arah produktivitas rakyat.
Mereka memilih cara baru, dengan keyakinan sederhana: “Kalau cara lama membuat kita gagal, maka kita harus berani mencoba cara baru.”
Keputusan itu menjadi tonggak sejarah. Dalam waktu tiga dekade, Vietnam menulis ulang nasibnya sendiri—dari bangsa miskin pascaperang menjadi salah satu ekonomi paling dinamis dan tangguh di Asia Tenggara.
Penyumbat ekonomi
Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara berekonomi maju. Tidak ada yang kurang secara sumber daya.
Penduduknya melimpah dan kini sedang menikmati bonus demografi yang langka dalam sejarah: lebih dari 190 juta jiwa (70 persen) berada dalam usia produktif. Ini modal sosial terbesar bagi perekonomian suatu negara.
Masyarakat Indonesia juga bukan bangsa pemalas. Mereka dikenal ulet, tangguh, dan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Sumber daya alam pun melimpah, dari energi, pertanian, hingga laut.
Dalam kondisi seperti ini, seharusnya tidak ada alasan bagi ekonomi Indonesia untuk tertahan. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi kita terus berputar di kisaran lima persen, tanpa pernah menembus batas pertumbuhan tinggi.
Masalah utama Indonesia bukan terletak pada rakyatnya, melainkan pada sistem ekonomi dan birokrasi yang mengatur bangsa ini.
Titik lemah terbesar Indonesia adalah adanya penyakit sistemik yang menyumbat energi produktif nasional. Dua di antaranya paling dominan: korupsi struktural dan birokrasi yang tidak produktif.
Korupsi hari ini tidak lagi semata tentang pencurian uang negara. Ia telah berevolusi menjadi korupsi struktural—penyimpangan yang dilegalkan melalui kebijakan dan regulasi. Kekuasaan dijadikan sarana mencari keuntungan, dan aturan diubah menjadi instrumen transaksi.
Regulasi dibuat berlapis, prosedur diperpanjang, dan dokumen dipersulit bukan demi memperkuat akuntabilitas, tetapi untuk menciptakan peluang ekonomi bagi mereka yang memegang kuasa.
Inilah yang saya sebut sebagai sistem bancakan: negara berubah menjadi arena pemerasan, di mana setiap prosedur dirancang untuk memperlihatkan kearoganan kekuasaan sekaligus membuka jalur "uang masuk” bagi pejabatnya.
Dalam sistem seperti ini, birokrasi perlahan menjelma menjadi sarang penyamun yang memeras energi produktif bangsa.
Korupsi seperti ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar pencurian uang rakyat. Ia tidak hanya menguras anggaran, tetapi juga mencuri efisiensi nasional.
Ia membuat proses pembangunan berjalan lambat, panjang, dan berbelit, sehingga biaya ekonomi membengkak. Kesempatan bangsa untuk tumbuh lebih cepat pun terampas oleh kepentingan pribadi yang sempit.
Masalah kedua adalah birokrasi yang kehilangan semangat inovasi. Banyak aparatur bekerja semata-mata untuk memenuhi prosedur, bukan untuk mencapai hasil.
Pola pikir yang dominan adalah: “asal sesuai aturan”, bukan “asal memberi manfaat.” Akibatnya, sistem administratif lebih sibuk menjaga kepatuhan daripada mengejar efektivitas.
Rutinitas menggantikan kreativitas. Dokumen menjadi lebih penting daripada dampak. Banyak proyek publik dirancang bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat, tetapi untuk memenuhi format yang telah ditetapkan.
Dalam situasi seperti ini, birokrasi kehilangan makna dasarnya sebagai pelayan publik dan berubah menjadi penjaga status quo.
Ironisnya, sistem ini justru dipertahankan dengan penuh keyakinan. Banyak yang merasa bahwa cara yang dijalankan selama ini sudah benar hanya karena telah lama dilakukan.
Padahal, jika sistem ini benar-benar efektif, ekonomi Indonesia tidak akan stagnan di angka lima persen selama puluhan tahun.
Vietnam, yang dahulu jauh lebih miskin dari Indonesia, sadar lebih cepat bahwa tidak ada bangsa yang bisa maju dengan sistem yang sesat.
Mereka melakukan reformasi total. Mereka lalu menyederhanakan birokrasi, menghapus regulasi penghambat, dan mengalihkan energi pemerintah ke arah produktivitas rakyat.
Masyarakat Produktif
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan melonjak hanya dengan menambah program baru. Yang dibutuhkan bukan lagi daftar proyek, tetapi reformasi sistemik yang menata ulang cara berpikir pembangunan—dari orientasi administrasi menuju orientasi produktivitas.
Selama ini, keberhasilan terlalu sering diukur dari banyaknya dokumen yang disusun atau program yang dijalankan, bukan dari hasil nyata yang dirasakan rakyat.
Padahal, birokrasi sejatinya bukan pengendali ekonomi, melainkan fasilitator pertumbuhan. Negara tidak semestinya menjadi pengatur yang rumit, melainkan penggerak yang memberi ruang bagi masyarakat untuk produktif dan berdaya cipta.
Kunci utama bagi negara untuk maju bukanlah pada besarnya angka makro, melainkan pada produktivitas manusianya.
Ekonomi hanya akan tumbuh apabila sebagian besar penduduknya bekerja, memiliki penghasilan, dan mampu menciptakan nilai tambah.
Karena 96,4 persen penduduk Indonesia merupakan masyarakat pekerja, maka pekerjaan menjadi kebutuhan fundamental—bukan sekadar sarana mencari nafkah, tetapi motor penggerak utama yang menjaga roda produksi dan konsumsi agar terus berputar.
John Maynard Keynes pernah mengingatkan hampir seabad lalu, “Selama masih ada orang yang menganggur, tugas negara adalah menciptakan pekerjaan.”
Dalam pandangan Keynesian, bahkan pekerjaan paling sederhana sekalipun—seperti menggali lubang dan menimbunnya kembali—lebih baik daripada membiarkan pengangguran.
Produktivitas, sekecil apa pun, tetap memiliki efek berantai terhadap pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi.
Pekerjaan adalah jantung perekonomian. Ketika orang bekerja, daya beli meningkat, konsumsi tumbuh, produksi bergerak, dan investasi tumbuh.
Negara yang berhasil bukanlah yang hanya menjaga stabilitas statistik, melainkan yang menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai inti dari kebijakan ekonominya.
Dalam konteks Indonesia, gagasan Ekonomi 8 persen bukanlah impian muluk, tetapi kemungkinan yang rasional dan terukur. Dengan 70 persen penduduk berada dalam usia produktif, Indonesia memegang kekuatan demografis yang luar biasa besar.
Namun, jika peluang ini tidak diiringi penciptaan lapangan kerja yang produktif, bonus demografi akan berubah menjadi beban sosial yang berat.
Karena itu, pembangunan sejati harus dimulai dari prinsip yang paling mendasar: menjadikan rakyat produktif—bukan sekadar patuh pada sistem, tetapi menjadi pelaku utama dalam menciptakan nilai bagi bangsanya.
Reformasi produktif bukan sekadar mengganti program, melainkan mengubah cara berpikir dan cara bekerja bangsa ini.
Reformasi semacam itu menuntut keberanian untuk menyingkirkan segala hambatan yang menyumbat energi produktif rakyat—baik berupa regulasi yang usang, birokrasi yang lamban, maupun kepentingan sempit yang hanya memperkaya segelintir orang.
Tanpa keberanian membongkar fondasi ekonomi lama dan menata ulang sistem pembangunan, mustahil Indonesia mampu menembus pertumbuhan delapan persen yang berkelanjutan.
Pertumbuhan delapan persen bukanlah sekadar angka, melainkan arah transformasi menuju ekonomi yang benar-benar digerakkan oleh produktivitas rakyat.
Jalan ke sana menuntut keberanian membangun sistem ekonomi yang menumbuhkan, bukan mengatur; yang menciptakan nilai, bukan menambah beban.
Skenario menuju pertumbuhan itu hanya bisa terwujud bila Indonesia menata kembali masyarakat produktifnya melalui tiga pilar utama pembangunan nasional:
ketahanan pekerjaan yang menjamin setiap warga memiliki akses kerja yang layak;
ketahanan industri yang memperkuat nilai tambah dan kemandirian ekonomi;
serta ekspansi pekerja global yang menjadikan tenaga kerja Indonesia bagian dari kekuatan ekonomi dunia.
Jika ketiga pilar ini dijalankan secara simultan dan terintegrasi dalam lima tahun pertama pemerintahan, maka pertumbuhan delapan persen bukan lagi mimpi atau retorika politik, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang bekerja dengan benar.
Hanya dengan langkah seperti itu, Indonesia tidak sekadar tumbuh, tetapi benar-benar naik kelas—dari bangsa yang bekerja untuk bertahan, menjadi bangsa yang bekerja untuk memakmurkan dunia.
Tag: #menata #ulang #mesin #pertumbuhan #ekonomi #beraca #pada #vietnam