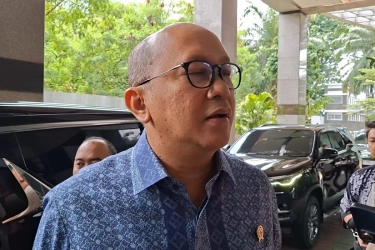Menakar Konsekuensi jika Gagal Bayar Utang Whoosh
PERINGATAN Prof Mahfud MD tentang potensi “taruhan” Natuna Utara jika Indonesia gagal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), jika demikian faktanya, kembali menggugah kesadaran publik bahwa utang besar selalu datang dengan risiko kedaulatan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyoroti dugaan mark up biaya proyek Whoosh dan mendesak pemerintah mengusut aliran dana yang membengkak.
Kritiknya bukan soal sentilan politik, tetapi lebih menjadi peringatan bahwa dalam dunia investasi strategis, batas antara kerja sama ekonomi dan tekanan geopolitik bisa sangat tipis.
Di balik kebanggaan nasional atas proyek sarana transportasi berkecepatan 350 kilometer per jam itu tersimpan pertanyaan, sejauh mana kemandirian fiskal dan kehati-hatian diplomatik Indonesia masih terjaga ketika utang publik menjadi alat tawar lintas batas.
China kini menyatakan kesiapan membantu Indonesia mengatasi krisis keuangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang membengkak hingga 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 117 triliun.
Dukungan tersebut tentu perlu dibaca sebagai bagian dari upaya Beijing mempertahankan reputasi Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara.
Di tengah tekanan fiskal dan ketegangan geopolitik, kesiapan China untuk merestrukturisasi utang Whoosh menjadi sinyal bahwa proyek ini tidak hanya soal transportasi, tetapi juga tentang kredibilitas politik lintas negara.
Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan akan menerbitkan Keputusan Presiden untuk menuntaskan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB) sebagai lembaga pembiayaan utama proyek ini.
Keputusan tersebut akan menjadi ujian awal kebijakan fiskal dan diplomasi ekonomi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo.
Di satu sisi, restrukturisasi menawarkan jalan keluar teknis untuk menunda beban keuangan negara. Namun di sisi lain, dapat menandai pergeseran posisi tawar Indonesia terhadap China dari mitra setara menjadi debitur yang harus tunduk di bawah kompromi yang mungkin saja akan terus berulang secara jangka panjang.
Polemik keuangan proyek Whoosh mencerminkan paradoks klasik pembangunan ambisius yang menuntut biaya politik yang ternyata jauh lebih mahal daripada ongkos konstruksi.
Biaya yang melonjak tiga kali lipat dari estimasi awal menunjukkan adanya persoalan tata kelola, dari perencanaan yang lemah hingga tumpang tindih tanggung jawab antara BUMN konsorsium dan kementerian teknis.
Dalam konteks ini, pertanyaan Mahfud MD tentang “ke mana larinya uang proyek” merupakan refleksi atas ketidakseimbangan antara kemegahan infrastruktur dan rapuhnya disiplin fiskal negara ini.
Bercermin dari sejarah yang mengingatkan bahwa kehilangan kendali atas aset vital bukan hanya asumsi atau hipotesis.
Banyak negara pernah mengalami bagaimana utang infrastruktur yang awalnya dijanjikan sebagai jalan tercepat menggapai modernisasi justru menjadi instrumen penguasaan sumber daya.
Republik Demokratik Kongo di Afrika, misalnya, menandatangani perjanjian resource-for-infrastructure dengan China senilai 6 miliar dollar AS pada 2008.
Kesepakatan ini menjanjikan pembangunan jalan, rumah sakit, dan jaringan listrik sebagai imbalan atas hak tambang tembaga dan kobalt di bawah proyek Sicomines.
Namun, setelah harga komoditas global jatuh dan penerimaan negara merosot, utang pun menumpuk. Ketika negosiasi ulang gagal, konsorsium perusahaan China mengambil alih sebagian besar hak operasi tambang, termasuk akses ke cadangan kobalt terbesar dunia.
Bagi Kongo yang semula berharap bisa mewujudkan industrialisasi, hasilnya justru kehilangan kendali atas sumber daya strategis yang menentukan masa depan industri kendaraan listrik dunia.
Nasib serupa menimpa Laos, negara kecil yang terjebak dalam gelombang proyek Belt and Road Initiative.
Untuk membiayai jaringan listrik nasional, Laos berutang besar kepada China Southern Power Grid. Ketika tekanan pembayaran meningkat, pemerintah negeri Seribu Gajah itu akhirnya menyerahkan mayoritas kepemilikan Electricité du Laos Transmission Company kepada kreditor asing.
Dampaknya, sistem transmisi listrik yang dulunya simbol kemandirian energi kini sebagian besar sudah dikendalikan dari luar negeri.
Arah ekspor energi ke Thailand dan Vietnam tak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan nasional, melainkan melalui pertimbangan komersial dan politik dari perusahaan yang berada di bawah pengaruh Beijing.
Di belahan Asia lain, Pakistan, skema serupa terjadi melalui proyek China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). Pelabuhan Gwadar yang dibangun dengan pinjaman China kini justru di bawah pengelolaan China Overseas Port Holding Company selama 40 tahun.
Pemerintah Pakistan secara resmi menyebutnya kerja sama pengelolaan jangka panjang, tetapi dalam praktiknya kontrak itu mengalihkan sebagian besar kendali ekonomi pelabuhan ke tangan asing.
Beijing lihai. Gwadar pun berubah menjadi simpul penting dalam strategi maritim China di Laut Arab.
Tak hanya pelabuhan dan listrik, jebakan serupa juga terjadi di sektor tambang dan energi.
Zambia, misalnya, terjerat utang besar dari proyek infrastruktur yang dibiayai oleh China Exim Bank. Ketika gagal bayar, sejumlah konsesi tambang tembaga dan proyek energi masuk dalam skema negosiasi ulang.
Pemerintah Zambia akhirnya harus menunda pembayaran obligasi negara dan melakukan restrukturisasi dengan risiko kehilangan aset produktif milik BUMN pertambangan.
Ekuador pun mengalami hal serupa setelah menandatangani kontrak pendanaan dengan China untuk proyek minyak mentah.
Sebagai jaminan utang, negara itu harus menyerahkan sebagian besar ekspor minyaknya kepada China National Petroleum Corporation (CNPC) dan PetroChina selama bertahun-tahun.
Akibatnya, pendapatan minyak yang seharusnya menopang fiskal nasional justru langsung dialirkan untuk membayar utang lama.
Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya alam kerap menjadi jalan terakhir ketika kemampuan bayar negara melemah.
Infrastruktur yang dibangun dengan utang besar tidak hanya mengubah neraca keuangan, tetapi juga struktur kedaulatan ekonomi negara.
Dalam banyak kasus, pinjaman luar negeri disertai klausul tersembunyi yang memungkinkan kreditor menuntut kompensasi atas aset strategis bila terjadi gagal bayar.
Bentuknya bisa beragam, mulai dari hak kelola pertambangan, izin ekspor sumber daya, hingga monopoli distribusi energi.
Konteks ini seharusnya menjadi cermin bagi Indonesia. Ketika biaya proyek Kereta Cepat Whoosh melonjak hingga 7,27 miliar dollar AS dan bergantung pada pembiayaan China Development Bank, maka risiko yang dihadapi tidak hanya soal fiskal, melainkan juga politik sumber daya yang menjadi keistimewaan negara ini.
Proyek seambisius Whoosh berdiri di atas fondasi utang yang menuntut kepastian pembayaran dalam jangka panjang.
Jika gagal, maka konsekuensinya bisa menjalar ke sektor lain, dari renegosiasi proyek infrastruktur hingga tekanan terhadap aset strategis negara, termasuk energi, logistik, bahkan potensi sumber daya laut.
Kita mungkin merasa jauh dari skenario seperti Sri Lanka atau Kongo. Namun, realitas fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan yang sama. Belanja negara untuk subsidi energi melonjak, penerimaan pajak belum sepenuhnya pulih, dan ruang fiskal kian sempit.
Dalam situasi seperti ini, menjaga kredibilitas fiskal bukan sekadar soal membayar utang tepat waktu, tetapi juga memastikan agar tidak ada celah bagi kekuatan eksternal menekan lewat mekanisme pinjaman.
Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan transparansi, pengawasan, dan negosiasi ulang yang sehat, Whoosh berpotensi menjadi preseden bagi proyek-proyek strategis lain yang berbasis utang besar, dari kilang minyak hingga jaringan logistik nasional.
Pelajaran dari berbagai negara jelas, kehilangan kendali atas sumber daya bukanlah peristiwa yang terjadi sekaligus, melainkan akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan keseimbangan antara ambisi pembangunan dan disiplin fiskal.
Indonesia memiliki peluang untuk tidak mengulang kesalahan itu, asal berani meninjau ulang setiap perjanjian utang dengan logika kedaulatan, bukan sekadar efisiensi teknokratis.
Dalam perspektif sejarah panjang ekonomi global, hubungan antara utang dan kedaulatan jarang bersifat netral. Di balik setiap proyek besar yang dibiayai pinjaman luar negeri selalu tersembunyi politik kekuasaan yang lebih dalam dari sekadar neraca fiskal.
Seperti dicatat Pierre Pénet dan Juan Flores Zendejas dalam Sovereign Debt Diplomacies, utang negara sering kali menjadi alat diplomasi terselubung, cara baru bagi kekuatan ekonomi besar menegakkan pengaruh tanpa harus menaklukkan secara militer.
Sejarah Amerika Latin, Afrika, hingga Asia mencatat bagaimana pinjaman publik, meskipun dikemas dalam bahasa indah pembangunan, kerap berujung pada pembatasan kebijakan domestik dan kehilangan kendali atas sumber daya strategis.
Pada abad ke-19, Inggris menggunakan jaringan perbankan dan perdagangan untuk menanamkan kontrol ekonomi di Amerika Latin.
Negara seperti Peru bahkan menyerahkan pengelolaan ekspor guano, komoditas utamanya, kepada perusahaan Inggris Gibbs & Sons yang sekaligus mengatur arus fiskal negara.
Pemerintah kehilangan kendali atas pendapatannya sendiri karena akses ke pasar modal London mensyaratkan jaminan atas komoditas ekspor.
Kasus ini menjadi cikal bakal dari apa yang kini disebut Pénet dan Zendejas sebagai debt diplomacy, sistem di mana pinjaman publik tidak hanya menumbuhkan infrastruktur, tetapi juga menanamkan struktur ketergantungan yang bertahan lintas generasi.
Model serupa juga berlaku pada banyak negara pascakolonial di Afrika dan Asia. Dalam konteks modern, utang infrastruktur kerap dikaitkan dengan proyek besar seperti Belt and Road Initiative China.
Polanya konsisten, negara penerima utang mendapatkan jalan, pelabuhan, atau pembangkit listrik. Namun di sisi lain membuka ruang kontrol atas logistik, energi, dan kebijakan fiskal nasional.
Ketika arus pembayaran tersendat, negosiasi restrukturisasi kerap diikuti oleh konsesi nonfinansial.
Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka hanyalah simbol paling kasat mata dari diplomasi utang semacam ini, tetapi di baliknya terdapat banyak contoh serupa yang tidak selalu terekspos ke ruang publik.
Pénet dan Zendejas menegaskan bahwa fenomena ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari transformasi global di mana sovereign debt menjadi instrumen baru kolonialisme ekonomi.
Negara berdaulat diposisikan bukan lagi sebagai mitra yang setara, melainkan sebagai entitas hukum yang kontraktual, tunduk pada klausul, arbitrase, dan yurisdiksi yang sering kali justru berpihak kepada kreditor.
Ketika gagal bayar terjadi, sanksinya tidak selalu berbentuk penyitaan aset langsung, tetapi berupa perubahan struktur kebijakan, dari penyesuaian fiskal hingga pembatasan eksplorasi sumber daya alam.
Lihat saja pengalaman Kongo dan Zambia, dua negara dengan kekayaan tambang luar biasa yang kini menghadapi dilema serupa.
Di Kongo, perjanjian resource-for-infrastructure dengan China menjanjikan pembangunan infrastruktur senilai miliaran dolar dengan imbalan hak tambang tembaga dan kobalt.
Namun, ketika arus kas negara melemah, penguasaan konsesi tambang berpindah ke perusahaan China. Hasilnya, negara kehilangan kontrol atas komoditas paling strategis di era transisi energi.
Zambia pun mengikuti jejak serupa ketika gagal membayar obligasi dan pinjaman infrastruktur, pemerintah harus menegosiasikan ulang utang dengan risiko kehilangan kendali atas aset pertambangan.
Fenomena yang oleh Pénet disebut legal colonization through debt contracts ini menjelaskan bagaimana kontrol atas sumber daya alam dapat berpindah tanpa penjajahan formal.
Negara tidak lagi dijajah dengan pasukan bersenjata, tetapi dengan klausul pinjaman dan perjanjian investasi.
Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi peringatan serius ketika proyek strategis nasional seperti Kereta Cepat Whoosh sangat bergantung pada skema pembiayaan luar negeri. \
Ketika biaya proyek melonjak hingga 7,27 miliar dollar AS dan pemerintah harus menerbitkan Keputusan Presiden untuk merestrukturisasi utang kepada China Development Bank, maka hubungan keuangan tersebut telah naik kelas menjadi hubungan politik.
Pénet dan Zendejas juga menghidupkan kembali gagasan klasik dari Mohamed Bedjaoui, pakar hukum internasional asal Aljazair, yang berargumen bahwa kedaulatan sejati mencakup hak untuk mengendalikan sumber daya alam tanpa tunduk pada kontrak kolonial.
Dalam konteks ini, Bedjaoui menolak pandangan bahwa negara penerus kolonial harus tetap membayar utang yang digunakan untuk menindas rakyatnya sendiri.
Ia menyebutnya sebagai odious debt, utang yang keabsahannya secara moral dan politik dapat dipertanyakan.
Konsep ini relevan untuk menilai proyek infrastruktur yang gagal membawa manfaat publik, namun justru membebani fiskal dan membuka peluang penetrasi asing terhadap aset strategis.
Pertanyaannya, apakah Indonesia sedang menuju situasi serupa. Secara formal, Indonesia masih dalam posisi aman, tetapi struktur pembiayaan proyek-proyek besar menunjukkan gejala ketergantungan yang memang semakin dalam.
Dari kereta cepat hingga kilang minyak, dari smelter nikel hingga proyek Ibu Kota Nusantara yang belum jelas nasibnya itu, sebagian besar pembiayaannya bergantung pada skema pinjaman bilateral atau pembiayaan sindikasi yang terhubung dengan kepentingan politik global.
Ketika utang ini direstrukturisasi, posisi tawar Indonesia otomatis melemah. Kreditor tidak hanya menuntut pembayaran, tetapi juga akses terhadap proyek, kontrak turunan, dan bahkan kebijakan sektor energi dan transportasi yang lebih luas.
Seperti diuraikan dalam Sovereign Debt Diplomacies, hubungan antara kreditor dan debitur selalu bersifat asimetris karena perbedaan kapasitas hukum dan politik.
Negara maju memiliki instrumen keuangan dan hukum internasional yang mampu memaksakan kepatuhan, sementara negara berkembang sering kali bergantung pada reputasi pasar untuk mempertahankan akses pembiayaan.
Akibatnya, negosiasi restrukturisasi jarang benar-benar setara. Kreditor bisa menentukan syarat yang melemahkan kontrol negara atas sumber daya, sebagaimana yang dialami Ekuador ketika terpaksa menyerahkan kontrak ekspor minyaknya kepada PetroChina sebagai jaminan utang.
Pelajaran paling penting dari semua ini adalah bahwa diplomasi utang tidak lagi berada di ruang fiskal semata, melainkan telah menjadi bagian dari diplomasi sumber daya. Penguasaan atas tambang, energi, dan logistik kini menjadi perpanjangan dari kontrak utang.
Dalam konteks Indonesia, jika proyek Whoosh gagal bayar atau direstrukturisasi secara berat sebelah, risiko tidak berhenti pada beban APBN.
Ia bisa merembet ke penguasaan infrastruktur strategis, jalur rel, lahan, bahkan hak operasi yang menjadi simbol konektivitas nasional.
Dalam skenario ekstrem, kreditor dapat meminta konsesi operasi jangka panjang sebagaimana yang terjadi di pelabuhan Gwadar atau Hambantota.
Di titik ini, utang berubah fungsi menjadi alat penataan ulang geopolitik. Bukan hanya soal bunga dan tenor, tetapi tentang siapa yang mengendalikan aset strategis di wilayah yang semakin vital secara ekonomi dan militer.
Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik memiliki posisi yang terlalu penting untuk membiarkan kebijakan utangnya ditentukan sepihak oleh kreditor asing.
Pemerintahan baru harus menyadari bahwa setiap keputusan fiskal adalah juga keputusan geopolitik.
Pénet dan Zendejas mengakhiri argumentasinya dengan peringatan, sovereign debt diplomacies selalu berkembang dalam bentuk yang kian kompleks. Namun, substansinya tetap sama, menentukan siapa yang berdaulat dan siapa yang tergantung.
Dalam dunia yang kini bergeser menuju multipolaritas, diplomasi utang menjadi medan baru perebutan pengaruh antara kekuatan lama dan kekuatan baru.
Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi ujian ganda, menjaga reputasi fiskal di mata investor sekaligus mempertahankan kedaulatan atas sumber daya nasional.
Karenanya, pilihan terbaik bukan sekadar menunggu restrukturisasi atau menyambut lampu hijau dari kreditor asing.
Yang dibutuhkan adalah strategi fiskal berdaulat, memperkuat pembiayaan domestik, menegakkan transparansi BUMN, dan memastikan setiap proyek strategis memiliki risk buffer yang realistis terhadap fluktuasi utang luar negeri.
Negara perlu menghidupkan kembali prinsip yang pernah diperjuangkan para ekonom dunia ketiga di era 1970-an, bahwa pembangunan tidak boleh dibayar dengan kehilangan kedaulatan.
Kereta cepat Whoosh seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan awal dari diplomasi utang baru yang justru akan mengikat generasi mendatang. Bijaklah terhadap masa depan anak cucu kita.
Bila kita gagal membaca tanda-tanda sejarah dari Kongo, Zambia, Sri Lanka, dan Ekuador, maka bukan tidak mungkin proyek ini akan tercatat bukan sebagai kebanggaan nasional, tetapi sebagai bab awal dari kehilangan kendali atas masa depan ekonomi sendiri.
Dalam dunia yang semakin saling tergantung, kedaulatan ekonomi bukan lagi soal siapa yang meminjam, tetapi siapa yang tetap berkuasa setelah utang itu jatuh tempo.
Tag: #menakar #konsekuensi #jika #gagal #bayar #utang #whoosh