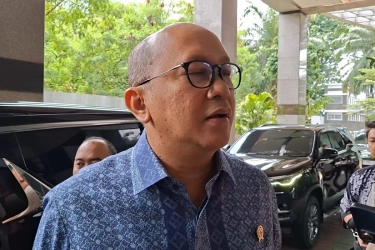Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Antara Mimpi Politik dan Realitas Ekonomi
JANJI Prabowo–Gibran untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun memantik harapan besar di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Target ini setara dengan sekitar 3,8 juta pekerjaan setiap tahun hingga 2029.
Dalam skala politik, angka itu terdengar meyakinkan; tetapi secara ekonomi, ia membutuhkan fondasi yang jauh lebih kokoh. Dengan tingkat pengangguran yang masih sekitar 4,8n dominasi pekerja informal yang mencapai 86 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2025), mampukah Indonesia benar-benar menepati janji tersebut?
Realisme target dan teori elastisitas pekerjaan
Secara empiris, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dijelaskan melalui teori elastisitas tenaga kerja terhadap PDB, yaitu sejauh mana peningkatan pertumbuhan mampu menyerap tenaga kerja baru.
Berdasarkan laporan Bank Dunia (2023), di negara berkembang elastisitas ini berkisar antara 0,3–0,5, artinya setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya menambah 0,3–0,5% pekerjaan. Maka, untuk mencapai tambahan 19 juta pekerjaan, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,5–8% per tahun dengan sektor yang padat karya dan produktivitas tinggi.
Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan yang cepat dan penyerapan tenaga kerja yang luas. Tanpa transformasi struktural, pertumbuhan justru bisa menciptakan lapangan kerja semu—pekerjaan informal dengan produktivitas rendah yang sulit diandalkan untuk menopang ekonomi jangka panjang.
Mesin pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja
Menurut teori employment multipliers (ILO, 2021), sektor berbeda memiliki daya pengganda lapangan kerja yang juga berbeda. Sektor konstruksi dan perumahan memiliki multiplier tinggi karena menggerakkan banyak sektor turunan—dari bahan bangunan, logistik, hingga jasa pendukung.
Selain itu, sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan komponen otomotif tetap menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja formal jika didukung dengan insentif logistik dan pajak yang tepat.
Sektor agro-maritim dan pengolahan pangan juga berpotensi besar untuk menciptakan jutaan pekerjaan baru di luar Jawa. FAO (2024) mencatat, industrialisasi pertanian di negara berkembang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja hingga 10% dalam satu dekade bila disertai investasi dalam rantai pasok dingin (cold chain) dan digitalisasi pemasaran.
Tak kalah penting, ekonomi pariwisata dan jasa modern mampu menjadi penggerak kerja cepat, terutama di wilayah urban dan destinasi wisata. Sementara itu, ekonomi perawatan (care economy)—yang mencakup sektor penitipan anak, layanan lansia, dan perawatan disabilitas—semakin diakui OECD (2022) sebagai pendorong baru pertumbuhan inklusif, terutama bagi perempuan.
Kebijakan yang mengubah pertumbuhan jadi kesempatan
Agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan elastisitas kesempatan kerja. Teori dual economy dari W. Arthur Lewis (1954) menjelaskan bahwa pertumbuhan inklusif hanya terjadi jika tenaga kerja berpindah dari sektor tradisional ke sektor modern dengan produktivitas lebih tinggi. Ini berarti program penciptaan kerja tidak cukup hanya dengan proyek besar negara, tetapi harus menyentuh level mikro—UKM, koperasi, dan usaha perdesaan.
Kebijakan yang dapat mempercepat proses tersebut meliputi perluasan kredit UMKM berbasis digital, program magang nasional untuk menjembatani lulusan muda dengan industri, serta percepatan proyek padat karya di perumahan rakyat, sanitasi, dan infrastruktur hijau.
Berdasarkan model Active Fiscal Employment Policy (IMF, 2023), setiap Rp1 triliun belanja padat karya mampu menciptakan antara 25.000–40.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung. Bila digerakkan secara konsisten, kombinasi fiskal dan vokasi semacam ini dapat menjadi motor utama menuju target 19 juta pekerjaan.
Kualitas kerja, bukan sekadar kuantitas
Namun, jumlah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Konsep Decent Work Agenda dari ILO (2019) menekankan pentingnya kualitas pekerjaan—upah layak, jaminan sosial, keselamatan, dan kesempatan karier. Indonesia perlu memastikan setidaknya 50% dari pekerjaan baru masuk kategori formal, dengan perlindungan sosial yang jelas.
Kualitas juga berarti inklusivitas. Partisipasi tenaga kerja perempuan dan pemuda harus menjadi indikator keberhasilan. OECD (2022) mencatat, peningkatan partisipasi kerja perempuan sebesar 10 kali lipat menambah PDB nasional hingga 2–3%. Dengan demikian, keberhasilan penciptaan kerja tidak hanya diukur dari berapa banyak orang bekerja, tetapi juga seberapa sejahtera dan produktif mereka.
Dari janji politik menuju kebijakan berbasis data
Target 19 juta pekerjaan baru bukanlah hal mustahil, tetapi juga bukan hal yang bisa tercapai secara otomatis. Ia membutuhkan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada lapangan kerja, kebijakan industri yang berpihak pada sektor padat karya, serta tata kelola fiskal yang disiplin dan terukur.
Pemerintah perlu mengukur keberhasilan bukan hanya melalui data penyerapan kerja, tetapi juga melalui indikator formalitas, produktivitas, dan kesetaraan. Transparansi data akan menjadi kunci agar janji besar ini tidak berhenti sebagai slogan politik, melainkan menjadi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mengubah struktur ekonomi Indonesia secara nyata.
Apabila konsistensi kebijakan dapat dijaga, maka “19 juta pekerjaan” bukan sekadar retorika, melainkan jalan menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Kita tidak boleh hanya terlihat sibuk, tetapi tidak produktif. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah siap membuktikan bahwa janji politik bisa menjadi realitas ekonomi?
Tag: #janji #juta #lapangan #kerja #antara #mimpi #politik #realitas #ekonomi