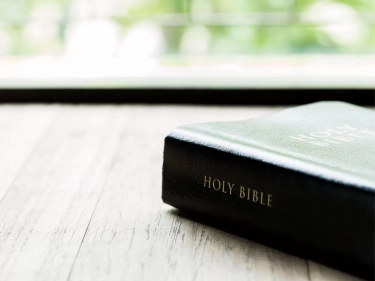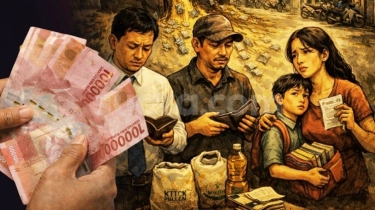Proyeksi Pertumbuhan dan Harapan Pekerjaan yang Lesu
MINGGU ini, Bank Dunia baru saja merilis publikasi terbaru mengenai proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Secara umum, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ini masih akan berada di atas rata-rata pertumbuhan global.
Namun, laju pertumbuhan tersebut diperkirakan melambat pada 2025 dan semakin menurun pada 2026. Sejumlah indikator menunjukkan tanda-tanda pelemahan momentum ekonomi.
Sebagai contoh, penjualan ritel memang mencatat peningkatan, tetapi tingkat keyakinan konsumen belum sepenuhnya pulih sejak pandemi COVID-19.
Sementara itu, produksi industri masih relatif kuat, namun kepercayaan dunia usaha tetap lemah.
China, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun ini, sebelum melambat menjadi 4,2 persen pada 2026.
Di sisi lain, negara-negara berkembang Asia lainnya diproyeksikan tumbuh sekitar 4,4 persen pada 2025 dan sedikit meningkat menjadi 4,5 persen pada 2026.
Adapun kawasan Pasifik diperkirakan mencatat pertumbuhan sebesar 2,7 persen pada 2025 dan 2,8 persen pada 2026.
Bagaimana dengan Indonesia? Bank Dunia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2025 dan 2026.
Proyeksi ini tidak banyak berubah dibandingkan berbagai perkiraan sebelumnya, yang juga menempatkan pertumbuhan Indonesia di bawah 5 persen.
Meski masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, publik di Indonesia umumnya baru dapat melihat data resmi sekitar satu bulan setelah berakhirnya kuartal.
Sebagai contoh, untuk kinerja ekonomi kuartal III, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data pertumbuhan pada 5 November 2025.
Beberapa faktor turut memengaruhi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan. Pertama, meningkatnya restriksi perdagangan antarnegara sebagai dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.
Di antara seluruh negara di Asia Pasifik, China menjadi yang paling terdampak, dengan kenaikan tarif perdagangan yang signifikan dibandingkan tahun 2024.
Kedua, meningkatnya ketidakpastian kebijakan di tingkat global. Presiden Trump dikenal dengan gaya kebijakan yang sulit diprediksi, sehingga memicu fluktuasi dalam sentimen pasar.
Berdasarkan konsep economic policy uncertainty yang dikembangkan oleh Dario Caldara dan rekan-rekannya (2020), tingkat ketidakpastian global meningkat tajam, baik terkait kebijakan ekonomi maupun kebijakan perdagangan internasional.
Ketiga, konsensus umum menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Ekspektasi pertumbuhan negara-negara anggota G7 berada di bawah 2 persen, sementara kelompok negara berkembang diperkirakan tumbuh di bawah 4 persen.
Keempat, di tengah turbulensi pasar keuangan global, pasar di kawasan Asia Pasifik masih mampu bertahan dalam kondisi yang relatif kondusif.
Selisih suku bunga riil antara negara-negara Asia Pasifik dan negara-negara maju yang masih lebar mendorong terjadinya aliran modal masuk ke kawasan ini.
Terakhir, negara-negara Asia Pasifik sebenarnya memiliki peluang untuk menumbuhkan ekonomi yang lebih dinamis. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar negara di kawasan ini masih memiliki kesenjangan dalam kualitas reformasi domestik dibandingkan dengan negara-negara maju.
Pengangguran generasi muda
Hal menarik dari laporan tersebut adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan generasi muda berusia 15–24 tahun, yaitu kelompok yang umumnya lahir setelah tahun 2000.
China dan Indonesia mencatatkan angka tertinggi di kawasan Asia Pasifik, masing-masing sebesar 15,9 persen dan 13,1 persen.
Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda menghadapi tantangan besar dalam memasuki pasar kerja. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai temuan di lapangan yang menggambarkan semakin sulitnya mencari pekerjaan, khususnya bagi generasi Z.
Salah satu kondisi utama yang muncul adalah semakin banyaknya lulusan baru yang memasuki pasar tenaga kerja, baik dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah, termasuk kelompok yang tidak sempat menikmati pendidikan menengah.
Namun, pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah pencari kerja tersebut.
Kemajuan teknologi turut membawa perubahan drastis dalam struktur ketenagakerjaan. Banyak jenis pekerjaan yang dulunya ada kini mulai menghilang, digantikan oleh pekerjaan baru yang menuntut keterampilan berbeda.
Sayangnya, tidak semua generasi muda memiliki kemampuan yang sesuai dengan keterampilan baru yang dibutuhkan pasar kerja saat ini.
Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul “Future Jobs: Robots, Artificial Intelligence, and Digital Platforms in East Asia and Pacific” yang diterbitkan pada pertengahan tahun ini, perkembangan teknologi telah dan akan terus mengubah lanskap dunia usaha.
Menurut asesmen Bank Dunia, ruang lingkup pekerjaan di banyak negara Asia Pasifik akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan robotika dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Adopsi teknologi robot diperkirakan akan mengubah secara drastis pola pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, antara tahun 2018 hingga 2022, penggunaan robot telah menggantikan sekitar 1,4 juta pekerja formal berkeahlian rendah (low-skilled formal workers) di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Namun, sesungguhnya otomatisasi juga telah meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja baru, terutama untuk jenis pekerjaan nonrutin yang memerlukan kemampuan kognitif lebih tinggi.
Walaupun dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap pasar kerja belum dapat diprediksi secara pasti, terdapat dua kemungkinan utama yang bisa terjadi.
Pertama, efek penggantian pekerjaan (displacement effect), yakni hilangnya beberapa jenis pekerjaan lama yang digantikan oleh munculnya jenis pekerjaan baru.
Kedua, efek peningkatan produktivitas tenaga kerja (augmentation effect), di mana AI membantu memperkuat kinerja manusia dalam bekerja.
Menariknya, efek penggantian pekerjaan ini tidak merata antarkelompok. Sejumlah temuan menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih banyak terdampak oleh otomatisasi dibandingkan laki-laki.
Terakhir, digitalisasi telah membawa perubahan besar pada pasar tenaga kerja. Pekerja dengan tingkat intensitas digital yang lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan lebih besar, termasuk di Indonesia.
Bahkan, pekerja di sektor informal dengan intensitas digital tinggi mendapatkan upah yang hampir setara dengan pekerja di sektor formal dengan intensitas digital rendah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi menjadi peluang untuk mengurangi kesenjangan upah antarkelompok pekerja.
Sebagai penutup, peningkatan kapasitas calon tenaga kerja menjadi hal yang mendesak, baik melalui lembaga pendidikan maupun pelatihan.
Selain itu, kualitas kesehatan juga perlu mendapat perhatian serius karena berperan penting dalam menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja.
Seluruh upaya tersebut harus disertai kebijakan yang berpihak pada perluasan kesempatan ekonomi.
Arah pembangunan ini dapat diperkuat melalui investasi yang berfokus pada penguatan infrastruktur, mulai dari sektor transportasi, energi, hingga digital, guna memperkuat daya saing nasional dan menciptakan iklim usaha yang sehat.