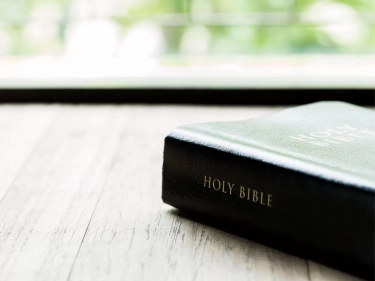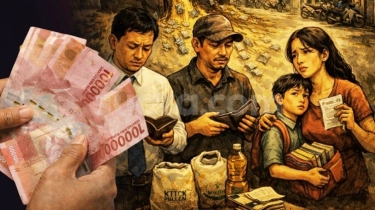BUMN Mesin Utama Pencipta Lapangan Kerja yang Terabaikan
SETIAP tahun, Indonesia menghadapi tantangan besar: menyediakan antara 3,6 juta hingga 4 juta lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah.
Tantangan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan tekanan struktural terhadap pasar kerja nasional yang semakin kompleks, kompetitif, dan tidak merata secara kualitas.
Lapangan kerja baru tidak tercipta secara spontan. Ia lahir dari sinergi berbagai sumber yang saling berinteraksi—investasi, pembangunan infrastruktur, kebijakan publik, dan inovasi sektor riil.
Investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, menjadi motor utama dalam menciptakan ruang kerja baru. Ketika investor membangun pabrik, membuka kantor cabang, atau memperluas lini produksi, peluang kerja nyata pun tercipta.
Sepanjang kuartal pertama tahun 2025, investasi sebesar Rp 465 triliun tercatat telah menciptakan lebih dari 594.000 lapangan kerja.
Pemerintah bahkan memproyeksikan bahwa investasi dapat menyerap hingga 2,9 juta tenaga kerja per tahun dalam lima tahun mendatang.
Selain itu, peluang baru juga diharapkan muncul dari sektor ekonomi hijau dan digital—melalui pengembangan energi terbarukan dan industri kendaraan listrik—dua bidang yang sebelumnya belum digarap secara optimal.
Peran BUMN juga tak bisa diabaikan. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, smelter, dan kilang minyak yang dijalankan oleh BUMN berkontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja, terutama di daerah tertinggal yang minim akses terhadap pekerjaan formal.
Kemitraan dengan UMKM dan koperasi turut menciptakan efek ganda terhadap lapangan kerja tidak langsung, meskipun sebagian besar masih bersifat informal dan belum sepenuhnya terlindungi.
Namun, di balik potensi besar tersebut, Indonesia masih menghadapi krisis ketersediaan lapangan kerja yang layak.
Fenomena ini terlihat dari membludaknya pencari kerja di setiap job fair, antrean panjang di bursa tenaga kerja, serta meningkatnya jumlah pengemudi ojek daring yang menggantungkan hidup pada sektor informal.
Survei Konsumen Bank Indonesia bahkan menunjukkan bahwa indeks ketersediaan lapangan kerja telah masuk ke zona pesimis—menandakan semakin sempitnya peluang kerja yang stabil dan bermartabat.
Krisis ini bukan hanya persoalan kuantitas, melainkan juga kualitas dan keberlanjutan. Tanpa strategi terpadu dan keberpihakan kelembagaan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia berisiko berubah menjadi beban sosial.
Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus menjadi agenda utama pembangunan nasional, bukan sekadar efek samping dari pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, penciptaan kerja tidak dapat disandarkan hanya pada sektor swasta atau proyek-proyek sesaat. Diperlukan aktor yang memiliki kapasitas besar, legitimasi publik, dan jaringan ekonomi nasional.
Di sinilah peran BUMN menjadi krusial. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN seharusnya tidak hanya mengejar efisiensi dan laba, tetapi juga menjadi mesin utama pencipta kerja produktif yang berkelanjutan.
Sayangnya, peran fundamental ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Penciptaan kerja di lingkungan BUMN masih muncul sebagai efek samping proyek, bukan mandat kelembagaan yang eksplisit dan terukur.
Mandat negara di tengah kosmetik sosial BUMN
Tren terbaru menunjukkan bahwa rasio serapan tenaga kerja terhadap nilai investasi terus menurun dari tahun ke tahun.
Jika pada masa lalu investasi sebesar Rp 1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja, maka pada tahun 2025 rasio itu turun drastis menjadi negara hanya sekitar 1.337 tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi.
Artinya, setiap satu tenaga kerja yang terserap kini memerlukan investasi sekitar Rp 748 juta. Fenomena ini menandakan bahwa investasi yang masuk semakin padat modal dan teknologi, bukan padat karya.
Penurunan rasio tersebut tidak hanya mencerminkan meningkatnya efisiensi, tetapi juga menunjukkan bahwa penciptaan kerja tidak lagi menjadi efek langsung dari pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar: ke mana harapan penciptaan kerja nasional seharusnya disandarkan?
Dalam konteks krisis ketenagakerjaan formal dan dominasi kerja informal, urgensi untuk menempatkan BUMN sebagai aktor utama pencipta lapangan kerja bermutu semakin menguat.
Gagasan ini bukan sekadar normatif, melainkan dapat menjadi pijakan bagi reformasi struktural yang berorientasi pada keberlanjutan sosial dan aman secara reputasional dalam kerangka kelembagaan negara berkembang.
Secara historis, BUMN di berbagai negara berkembang berfungsi sebagai employer of last resort—penyerap surplus tenaga kerja terdidik yang tidak tertampung oleh sektor formal.
Fungsi ini bukan dimaknai sekadar sebagai “penampungan tenaga kerja”, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang kompetitif melalui integrasi ke dalam sistem kerja yang terstruktur, produktif, dan berorientasi pelayanan publik.
Dalam praktik kelembagaan, banyak BUMN di Indonesia menunjukkan kecenderungan budaya organisasi yang berorientasi pada logika kapitalisme negara, di mana efisiensi dan profitabilitas ditempatkan sebagai tujuan utama.
Orientasi ini mendorong strategi operasional yang mengutamakan penggunaan modal dan tenaga kerja secara minimal, sehingga fungsi penciptaan lapangan kerja belum terintegrasi sebagai prioritas strategis.
Model bisnis semacam ini mencerminkan rasionalitas ekonomi jangka pendek yang mengabaikan dimensi sosial dari mandat institusional BUMN.
Lebih jauh lagi, dalam sejumlah kasus, BUMN memperlihatkan budaya organisasi yang bersifat feodal dan eksklusif.
Gaya hidup korporat yang menonjolkan simbol status sosial—seperti golf, perjalanan luar negeri, dan konsumsi berkelas—membentuk citra institusi yang berjarak dengan realitas sosial masyarakat sekitar.
BUMN tampil sebagai entitas ekonomi dominan, tapi minim sensitivitas sosial, menyerupai “tuan tanah baru” yang justru meminggirkan komunitas lokal dari proses pembangunan.
Transformasi budaya organisasi BUMN menjadi sangat krusial untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Tanpa perubahan paradigma kelembagaan yang menempatkan penciptaan kerja bermutu sebagai mandat utama, BUMN berisiko kehilangan relevansi publik dan gagal menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan inklusif.
Sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Konsekuensi logis dari amanat ini adalah kewajiban negara untuk menjamin hak atas pekerjaan secara aktif, bukan sekadar reaktif.
Dalam kerangka tersebut, BUMN sebagai instrumen negara semestinya dimandatkan untuk menjalankan fungsi penciptaan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pembangunan nasional.
Namun, regulasi yang mengatur BUMN, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta revisinya pada 2025, belum secara tegas menetapkan penciptaan kerja sebagai indikator kinerja utama.
Fungsi tersebut masih dianggap efek samping dari kegiatan bisnis, bukan tujuan kelembagaan yang terukur.
Bahkan dalam dokumen strategis seperti RPJMN dan RPJPN, peran BUMN sebagai instrumen pencipta kerja memang disebutkan, tetapi tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang mengikat dalam tata kelola korporasi.
Dalam praktiknya, BUMN beroperasi dengan logika korporasi yang menempatkan tenaga kerja sebagai alat produksi, bukan subjek pembangunan.
Model bisnis dengan jumlah pekerja terbatas dan upah minimum dianggap efisien secara finansial, tetapi berisiko tinggi terhadap keberlanjutan sosial.
Akibatnya, lapangan kerja yang tercipta sering kali bersifat temporer, rentan terhadap PHK, dan tidak menjamin penghidupan yang layak.
Kesenjangan serius pun muncul antara mandat konstitusional dan praktik kelembagaan. Tanpa reposisi fungsi penciptaan kerja sebagai indikator kinerja utama, BUMN berisiko kehilangan legitimasi sosialnya sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan inklusif.
KPI BUMN: Pembukaan lapangan kerja
Di tengah krisis ketenagakerjaan formal dan dominasi kerja informal, reposisi BUMN sebagai mesin utama pencipta lapangan kerja bermutu bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak.
Sebagai entitas dengan kapasitas modal besar dan jangkauan ekonomi luas, BUMN memiliki potensi strategis untuk menjalankan fungsi protektif terhadap pasar tenaga kerja nasional. Namun, potensi tersebut belum dioptimalkan secara sistemik.
Beberapa BUMN dengan modal usaha ratusan triliun rupiah hanya menyerap sekitar 10.000–15.000 tenaga kerja langsung, jauh dari prinsip investasi sosial yang idealnya menciptakan 1.000 lapangan kerja per Rp1 triliun.
Data nasional menunjukkan bahwa investasi Rp 942,9 triliun hanya menyerap 1,26 juta tenaga kerja, dengan rasio Rp 748 juta per orang—angka yang terus meningkat dan menunjukkan investasi semakin mahal secara sosial.
Di tingkat korporasi, rasio antara modal dan tenaga kerja menunjukkan kecenderungan yang semakin ekstrem.
Sebagai contoh, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Wijaya Karya masing-masing memiliki rasio investasi sebesar Rp 9 miliar – Rp 12 miliar per tenaga kerja, dengan mayoritas karyawan berstatus non-organik (PKWT).
Sementara itu, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) diproyeksikan memiliki total aset sebesar Rp 111 triliun pada 2025, tetapi target jumlah tenaga kerja hanya sekitar 8.012 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa rasio aset terhadap tenaga kerja di PIHC jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, mencerminkan karakteristik industri yang padat modal serta menegaskan tingkat efisiensi dan otomatisasi yang tinggi dalam operasional perusahaan.
Ketimpangan ini menandakan bahwa penciptaan kerja belum menjadi orientasi utama dalam desain kelembagaan BUMN.
Logika efisiensi dan profitabilitas masih dominan, sementara kontribusi terhadap sektor informal tidak terstruktur dalam indikator resmi. BUMN belum berfungsi sebagai mesin pencipta kerja formal yang stabil dan bermartabat.
Lebih dari itu, target karyawan dalam RKAP pun sering tidak tercapai, dengan realisasi hanya berkisar sekitar 90-97 persen. Sebagian besar tenaga kerja yang direkrut berstatus non-organik (PKWT), yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan minim jaminan karier.
Praktik ini memperlihatkan bahwa penciptaan kerja belum menjadi mandat utama, melainkan efek samping dari aktivitas bisnis dan pembiayaan.
Karena itu, diperlukan reformasi KPI yang menempatkan indikator sosial sejajar dengan indikator keuangan. BUMN harus menimbang penciptaan kerja sebagai ukuran kinerja utama—bukan pelengkap.
Penerapan KPI sosial ini perlu diikuti oleh desain kelembagaan yang mendorong kemitraan dengan UMKM, penguatan pelatihan kerja, serta inovasi berbasis lokal yang dapat memperluas dampak penciptaan kerja.
BUMN bukan sekadar mesin ekonomi. Ia adalah wajah negara dalam kehidupan rakyat. Ketika efisiensi dijalankan tanpa penciptaan kerja baru, negara kehilangan wajahnya.
Apabila mandat penciptaan kerja tidak ditata ulang secara struktural dan naratif, BUMN berisiko terus terjebak dalam ketegangan antara orientasi laba dan tuntutan legitimasi sosial.
Ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat BUMN dalam menjalankan peran historisnya sebagai pilar pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Tanpa reposisi kelembagaan yang menempatkan penciptaan kerja bermutu sebagai tujuan utama, BUMN akan kehilangan relevansi publik dan gagal memenuhi mandat konstitusional sebagai instrumen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Lebih jauh, dalam absennya koreksi terhadap logika korporatis yang dominan, BUMN berpotensi bertransformasi menjadi entitas kapitalis negara—yakni institusi yang tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan merebut ruang usaha rakyat dan memarginalkan mereka dari proses pembangunan.
Dalam konteks ini, BUMN tidak hanya gagal menciptakan kerja, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial melalui ekspansi modal yang tidak disertai dengan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan.
Tag: #bumn #mesin #utama #pencipta #lapangan #kerja #yang #terabaikan