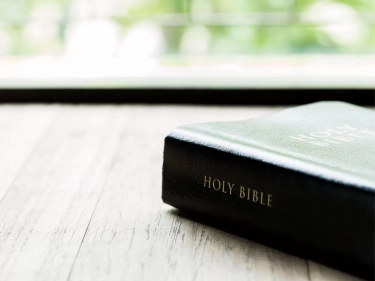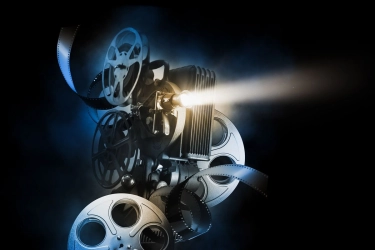Libur Telah Tiba, tapi Daya Beli Masih Cuti
KITA tentu masih ingat lagu “Libur Telah Tiba” yang begitu ikonik dalam memori anak-anak Indonesia. Lagu yang dipopulerkan Tasya Kamila itu selalu mengiringi euforia liburan sekolah.
Narasi kegembiraan, kebebasan, dan waktu untuk bermain seakan terpatri dalam setiap bait liriknya.
Namun, libur sekolah Juli 2025 datang dengan wajah berbeda. Di satu sisi, anak-anak tetap menyambutnya dengan antusias. Liburan, bagi mereka, adalah kebutuhan untuk tumbuh, bermain, dan merawat kebahagiaan.
Di sisi lain, orangtua dihadapkan pada realitas yang tidak sesederhana itu. Di tengah tekanan biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan daya beli yang belum pulih, liburan mulai bergeser dari kebutuhan menjadi pilihan yang penuh kalkulasi.
Jika merujuk pada hierarki kebutuhan Maslow, rekreasi dulu mungkin ditempatkan pada level kebutuhan sosial—rasa memiliki, penghargaan, atau bahkan aktualisasi diri.
Namun, dalam praktik kehidupan modern, liburan semakin diakui sebagai bagian dari kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan mental, keseimbangan emosi, dan kualitas relasi keluarga.
Sayangnya, kenyataan ekonomi kerap memaksa prioritas bergeser. Libur sekolah yang semestinya menjadi momentum pemulihan batin justru dihadapkan pada ironi.
Destinasi wisata yang sempat digadang ramai, tampak lengang. UMKM wisata mengeluh lesu. Sementara sebagian besar masyarakat memilih menahan diri, tinggal di rumah, atau sekadar staycation hemat.
Daya beli mandek, liburan tersendat
Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari daya beli yang terkikis, perubahan pola konsumsi keluarga, dan prioritas yang bergeser ke kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2025 mengungkap, 67 persen keluarga di Jabodetabek lebih memprioritaskan dana pendidikan dibandingkan alokasi untuk liburan.
Konsekuensinya terasa langsung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pengeluaran rumah tangga untuk rekreasi menurun 4,1 persen pada kuartal II 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lebih jauh, perilaku wisatawan juga mengalami pergeseran. Sebanyak 78 persen wisatawan domestik Juli ini memilih berdiam di akomodasi tanpa banyak melakukan eksplorasi destinasi.
Staycation menjadi solusi kompromi: tetap merasakan liburan, tetapi dalam batas pengeluaran yang lebih terkendali.
Di permukaan, media sosial tetap diramaikan unggahan bertema healing, piknik tipis-tipis, atau staycation yang tampak mewah.
Namun, realitas di balik layar seringkali berbeda. Banyak keluarga harus merelakan keinginan berlibur, memilih berhemat demi memenuhi kebutuhan lebih fundamental.
Jeda untuk refleksi
Pemerintah memang telah merespons dinamika ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, meluncurkan lima program prioritas nasional: Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0, Pariwisata Naik Kelas, Event Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Penguatan Desa Wisata.
Menurut Menpar, tahun 2025 adalah momentum membangun fondasi quality tourism yang berkelanjutan dan bernilai tambah.
Namun, implementasi di lapangan jauh dari tanpa tantangan. Gerakan Wisata Bersih, misalnya, tak akan optimal jika sanitasi di banyak desa wisata masih jauh dari memadai.
Tourism 5.0 yang berbasis teknologi canggih menghadapi kenyataan bahwa baru 12 persen fasilitas spa dan wellness yang telah terakreditasi secara medis, menurut data Kementerian Kesehatan per Juni 2025.
Dari sisi ketenagakerjaan, tantangan tidak kalah besar. Sebanyak 63 persen pekerja informal di sektor pariwisata belum tercakup dalam skema perlindungan sosial.
Tanpa perlindungan memadai, mereka sangat rentan terhadap gejolak pasar, termasuk fluktuasi kunjungan wisata selama libur sekolah.
Situasi ini membutuhkan lebih dari sekadar narasi promosi. Solusi harus konkret dan berpihak.
Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan kalender pendidikan dengan promosi wisata domestik berbasis keluarga.
Ini bukan sekadar penyesuaian jadwal, tetapi upaya menciptakan paket wisata yang sejalan dengan kebutuhan edukasi dan rekreasi anak-anak.
Kedua, insentif musiman berbasis data konsumsi rumah tangga dapat menjadi solusi. Pemerintah daerah bisa memberikan subsidi bunga pinjaman bagi UMKM wisata atau pembebasan pajak sementara bagi pengelola akomodasi dan atraksi yang berhasil meningkatkan kunjungan domestik pada periode low season.
Di sisi sumber daya manusia, penguatan kapasitas pelaku wisata desa menjadi kunci. Balai Latihan Kerja (BLK) sektor jasa bisa menjadi pilar pelatihan digital marketing, manajemen layanan hospitality, hingga produksi konten kreatif.
Kemitraan dengan platform digital lokal bisa mempercepat transformasi ini.
Terakhir, akselerasi akreditasi wisata kesehatan harus dipacu. Penyederhanaan perizinan, penguatan standar layanan, serta insentif bagi investor yang membangun atau meningkatkan fasilitas wellness dan wisata medis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peta jalan ini.
Dana CSR dari perusahaan atau pengabdian masyarakat dari kampus dapat diarahkan untuk membangun fasilitas edukasi, pusat sains mini, atau wahana belajar yang memperkaya pengalaman wisata keluarga.
Libur sekolah mestinya tidak hanya menjadi ruang untuk jeda, tetapi juga waktu untuk tumbuh, belajar tanpa tekanan, dan memperkuat relasi keluarga.
Namun, ketika liburan terganjal oleh daya beli yang kian tertekan, maka yang hilang bukan sekadar kesempatan rekreasi, tetapi juga hak anak untuk tumbuh bahagia.
Pilihan akhirnya kembali ke kita bersama. Apakah liburan akan terus kita pandang sebagai kemewahan yang boleh dilewatkan, atau sudah saatnya ia diakui sebagai bagian dari kebutuhan dasar keluarga Indonesia?